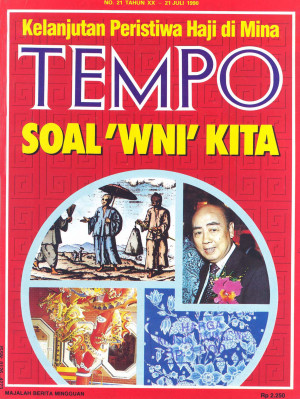KALAU dinding bisa bicara, maka ia akan berkisah. Bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba dari hutan dikawal 30 serdadu pilihan. Bagaimana derap lars bergema di sebuah ujung lorongnya, 45 tahun lalu. Namun, bahkan dinding-dinding saksi sejarah itu sudah tidak ada. Dinding-dinding putih Stasiun Gambir, Jakarta, itu sudah dirobohkan. Tak secuil puing kini tersisa. Menurut penuturan kontraktornya kepada Rizal Kusumaatmadja dari TEMPO, di sini akan dibangun kompleks pertokoan yang merupakan bagian bawah stasiun. Stasiun sendiri akan dibangun di bagian atas. Jalur layangnya kini sudah mulai dikerjakan. "Ada yang hilang," keluh Ir. Martono Yuwono, Kepala Subdinas Strategi Pengembangan Rencana Kota Dinas Tata Kota Jakarta. "Kita memacu pembangunan tanpa mengacuhkan nilai-nilai." Nilai itu, oleh Ir. Yuswadi Saliya, pengajar Jurusan Arsitektur ITB, diterjemahkan sebagai ungkapan totalitas budaya masyarakat. "Bila suatu daerah perumahan dibangun menghadap ke selatan, secara arsitektur konsep tersebut harus merupakan rekaman totalitas sosial budaya masyarakatnya," katanya kepada Dwiyanto Rudi dari TEMPO. Pendapat-pendapat itu dikemukakan Martono dan Yuswadi sebagai pembicara seminar "Dimensi Sejarah Dalam Proses Modernisasi Kota". Seminar yang berlangsung di Jakarta Design Centre, Sabtu pekan lalu, diselenggarakan oleh Yayasan Pelestari Budaya Bangsa, lembaga yang antara lain beranggotakan pengusaha Aburizal Bakri, Gubernur Wiyogo, budayawan Umar Khayam. Martono, yang belasan tahun bertugas di Dinas Museum dan Pemugaran, menekankan konsep pelestarian. "Bila seseorang kesasar, sebaiknya ia berhenti dulu dan bertanya," katanya. "Arsitektur Indonesia dalam keadaan bingung, sebab sampai saat ini belum ada apa yang disebut arsitektur Indonesia. Maka, sebaiknya kita berhenti dulu, melihat ke belakang dan melestarikan apa yang dinilai baik." Martono yang arsitek lulusan ITB itu menegaskan, konsep pelestarian bukan konfrontasi tua versus baru arsitektur klasik versus post-modern. "Pembangunan kota adalah upaya etis-moral manusia dalam perjuangan hidupnya menciptakan lingkungan dambaan," ujarnya. Maka semua usaha di masa lalu harus dihargai. Yuswadi mengkaji kendala pengkajian nilai-nilai. "Dari segi ekonomis, developer yang ingin membuat pusat pertokoan, mencari lahan strategis dengan tujuan mancari untung," katanya. "Ia tidak peduli nilai apa yang ada di atas tanah strategis itu." Yuswadi menyebut bangunan dengan pertimbangan ini Mercantile Architecture atau arsitektur yang didorong semangat dagang, bukan budaya. Arsitektur macam inilah yang menggantikan hotel Des Indes dan Stasiun Gambir. Juga bangunan-bangunan bersejarah lainnya kalau saja, pada tahun 1972 tidak keluar sebuah peraturan Gubernur. Dalam peraturan setebal 25 halaman ini tercantum 94 gedung bersejarah yang dilindungi undang-undang. Pendataan serupa kini sedang dilakukan Martono di kawasan Menteng seluas 350 hektar. Namun, konsep totalitas sosial budaya masyarakat bisa menimbulkan masalah. Apakah rumah-rumah tua di Menteng bisa dikatakan kebudayaan Indonesia? Juga Stasiun Gambir yang dibangun penjajah? "Tapi, selama arsitektur Indonesia belum terungkap, tidakkah sebaiknya kita belajar dari apa yang ada dulu?" Martono balik bertanya. Biang keladinya, menurut lulusan ITB ini, adalah paham gerakan Bauhaus di Jerman. "Mereka mengatakan, arsitektur selalu harus mulai dari nol," demikian Martono. "Seolah-olah tidak pernah ada sejarah dan budaya sebelum Bauhaus." Pada tahun 1962, Presiden Soekarno mempunyai impian serupa. Ia ingin menyulap Jakarta menjadi kota termegah. "Bukan sekadar gedung-gedung pencakar langit dan jalan raya, tapi berfungsi juga sebagai mercu suar." Keinginan megah yang terdorong trauma penjajahan itu lupa menggali nilai-nilai lokal. Pencakar langit Jakarta akhirnya tidak lebih dari jiplakan New York atau Hong Kong. Dalam suasana seperti ini, sejak tahun 1987, Yayasan Pelestari Budaya Bangsa mencoba mengimbangi semangat mencari kemegahan dengan pelestarian dan pemugaran. Satu di antaranya memacu Sunda Kelapa Redevelopment Project yang memang sudah direncanakan Pemda DKI. Alhasil, proyek tersebut akan dipamerkan di Rotterdam, Belanda, September mendatang. "Kami mengharapkan kerja sama antara pihak Indonesia dan Pemerintah Belanda," tutur Ir. Martono, yang menjabat ketua yayasan itu. Yang akan diabadikan pada proyek itu bukan cuma bangunan bersejarah seperti masjid abad ke-18 di kampung Luar Batang atau Menara Syahbandar. Tapi, juga perumahan rakyat dan pelabuhan. "Daerah seluas 300 hektar itu nantinya akan mempunyai promenade, teater, taman laut, dan restoran di atas kapal pinisi," ujarnya. Biaya pemugaran ini cukup besar, mencapai puluhan milyar rupiah. Investasi ini, konon, akan diimbangi income dari pariwisata yang tidak kalah besar. Namun, menurut Martono, aspek ekonomi bukan perhitungan utama pemugaran kawasan bersejarah. "Pelestarian bermaksud mempertahankan kesinambungan nilai-nilai yang tidak ternilai harganya," katanya. Yudhi Suryoatmodjo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini