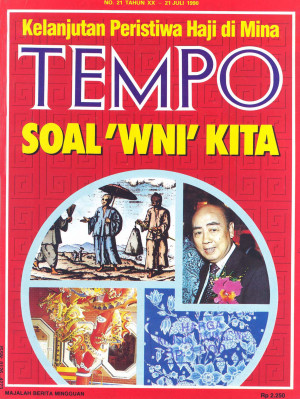MENYEBUT mereka saja sulit. Orang Cina? Mereka banyak yang tak bisa berbahasa Cina, dan tak merasa bertanah air di RRC. WNI? Mereka memang WNI, tetapi yang Jawa, Bugis, Irian, Arab, dan lain-lain juga "warga negara Indonesia". "Nonpribumi"? Di beberapa wilayah Indonesia, misalnya di Singkawang, Kalimantan, mereka yang punya kakek nenek kelahiran setempat sekian ratus tahun yang lalu mungkin lebih "pribumi" ketimbang si Jawa yang baru di abad ke-20 datang ke sana. Jangan-jangan nanti orang Batak yang berbisnis di Timor Timur juga bisa disebut "nonpri". Maka, disebutlah mereka "keturunan Cina" -- meskipun banyak yang waswas jika sebutan ini akan memisahkan mereka dari warga lainnya. Sungguh sulit. Soalnya, hubungan antarras di Indonesia, sebenarnya juga di banyak negara, bisa menimbulkan ketegangan dan saling curiga yang merusak dan sering menyedihkan. Apa sebenarnya soalnya: soal rasial, atau soal kultural, atau soal jurang sosial ekonomi? Nampaknya, perihal "keturunan Cina" ini belakangan kian mendesak dibahas. Sebuah simposium yang bertema The Role of the Indonesian Chinese in Shaping Modern Indonesian Life diselenggarakan oleh Cornell University, Ithaca, AS, 13-15 Juli 1990 lalu, mencoba menyoroti lebih jauh perkara ini. Yang bicara orang dari dunia akademi dan juga orang dari lapangan hidup -- dan dari Indonesia hadir satu rombongan besar, sebagian besar cendekiawan keturunan Cina (lihat: Mendobrak Tabu di Ithaca). Seminar di Ithaca itu belum tentu menambah soal jadi gampang, malah mungkin -- seperti banyak terjadi dengan seminar para pakar -- menambah ruwet. Di Indonesia sendiri, soalnya lebih difokuskan bukan kepada soal budaya, tapi pada soal sosial ekonomi: sebab diduga keras bahwa warga keturunan Cina yang jumlahnya berkisar 3-4 juta itu menguasai perekonomian Indonesia. Betulkah? Itu hanya mitos, kata James Mackie, seorang sarjana peneliti terkemuka dari kancah Australian National University di Canberra. Kalau toh ada perusahaan Cina yang sukses, kata Mackie di seminar di Ithaca itu, biasanya hanya bertahan dalam tiga siklus generasi -- karena generasi penerusnya tak segigih pendahulunya. Christianto Wibisono, komentator soal-soal ekonomi yang banyak menulis itu, juga pernah mencoba membantah "mitos" itu. Menurut Christianto, negaralah yang masih jadi pemegang modal terbesar. Pendapat ini tak mudah dibantah, tapi tak otomatis menampik anggapan bahwa penduduk keturunan Cina -- sebuah minoritas -- kebagian kue ekonomi yang lebih lezat ketimbang penduduk lainnya. Lihat saja daftar pembayar pajak perseorangan terbesar tahun 1988, yang diumumkan pada tanggal 25 Juni 1990 silam. Dari 10 nama pembayar pajak terbesar, tujuh di antaranya adalah pengusaha keturunan Cina -- seperti Liem Sioe Liong, Robert Budi Hartono, Atang Latief, Anthony Salim, atau Jan Darmadi. "Saya bayar Rp 16 milyar," kata Om Liem yang terpilih sebagai pembayar PPh terbesar. Ada yang menebak -- taruhlah dia membayar PPh 30% -- pendapatan tokoh yang dijuluki Raja Semen itu tak kurang dari Rp 54 milyar. Ingat, itu penghasilan dua tahun yang silam. Tahun lalu, pendapatannya ditaksir bakal melonjak dua kali lipat. Lalu, siapa Robert Budi Hartono alias Oei Hwie Tjiong? Dialah raja kretek dari Kudus yang mengelola pabrik Rokok Djarum yang omset perusahaannya sekitar Rp 1,5 trilyun setahun. Majalah Warta Ekonomi edisi Januari 1990 silam juga mengeluarkan daftar 25 orang terkaya di ASEAN. Di situ, lagi-lagi terlihat keturunan Cina mendominasi bisnis Asia Tenggara. Dari 25 nama tadi, 21 adalah keturunan Cina. Dan, sepuluh di antaranya, atau hampir separuhnya, berasal dari Indonesia. Anda mau tahu siapa mereka? Liem Sioe Liong (kekayaannya US$ 2,4 milyar), William Soeryadjaya (US$ 700 juta), Eka Tjipta Widjaja (US$ 500 juta), Rachman Halim (US$ 400 juta), Hartono Bersaudara (US$ 400 juta), Mochtar Riady (US$ 350 juta), Suhargo Gondokusumo (US$ 200 juta), Jan Darmadi (US$ 160 juta), The Ning King (US$ 150 juta), dap Bob Hasan (US$ 140 juta). Belum lagi melihat 10 bank swasta peringkat atas di Indonesia kini: hanya satu yang dimiliki oleh pengusaha bukan keturunan Cina. Tampaknya, sejumlah fakta di atas itu memang bisa dijadikan pembenaran adanya supremasi pengusaha keturunan Cina. Di pasar modal juga tak jauh berbeda. Seorang konsultan memperkirakan 80% dari perusahaan yang go public itu adalah milik keturunan Cina. Padahal, kekayaan perusahaan yang go public ini besar-besar. Menurut perhitungan usahawan Probosutedjo, dana masyarakat yang didapat oleh 106 perusahaan yang telah go public tadi mencapai Rp 7,126 trilyun alias seperlima APBN tahun ini. "Maka, timbullah kecemburuan," ujar Probo. Istilah "kecemburuan" mungkin cuma berlaku buat antarpengusaha yang bersaing. Bagi para pengamat, yang berlaku adalah kekhawatiran: jarak kekayaan yang besar antara anggota masyarakat, apalagi bila diwarnai perbedaan rasial, umumnya bisa menimbulkan perpecahan, malah kerusuhan. Kerusuhan rasial memang terbukti sudah sering terjadi di pesisir utara Pulau Jawa sejak abad silam. Pada mulanya adalah munculnya kelas pedagang, yang sebelumnya tak dikenal oleh masyarakat Indonesia yang agraris. "Budaya agraris sangat anti terhadap kaum pedagang yang dianggap kikir dan suka menipu," kata Sejarawan Onghokham. Dan ternyata kaum pedagang yang ditentang itu kebanyakan adalah keturunan Cina perantauan. Kaum perantauan memang selalu terpaksa memasuki bidang kerja yang oleh orang asli dianggap tak patut. Dan jadi pedagang oleh aristokrasi orang Jawa, khususnya, memang dianggap rendah. Belanda ketika berkuasa di negeri ini cukup jeli melihat potensi peranakan Cina. Itu sebabnya banyak orang Cina yang kemudian dibiarkan leluasa berniaga untuk memasok keperluan penjajah Belanda. Taipan pertama di Indonesia barangkali adalah Souw Beng Kong, yang kemudian menjadi pemimpin masyarakat keturunan Cina dengan dapat gelar "Kapten". Pada pertengahan abad XIX dia kondang sebagai pengusaha kakap yang bermarkas di Batavia. "Konglomerat" pertama di zaman penjajahan Belanda adalah NV Kian Gwan di Semarang yang banyak bergerak di bisnis gula. Konglomerat ini lebih populer dengan sebutan Oei Tiong Ham Concern yang cabangnya merebak ke berbagai kota di penjuru dunia, seperti Singapura, Kobe, Shanghai, Calcutta, London, Amsterdam, New York, Rio de Janeiro, dan lain-lain. Oei Tiong Ham Concern kemudian limbung karena generasi penerusnya tak mampu mengembangkan perusahaan. Akhirnya, NV Kian Gwan tergilas pengambilalihan oleh negara di tahun 1960-an. Rontok. Zaman berubah. Ada pelajaran dari rontoknya Oei Tiong Ham Concern. Kini, menjelang akhir abad ke-20, pelan-pelan manajemen dan modal tak lagi bertumpu di tangan anggota keluarga. Sejumlah profesional digaji untuk mengurus perusahaan dan sebagian modal malah ditawarkan ke bursa saham. Konsekuensinya: perusahaan yang mau menjual sebagian sahamnya harus dikenal secara luas. Itu berarti pemiliknya juga harus sering pasang muka di berbagai media massa. "Promosi itu memang harus dilakukan, a part of the business. Bahwa mereka mau nampang, itu bukan politis," kata Sofjan Wanandi, bos kelompok Gemala dan Pakarti. Tapi ada yang melihatnya ini sebagai gejala yang positif. Ini pertanda bahwa keturunan Cina merasa sudah "aman" di Indonesia. Mereka tak perlu lagi sungkan-sungkan menunjukkan identitasnya untuk tampil di masyarakat. Rasa aman ini nampak juga dalam cara mereka membangun rumah: cukup mewah -- seperti halnya yang juga lazim dimiliki oleh orang-orang pribumi yang kaya, yang tak takut terkena sita atau huru-hara. Juga untuk menghabiskan waktu senggangnya, mereka tak lagi khawatir. Di restoran, hotel, tempat rekreasi kelas satu mayoritas yang ada adalah keturunan Cina. Meskipun ini mungkin disebabkan oleh cara mereka menghabiskan waktu luang yang berbeda dengan orang Jawa, Sunda, atau Makassar, tak urung dan bisa dimengerti bila banyak orang yang bukan peranakan Cina merasa terpojok di tempat-tempat mewah itu. Apalagi bila di tempat yang seperti klub malam Dynasty di wilayah Glodok, Jakarta. Klub ini yang dibangun dengan dana sebesar Rp 5 milyar. Ruangannya mampu menampung 3.000 tamu sekaligus. Inilah klub malam paling megah dan luas di Asia. Untuk memenuhi selera para tetamu, makanan dimasak oleh tujuh koki yang khusus didatangkan dari Hong Kong. Dengan begitu, para taipan Indonesia tak perlu lagi harus sembunyi-sembunyi pergi ke Hong Kong, atau Singapura untuk mendapatkan layanan ala para mandarin. Dynasty juga tampaknya tak melulu konsumsi buat taipan Indonesia. Kini investasi dari beberapa negara yang "berbau Cina" seperti Singapura, Hong Kong, dan Taiwan semakin meningkat. Nilai investasi Hong Kong dalam paruh pertama tahun ini saja sudah melampaui investasi Jepang. Sedangkan investasi Taiwan di tahun ini meningkat 100% ketimbang tahun sebelumnya (lihat Grafik). Ini berarti banyak pengusaha Taiwan, Hong Kong, atau Singapura yang mondar-mandir ke Jakarta. Malah ada yang bermukim sementara sebagai tenaga asing alias expatriate. Mereka ini kian menyebabkan terasa hadirnya sosok "Cina" di Indonesia -- yang oleh orang banyak sulit dibedakan mana yang "orang Cina sini" dan yang "orang Cina sana". Ini semua tak lepas dari dampak deregulasi ekonomi di awal tahun 1980-an. Tanpa banyak hambatan lagi, perusahaan Indonesia yang dimiliki keturunan Cina -- yang sudah mapan -- jadi mitra perusahaan dari Timur Jauh yang datang itu. Citra yang timbul ialah suatu gabungan atau persengkongkolan -- seakan antara perusahaan "Cina" tak terjadi saling hantam. Orang belum tahu misalnya kini berlangsung kongkurensi sengit di pasar modal antara Gudang Garam dan Sampoerna. Atau orang bisa bilang: apa beda antara keduanya? Keduanya kan bukan "pribumi"? Soalnya kemudian: mau diapakan mereka yang "bukan pribumi" itu. Sejauh ini belum terdengar jalan lain dalam menghadapi pengusaha keturunan Cina itu. Meniadakan peran mereka, atau memanfaatkannya? Sikap pragmatis dipilih oleh Presiden Soeharto. Seperti yang terungkap dalam biografinya yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, "Saya pun melihat, modal orang-orang Tionghoa itu berkembang di sini dengan cepat. Memang mereka mempunyai kemampuan pula. Kita manfaatkan hal ini untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional kita. Jangan salah terka! Pemerintah kita punya kekuasaan untuk memanfaatkan dan mengatur. Mengapa mesti takut?" Bagaimana "memanfaatkan dan mengatur" ini ditunjukkan caranya kemudian. Tak lama setelah biografinya diterbitkan Pak Harto mengumpulkan 31 pengusaha kelas kakap -- yang sebagian besar adalah keturunan Cina -- di Tapos, awal Maret 1990 silam. Di situ Presiden meminta kepada mereka untuk menjual 25% sahamnya kepada koperasi. Adakah itu akan jadi katup pengaman agar tak terjadi pemindahan dana ke luar negeri? Atau justru mendorong orang mengungsikan kapital? "Kami tak akan lari ke luar negeri. Indonesialah yang membesarkan kita," ujar Sofjan Wanandi, aktivis Angkatan '66 yang juga juru bicara para pengusaha yang pernah diundang Pak Harto ke Tapos itu. Itu belum tentu segera menyelesaikan soal jurang sosial dan prasangka rasial. Biarpun telah disusul tindakan lain, misalnya kerja sama ekonomi organisasi Islam NU dan Muhammadiyah dengan para "konglomerat" (lihat Dari Muhammad Japar sampai Kho Ping Ho). Di satu pihak, harus diakui, ada pembatasan tertentu bagi warga keturunan Cina -- yang KTP-nya pun kadang masih diberi kode tertentu. Yang menonjol ialah pemberian kuota bagi siswa keturunan Cina buat masuk ke perguruan tinggi negeri yang beken. Alasannya bisa dimengerti: jika siswa "pribumi" terdesak, seperti di zaman kolonial dulu, rasa pahit terhadap keturunan Cina akan kian keras. Tapi dengan kuota, kini satu akibat lain juga terjadi: banyak siswa keturunan Cina bersekolah di luar negeri. Bukan saja mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Juga mereka mengalami proses sosialisasi yang berbeda dengan anak Indonesia yang bersekolah di dalam negeri. Masih belum diteliti, kian jauhkah sebagian besar mereka dari "akar" Indonesia. Yang bisa diduga, jurang dan beda pengalaman generasi muda ini bisa tambah lebar kelak. Kecuali bila para sarjana keturunan Cina memilih utuk tak kembali -- satu hal yang juga bisa merugikan, bila merupakan proses braindrain, atau hijrahnya orang pintar, seperti yang dialami oleh Filipina dan India. Apalagi proses sosialisasi para keturunan Cina kini memang agak terbatas di kalangan sendiri, justru ketika posisi ekonomi mereka menjulang. Mereka cuma bergerak di dunia bisnis, yang isinya sebagian besar kalangan mereka juga. Mereka tak mudah masuk ke aparat negara, di mana bisa diharapkan ada gemblengan pengabdian dan rasa kesatuan bangsa. Dulu, di zaman demokrasi parlementer, partai dan gerakan masyarakat merupakan wadah lain bagi penggemblengan itu. Dulu bahkan sampai ada yang jadi menteri, misalnya Ong Eng Die (Menteri Keuangan) dan Lie Kiat Teng (Menteri Kesehatan). Yang terakhir ini malah anggota Partai Syarikat Islam Indonesia. Kini, normalisasi hubungan diplomatik RI-Cina sudah di ambang pintu. Sebuah babak baru buat kedua negara bakal dimulai, setelah 8 Agustus 1990 nanti cair kembali hubungan diplomatik. Ada anggapan langkah pemerintah ini akan menyenangkan warga keturunan Cina. Ini anggapan yang tak betul, sebab para pengusaha itu (kebanyakan bersikap antikomunis) justru mengalami trauma akibat hubungan Beijing-Jakarta. PKI waktu itu lebih dekat ke RRC ketimbang ke Uni Soviet. Akibatnya, semua warga Indonesia keturunan Cina kena getahnya. Toh anggapan salah tentang normalisasi itu menunjukkan soal lain yang agaknya nyaris luput dari perhatian. Menurut Juwono Sudarsono, itu adalah soal "pembangunan politik kita". Buat Juwono, normalisasi hubungan "pri" dan "nonpri" juga tak kalah penting dengan dibukanya kembali hubungan diplomatik RI-Cina. Ahmed K. Soeriawidjaja, Liston P. Siregar, G. Sugrahetty Dyan K. (Jakarta), dan Bambang Harymurti (Ithaca) TB. ----------------------------------------------------------------- INVESTASI ASING ----------------------------------------------------------------- 1986 1987 1988 1989 1990 ----------------------------------------------------------------- Jepang 85,7 896,6 353,9 768,7 564,5 Hongkong 129,6 192,0 244,0 406,8 639,6 Taiwan 17,0 8,4 903,8 156,2 334,6 Singapura 104,1 42,2 236,8 166,1 170,6 ----------------------------------------------------------------- Sumber: BKPM
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini