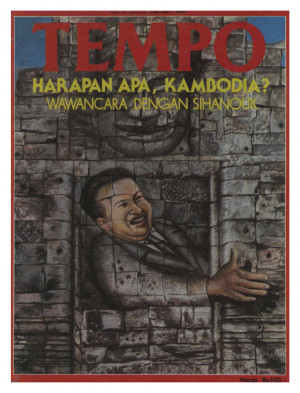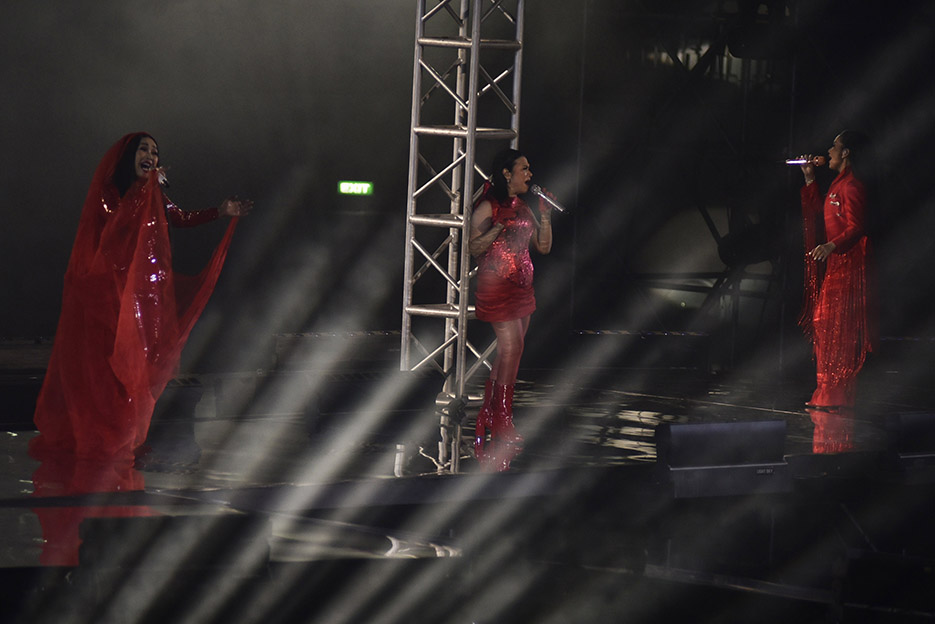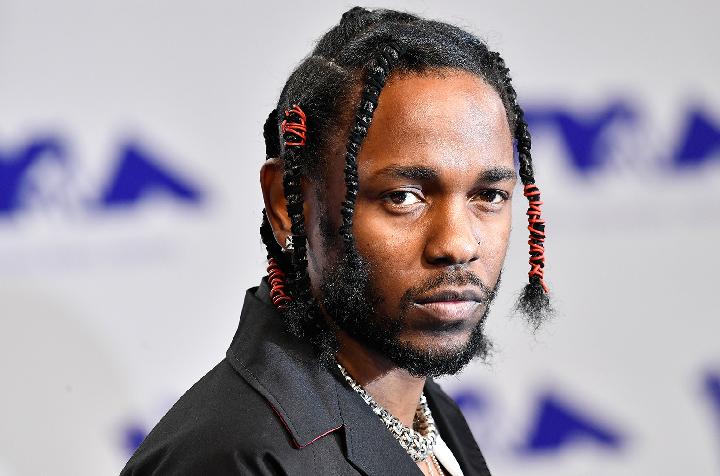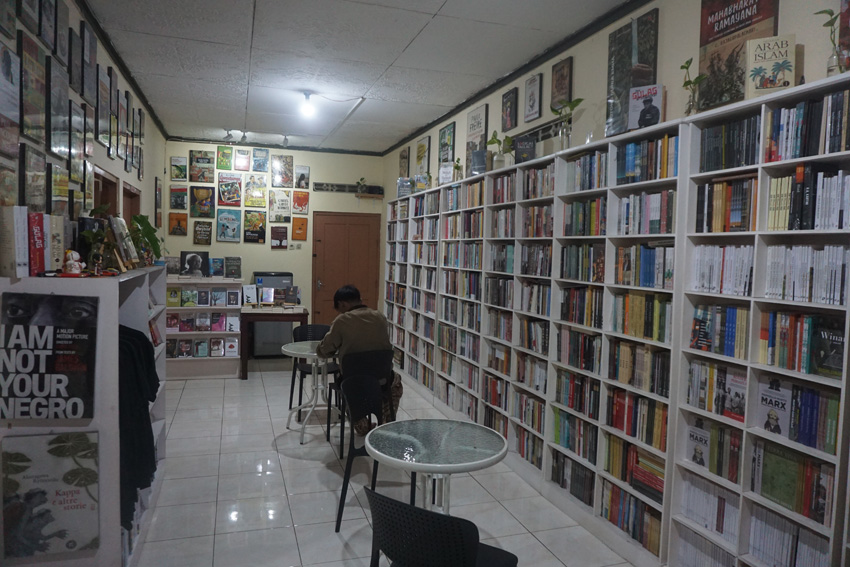KEMUDIAN, memang ada pikiran-pikiran baru, perspektif baru dalam
kehidupan musik kita -- yang kini seolah-olah macet. Tuuh
komp,onis muda itu -- baik yang bertolak dari tradisi musik
Barat maupun Jawa, Sunda atau Bali --menyuguhkan karya-karya
yang boleh dibilang selama ini tak pernah kita dengar.
Jadi, Pekan Komponis Muda yang pertama ini, 19-22 Desember yang
lalu di Taman Ismail Marzuki, memang menelurkan hasil yang
bermanfaat. Sebuah karya bertolak dari musik Sunda karya Nano
Suratno, 35 tahun, misalnya, memasukkan unsur baru: macam-macam
instrumen yang belum pernah dikembangkan sebelumnya.
Sangkuriang, judul karya itu, makan waktu sekitar empat puluh
menit, menyerap masuk berbagai alat musik tiup bambu berbagai
ukuran yang khusus dibuat dan dikembangkan oleh Tatang Suryana
-- seorang tokoh musik Sunda. Alat-alat itu, dengan cerdik
diaduk Nano Suratno ke dalam karawitan Sunda, sehingga
menimbulkan beragam efek, bunyi penuh warna.
Sebagai alat tiup, instrumen bambu itu, di samping rebab dan
suling, sangat penting dan potensial sekali untuk membentuk
garis suara bersambung dan memanjang. Manfaatnya, sebagai
imbangan dan kontras dari bunyi pendek dan terputus alat gamelan
kita yang sifatnya perkusip. Nano, yang kini mengajar di Sekolah
Menengah Karawitan Indonesia di Bandung, juga memasukkan mainan
anak-anak seperti gasing, kaleng biskuit yang diberi tali (yang
mengeluarkan bunyi kalau tali ditarik). Bahkan ia juga
memasukkan macam-macam bunyi yang distilisasi dari bunyi tepuk
tangan dan mulut.
Ilmu Sekolah
Juga pada peserta-peserta lainnya, perasaan tidak puas dan
merasa butuh untuk tidak mandeg pada tradisi, untuk bergerak
keluar lebih jauh dari dalamnya, sangat nyata. Komang Astita, 27
tahun, dari Bali juga berpijak pada landas pemikiran yang
serupa. Dalam karyanya Gema Eka Dasa Rudra yang panjangnya lebih
dari setengah jam, ia bahkan memasukkan sapu lidi, lesung dan
penumbuk padi, kentongan balai desa sebagai instrumen musik.
Dengan pintar Sarjana Muda Akademi Akademi Seni Tari Indonesia
di Denpasar ini, mengorkestrasi alat-alat itu, sehingga
benar-benar terkait dan terasa akrab dengan bunyi gamelan Bali.
Digantungkannya bermacam-macam gong dengan tali langsung dari
atap Teater Arena. Sementara jenis gong lainnya (bende?) dengan
cara yang sama digantung di seberang sudut yang lain, di antara
dua kentongan. Gong dan kentongan itu ditabuh oleh seorang
pemain, yang karenanya harus terus-menerus bergerak ke sana ke
mari. Ini tidak saja memberikan efek teatral dan komposisi
pandang yang geniai, tapi sekaligus menyuguhkan efek akustis dan
gerak ritmik abstrak yang brilyan.
Pemecahan efek akustis ia capai dengan menempatkan instrumen
secara menyebar ke seluruh ruang arena. Tidak mengelompok,
seperti biasa dilakukan pada karawitan kita atau bentuk ensembel
lainnya. Akibatnya suara tidak datang dari satu pusat arah saja,
tetapi terpencar dengan bagus sekali. Pada hakikatnya ini memang
sudah lazim dalam teater Bali: bahwa bunyi (musik), gerak
(tari), dan lakon (teater) saling bertumpangan satu sama
lainnya.
Dengan siasat yang mirip, Rahayu Supanggah, 30 tahun dari
Surakarta dengan karyanya Gambuh tidak saja memakai alat lain
yang "non-gamelan", tapi juga menggunakan mantra, mainan
anak-anak, permainan kata yang distilisasi sebagai sumber efek
bunyi. Hasilnya cukup mempesonakan. Terasa bahwa Supanggah,
lulusan Akademi Seni Karawitan Indonesia di Surakarta ini,
menguasai teknik orkestrasi, akrab dengan bunyi, mengenal medan
dan tahu sasaran. Hasil yang sama sebenarnya dapat juga dicapai
oleh koleganya se"tanah air", Sri Hastanto. Tapi Dandang Gula
Sri terasa terlalu di'organisasi', sehingga kesan "resmi"nya tak
terelakkan.
Justru Berontak
Kesan "resmi" untuk menerapkan ilmu sekolah bahkan sangat terasa
pada karya Kristyanto Christinus, 20 tahun, mahasiswa Akademi
Musik Indonesia di Yogyakarta, yang berjudul A dan B.
Semua ide bisa jadi "barang" besar, kalau orang mengerti cara
dan sigap menggarap masalahnya. Seperti terjadi pada karya
elektroniknya Otto Sidharta Kemelut, yang baru permainan fantasi
itu. Tapi, ide penggarapan air sebagai sumber bunyi (musik)
dengan media elektronik patut dihargai. Seperti banyak dilakukan
di Eropa, Amerika dan Jepang, terutama pada pertengahan abad XX
ini, modul-modul bunyi yang keluar lewat media elektronik dapat
melahirkan musik, atau seni bunyi, yang tak kalah hebatnya
dengan musik konvensional. Demikian pula karya Otto, 24 tahun,
mahasiswa Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, ini.
Musik konvensional, seperti kita kenal sehari-hari inilah yang
ingin dilawan oleh Sutanto, 25 tahun, mahasiswa AMI di
Yogyakarta, dengan karya absurdnya Sketsa Ide. Agak
mencengangkan (atau justru logis?) bahwa anak muda dari
Yogyakarta, kota yang terkenal klasik itu, justru berontak
melawan arus kebiasaan legitimitas musik. Ia bahkan tidak
berpretensi menyebutkan karyanya sebagai musik. Karya musik yang
gaduh ini, atau simponi hiruk-pikuk, tidak saja mengerahkan
sejumlah pemain -- yang tidak profesional -- bahkan juga seluruh
penonton. Musik Sutanto menyarankan agar kita berpikir dan
merenung kembali apakah masih perlu dan ada gunanya melanjutkan
kebiasaan membosankan dalam kehidupan (musik) kita sehari-hari.
Dan itulah kesan keseluruhan Pekan Komponis Muda yang pertama
ini.
Suka Hardjana
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini