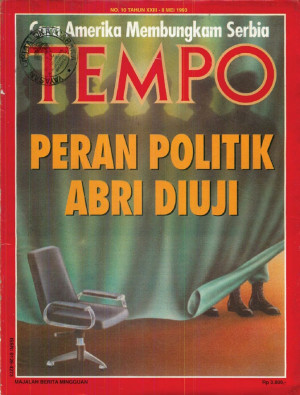TERSEBUTLAH seorang pemuda sederhana bernama Uca, yang sehari- hari bekerja sebagai pengurus kuda. Uca (dimainkan Cok Simbara), seorang sarjana hukum, hidup bahagia dengan istrinya, Desi (diperankan dengan baik oleh Tarida Gloria), tanpa beban apa-apa dan tanpa ambisi hidup. Memandang kehijauan kebun teh sambil mengurus kuda-kuda tuan besar Darma (Dedy Mizwar) seorang konglomerat terkemuka sudah cukup membuat hatinya tenteram. Suatu hari mendadak Tuan Darma yang juga adalah mertuanya mengangkat Uca menjadi direktur anak perusahaannya. Ini bukan saja mengejutkan Uca, tapi sekaligus menimbulkan rasa cemburu Bandawa (Priyo Winardi), Sugih (Muni Cader), dan Harta (Zaenal Abidin), tiga eksekutif yang merasa lebih senior, lebih cakap, dan lebih berpengalaman. Kisah ini sebenarnya sebuah cerita klasik politik perkantoran yang terjadi pada banyak perusahaan besar di Indonesia. Tak mengherankan jika Uca harus tabah menghadapi cemooh, ancaman pembunuhan, surat kaleng, telepon gelap, dan berbagai bentuk teror lainnya. Tak cukup dengan teror-teror semacam itu, Uca ''diumpani'' dengan seorang sekretaris cantik, Iin (Georgiana Supit), agar Uca terlena dalam pekerjaannya. Tapi jangan mengharapkan Putu Wijaya akan menyodorkan resep bagaimana cara menghadapi keculasan rekan sekantor. Ia bukan seorang seniman yang gemar mengumbar kepedihan dengan cara yang getir. Segala kepahitan yang dialami Uca menjadi sebuah karikatur yang bukan saja menggelitik, tapi juga memancing kita untuk merenung. Uca, dengan segala idealisme dan kenaifannya, masih percaya bahwa kejujuran dan ketulusan masih bisa mengatasi intrik-intrik politik yang dilancarkan rekan-rekannya yang senior. Sementara itu, trio Bandawa-Sugih-Harta dengan segala cara berusaha mendepak Uca dari kantor itu. Sementara Uca sibuk bertempur di kantor melawan intrik politik, Desi membeli perabotan rumah tangga modern dengan nafsu yang menggebu-gebu. Sedemikian nafsunya untuk menjadi istri direktur yang ideal, Desi bahkan mengadakan ''kursus'' untuk pembantunya tentang etika menjawab telepon. Lantas pembantunya, yang biasa memakai kebaya, langsung diberi seragam putih agar ia tampak seperti suster. Penyakit OKB (orang kaya baru) ini terlihat semakin parah ketika Desi membeli sebuah lukisan reproduksi Picasso dan memasangnya secara terbalik di dinding. Inilah cara Putu Wijaya menyajikan sebuah persoalan rumit. Ia tidak berpretensi untuk memberi obat mujarab, melainkan memperlakukan persoalan itu sebagai sebuah lelucon yang perlu dinikmati dan dihayati. Semua tokoh Putu memiliki kelemahan. Uca yang naif, Desi yang ambisius, Darma yang mempermainkan ambisi perebutan kekuasaan di antara anak-anak buahnya, dan trio Bandawa-Sugih-Harta yang culas dan gemar menjilat atasan. Putu tak perlu berteriak-teriak ketika mengkritik dan bahkan tak percaya dengan ucapan-ucapan verbal untuk menjelaskan misinya. Terkadang kritik Putu berupa pertanyaan-pertanyaan yang perlu direnungkan penonton. Bagaimana seorang konglomerat merekrut seorang sekretaris cantik hanya karena wanita itu bersedia nyemplung ke sungai? Bagaimana kita bisa menjelaskan pemikiran Darma yang sengaja membiarkan ketiga koleganya mempermainkan menantunya sendiri dalam pertandingan kekuasaan? Apa pula artinya jika karyawan-karyawan perusahaan hanya tertawa jika Bos Besar tertawa dan hanya berdiri dengan sikap ngapurancang ketika Bos Besar berpidato? Sebagai seorang cerpenis, novelis, dan dramawan, Putu memang telah menunjukkan kelasnya. Namun film adalah sebuah kesenian yang kesempurnaannya bukan hanya terletak pada jalan cerita dan akting pemain, melainkan juga pada aspek-aspek lainnya seperti kecerdasan menyunting, permainan kamera, pencahayaan, dan ilustrasi musik. Setelah Cas Cis Cus dan Zig Zag, Putu belum memperlihatkan kesempurnaan aspek-aspek perfilman tersebut sebaik ia merancang teaternya. Ilustrasi musik dikerjakan Areng Widodo tidak jelas juntrungan ritmenya. Putu juga belum mengeksploitasi kamera semaksimal mungkin untuk menumbuhkan imajinasi penonton. Gambar-gambar dan adegan yang tercipta, meski tidak jelek, tidak orisinal. Kelebihan Putu masih merupakan kelebihan seorang novelis yang pandai bercerita. Ia bercerita dengan lancar dan menciptakan dialog yang tangkas. Tapi Putu masih belum membuktikan betapa layar perak mampu menerjemahkan ide-idenya dengan gambar yang fantastis. Plong sama sekali tidak berkisah tentang pertandingan yang menghasilkan pemenang. Memang Uca akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan dan kembali ke profesinya sebagai pengurus kuda, tapi ia tidak kalah dalam pertarungan. Ia merasa lega karena tetap mempertahankan integritasnya sebagai seorang manusia. Trio Bandawa-Sugih-Harta yang selalu dibela oleh Bos Besar Darma demi nama Angkatan 45 juga tak bisa dikatakan pemenang. Plong adalah sebuah otokritik jenaka. Leila S. Chudori
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini