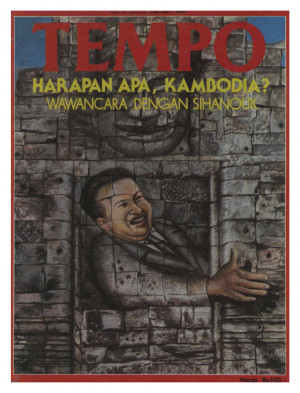BERLINDUNG di depan agak ke samping sebuah lokomotip, dua
pejuang itu beraksi. Seorang berbaret merah memberondongkan
peluru dari mitraliyur. Seorang berbaret hijau membidikkan
karabennya. Sementara di belakang mereka, seorang pejuang yang
lain mengendap mencoba maju.
Itulah salah satu lukisan dalam Pameran 400 Lukisan Realistik
yang bertemakan Perang Kemerdekaan dan juga kehidupan
sehari-hari, di Aldiron Plaza, Blok M Jakarta, 20 Desember-2
Januari ini. Para pelukisnya adalah warga Himpunan Budaya
Surakarta (HBS) dan Sanggar Pejeng, Bali -- kedua perkumpulan
pelukis itu dipimpin oleh pelukis Dullah, 60 tahun.
Sebetulnya, karya-karya itu -- lukisan Perang Kemerdekaan
terutama -- bukan pertama kali ini dipamerkan. Mei 1978 yang
lalu, telah dipamerkan di Yogyakarta. Sambutan para pelukis dan
pengamat seni lukis memang ramai. Terutama ditujukan kepada
karya-karya yang benar-benar orisinal, yang dibuat semasa Perang
Kemerdekaan di tahun 1949 di Yogyakarta. Dan pelukisnya --
Mohammad Toha, Muhammad Affandi, FX. Soepono, Sri Soewarno dan
Sarjito -- waktu itu masih tergolong anak-anak berusia antara 11
sampai 15 tahun.
Pelukis Affandi memujinya sebagai karya-karya yang "komposisinya
hebat, ceritanya padat dan memikat karena dibuat langsung".
Mungkin Affandi agak berlebihan. Sebuah karya M. Toha misalnya,
menggambarkan tentang penggeledahan rumahnya oleh Belanda,
karena diketahui pamannya, Achmad Tirtosudiro (sekarang Dirjen
Pariwisata), ikut bergerilya. Dalam bidang gambar berukuran
sekitar 7 x 10 cm, memang tak bisa secara jelas menggambarkan
bagaimana suasana ketika penggeledahan itu. Hanya ada beberapa
baju hijau, seorang tua berkopiah dan seorang wanita berkebaya
ayah dan ibu Toha) dan seorang anak duduk diam (tentu, ini si
Toha kecil). Terus terang saja, gambar ini bisu: tak ada suasana
di situ. Apakah itu ketakutan, apakah itu kekejaman si Belanda.
Bunda Maria
Tapi barangkali sebagai anak berusia 11 tahun, Toha lebih cocok
dengan gambar-gambar adegan perang, atau iring-iringan panser
dan yang semacamnya. Untuk yang ini pujian Affandi memang tepat.
"Waktu itu kendaraan-kendaraan itu memang menarik saya sebagai
anak-anak," kata pelukisnya yang kini bekerja sebagai Sekretaris
Direksi di Persero Nindya Karya. Dan karya-karyanya yang bertema
begitu memang pantas dipuji suasana terasa, dan kepolosan (yang
biasanya memang selalu menjadi ciri lukisan anak-anak)
menjadikan karya itu bersih dari kesan-kesan bahwa itu untuk
dokumentasi atau yang lain.
Karya Toha dan kawan-kawan sebayanya memang bernilai
dokumentatif -- langsung dibuat berdasarkan rekaman pandangan
mata sendiri. Tentu, nilai itu dalam lukisan perjuangan bisa
juga dicapai tanpa harus si pelukis menyaksikan sendiri
peristiwanya. Misalnya dengan riset, agar pelukisnya benar-benar
yakin bahwa yang akan digambarkan bukanlah isapan jempol. Itulah
yang dilakukan pelukis-pelukis muda dari HBS dan Sanggar Pejeng.
"Mereka membaca koran-koran lama koleksi saya untuk memperoleh
gambaran perang yang tak pernah disaksikannya," kata Dullah.
Dan dari segi sah atau tidaknya cara itu untuk menggambarkan
lukisan perluangan, kata Dullah: "Apakah Rembrandt pernah
menyaksikan Kristus disalib? Toh karyanya dianggap sebagai karya
besar."
Tapi perlu diketahui, pelukis-pelukis yang menggambarkan Kristus
pertama-tama bukanlah ingin menampilkan gambaran visualnya, tapi
spiritualnya. Bahkan Michelangelo, pematung Italia terkenal itu,
mematungkan Bunda Maria dengan wajah jauh lebih muda dari Jesus,
putranya. Sebagai Perawan Suci, tentulah Bunda Maria tetap muda,
begitu kira-kira jawab Michelangelo ketika ditanya pemesannya.
Alasan atau dasar penciptaan seperti pada Michelangelo itu,
mungkin dilupakan Dullah dan siswa-siswanya. Bisa dilihat
bagaimana para pelukis di bawah asuhan Dullah ini menggambarkan
Perang Kemerdekaan para pejuang itu sepertinya barusan beli
celana dan baju. Tidak hanya itu cara melukiskan aksi para
pejuang pun sepertinya tak jauh berbeda dengan poster-poster
film perang: menonjolkan adegan fisik, dengan figur-figur yang
gagah perkasa. Sebuah lukisan Raka, 23 tahun, menggambarkan
sepasukan gerilya sedang istirahat di bawah pohon rindang:
sepertinya serombongan anak muda sedang menikmati liburan
mengarungi hutan.
Sebuah lukisan Dullah sendiri, berukuran 3,5 x 2 meter,
menggambarkan sebuah adegan di markas Belanda ketika menangkap
gadis kurir gerilya. Adegan sadis ini -- melucuti pakaian gadis
kurir gerilya itu -- kita percaya memang pernah, bahkan sering
terjadi benar dulu itu. Cuma cara penggambaran Dullah, yang
menonjolkan paha, agaknya menjadikan lukisan perjuangan ini
terasa murah. Yang tampil di situ adalah perkosaan terhadap
seorang gadis cantik, dan bukannya kekejaman terhadap
perjuangan.
Basuki Abdullah
Lagi pula, apabila mau diamati betul ada hal-hal yang janggal
dari segi anatomi pelukisan figur. Sebuah contoh: lukisan Zain
Ahmar, 24 tahun, menggambarkan pertempuran di Surabaya. Cara
membungkuk dua pejuang di baris belakang terasa tak wajar.
Apalagi karya-karya ini kalau kita bandingkan dengan sejumlah
lukisan perjuangan yang dibuat pada zaman tersebut, oleh antara
lain Sudjojono, Sudarso, Harjadi, Hendra dan beberapa lagi
(TEMPO, 10 November 1979) betapa jauh perbedaannya. Yang disebut
belakangan ini memang mengetengahkan perjuangan dan bukan
sekedar adegan fisik orang bawa bedil.
Menengok sejumlah lukisan yang bertema kehidupan sehari-hari,
barangkali bisa menjelaskan duduk perkaranya. Tak jauh dari
karya-karya pelukis populer Basuki Abdullah, karya pelukis HBS
dan Sanggar Pejeng pun hanya mencerminkan satu usaha teknis
untuk mencapai bentuk seperti dilihat mata. Tanpa penghayatan,
katakanlah, segi nonvisualnya.
Sikap seperti itu bisa menghasilkan hal-hal janggal. Sebuah
lukisan Kok Poo, 42 tahun, menggambarkan pengemis wanita tua
dipandu (mungkin) anaknya perempuan, menyodorkan tangan kepada
seorang tuan duduk di kursi dengan sebotol bir di meja.
Bisa-bisa orang menangkapnya sebagai lukisan tentang pengambilan
adegan sebuah film -- yang duduk si sutradara, yang dua wanita
si artis sedang melakukan sebuah adegan.
Dengan begitu sebetulnya kesan-kesan yang ditulis sejumlah
peminat lukisan pada pameran di Yogya tahun lalu, tak berdasar
Ketakutan kehilangan lukisan-lukisan perjuangan yang ini, hanya
pantas ditujukan kepada sejumlah lukisan karya Toha dan
teman-teman sebayanya itu. Pelukis mana pun mungkin saja melukis
seperti yang dilakukan para pelukis ini. Dan sejumlah pelukis
muda dari Yogyakarta yang muncul di tahun 1977, angkatan Dede
Eri Supria misalnya, yang mempunyai ketrampilan teknis melukis
realistik yang hebat, mungkin akan jauh lebih berhasil dari
mereka ini.
Bambang Bujono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini