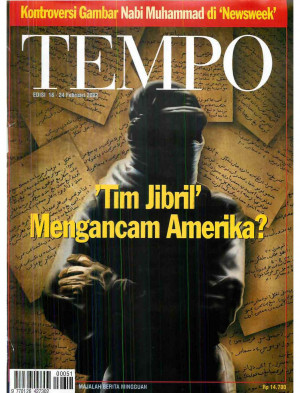Black Hawk Down
Sutradara : Ridley Scott
Skenario : Ken Nolan
Pemain : Josh Harnett, Ewan McGregor, Sam Shephard
Produksi : Columbia, 2001
Musim gugur di Mogadishu, Oktober 1993, mengembuskan sebuah tanda kematian. Ketika fajar tiba memulai tanggal 3 Oktober, peluru dan granat menyalak tak berkesudahan. Ketika 160 orang pasukan militer Amerika Serikat menembus lorong-lorong Mogadishu, Somalia, 3 Oktober 1993. Semula, di bawah pimpinan Jenderal William F. Garrison (Sam Shepard), mereka diberi tugas menculik letnan-letnan utama Jenderal Muhammad Farrah Aidid, warlord yang menguasai kawasan ibu kota tersebut. Operasi ini dijadwalkan berlangsung 30 menit saja. Namun, misi yang semula dianggap enteng ini berujung bencana. Dari sore hingga fajar pecah keesokan harinya, peluru, granat, dan berbagai macam senjata yang diperjualbelikan di Mogadishu bak kacang goreng itu tak henti-hentinya menghajar dan mencabik tubuh mereka. Dua helikopter Amerika juga ditembak jatuh. Seluruh kota seperti telah melawan mereka sehingga tak ada pilihan selain balas mengamuk. Peristiwa ini menyebabkan 10 orang pasukan AS tewas dan puluhan orang luka berat. Maka, ini kemudian menjadi tragedi terbesar pada masa pemerintahan Bill Clinton.
Inilah peristiwa hitam—jauh sebelum Tragedi World Trade Center—yang direkam oleh wartawan Philadelphia Inquirer dalam buku berjudul Black Hawk Down, yang kemudian diangkat ke layar lebar oleh sutradara Ridley Scott. Inilah kisah nyata ketika 250 ribu pasukan marinir AS yang bertugas bersama PBB untuk mendistribusikan makanan di Somalia merasa "impoten" dalam perang sipil yang dikuasai milisia yang luar biasa brutal itu. Kebijakan AS saat itu: menangkap Muhammad Farrah Aidid. Dan Jenderal Garrison sudah melampaui batas waktu penangkapan yang diberikan oleh Washington. Maka terjadilah peristiwa nahas itu.
Sutradara Inggris yang tahun lalu filmnya, Gladiator, terpilih sebagai film terbaik Academy Awards ini menggunakan pendekatan semidokumenter dalam film ini untuk membawa penonton pada gambaran nyata sebuah perang. Ia tak segan-segan menyodorkan gambar tangan terputus atau badan tentara yang terbelah total tetapi toh bibirnya masih sempat berbicara. Kiat ini bukan barang baru. Oliver Stone telah menggunakannya dalam Platoon, begitu juga Steven Spielberg dalam Saving Private Ryan. Namun kebrutalan perang dalam Black Hawk Down semakin terasa nyata karena ia tampil dua jam nyaris tanpa jeda, sehingga film terasa lebih menohok dan butuh ketabahan tersendiri untuk menontonnya.
Sayang sekali, informasi sebab-musabab awal keterlibatan AS dan negara-negara lain yang berdatangan ke Somalia untuk membantu ditampilkan cuma sekelebat. Latar belakang historis perang antarklan juga mengawang, sehingga tokoh-tokoh milisi Somalia hadir brutal tanpa alasan yang cukup. Alasan strategis peluncuran misi penculikan juga tak pernah jelas karena lawan politik Aidid tak dimunculkan. Akibatnya, dalam beberapa adegan film ini jadi kehilangan konteks. Film ini punya potensi menerbitkan salah paham bahwa mayoritas warga Somalia haus darah. Namun, di sisi lain, hal ini malah menimbulkan efek dramatis ketika para prajurit harus terus bertempur di tengah ketidakyakinan mereka terhadap misi ini. Karena itu, tanpa disadari—barangkali—Ridley telah menciptakan sebuah film perang yang antiperang, seperti sikap sutradara Kenneth Brannagh dalam film Henry V.
Itulah sebabnya, meski berkisah tentang serdadu Amerika, Black Hawk Down bukanlah film laga ala Rambo, yang tak tahu malu mengagumi aksi norak koboi militer negara adidaya itu di wilayah orang lain. Film ini tak menyajikan sosok Mel Gibson atau Tom Cruise, apalagi Sylvester Stallone untuk membuat penonton merasa tenang bahwa akhir dari seluruh kerusuhan ini akan beres karena datangnya sang jagoan. Sebaliknya, ini adalah film yang secara terus terang menyuguhkan kisah militer Amerika sebagai pecundang. Dari perimbangan angka korban, pasukan Amerika unggul banyak, 18 prajurit lawan seribu orang warga Somalia. Namun, bukankah ini satu bentuk kekalahan telak, sebuah misi yang tak jelas akhirnya merenggut nyawa sekian banyak manusia?
Adegan-adegan yang menampilkan warga sipil Somalia sangat menyentuh. Seorang wanita dan anak-anaknya terduduk di pojok rumahnya dalam roman ketakutan saat se-orang serdadu Amerika masuk. Seorang anak lelaki kencur menangis hebat saat tembakannya yang diarahkan ke pasukan Amerika salah sasaran dan mengenai ayahnya sendiri. Seorang perempuan merenggut senapan dari pasangannya yang tewas dan menembaki para tentara asing sebelum akhirnya ia sendiri jatuh terkena peluru. Dengan cara penyampaian seperti itu, Black—yang dalam ajang Academy Awards tahun ini sudah berhasil meraih lima nominasi (sutradara, penyuntingan, sinematografi, tata suara, dan penyuntingan suara)—tak perlu lagi menggunakan kata-kata petuah tentang kengerian perang.
Sinematografer Slawomir Idziak punya andil besar dalam menciptakan suasana kelam. Penonton seperti bisa merasakan taburan debu dan pecahan batu saat helikopter Amerika jatuh. Idziak menghindari warna-warna cerah untuk penggambaran adegan tempur. Ia menampilkan gambar memburam secara bertahap seiring dengan malam tiba. Penyuntingan tangkas yang dilakukan Pietro Scalia membuat hasil kerja Idziak kian menggigit. Musik yang ditata Hans Zimmer ikut menambah getar, namun senandung sedih yang jadi lagu penutup terlalu mirip karyanya dalam film Gladiator, film terbaik Oscar tahun 2001 lalu yang juga disutradarai Scott. Setiap pemain dalam film ini mendapatkan porsi yang relatif berimbang. Josh Harnett, Ewan McGregor, Sam Shepard, ataupun Tom Sizemore bermain standar. Karakter yang mereka mainkan praktis statis karena film ini hanya menyorot 15 jam kehidupan serdadu Amerika di Somalia.
Tanpa paham konteks cerita, penonton akan menjumpai lubang besar saat menyimak Black Hawk Down. Yang juga patut disayangkan adalah saat Scott menghindari menampilkan gambar paling dramatis dari kejadian nyata hari itu, mayat Sersan Gary Gordon yang diseret sepanjang jalan Mogadishu dalam keadaan setengah telanjang. Scott mungkin tak ingin kenangan pahit tersebut kembali meneror (penonton Amerika). Tapi meninggalkan momen ini seperti menghilangkan ironi terbesar: prajurit Amerika yang datang dengan misi kemanusiaan—terlepas dari segala kepongahannya—harus menjumpai nasib mengenaskan di bumi kerontang Afrika.
Yusi Avianto Pareanom
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini