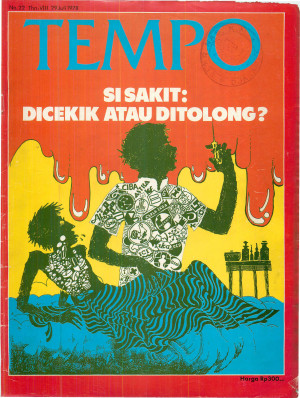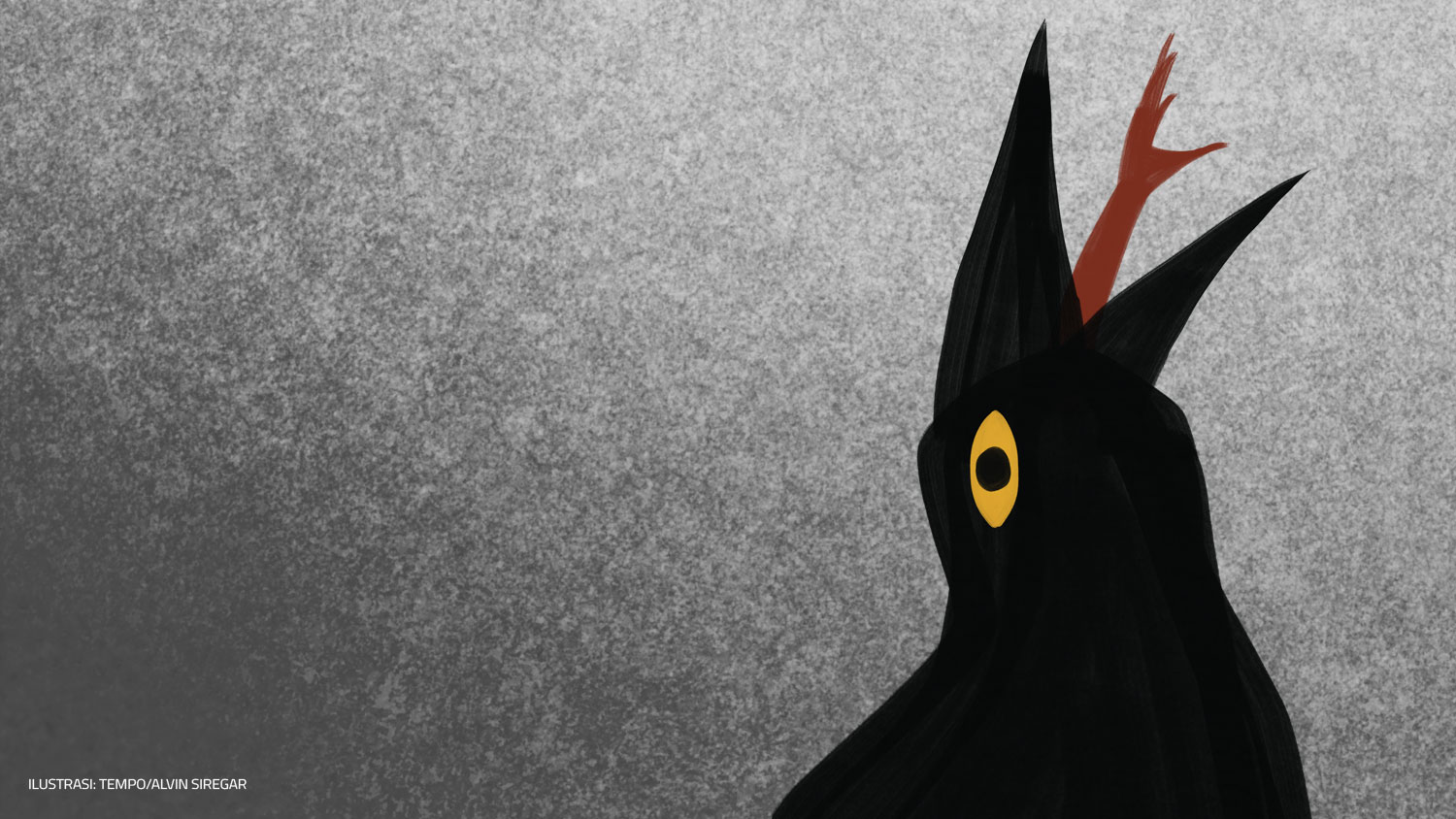DENGAN populernya pembacaan sajak, yang dulu dikenal sebagai
deklamasi, apa yang disebut puisi bukan sesuatu yang asing.
Apalagi ruangan anak-anak di surat kabar dan juga majalah
anak-anak (Kawanku, Bimba, Bobo, dsb.) selalu tak absen
menghadirkan puisi.
Dalam Puisi Asean 78, di TIM, 17-20 Juli, salah satu acaranya
ialah 'Pameran Puisi Konkrit'. Sutardji Calzoum Bachri, penyair
bir yang populer itu, dan juga beberapa peserta yang lain,
mencoba menjelaskan apa itu 'puisi konkrit' (lihat box).
Barangkali bisa diterankan lagi demikian. Sebelum sastra
dituliskan, bentuk kesenian ini hanya dikomunikasikan secara
lisan. Karena itu kata-katanya dipilih sedemikian rupa hingga
enak didengar. Keenakan bunyi kemudian jadi nomor satu, dan arti
atau maksud kata-kata boleh dikesampingkan. Contoh yang jelas
adalah mantra-mantra, atau juga suluk sang dalang wayang.
Sutardji sendiri yang mengaku terpengaruh mantra salah satu
sajaknya demikian:
lima percik mawar/tujuh sayap merpati/
sesayat langit perih/dicabik puncak gunung/
sebelas duri sepi/dalam dupa rupa/
tiga menyan luka/mengasapi duka
puu . . . aah!/kau jadi Kau!/Kasihku
Apa artinya? Tidak penting. Yang penting, bagaimana melodi yang
terdengar dari susunan kata-kata itu -- yang memang membawa
suasana tertentu.
Kemudian orang menemukan tulisan. Dan tulisan adalah gambar
kata-kata. Tulisan memang hanya mengantarkan maksud, tapi
sebenarnya, 'gambar tulisan' itu sendiri toh mempunyai nilai
sebagaimana 'bunyi' (tanpa arti) mempunyai nilai. Maka cara
menuliskan sajak -- dengan huruf besar atau kecil, urut ke bawah
dengan teratur atau disusun bak anak tangga -- bisa menjadi
lebih dikemukakan daripada arti kata-kata. Dan perkembangan
mementingkan cara menuliskan sajak itulah yang kemudian
melahirkan 'puisi konkrit'. Bentuk visualnya yang kemudian
menjadi bahasa utama.
Cobalah anda kunjungi Pameran Puisi Konkrit di Galeri Baru TIM.
Ada peta Indonesia dibikin dari tripleks dan tiap pulaunya
berisi sajak. Itu karya penyair Padang, Hamid Jabbar. Ada
tempelan-tempelan guntingan koran. Ada sangkar dicat warna emas
dan di dalamnya bertengger seekor burung kertas bertuliskan
"Puisi 78", karya Sutardji. Lalu ada kanvas berbentuk lingkaran
dan tersusun sebagai jari-jarinya tulisan Allah -- yang makin
mendekat ke titik pusat makin kecil akhirnya pada titik pusat
sebuah gambar bulan sabit lengkap dengan bintangnya. Judul karya
itu Tuhan yang Tuhan, karya pelukis dan cerpenis Danarto.
Masih juga karya Danarto, deretan foto kopi lembaran
sepuluhribuan bernilai seribu milyar rupiah ditempel rapi, dan
di bawahnya ada tulisan "di Swiss di Swiss, daerahku yang akan
datang .... " Ada karya Latiff Mohidin, penyair Malaysia, dengan
judul Puisi Salah Lagi berisi ketikan-ketikan yang ditumpuk
huruf x karena salah ketik, dan di atasnya tulisan tangan salah
atau salah lagi.
Reportase singkat bagi anda yang tak sempat nonton pameran itu,
mudah-mudahan meyakinkan bagaimana sebetulnya "puisi konkrit"
itu. Dan lebih penting: bagaimana kata kemudian tak dipercaya
mengantarkan arti yang dikandungnya tanpa "gangguan". Kata itu
musti digoncang, entah bagaimana caranya, agar memberikan
dimensi yang lain. Lebih lagi, kata hanya menjadi hiasan yang
penting perwujudan visualnya.
Mentah dan Dangkal
Lihat, satu kertas panjang yang menjalar di lantai bertuliskan
masa depan, masuk mesin tulis, dan di papan di atas mesin tulis
ada potret diri penyairnya, Slamet Kirnanto, di bawahnya tertera
tulisan misteri. Nah, sampai di sini jelas bahwa bentuk visual
yang ditekankannya tentulah mengundang kriteria yang sifatnya
visual juga dan mau tak mau seni rupa ikut bicara.
Bertolak dari itu, sebetulnya pameran ini hanya dihidupkan oleh
seorang pelukis saja Danarto. Karya-karyanya rapi, enak dilihat.
Bukan sekedar mewujudkan kata dalam bentuk yang aneh-aneh.
Bicara soal ide barangkali memang semua peserta punya ide yang
unik. IHanya kemampuan mewujudkan ide, yang tentunya butuh
disiplin tersendiri, tak dimiliki para penyair itu. Dan Danarto
memang pelukis.
Di jaman ini memang cabang-cabang kesenian saling mendekat dan
bersentuh. Ingat saja Pameran Seni Rupa Baru yang menggunakan
segala macam medium. Apa pun bentuk karya seni itu, agaknya
memang sah. Seperti tulis Sutardji " . . .mungkin lebih tepat
dikatakan kehidupan modernlah yang mempengaruhi dan merangsang
timbulnya puisi konkrit." Kalau karya-karya puisi konkrit
demikian mentah dan dangkal, barangkali kehidupan modern kita
kini memang mentah dan dangkal.
Sebelum keluar dari Galeri Baru sempat terbaca karya Baharudin
M.S. -- pelukis dan kritikus senior -- sebuah kaligrafi yang tak
bagus "Ya, Tuhan ampunilah dosa kami." Setelah pusing
berkeliling melihat satu per satu karya, kaligrafi Bahar rupanya
memberi kekuatan pada kita, hingga tak usah takut terjatuh
ketika menuruni tangga dari lantai tiga TIM itu untuk pulang.
Maklum semuanya itu memang tak begitu penting.
Bambang Bujono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini