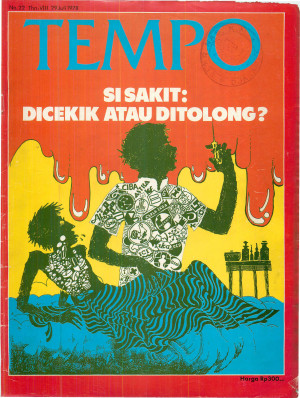SISTEM pendidikan seperti yang diterapkan di sekolah saya ini,
patutlah disebut "sistim pendidikan kolosal". Bukan saja berarti
kelas yang sumpeg oleh napas 37 kepala, tapi lebih sebuah sistim
yang serba "digeneralisir". Pribadi dan potensi tiap anak tidak
mendapat tempat. Pak guru hanya kenal siswa yang tercantik,
terpinter, terjelek, dan terbandel. Sekolah berarti mendengar
yang dikatakan pak guru, menulis apa yang ditulis pak guru, dan
menyalin kembali apa yang dikatakan dan ditulis pak guru pada
kertas ulangan. Pengajaran yang sangat berorientasi pada guru,
sampai kadang-kadang akan mengurangi wibawa guru jika seorang
siswa menolak mencatat dan bertanya buku karangan siapa yang
dipakai mengajar beliau. Ditambah mata pelajaran yang banyak dan
berwarna-warni, sampai susah dicari hubungan dan relevansinya.
Maka lengkaplah untuk bertanya: inikah sistim pendidikan yang
menyiapkan para teknokrat, enterpreneur dan pemimpin bangsa?
Dengan cara inikah mereka disiapkan menjawab persoalan-persoalan
nasional kelak? Sistim ekonomi nasional, sistim pemerintahan
nasional, sistim pendidikan nasional? Bagaimana bisa diharap
penilaian tinggi atas hasil karya, keinginan berprestasi, dan
achievement?
Tiap tahun naik kelas, sudah cukup. Buat apa jadi bintang kelas,
toh tak ada jaminan diterima di PT (sayang saya dari jurusan
sastra, jadi tidak bisa belajar di institutnya Andi Hakim atau
masuk AKABRI). Sementara agar tiap tahun naik kelas sendiritidak
penting. Nyontek itu sudah biasa. Sudah bukan rahasia dan
dianggap "seni"nya bersekolah. Pak guru juga maklum saja. Sebab
jika beliau memberi angka 6, dalam hati kecilnya menulis 4.
Sebab untuk kesediaan menyontek saja, mustinya sudah dipotong
20%. Kurikulum boleh berganti setiap perubahan kabinet. Tapi tak
akan merubah apa pun jika hanya merubah apa yang harus
dipelajari, bukan bagaimana mempelajarinya.
Nyontek memang bentuk struggle yang orisinil, dan cukup menjadi
bukti bahwa otak jalan. Nyontek adalah kemampuan yang meliputi
pengalaman ketrampilan, akting, timing, dan teknik-teknik
memperdaya guru. Dan jika ini dilakukan, mereka sadar benar
keadaan menghendaki begitu. Apalagi memang manjur dan sudah
terbukti kasiatnya. Cuma yang jadi soal, ini tidak cocok untuk
maksud pendidikan apa pun. Kecuali jika maksudnya mencetak
bandit, pemimpin-pemimpin korup yang pandai mengkotak-katik
"sikon".
Adalah omong kosong jika sekolah mendidik siswa berdisiplin.
Tapi memang ya, jika yang dimaksud itu "menurut". Sebab disiplin
di sini tak lebih dari setumpuk aturan tentang bagaimana siswa
memelihara rambut, memakai pakaian, dan bagaimana membohongi
guru kalau bolos. Yang terakhir ini harap diperhatikan. Kalau
perlu memalsu tanda tangan orangtua, agar pak guru tidak
tersinggung dan merasa diperhatikan.
Barangkali inilah kenapa siswa SMA tidak menjadi lebih dewasa.
Berapa kali terjadi kasus ancaman atau pemukulan siswa atas
gurunya? Ini tak bakal terpikir, jika siswa pernah datang di
rumah gurunya. Ngobrol sebagai manusia, saling merasakan dan
mengerti. Persis kata orang, hubungan guru dan murid tak lebih
dari penjual dan pembeli. Selagi jadi murid ia akan melakukan
apa saja (sampai tingkat over acting pun). Tapi begitu STTB di
tangan, jangan harap ditegur waktu ketemu di jalan, atau
dipanggil pak atau bu. Penekanan disiplin macam ini tak bakal
sampai pada tujuannya -- paling banter hanya mewariskan cara
bersikap dan berpikir feodal. Sebab disiplin murni hanya bisa
dilihat dalam siswa mengerjakan ulangan.
Sementara tiap tahun makin jelas adanya jurang pemisah antara
Pra-PT dan PT, pelajaran sekolah lebih tak mampu mengajak siswa
melihat masyarakatnya dengan lebih baik. Bagaimana dapat
mengikuti perkembangan sastra sekarang, jika pelajaran sastra
(pun untuk jurusan Sos/Bud) cukup berhenti pada Angkatan '45 dan
Chairil Anwar? Apa ini tak membingungkan: 70% penduduk Indonesia
hidup dari pertanian dan lebih 70% bergantung dari pertanian,
dan sektor ini menghasilkan 56% pendapatan nasional (Geografi
Indonesia, Djenen, drs, MSc) sementara tiap tahun negara impor
beras, dan di Karawang rakyat makan enceng gondok? Siswa boleh
baca koran, tapi tak akan lebih jelas apa itu "Tri Tura", ORBA,
jika pelajaran sekolah cukup berpusing-pusing tentang zaman
Mojopahit atau zaman kolonial.
Pak guru Civics akan lebih banyak ditanya siswa, dan akan
semakin tak pandai menjawab. Kenapa Golkar punya hak
pengangkatan? Apa Golkar berbeda dengan parpol lain? Bukankah
"utusan-utusan daerah dan golongan" sudah direalisir dalam
Fraksi ABRI dan Utusan Daerah? Dan pak guru terlalu lama
mengangguk-angguk, sampai berkata: "Saya mengajar teori, bukan
praktik!" (Waktu itu baru hangat-hangatnya Pemilu. Hampir semua
siswa sudah berhak nyoblos. Mereka juga ikut kampanye di
jalan-jalan, kebanyakan untuk PPP atau PDI atau kedua-duanya.
Kalau Golkar, malu -- sebab seperti orang tua). Tak tahulah apa
ini pendidikan yang didaktik metodik. Yang jelas tidak membuat
kami intens dengan persoalan masyarakat. Sudah untung mau pegang
koran. Buat apa payah-payah baca, toh tidak keluar dalam
ulangan? Kegemaran membaca adalah nonsens, jika sistim
pendidikan sekedar didaktik metodik yang tidak menarik.
Rasanya lebih banyak pelajaran yang menjadi beban dari
berfaedah. PKK misalnya, sudah tidak menarik lagi jika hanya
bicara bagaimana mengatur kamar, mencuci, dan membuat sambal.
Lebih mendesak mereka diajarkan doktrin-doktrin ORBA, atau
pendidikan seks, agar ini semua bukan hanya isyu nasional. Sebab
tahun 66 mereka masih SD, dan setelah SMA sekarang melihat
betapa "lokalisasi-lokalisasi" menjadi sah untuk sebuah
masyarakat modern.
Saya tak habis mengerti: untuk apa siswa SMA yang akan ujian
mesti menempuh dulu ujian kepramukaan, jika hanya berarti
baris-berbaris dan membuat tali simpul. Lebih beralasan jika
mereka diajar diskusi atau kuliah-kuliah politik, supaya jika
jadi mahasiswa nanti bukan sekedar badut politik, moral force
yang tak punya konsepsi. Regenerasi sudah ternyata gagal jika
hanya bertumpu pada pendidikan di PT. Jika Ketua MPR/DPR lain
tak ingin terkejut dan pingsan, seperti Adam Malik dulu
mendengar Young Ambon, mereka mesti menengok SMA. Sebab siswa
SMA-lah yang paling tipis kadar nasionalismenya. Mereka yang
perlu diregenerasikan, diintegrasikan. Kalau perlu dengan
merombak materi pengajaran.
Pelajaran Sejarah Indonesia mesti dimulai dari periode
Pergerakan Nasional. Supaya mereka tidak hanya kenal nama
Soekarno dan Hatta, tapi juga Syahrir Mohammad Roem, Tan Malaka
dan Kahar Muzakar. Lengkap dengan pikiran-pikirannya agar kelak
siswa lebih kenal dirinya dan negaranya. Pelajaran Sejarah Dunia
mesti dimulai dari periode setelah Perang Dunia II, agar siswa
lebih sadar kapan dan di dunia mana ia hidup. Juga pelajaran
Ekonomi mesti dimulai dengan "Ketidaksamaan Ekonomi Regional dan
Internasional", agar relevan dengan status underdeveloped negeri
ini lengkap dengan persoalan penduduk, tenaga kerja dan
transmigrasi.
Akhirnya jika ada yang bertanya, apa yang saya hasilkan selama
di SMA. Inilah jawabnya. Tapi jika anda bertanya, kenapa saya
masuk SMA. Apakah saya punya pilihan lain?
M.S.B. BARON
(SMA Tld. Yogyakarta)
Kauman Gm. IV/242,
Yogyakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini