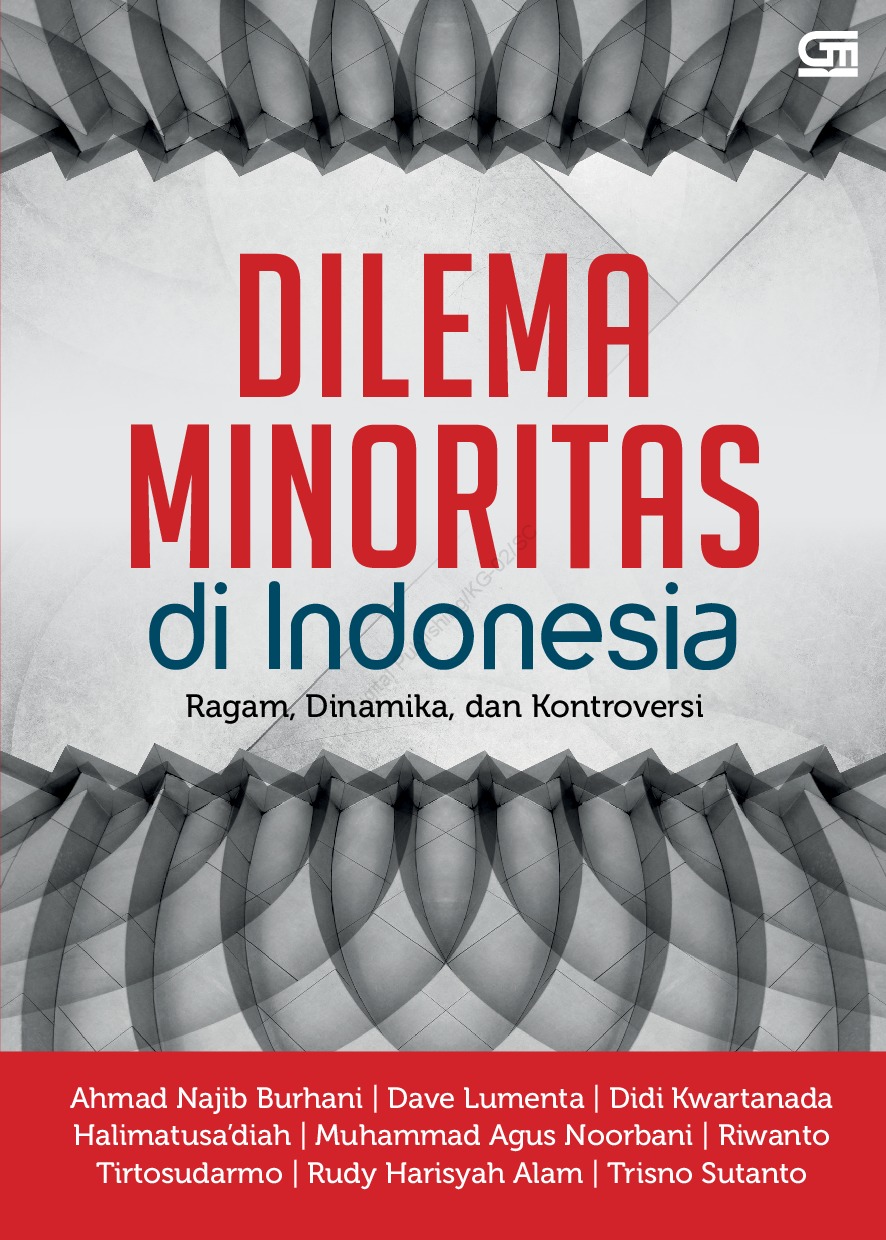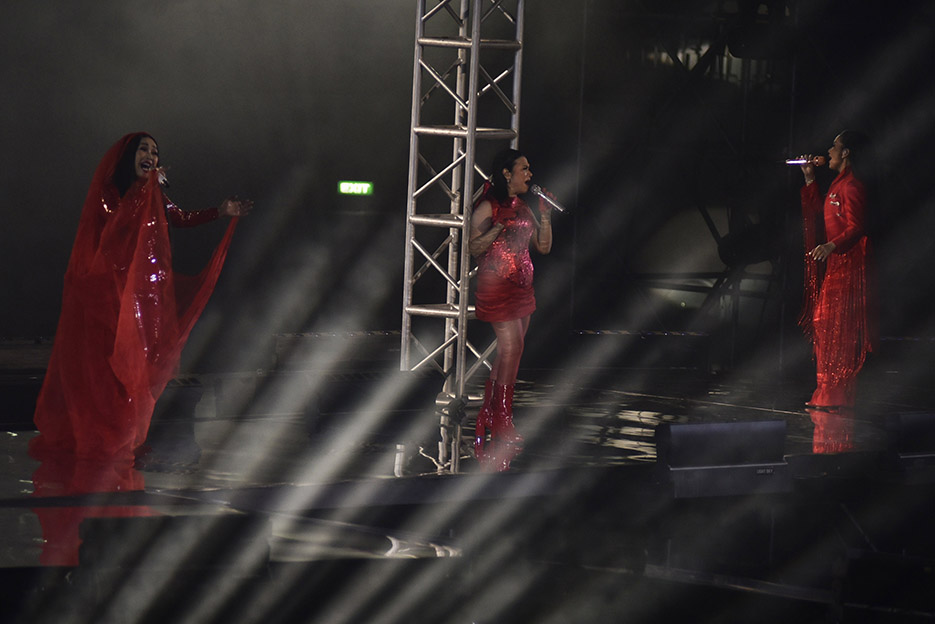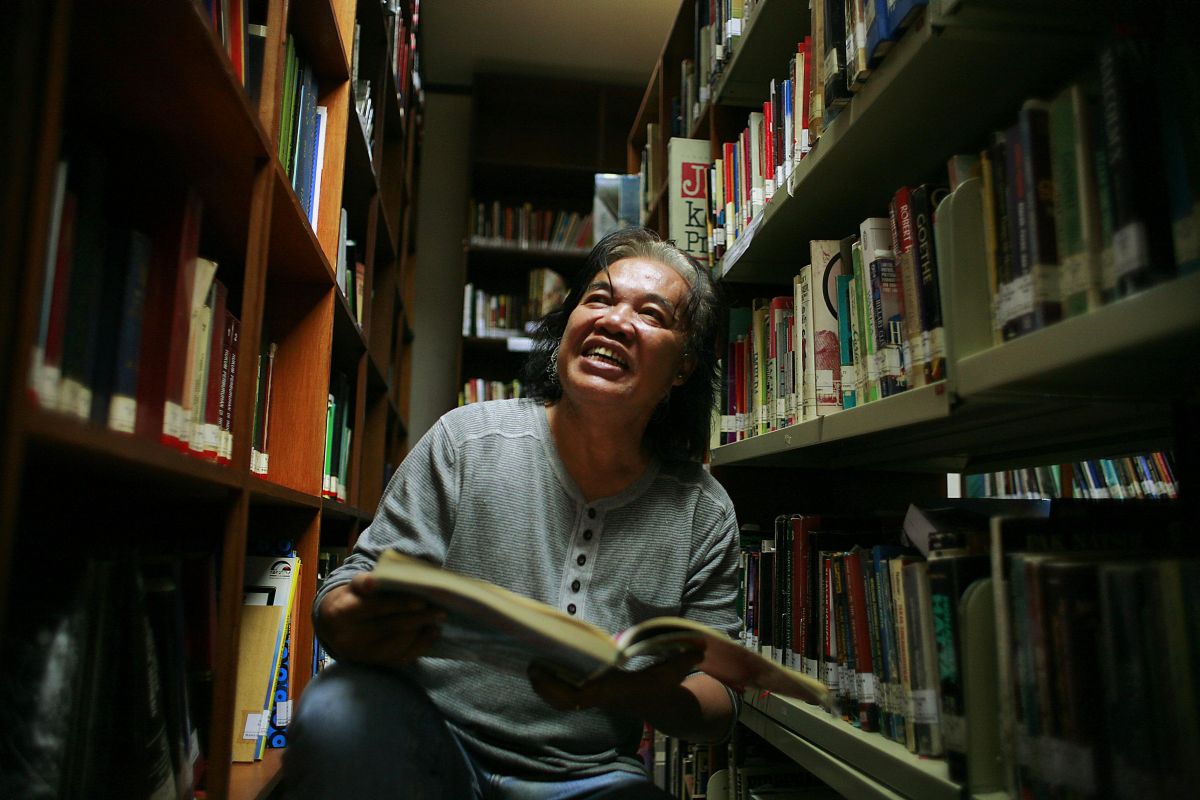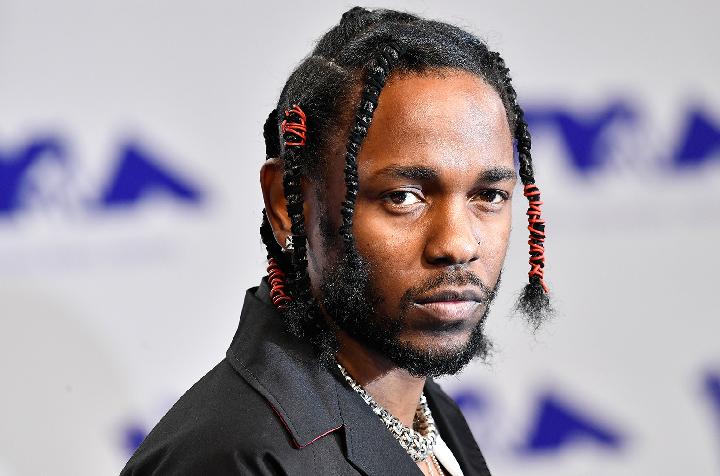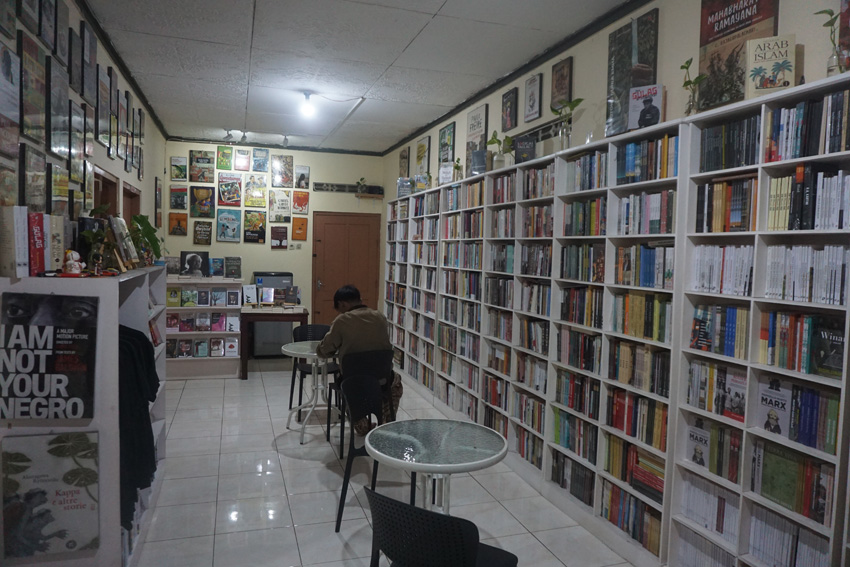Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Agus Wedi
Peminat kajian sosial dan keislaman
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tumbuh suburnya politik dan kelompok keagamaan menjadi penanda keragaman hidup dalam demokrasi di Indonesia. Namun, tambah ke sini, dengan terbukanya keran demokrasi, bukannya tambah dinamis, tapi justru menjadi dilema. Kelompok minoritas menjadi problem sosial dari relasi sistem timpang (kuat/kuasa dan lemah/dilemahkan) yang menciptakan sistem diskriminatif, subordinatif, bahkan kekerasan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Fenomena itu dikemukakan dalam buku ini, Dilema Minoritas di Indonesia: Ragam, Dinamika, dan Kontroversi (2020). Ironisnya, dilema minoritas di Indonesia justru berangkat dari istilah itu sendiri. Istilah dan konsep “minoritas” problematik. Kendati demikian, penggunaan istilah itu seperti menjustifikasi kelompok tertentu atau alergi digunakan. Bahkan konsep minoritas dianggap tak menguntungkan.
Kelompok minoritas di Indonesia seperti buah simalakama; apa pun pilihannya, sering dipandang salah. Dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, misalnya, kelompok minoritas sering dituduh subversif atau oportunistis. Dalam basis agama, mereka mendapat stigma sebagai kelompok sesat atau bermasalah.
Tapi hal yang menjadi dasar tesis dalam buku ini adalah disharmoni sosial sosial-politis dan penghayat-kepercayaan-agama hingga konfliknya. Muasalnya dari diskriminasi struktural negara di satu sisi dan komunitas mayoritas di sisi lainnya. Superioritas negara menjadi kunci pembuat kebijakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kelompok mayoritas dengan teologi eksklusivismenya mengklaim yang paling benar. Kendati demikian, keduanya saling meneguhkan.
Kasus penyegelan pasarean sesepuh masyarakat Akur Sunda Wiwitan di Curug Goong, Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, belum lama ini, misalnya. Peristiwa itu menambah panjang daftar kasus diskriminasi oleh aparat negara dan masyarakat mayoritas terhadap kelompok minoritas.
Praktik diskriminatif terhadap mereka yang masih mempertahankan agama leluhur Nusantara atau kelompok minoritas (LGBT, difabel, komunitas adat, penghayat, Syiah, Ahmadiyah, Lia Eden, dan Gafatar) yang ditunjukkan dalam buku ini punya sejarah panjang. Hal itu berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif. Praktik tersebut berakar pada “politik pembedaan” antara yang disebut agama dan kepercayaan yang terekam dalam No. 1/PNPS/1965 (hal. 26).
Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hanya terdapat tiga kategori agama yang direstui di Indonesia. Pertama, enam agama yang diakui. Kedua, kelompok yang dibiarkan adanya, seperti Baha’i, Sikh, dan Yahudi. Ketiga, kelompok penghayat kepercayaan. Undang-undang itu tak mengakomodasi hak-hak kepentingan kelompok penghayat (baik pengakuan maupun perlindungan sebagaimana digariskan UUD 1945) dan dua kelompok agama minoritas yang ada di masyarakat, seperti Syiah dan Ahmadiyah, serta mereka yang disebut sebagai new religious movement, Lia Eden dan Gafatar.
Hak-hak sipil mereka sebagai warga negara, dari pengurusan akta kawin, akta lahir, KTP, KK, akses pendidikan, tempat ibadah, bahkan hingga penguburan jenazah, dinafikan. Akibat peminggiran ini, sejak 1949 hingga 1992, terdapat 517 aliran kepercayaan yang mati di seluruh Indonesia.
Segregasi sosial yang marak terjadi terhadap kelompok minoritas agama, komunitas adat, ras, dan etnis sekedar ingin mempertahankan tradisi dan hak-hak mereka di hadapan kehidupan bernegara. Tapi hak-hak mereka terampas atas sebuah alasan pendisiplinan kebijakan. Trisno Sutanto mengemukakan secara bernas dalam artikel Diskriminasi terhadap Penghayat: Sampai Kapan? dalam buku ini.
Konstitusi dan hak asasi manusia di sana mati seiring dengan menguatnya irisan politik mayoritas dan negara. Dalam konteks ini, bagi Sutanto, membawa sebuah kemajemukan baru yang ahistoris atau pengikisan ikatan komunitas leluhur. Karena itu, hal tersebut mempertajam batas antar-etnis. Secara tidak langsung, kelompok minoritas diproduksi atas relasi dalam konteks konsolidasi negara, yang pada akhirnya terjadi sejenis “genosida kultural” (hal. 48).
Lebih jauh, peminggiran minoritas termasuk struktural yang ditandai dengan defisitnya akses pendidikan, pekerjaan, tradisi, dan sumber-sumber ekonomi di beberapa tempat. Sistem yang ada di masyarakat dikuasai segelintir orang. Di Bali, misalnya, seperti dikemukakan Halimatusa’diah dalam artikel Manyama Braya, Tradisi Ngejot, dan Tat Twam Asi: Modal Sukses Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di Bali.
Menurut dia, kebijakan publik, seperti administrasi sosial dan perlindungan hukum, pincang. Dalam analisisnya, pemicu konflik di Bali bukanlah stereotip latar belakang agama, etnis, maupun perbedaan budaya atau golongan kesukuan, melainkan perebutan ruang-ruang ekonomi. Sayangnya, masyarakat adat selalu kalah dan terpinggirkan.
Peminggiran hak-hak sosial-ekonomi dan kultural-agama bagi minoritas di Indonesia sungguh mendalam. Akibatnya, hilanglah hak sipil atau ekonomi kependudukan. Kepercayaan dasar atau warisan budaya spiritual yang mereka hayati sehari-hari juga dinafikan. Mereka ada dan diakui sebagai warisan budaya sebatas apabila siap dipasarkan demi pariwisata (hal. 48).
Pada titik ini, minoritas menjadi mustadh’afin (kelompok tertindas). Mereka perlu dilindungi dan ditemani sebagai pijakan bahwa setiap warga negara di Indonesia berhak dan mendapat jaminan untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing, termasuk menjalankan tradisi-ritual, pendidikan, dan politik sesuai dengan UUD 1945.
Kekuasaan (pengikisan konstitusi) dan fanatisme golongan yang menyuburkan kekerasan terhadap kelompok minoritas (agama-adat) menjadi hal nyata di hadapan kita. Pengakuan terhadap pluralisme agama adalah menjanjikan kemaslahatan bersama dalam sebuah komunitas sosial. Dalam prosesnya, agama dan politik harus mengembangkan cara pandang yang humanistis, autentik, dan adil terhadap perbedaan.
Buku ini berisi delapan artikel yang mendedah dan mengajak semua komponen umat untuk tidak melihat minoritas sebagai konsepsi realitas. Kelompok minoritas membutuhkan keberpihakan dan pembelaan atas nama kewarganegaraan sebangsa. *
Judul buku: Dilema Minoritas di Indonesia: Ragam, Dinamika, dan Kontroversi
Penulis: Ahmad Najib Burhani, dkk
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Cetakan I: April, 2020
Tebal: 324 halaman
ISBN: 978-602-06-3867-6
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo