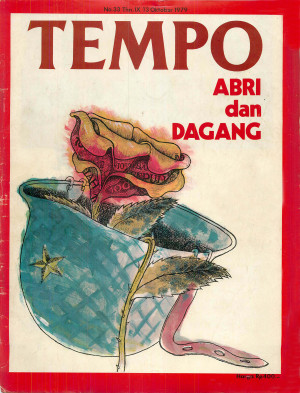BOLEH jadi karena SEA Games X, atau hujan yang turun sejak sore.
Teater Arena, 25-27 September lalu, tak dipenuhi penonton.
Padahal Langen, Mandra Wanara Yogyakarta ini jarang muncul dan
termasuk tontonan yang unik. Untunglah, dari yang sedikit itu
beberapa ternyata hanyut dalam tontonan, ikut melontarkan
senggakan, menjadikan suasana santai dan akrab - suasana yang
memang dituntut jenis tontonan ini agar berhasil.
Langen Mandra Wanara yang kemudian lebih dikenal dengan Langen
Wenaran atau bahkan Wenaran saja, lahir pada tahun 1895 di
pendapa Yudonagaran, Yogyakarta, atas prakarsa KPH Yudonegoro
III yang kemudian menjadi patih dalem Sri Sultan Hamengku Buwono
VII dengan gelar Kanjeng Paneran Aryo Adipati Danurejo.
Disebut wenaran (kera) karena lakon yang diambil selalu dari
epos Ramayana, dengan sumber Serat Rama dan Lokapala Yasad
ipuran, yang banyak menampilkan peran kera.
Di Yogyakarta penampilan ceritera Ramayana dalam tari ini
merupakan babak baru. Sebelumnya ceritera Mahabharata, Panji dan
Menak jauh lebih disenangi, terutama di dalam keraton. Tapi
wenaran kemudian berkembang pesa tidak hanya di kampung Yogya
seperti Notoyudan, Kumendaman, Condronegaran dan Sosrowijayan
tetapi juga hidup subur di daerah pedesaan Bantul dan Sleman.
Kini, wenaran sudah jarang sekali dipertunjukkan. Hanya berkat
kerja sama Dinas P dan K Daerah Istimewa Yogyakarta, sejumlah
tokoh tua dan muda pendukung tontonan khas Yogya ini dapat
pentas di TIM.
Santai, Minum Kopi
Subali Leno--lakon yang dipentaskan malam itu--menarik bukan
saja kita diberi kesempatan menjenguk sebuah tontonan Mataraman
tempo doeloe, tetapi penanganan Ben Suharto anak muda dari
Akademi Seni Tari Indonesia, Yogya--memang cukup bersih. Sudah
barang tentu ini dicapai berkat dukungan tokoh tua, antara lain
Ki Danusupi (53 tahun)--kecuali sebagai penata naskah berhasil
pula memerankan Subali dengan warna suara, sikap gerak dan
ekspresi yang meyakinkan.
Sugriwa -- adik Subali -- diperankan RB Gonjanganom yang meski
sudah menginjak usia 60-an tahun, bekas kecekatan gerak serta
cengkok tembang wenarannya masih cukup mantap.
Di bagian pangrawit, RB Banjaransari -- sebuah nama yang tak
asing bagi pendengar setia Studio RRI Nusantara II -- bertugas
sebagai dalang Nyi Rio Larasati, pangrengga swara (pesinden),
walaupun sudah lebih 70 tahun lengkbgan suaranya masih belum
goyah.
Konsep tempo di jaman doeloe dengan tempo masa sekarang --
lebih-lebih untuk Jakarta--agaknya memang berbeda. Tontonan ini
pada mulanya memang diciptakan bagi masyarakat yang dapat
bermewah-mewah dengan waktu. Dengan kata lain: musti dinikmati
secara mat-matan, santai sambil minum kopi atau teh tubruk
nasgitel (panas, manis dan kental). Ia cenderung ditata untuk
telinga daripada untuk mata.
Ben Suharto sebagai penata laku, bukan tak menyadari hal ini. Ia
telah berusaha keras, namun hasilnya memang masih berkesan
lamban -- setidaknya bagi penghuni ibu kota. Untung sekali
setelah bagian depan yang meski rapi tapi terasa datar, adegan
matinya Suhali di bagian akhir cukup membekas.
Yang juga menarik adalah tampilnya penari-penari muda, yang
ternyata berdampingan dengan tokoh-tokoh tua tak tenggelam baik
vokal maupun gerak tarinya (ini mustahil dilakukan 5 tahun yang
lalu). Sementara dari yang tua ada juga penyesuaian: menyadari
fisik yang tak lagi sentosa mereka lebih menekankan pada
olah-suara dan penghayatan peran.
Peran dan tata-gerak Rama dan Lesmana (Ben Suharto dan Bambang
Pujaswara keduanya dari Akademi Seni Tari Indonesia Yogya)
benar-benar memikat. Gerakan keduanya sangat halus, mengalir
tenang mirip dua tokoh kembar satu merupakan bayangan yang lain.
Ditambah paduan warna kostum keduanya yang hanya hijau tua,
nampak bersih dan pas--karena sederhana.
Di bagian lain peran Anoman dan Anggodo yang belia (Maryono dan
Sunardi, siswa-siswa Sekolah Menengah Karawitan Indonesia,
Yogya) sempat memperlihatkan bakat-bakat yang dapat dikembangkan
di masa depan. Sayang, anak-anak muda ini tak. mendapat
kesempatan yang cukup untuk berokal. Sementara Rahwono
(Djokosuseno) walaupun kurang greget dan gregel memiliki dasar
volume suara dan gerak tari yang tak mengecewakan.
Suara Kereta Api
Tentu saja, kekurangan masih ada di sana-sini.
Posisi menari berjongkok yang diprtahankan sepanjang lakon (dan
yan merupakan ciri khas tontonan ini) ternyata membatasi
pengolahan ruang terutama level atau tinggi rendah tatanan
gerak. Memang, dalam beberapa gerakan dan dalam adegan perang
ada sedikit kelonggaran bagi penari untuk berdiri. Namun itu
saja belum memadai.
Apalagi bloking selalu statis. Penggarapan level dan bloking
tontonan ini rasanya memang masih bisa dikembangkan.
Yang membantu memecah rasa-datar adalah senggakan khas wenaran
yang lugu dan spontan, yang menggelitik penikmat justru karena
lepas dari lakon. Misalnya: tiba-tiba ada yang menirukan suara
kereta api "jes . . . jes . . . jes . . "
Penyederhanaan kostum men.ang menguntungkan. Tidak dipakainya
topeng memungkinkan penari leluasa bersuara. Tapi rias muka
penari, terutama untuk penari-penari kera, terasa agak
berlepotan. Mungkin karena tontonan ini dipentaskan di sebuah
teater arena yang jarak antara penari dan penonton amat
dekat.
Rias yang hanya menguatkan garisgaris wajah akan lebih serasi,
dan akan merangsang akting penari lebih mantap. Gerak tingkah
peran Anggodo misalnya, toh cukup menampilkan ciri khas tarian
kera, walau misalnya tanpa tata rias.
Usaha mempersempit ruang pentas dengan meletakkan gamelan
Slendro pcngiring tarian di atas panggung, sesuai dengan
keperluan tontonan. Para penari yang duduk bersama para pemukul
gamelan, di samping mempercepat keluar masuk mereka, juga
menambah semarak pemandangan di arena. Dan itu sangat menolong
pertunjukan yang sebetulnya lebih ditujukan bagi telinga ini.
Sal Murgianto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini