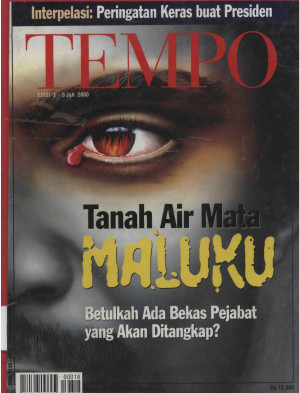Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sesungguhnya buku karya Tan Malaka itu hanyalah satu dari beberapa buku ganda—satu judul tapi diterbitkan banyak penerbit—yang ramai beredar di pasaran. Buku lainnya, antara lain Gerpolek: Gerilya Politik Ekonomi, juga karya Tan Malaka, diterbitkan oleh Djambatan dan Jendela. Sedangkan karya Tan Malaka yang lain, Massa Aksi, diterbitkan tiga penerbit sekaligus: Komunitas Bambu, Yayasan Massa, dan Cedi Aliansi Press. Novel Student Hijo karya Mas Marco diterbitkan oleh Aksara dan Bentang. Tak ada yang berbeda dari buku-buku itu kecuali gambar sampul dan harganya.
Maraknya gejala ini tak bisa dilepaskan dari keterbukaan sejak Orde Baru tumbang. Selepas rezim itu runtuh, berbagai buku-buku "kiri" yang dilarang semasa Soeharto berkuasa tiba-tiba luber di toko-toko buku. Komunitas Bambu termasuk yang pertama menerbitkan kembali naskah-naskah lama ini, terutama yang "kiri", atau katakanlah buku-buku yang mengungkap tema yang tabu dibicarakan di masa pemerintahan Soeharto. Pada awal reformasi, sebelum Soeharto jatuh, kelompok anak muda ini urunan untuk menerbitkan buku. Mereka tertarik sosok Tan Malaka. Kebetulan pula, saat itu mereka menemukan naskah tua Islam dalam Tinjauan Madilog, yang kemudian mereka terbitkan dengan nama Seri Kitab Klasik. Selanjutnya, mereka menerbitkan trilogi Tan Malaka, Menuju Republik, Massa Aksi, dan Pandangan Hidup.
Bak oasis di padang gersang, kehadiran buku-buku itu pun langsung diburu pembaca. Menurut Filise da Silva, Staf Manajer Toko Buku Gramedia Matraman, buku-buku "kiri" ini tergolong laku. Di tokonya saja, dalam empat bulan terakhir, mereka mampu menjual buku Tan Malaka dari berbagai judul dan penerbit sebanyak 900 eksemplar.
Tentu saja ini dilihat sebagai peluang bisnis yang gurih. Rezeki yang diperoleh itu membuat penerbit lain ingin memperoleh keuntungan yang sama. Teplok Press menerbitkan Madilog, yang sebelumnya diterbitkan Pusat Data Indikator. Sedangkan Bentang menerbitkan Student Hijo karangan Mas Marco, yang lebih dulu diterbitkan Aksara. Hasilnya? Mualim dari Toko Buku Kalam menyatakan, paling tidak untuk pembeli di tokonya, penjualan buku Madilog yang diterbitkan Teplok Press mengalahkan Madilog-nya Pusat Data Indikator.
Menurut Buldanul Khuri, pemilik penerbit Bentang, motivasi mereka menerbitkan buku-buku lama tak lain karena pertimbangan bisnis. Selain itu, ia juga merasa puas karena dapat menerbitkan kembali buku-buku yang dulu dilarang atau tidak bisa diterbitkan semasa rezim Soeharto. "Konsumen akan punya pilihan," kata Buldanul Khuri.
Sedangkan bagi penerbit Aksara, yang berbasis di Yogyakarta, mereka sengaja menerbitkan Student Hijo untuk mendongkrak popularitasnya. "Kami baru mulai mengerek bendera di dunia penerbitan. Jadi, perlu gebrakan," kata Subandi, salah seorang pengurus penerbit Aksara yang mengaku memperoleh buku Student Hijo dari aktivis Partai Rakyat Demokratik.
Namun, keuntungan yang diperoleh dari penjualan buku itu, menurut Subandi, tidaklah besar. "Kami masih penerbit kecil. Kalau buku kami habis terjual, itu hanya bisa untuk modal menerbitkan buku lain," katanya. Dengan menerbitkan buku-buku berbau kiri itu, mereka juga ingin memberi wacana alternatif dalam bacaan.
Alasan yang nyaris sama dikemukakan Agus Edy Santoso, Pejabat Humas Teplok Press. Tujuan mereka menerbitkan buku-buku itu bukan karena faktor uang semata. Tapi, keuntungan yang diperoleh dari penjualan buku-buku itu terbilang lumayan. Dari penjualannya, mereka bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 3.000 per buku. Nah, tinggal dikalikan dengan jumlah yang laku terjual.
Yang lebih menarik, para pelaku bisnis buku lama tidak dipusingkan soal hak cipta. Dalam menerbitkan buku-buku lama itu, praktis mereka tidak perlu membayar royalti kepada penulisnya. Lo, kok begitu? Menurut konvensi internasional, masa kedaluwarsa hak cipta sebuah buku adalah 50 tahun, terhitung sejak pemilik hak itu meninggal dunia. Setelah masa itu, hak ciptanya menjadi milik publik.
Hal ini dibenarkan A. Zen Umar Purba, S.H., L.L.M., Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Menurut dia, hak cipta atau copyright itu hanya berlaku pada penulis selama dia masih hidup. Jika sudah meninggal, hak itu berpindah pada ahli warisnya dalam jangka waktu lima puluh tahun terhitung sejak kematian penulis. "Sehingga, dalam masalah ini, hak cipta Tan Malaka sudah menjadi milik umum," katanya. Tokoh Murba itu meninggal pada tahun 1949.
Namun, bila masa kedaluwarsanya belum tuntas, penerbit harus beroleh izin dari penulisnya. Tanpa izin, pelanggarnya bisa diganjar sanksi yang berat. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, pelanggarnya bisa diganjar hukuman penjara maksimum tujuh tahun atau denda sebanyak Rp 100 juta.
Hampir semua penerbit tampaknya mengambil sikap hati-hati dalam soal itu. Yang berbeda hanyalah Teplok Press. Dengan tegas mereka tidak mengindahkan hak cipta penulisnya. "Kita memang anti-copyright, " kata Agus Edy Santoso. Menurut pria yang akrab dipanggil Agus Lennon ini, semua buku yang diterbitkannya tidak diiringi copyright dari penulisnya.
Dengan dalih itu, katanya, harga buku-bukunya bisa ditekan lebih murah. "Kalau mereka (para ahli waris) hanya mau minta duit, ya kita kasih. Kita akan kasih data-data kita, berapa pemasukan, pengeluaran kita. Kita biarkan ia berpikir sendiri," katanya. Namun, ia mensyaratkan agar mereka bisa menunjukkan surat tertulis penyerahan copyright. Di dalam bukunya, mereka memang tidak mencantumkan label "hak cipta ada pada penerbit". Sebaliknya, mereka juga merelakan jika buku-bukunya kemudian dibajak orang.
Tak hanya buku Tan Malaka, untuk menerbitkan buku Demokrasi untuk Indonesia karya Hasan Tiro, Agus mengaku tidak meminta hak penerbitan kepada penulisnya.
Tampaknya itu pula yang mengecewakan pihak keluarga Tan Malaka, yang buku-bukunya paling banyak diterbitkan kembali. Meski sebenarnya merasa gembira dengan terbitnya kembali buku-buku itu, Zulfikar Kamaruddin, kemenakan Tan Malaka yang kini menjadi ahli waris sang penulis itu, belakangan mengaku agak kecewa juga dengan polah penerbit yang tanpa meminta izin kepadanya. Sebab, menurut dia, Tan Malaka masih memiliki ahli waris, yakni dirinya.
Zulfikar merupakan ahli waris Tan Malaka secara tidak langsung. Tan Malaka sepanjang hidup tidak pernah menikah. Salah satu ahli warisnya adalah Kamaruddin Rasad, sang adik, yang tak lain adalah ayah dari Zulfikar. Hubungan keduanya memang dekat. Nah, selanjutnya Kamaruddin menyerahkan ahli warisnya kepada anaknya, Zulfikar. Penyerahan ahli waris itu dikuatkan dalam surat bernomor 91/AW Tahun 1956, yang disahkan pemuka adat Minang.
Menurut dia, hanya ada dua penerbit yang kabarnya meminta izin langsung kepadanya, yaitu Pusat Data Indikator dan Komunitas Bambu. "Namun, ada orang-orang (lain) yang tidak mempedulikan nilai-nilai ahli waris itu. Sebagai bangsa yang beradab, ini namanya kurang etis," katanya.
Agaknya keluh-kesah ini patut diperhatikan. Masalahnya, dalam waktu dekat penerbit-penerbit itu merencanakan untuk menerbitkan kembali beberapa naskah kuno. Komunitas Bambu, misalnya, merencanakan akan menerbitkan karya H.O.S. Cokroaminoto, Islam dan Sosialisme. Begitu pula Bentang, yang tengah mempersiapkan penerbitan sepuluh buku lama. Sedangkan Aksara akan menerbitkan kumpulan tulisan tokoh seni rupa modern Indonesia, S. Sudjojono, yang pernah terbit pada 1946. "Buku ini jelas copyright-nya sudah kedaluwarsa," kata Subandi. Dia mengaku sudah memberi tahu anak dan istri kedua Sudjojono.
Memang seharusnya begitu. Seperti permintaan Zulfikar, sekadar memberitahukan kepada ahli waris untuk menerbitkan buku keluarganya tentu bukanlah sebuah hal buruk.
Irfan Budiman, Darmawan Sepriyossa, Gita W. Laksmini, Raihul Fadjri (Yogyakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo