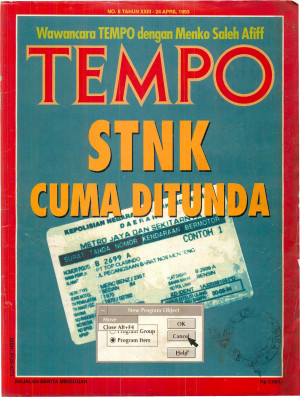ALAM yang bisik-berbisik dan batin yang merindukan keakraban kasih sayang bertemu dalam keheningan. Itulah musik yang sejati, musik yang amat kaya dengan bunyi. Dan hakikat musik tiada lain adalah bunyi itu sendiri, tak peduli dari alat apa sumbernya. Itulah konsep musisi kontemporer Slamet Abdul Syukur. Ia rupanya mulai bosan dengan jenis musik ''metal'' atau musik '''ngak-ngik-ngok'', yang memang dijejalkan ke konsumen di kota- kota sebagai komoditi industri. Karena musik jenis ini bisa kehilangan ''roh'' musik itu sendiri, yaitu pantulan jiwa yang merindukan keheningan dan penghiburan. Barangkali itulah sebabnya, Minggu sore lalu ia ingin membuktikan konsepnya bahwa ''hakikat musik ialah bunyi itu sendiri''. Dan bunyi apa pun yang diperdengarkan, sesungguhnya sangatlah kaya dan imajinatif tak peduli dari mana sumbernya atau dari alat apa bunyi itu dihasilkan. Maka, ia pun memilih tempat pergelaran ''konser'' itu di tengah hutan. Di tengah hutan? Tentu saja, sebab di sanalah jauh dari kebisingan kota keheningan itu ada. Waktunya pun dipilih saat senja menjelang matahari terbenam, ketika burung dan margasatwa lainnya pulang kandang sembari bergaung atau cuat-cuit bernyanyi. Konser itu di areal sebuah hutan lindung di kaki Gunung Penanggungan, di kawasan Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Ini sungguh unik. Bayangkan, 40 orang pemainnya terdiri dari para petani laki perempuan yang tak pernah ''makan'' sekolah musik. Instrumennya pun terdiri dari 17 jenis bukanlah alat musik yang biasa digunakan buat sebuah pergelaran musik. Bahkan gitar pun tak ada. Satu-satunya alat musik yang ''normal'' hanyalah seruling bambu. Instrumen lainnya semua dibikin sendiri oleh para pemain terdiri dari alat yang akrab dengan penduduk. Ada sapu lidi, bakiak, kaleng bertali, kentongan, kitiran, terompet. Dari alat-alat ini muncul suara seperti anjing menggongong, ayam berkotek, burung bersiul, dan suara hewan lain seperti katak dan jangkrik. Dengungan lebah dihasilkan dari mainan yang disebut sowangan. Suara-suara itu bersahutan. Juga ada suara perempuan menyapu dan teplak-teplok bakiak. Slamet Abdul Syukur hanyalah bertindak sebagai penggagas. Jenis instrumen dipilih sendiri oleh para pemain. Slamet juga tidak bertindak sebagai dirigen, melainkan hanya mengatur tempat dan waktu permainan. Karena pergelaran ini tanpa sound system, Slamet mengatur kedudukan para pemain berpencar. Selain untuk mendapatkan efek alami suatu suara muncul dari daerah tertentu juga untuk mengatur intensitas bunyi: instrumen yang suaranya lemah di- tempatkan dekat arena, yang bersuara keras agak jauh. Sahut- menyahut bunyi-bunyian itu merupakan duplikat dari alam. Alam sendiri bahkan diikutsertakan dalam konser ini, seperti nyanyian burung di pepohonan yang terdengar jelas ketika para pemain sengaja menghentikan permainan dalam sebuah jeda hingga tercipta keheningan. Keheningan memang merupakan salah satu unsur dalam konser ini, hingga desau angin, gesekan dedaunan, dan bahkan keheningan itu sendiri terasa nikmat. Slamet juga berusaha melukiskan suka-duka dan kegaduhan penduduk menghadapi banjir atau kebakaran hutan, ketika para pemain secara bersama-sama dan serentak membunyikan instrumen. Namun, ia ''toleran'' terhadap kegaduhan yang mengganggu keheningan itu. Letupan knalpot sepeda motor yang sesekali melintas di pinggir hutan seperti bersatu secara wajar. Tony Prabowo, musisi terkemuka yang hadir dan merekam pertunjukan ini, menilai bahwa konser ini benar-benar diilhami oleh kebesaran alam. ''Bunyi-bunyian yang diperdengarkan dari alat-alat sederhana itu sangat indah. Dan suasana hening yang setiap kali ditampilkan benar-benar merasuk ke dalam jiwa pemain dan penonton,'' kata bekas murid Slamet itu. Konser yang bagi orang-orang musik mungkin dianggap aneh ini, oleh Slamet, diberi judul Konser Minimax. Maksudnya, dengan sarana tempat, pemain, dan instrumen seminimal mungkin, konser ini ingin mencapai hasil yang maksimal. Maksud Slamet ber-minimax itu tercapai karena para pemain dan penonton tampaknya merasa senang dan bahagia. Konser selama satu jam itu seperti permainan mereka sehari-hari, sebagai ungkapan jiwa dan perasaan mereka sendiri. Mereka bermain dengan suka rela dan senang hati, meskipun menurut Slamet ''bisa membingungkan para pemusik''. Nurul tampak bersungguh-sungguh meniup seruling. Padahal, gadis 20 tahun tamatan SMA Mojokerto yang lagi nganggur ini tak bisa meniup seruling. Ia memang tidak membawakan sebuah lagu tapi sekadar meniup seruling. Mula-mula dengan nada rendah, makin lama makin meninggi dan memanjang. ''Ini mengingatkan saya pada permainan anak-anak desa di zaman dulu ketika saya masih kecil,'' kata seorang perempuan tua. Pengamatan orang desa ini persis sama dengan apa yang ditangkap oleh Sapto Rahajo, musisi kontemporar asal Yogya. Katanya, ''Konser ini sungguh alami dan menyuguhkan nilai spiritual. Slamet mampu menghadirkan kembali sesuatu yang telah hilang.'' Budiman S. Hartoyo dan Zed Abidien
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini