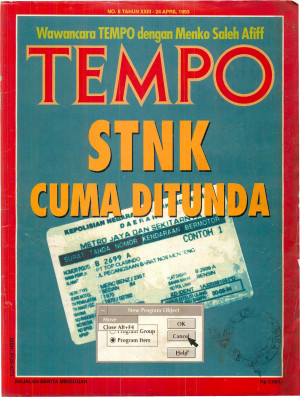IBRAHIM Hasan, Gubernur Aceh, telah "tercerabut" ke Jakarta untuk menjadi Menteri Urusan Pangan dan Kabulog. Apakah yang dipikirkan Hasbi Burman, penyair "bohemian" merangkap tukang parkir di situs Rex Banda Aceh, tentang hal ini? Suatu malam, akhir Juni tahun lalu, di lapangan parkirnya, Burman memperlihatkan sebuah cek kepada saya. "Ini honor dari Pak Gubernur," tljarnya bangga. Seraya menenggelamkan kembali cek tersebut ke dalam saku bajunya, ia berkata: "Honor terbesar yang pernah dibayar kepada seorang penyair Aceh." Ibrahim Hasan telah membuat tradisi baru. Dalam acara perkawinan putrinya, ia bukan saja mengundang para penari dan penyair tradisional. Tapi juga yang "kontemporer". Burman, yang memulai kehidupan malamnya di tempat parkir, warungwarung rakyat, dan mengakhirinya di sebuah gubuk terbuka Balai Budaya Banda Aceh, ikut diundang. Dan cek itu, yang, menurutnya, tak akan dicairkan dengan cepat, adalah hasilnya. Hampir satu dekade ini, Aceh banyak berubah. Pemba ngunan prasarana fisik yang dilancarkan, terutama sejak kemenangan Golkar pada tahun 1987, telah menjadi dasar perubahan itu. Di samping kelancaran komunikasi, pertambahan gedung-gedung baru serta perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, kita juga menyaksikan munculnya lapisan kaum bisnis baru yang - untuk ukuran Aceh - tumbuh cepat. Omset seorang pengusaha lokal, misalnya, bisa mencapai seratus sampai dua ratus miliar per tahun. Tapi kemunculan kaum "semi-borjuis" ini- tidak didukung oleh sebuah orientasi kultural yang jelas. Sebagian besar elite bisnis Aceh dewasa ini tum buh dari kalangan "pedagang". Walau kini telah mulai dianggotai kaum muda terpelajar, namun umumnya apresiasi budaya mereka masih relatif "kacau". Tampaknya mereka tumbuh dengan basis materi baru, tanpa, secara kuaiitatif, basis budaya. Mereka toh secara fungsional tak bisa lagi menengok ke belakang. Sementara yang baru pun hanya tersentuh secara samarsamar. Terutama untuk jangka panjang, aneh juga rasanya menyaksikan pertumbuhan sebuah kalangan "borjuis" dengan basis budaya "apa adanya" - sisa-sisa budaya Aceh bercampur aduk dengan budaya kosmopolitan "pinggiran". Maka, tidak seperti di Padang, apalagi di kota-kota besar Jawa, kreativitas sastra terutama teater, di Banda Aceh, tak bersentuhan dengan kalangan ini. Relatif redup, para sastrawan dan teaterwan berjuang sendiri, sekadar untuk survive. "Kalau kami tak bertahan," kata Maskirbi dan kawan-kawan dari Taman Budaya, "bagaimana nasib teater Aceh di masa depan?" Berlagak sebagai "makelar budaya", saya mengusulkan sebuah malam baca puisi kepada Gubernur Ibrahim Hasan. Ajaib juga, bukan saja diterima, tapi malah dia lebih antusias. "You yang harus jadi ketua panitianya. Saya sendiri akan ikut baca puisi malam itu." Serta-merta ia merogoh kocek. Dan dua malam berikutnya, di hadapan para pengusaha, ia mengumumkan acara yang kemudian menjadi penting itu. "Panitia masih kekurangan dana," ujarnya. Tiba-tiba, Ibrahim Pidie, seorang pengusaha sukses berdiri: "Semua kekurangan dana kami tanggulangi." Sejak itu, Banda Aceh seakan mengalami "demam puisi". Dengan mengabaikan penelitian selama dua minggu, bersamasama wartawan Harian Serambi Indonesia, pengurus Balai Budaya, dan dibantu mahasiswa Unsyiah serta IAIN Banda Aceh saya mulai bekerja sebagai ketua panitia "karbitan". Demam puisi itu tampaknya menjadi serius, sampai-sampai Sayed Mudlahar Ahmad, Bupati Aceh Selatan waktu itu, bersedia menjadi pengantar surat undangan. Bukan saja kepada sesama bupati tetapi juga kepada ketua Bappeda Aceh Selatan, bawahannya sendiri - karena sang bawahan dikenal sebagai penyair. Dan mungkin, karena langkanya acara itu, banyak kalangan, terutama pejabat menjadi heran. Bagaimana mungkin membaca sajak - yang tentu saja biasa mereka temui dalam buku pelajaran Bahasa Indonesia anak-anaknya - menjadi acara yang begitu serius? Dan karena acap mendapat pertanyaan "dalam rangka apa", panitia menjadi siap dengan jawaban: dalam rangka baca puisi! Untuk ukuran Banda Aceh, acara yang berlangsung di panggung terbuka Anjong Mon Mata itu berjalan bagus. Tradisi politik Aceh yang mahal senyum tercairkan malam itu, ketika sebuah fragmen justru mengritik sikap politik gubernur. Dan Teuku Djohan, seorang militer dan Wagub Aceh, yang pendiam dan terkesan angker muncul mempe sona. "Saya sebenarnya sudah siap dengan dua-tiga puisi," ujarnya di depan khalayak. "Tapi karena gubernur cuma punya satu puisi, saya tak berani membaakan semua." Lalu pengantarnya itu ditutup dengan kata-kata yang menggelitik: "Mana berani saya melebihi atasan." Para penyair, yang sebelumnya merasa tak mendapat tempat dalam perubahan sosial ekonomi Aceh, tiba-tiba menemukan kepercayaan diri. Seorang penyair muda, melalui Radio Flamboyant, berkata setelah acara itu: "Kini kami merasa dihargai." Tapi kini, Ibrahim Hasan, sang "promotor puisi" harus pindah ke Jakarta. Saya tak tahu apakah tradisi baru itu akan berlanjut. Hasbi Burman, yang juga tampil membacakan "Untuk Nona N" - sajak yang diperuntukkan kepada seorang gadis penjaja makanan di Rex - pastilah merasa kehilangan. Wong cilik sahabat gubernur itu, munkin hanya bisa mendendangkan lagu sendu di atas sebuah jembatan panjang, yang menghubungkan Banda Aceh dan Darussalam, di kegelapan malam seperti biasa dilagukannya: Pujaanku dosakah hambaKalau kutanya padamu/Mengapa aku slalu derita .... Dan angin malam Gunung Seulawah, menusuk-nusuk tubuhnya yang kering dan kurus itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini