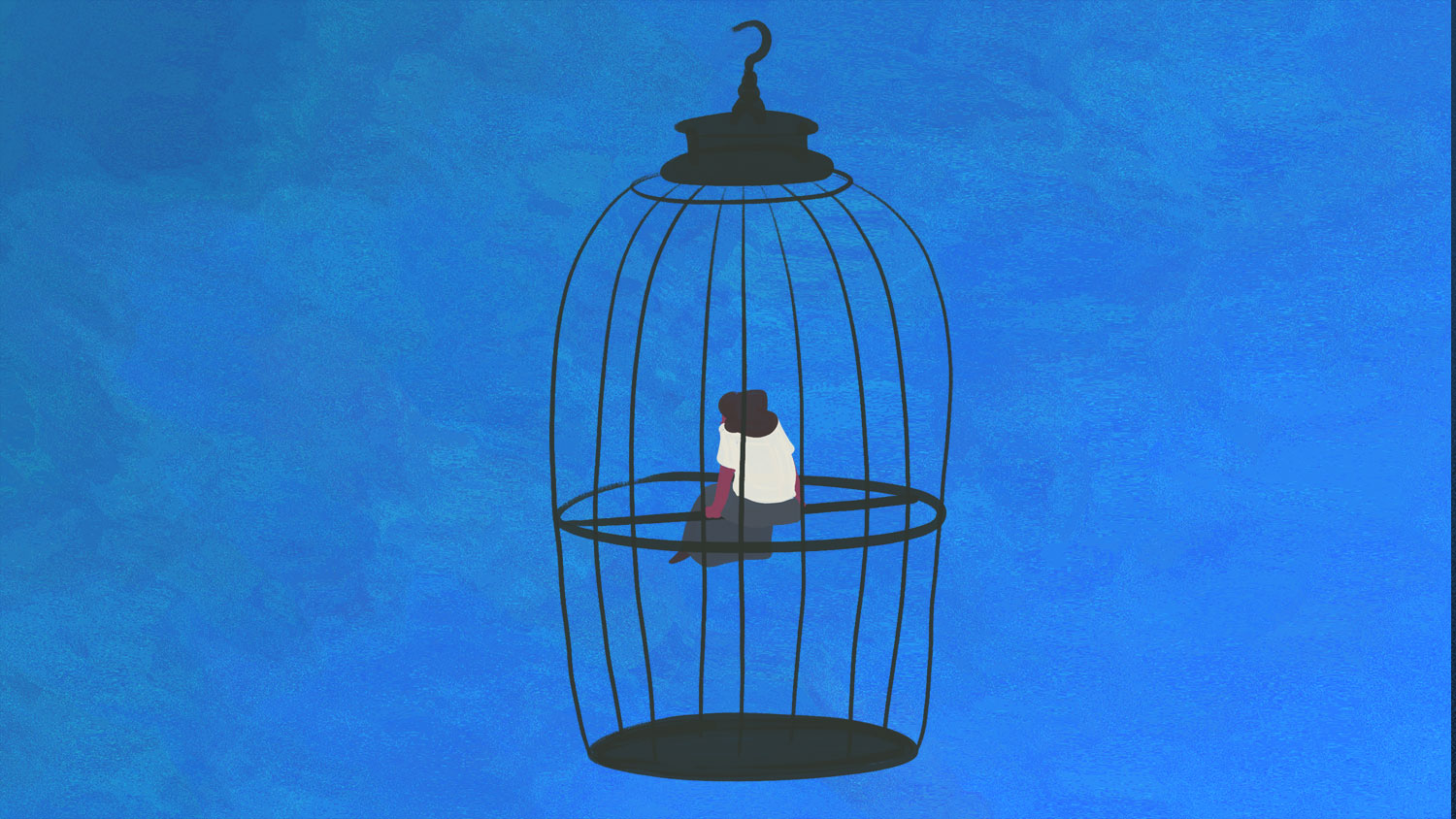Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tiga Kisah Patah Hati
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anton Kurnia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Garis Batas
Ada sebuah ruas jalan di kotamu yang lekat di hatimu seperti sisa es krim yang melengket di sela jemari. Di ujung selatan ruas tengah Braga yang kedua sisinya didereti toko-toko antik berjendela kaca lebar dan bangunan kuno berarsitektur art deco, terdapat sebuah kafe tua yang menjual es krim bikinan sendiri. Ke Café Canary itulah ibumu mengajakmu pada satu sore cerah yang muram.
Umurmu baru sekitar tiga minggu menjelang genap sepuluh tahun. Tetapi, setahun sebelumnya kau sudah kehilangan ayah. Kanker tulang belakang telah merenggutnya setelah bertempur hebat selama dua tahun sehingga tubuhnya yang subur menyusut menjadi amat kurus di saat-saat terakhir.
Di bangku itu kau duduk menghadapi semangkuk kaca es krim vanila. Sepasang bola matamu yang cokelat menatap mangkuk es krim. Sesekali kau menggaruk tahi lalat di atas bibirmu yang sebetulnya tak gatal. Kau melakukannya hanya karena kau tak bisa mengontrol gerakan itu saat kau gugup atau sedih atau gundah.
Kau amat suka rasa es krim vanila yang putih dan lembut dan manis. Namun, kau mendadak merasa lidahmu seolah pahit sehingga kau teringat sebuah cerita lama yang pernah kaubaca di sebuah majalah anak-anak tentang seorang pendekar berlidah pahit. Kau juga merasa lidahmu kelu. Tak mampu bicara.
Ibumu baru saja berkata dia akan menikah lagi dan suaminya yang baru akan membawa kalian pindah ke lain kota. Itulah yang membuat es krimmu jadi tak terasa manis, hanya dingin dan kebas. Padahal sore itu cuaca amat cerah.
Ada semacam luka halus yang menggores di dalam hatimu. Sesungguhnya kau tak rela ibumu memiliki dan dimiliki lelaki lain selain kau dan ayahmu. Kau tak suka ada lelaki lain di dalam hidupmu, di antara kau dan ibumu. Kau tak ingin ibumu beralih dari ayahmu yang telah tiada. Kau sedih, tetapi tak berdaya. Namun, kau tak menangis. Kau hanya diam membisu.
Diam-diam kau menelan es krimmu yang mencair di lidah, serupa menelan gumpalan kesedihan yang patah. Seakan-akan ada rumpang di hatimu yang perih. Seolah-olah ada semacam lubang di sana yang membuatnya tak akan pernah lagi utuh.
Saat itu kau belajar satu hal: di dalam hidupmu kau tak hanya bisa kehilangan orang-orang yang pergi tak kembali seperti ayahmu, tetapi kau juga bisa kehilangan orang-orang yang masih ada serupa ibumu. Atau setidaknya, kau terpaksa harus berbagi. Tak lama lagi, ibumu bukan milikmu sepenuhnya walaupun kau anak satu-satunya.
Saat itulah kau mulai mengenal bagaimana rasanya patah hati.
Seorang Gadis yang Meminta Api
Kau terbangun menjelang Mannheim. “Carmina Burana” gubahan Carl Orff mengentak di telinga. Pagi baru menggeliat. Kau duduk mengantuk di atas bus yang melaju ke timur. Sepanjang jalan melintasi daratan Jerman pepohonan hijau kuning kemerahan musim gugur terhampar. Sebagian telah ranggas. Langit mendung. Kabut mengambang di atas sungai. Terasa sebersit nuansa indah di tengah kemuraman.
Beberapa jam sebelumnya kau duduk di beranda sebuah kafe di St. Michel, di satu kawasan ramai Paris yang kerap disebut Latin Quarter. Usai berjalan-jalan mengelilingi Paris seharian, kau duduk-duduk minum kopi sebelum naik metro menuju Porte Maillot untuk mengejar bus malam terakhir ke Praha.
Saat kau asyik duduk sendiri mengisap kretek seraya menghadapi secangkir kopi di meja, matamu menangkap seorang gadis berambut panjang keluar dari dalam kafe. Di pundaknya tersampir sebuah tas. Kulitnya tak terlalu terang. Rambutnya legam. Sosoknya ramping dengan tinggi badan sedang. Wajahnya mengingatkanmu kepada Djamila Bouhired—pejuang kemerdekaan Aljazair. Ada sebungkus rokok di tangannya. Mungkin dia baru membelinya di konter kafe.
Tak sengaja matamu bersirobok dengan matanya yang kemerjap. Dia lalu berjalan menghampirimu yang duduk di sudut di antara beberapa pasang bule setengah baya di meja lain.
"Ecuse moi," kata dia. Gadis itu lalu meminta api dengan sopan.
Kau menjawab gugup dalam bahasa Inggris. Tetapi sialnya kau lupa di mana tadi menaruh geretan. Kau berdiri, mencoba mencari-cari. Gadis itu mulai gelisah. Untunglah geretan itu segera ditemukan. Ternyata ada di saku jaketmu.
Lekas kau nyalakan rokok di bibirnya dengan geretanmu. Dia tersenyum dan berterima kasih. “Merci,” katanya.
Kau lalu menawari dia duduk. Dia menggeleng, mengatakan harus segera pergi seraya menunjuk ke satu arah. Lalu dia tersenyum sekilas dan melambai. Kau membalas senyumnya dengan hati sedikit kecewa.
Lalu, saat bus melaju menuju Nurnberg setelah melewati persimpangan antara Basel dan Stuttgart, kau teringat Montmartre. Ketika kau menyusuri sepanjang jalan di sekitar kawasan lampu merah itu, kau bersua dengan klub legendaris Moulin Rogue. Kau pun terkenang sebuah film lama. Film itu berkisah tentang percintaan yang sedih antara seorang seniman miskin dan seorang primadona di panggung kabaret.
Dua puluh tahun silam, semasa mahasiswa di Bandung, sebagai pemuda yang ingin jadi penulis kau sesekali nongkrong di Cafe Terminus, di Pusat Kebudayaan Prancis. Di salah satu dindingnya saat itu ada mural warna-warni tentang kehidupan di Paris. Di situ tertera sebuah kalimat yang membuatmu tersenyum geli, "Aku rela menjual becakku demi pergi ke Paris."
Bus terus melaju. Menuju Praha. Kau teringat Kafka dan Kundera dan novel-novel mereka yang kaubaca sejak belasan tahun silam. Kau pun terkenang lagi pada seorang gadis yang meminta api lalu pergi dengan meninggalkan semacam patah hati.
Misalkan pada suatu hari kau berjumpa tanpa sengaja dengan seseorang tak dikenal di kota yang asing nun jauh dari negeri asalmu saat sama-sama sedang menunggu bus atau pesawat yang masih lama berangkat, katakanlah seperti ini: “Selepas senja Anda duduk di sebuah kafe di kawasan Latin Quarter menghadapi secangkir kopi. Di depan Anda orang-orang berlalu-lalang di trotoar. Tiba-tiba seorang gadis berambut panjang dengan mata seperti kejora berjalan mendekati Anda. Dia meminta api. Anda menyalakan geretan lalu menyorongkan ke ujung rokok yang terselip di bibirnya. Dia mengucapkan ‘Merci’ seraya tersenyum sekilas. Lalu seumur hidup Anda tidak pernah bertemu lagi dengan gadis itu. Pernah mengalami seperti itu?”
Perempuan yang Menulis di Dalam Bus
Ketika bus berhenti di Manchester, kau terjaga. Langit masih gelap. Mungkin sudah menjelang subuh. Kau tak menyalakan ponsel untuk memastikan waktu. Matamu masih terasa berat oleh kantuk. Saat kau kembali memejamkan mata, terdengar suara lembut perempuan dekat sekali dari samping kirimu, "May I sit here?"
Kau membuka mata dengan enggan. Mencoba tersenyum tipis. "Sure," katamu. Bagaimanapun dia lebih berhak duduk di atas kursi di sampingmu ketimbang ransel hitammu yang sesak oleh buku.
Kau meraih ransel itu dan menaruhnya di bawah kursimu. "Thank you," kata dia seraya duduk tepat di sebelahmu. Padahal, selepas dari stasiun bus Glasgow beberapa jam sebelumnya kau sudah senang bisa menguasai dua kursi paling depan di bagian atas Megabus menuju London itu.
Selintas pandang dia perempuan sebayamu atau lebih tua beberapa tahun, berambut brunette panjang lurus sepunggung. Dia mengenakan rok mini hitam melapisi legging yang tampaknya berwarna ungu atau magenta barangkali. Lalu, kau mencoba meneruskan tidurmu yang sempat terusik.
Menjelang Birmingham kau terbangun oleh sengatan sinar matahari yang hangat. Saat kau membuka mata, silau menyergap. Lekas kau memakai kacamata minus yang semula kau sisipkan di saku kemejamu. Lensanya yang bening segera menjadi gelap ditimpa sinar ultraviolet. Kau meraih ponsel di saku jaket dan menyalakannya. Sudah menjelang pukul delapan.
Kau memasang earphone. “Ruby Tuesday” yang dimainkan The Rolling Stones mengalun di telinga: “‘There’s no time to lose,’ I heard her say. Catch your dreams before they slip away.” Lagu itu bercerita tentang seorang perempuan misterius yang datang dan pergi semaunya.
Pagi baru menggeliat. Kau duduk mengantuk di atas bus yang melaju. Di sebelahmu perempuan berambut panjang itu sedang asyik menulis. Dia menulis dengan pena bertinta hitam di atas sebuah buku besar folio bergaris yang terbuka di pangkuannya.
Kau mengintip lewat sudut matamu. Tampaknya dia sedang menulis surat. Atau sebuah cerita pendek? Dia terus menulis. Sementara itu, kau terus menatap pemandangan sekitar jalan tol menuju kota. Kau sempat berpikir untuk menyapa perempuan itu. Namun, kau tak ingin mengganggu keasyikan dia menulis.
Ada sesuatu pada dirinya yang mengingatkanmu kepada seseorang nun di masa lalu, tapi entah apa. Seseorang itu pernah begitu dekat denganmu, tetapi kini terasa begitu jauh. Kau bahkan tak tahu bagaimana kabarnya dan di mana dia sekarang. Ingatan itu membuat sesuatu yang lembut dan perih terasa menggores lagi hatimu.
Terbuat dari apakah ingatan? Apa sesungguhnya ingatan itu? Jika ingatan berwarna, apakah warna sebuah ingatan yang membuatmu sedih?
Di pinggiran Birmingham bus berhenti di satu halte di tepi jalan. Perempuan dari Manchester itu berkemas. Sebelum beranjak, dia berpamitan kepadamu. "Bye," ujarnya seraya tersenyum. Kau balas tersenyum, tetapi tak berkata apa-apa.
Kau belum sempat berkenalan dengannya.
Paris-Praha, 2016—Glasgow-London, 2019—Istanbul-Amsterdam-Jakarta, 2021
-------------------
Anton Kurnia menulis cerpen, esai, dan nonfiksi naratif. Kumpulan cerpen pertamanya, Insomnia (2004), diterjemahkan ke bahasa Inggris sebagai A Cat on the Moon and Other Stories (2015) dan ke bahasa Arab sebagai Qithah ’alal Qamar (2020)—diterbitkan Noon Publisher di Kairo, Mesir. Kumpulan cerpennya yang kedua berjudul Seperti Semut Hitam yang Berjalan di Atas Batu Hitam di Dalam Gelap Malam (2019). Buku esainya yang kelima adalah Menuliskan Jejak Ingatan (2019). Kumpulan tulisan perjalanannya ke berbagai negara akan segera terbit sebagai Banyak Jalan Menuju Praha: Catatan Perjalanan dan Pertemuan. Kini dia tengah menyelesaikan buku terbarunya, Menulis dengan Cinta: Pengantar Belajar Menulis.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo