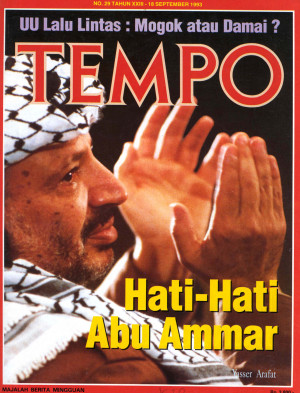BOLEH dibilang, Yang Muda Yang Bercinta menjadi film Rendra, bukan film tentang Sonny, tokoh rekaan Umar Kayam. ''Sonny yang saya tulis dalam skenario asli adalah seorang mahasiswa rata- rata, bukan penyair. Ia memang kritis, tapi tak terlalu pemberontak seperti yang digambarkan dalam film,'' demikian kata Umar Kayam. Tapi Sonny yang Anda lihat dalam film ini adalah Rendra. Ia seorang penyair, kritis, ganteng, perayu. Sonny (yang diperankan Rendra) adalah seorang mahasiswa dari kelas menengah, priayi Jawa yang hidup pas-pasan, dan pacaran di atas bus. Pacarnya, Titi (Yati Octavia), cantik, bahenol, anak tukang kue. Skenario aslinya menceritakan kedua kekasih ini dimabuk cinta di tengah semrawutnya Jakarta yang sumpek, di tengah kebingungan Sonny sebagai mahasiswa yang anak priayi. Lalu si pacar bunting, dan Sonny ''menyendiri'' untuk kemudian kembali ke pelukan sang pacar. Habis. Itu cerita asli. Tapi Sjuman menyulap Sonny menjadi mahasiswa yang galak. Bukan hanya pemerintah dan cukong yang diterabasnya melalui sajak-sajaknya. Dia meledek pula bapaknya (Maruli Sitompul) sebagai generasi lama berpikiran macet. Dia gerah ketika mengetahui bahwa paman idolanya, Karjo (Soekarno M. Noor), ternyata seorang germo kelas tinggi. Beberapa perubahan skenario yang dilakukan Sjuman sebenarnya masih wajar dan relevan dengan jalan cerita. Kisah Sonny yang mahasiswa merangkap sebagai penyair masih bisa diterima. Bukan saja karena Rendra yang memerankannya sudah telanjur diidentikkan dengan sajaknya, tapi mahasiswa (paling tidak di tahun 1960-an dan 1970-an) juga identik dengan sebuah dunia yang resah, gelisah, dan kritis. Jadi, adegan-adegan pembacaan sajak itu sebenarnya tidak perlu menjadi ancaman bagi pihak keamanan. Tokoh Sonny juga sebenarnya sebuah sosok tragis-komis yang terkadang perlu ditertawakan. Dia mahasiswa yang gemar mengkritik, hantam kiri-kanan, tapi dia masih merengek kepada orang tuanya minta dibelikan jas, dan kabur ketika pacarnya bunting. Sonny, baik versi Umar Kayam maupun Sjuman, bukanlah seorang pahlawan besar. Pada awalnya ia mewakili sebuah generasi yang resah gelisah, yang punya keinginan besar untuk membela rakyat yang lemah. Belakangan, keresahannya tidak lagi disebabkan oleh ketimpangan sosial di sekelilingnya, tapi oleh tuntutan tanggung jawab akibat menghamili kekasihnya. Yang membuat film ini istimewa justru bukan kritik-kritik sosial Sjuman Djaja, melainkan adegan demi adegan serta dialog- dialog keluarga yang berjalan begitu wajar, jujur, dan proporsional. Harap ingat, kewajaran adalah barang langka dalam kamus akting perfilman Indonesia. Lihatlah dialog bapak dan anak yang mengharukan tentang masa depan, sementara sang anak ikut belajar melinting rokok. Adegan ini adalah salah satu adegan yang terbaik yang sulit ditemukan dalam film Indonesia. Lalu, lihatlah adegan Sonny mencium kekasihnya dengan begitu mesra, asyik, dan wajar (tanpa sensor berlebihan). Terus terang, akting yang cemerlang dari Maruli Sitompul, Rendra, maupun Soekarno M. Noor meniupkan kesegaran bagi perfilman Indonesia yang sedang sumpek ini. Dan yang membuat film ini tetap relevan dengan persoalan masa kini bukan hanya karena lagu-lagu Koes Plus dan celana cutbrai menjadi mode lagi, tapi juga karena Sjuman dan Kayam berhasil menampilkan persoalan-persoalan yang khas di masa itu sebagai persoalan yang bisa cocok di masa kini. Feodalisme, korupsi, keresahan anak-anak muda, dan cinta yang bergelora. Tentu saja bahasa gambar khas Sjuman yang hitam-putih tetap ada. Kelemahan Sjuman, seperti dalam filmnya yang lain, adalah kegemarannya menyajikan perbandingan kaya-miskin dengan gambar- gambar yang mentah tentang kehidupan yang mewah dan melata. Sebenarnya, Sjuman memberikan sebuah gambaran yang relevan dengan masa kini ketika wajah Sonny disemprot lumpur oleh mobil-mobil reli yang menjelajahi sawah di desa. Sjuman ingin memperlihatkan betapa kurang ajarnya mereka yang kaya dan membuang uang ratusan juta dan seenaknya merusakkan mata pencaharian orang di desa. Tapi kemudian ada mobil reli yang dikendarai teman-teman Sonny yang nyemplung ke lumpur. Para petani lantas dengan wajah amarah berdiri mengelilingi kedua orang kota yang tampak tolol itu. Adegan belakangan ini menjadi sebuah tempelan yang tak ada gunanya. Adegan-adegan tempelan lainnya, seperti sejarah Paman Karjo, juga layak dibabat habis. Tapi film ini tetap layak dinobatkan sebagai film Indonesia terbaik saat ini, setelah tiga tahun terakhir kita kenyang disuguhi film-film komedi konyol dan sinetron televisi yang semakin tidak keruan. Ironisnya, pada tahun 1978, film itu hanya meraih piala Citra bagi Nanny Wijaya sebagai aktris pembantu terbaik. Sementara tahun ini Teguh Karya belum juga berkarya, Eros Djarot sibuk dengan tabloid beritanya, Slamet Rahardjo masih merenung, dan Putu Wijaya belum juga membuat ledakan besar, Yang Muda Yang Bercinta akan menjadi film terbaik Indonesia untuk waktu yang lama. Leila S. Chudori
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini