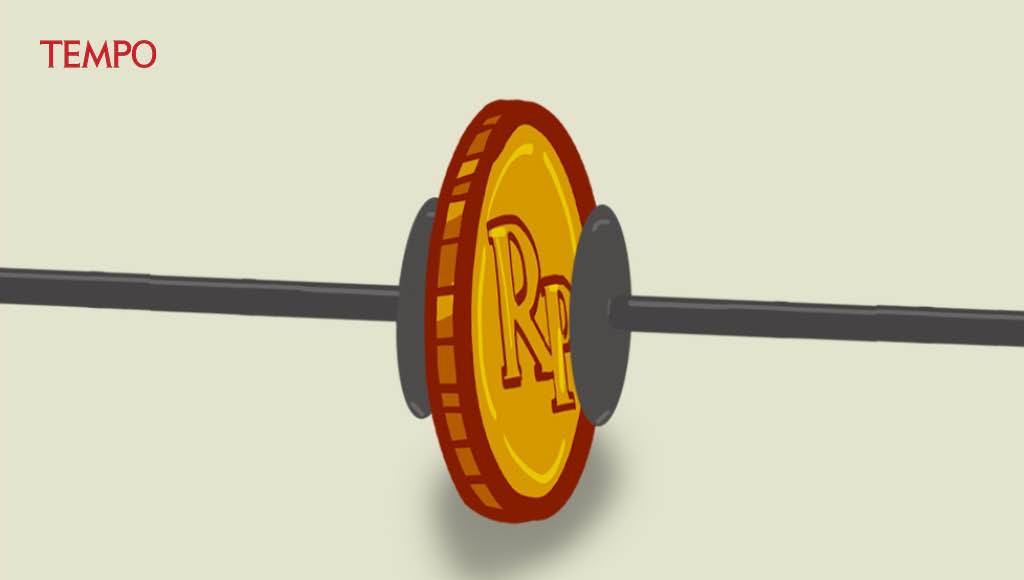ASAL mulanya B.M. Diah membangkitkan perhatian bahwa perlu
dibentuk Serikat Sekerja Wartawan. "Bikinlah itu, kalau
betul-betul PWI menurut saudara bukan serikat sekerja wartawan,"
katanya seperti dikutip Merdeka, koran yang dipimpinnya pula.
Ucapannya itu keluar sesudah ia baru saja diterima oleh Wakil
Presiden Adam Malik. Keduanya telah membicarakan masalah
kampanye kode etik jurnalistik sepanjang Pebruari ini dan soal
kesejahteraan wartawan. Ketika itu suara Diah berdering karena
ia menjabat Ketua Harian Dewan Pers, malah Pembina PWI pula.
Maka soal SSW dari mulut Diah-apalagi bukan karena lidah yang
meleset -- tidak lewat begitu saja. Banyak wartawan, anggota PWI
atau bukan, memberi reaksi: "Ah, boleh juga Pak Diah ini."
SSW selama ini menjadi soal peka. Suara resmi PWI menafsirkan
bahwa wartawan itu bukan buruh. Agus Sudono, Ketua FBSI
(Federasi Buruh Se-lndonesia), pernah menganjurkan tahun lalu
supaya basis FBSI dibentuk di tiap perusahaan suratkabar dan
media lainnya. Artinya, wartawan bergabung dalam Serikat Sekerja
di tempat kerja masing-masing, supaya bisa memperjuangkan
perbaikan nasibnya secara kolektif menghadapi majikan.
Suratkabar memang diterbitkan oleh perusahaan, di mana wartawan
nyatanya menjadi karyawan.
FBSI selalu menuntut diadakannya perjanjian kerja secara
kolektif, lazim disehut CLA (Collective Labozir Agreement) di
perusahaan. CLA itu selalu diperbaharui, sebagai hasil kompromi
antara SS dan pihak manajemen (majikan). Sudah banyak kelihatan
faedahnya.
Tapi CLA itu sukar dicapai di perusahaan media selama tiadanya
SS di tempat. PWI pada hakekatnya menolak diadakan SS untuk kaum
wartawan. Perusahaan media pun, tentu saja, tidak mengadakannya.
Dengan latarbelakang ini keterangan Diah tadi menjadi menarik.
Wartawan umumnya masih memperoleh penghasilan rendah. Di Ambon,
demikian Antara, Kaji wartawan hanya Rp 15.000 sebulan, malah
ada yang kurang dari jumlah itu. Sedangkan upah buruh kasar di
situ minimal Rp.700/hari atau Rp 21.000/bulan.
Pelanggaran kode etik jurnalistik justru sebagian besar
disebabkan oleh rendahnya pendapatan wartawan. Di luar ia
tergoda -- disuap atau memeras, sedang di dalam perusahaan
nasibnya tak terjamin. Kasus terakhir tentang tiadanya jaminan
itu terjadi di majalah Dialog yang bersaudara dengan majalah
Kartini. Pimpinan media itu sewenang-wenang memecat sejumlah
wartawannya, dengan alasan penerbitan Dialog dihentikan. Tapi
caranya mendadak dan kasar, tanpa jaminan pesangon yang wajar
pula. Para wartawan di situ dalam posisi lemah. Dalam kasus
seperti ini PWI tidak bisa berbuat banyak.
Ketua PWI Pusat, Harmoko, mengakui adanya tindakan
sewenang-wenang oleh pihak majikan pers. Tapi pembentukan SSW
sebagai jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan tetap
ditolaknya. Dengan SSW itu, katanya, akan timbul "kotak-kotak
wartawan sehingga ada kelas majikan dan kelas buruh."
Ada Tauke
Perbedaan 'majikan' dan 'buruh' sudah menjadi kenyataan
sesungguhnya antara sesama wartawan. Bahkan Adam Malik, sesepuh
wartawan, pekan lalu dalam suatu percakapan dengan beberapa
'buruh' pers di Bina Graha memakai istilah wartawan tauke.
"Banyak tokoh wartawan yang juga menjadi tauke," katanya.
Soalnya ialah apakah sang wartawan mendapat tauke yang baik.
Mereka yang bekerja di Sinar Harapan, misalnya, tidak mempunyai
alasan untuk mengeluh dalam soal kesejahteraan. Pemimpin Umum
H.G. Rorimpandey di harian yang beroplah besar itu mengatakan di
SH ada Yayasan dan Koperasi oleh dari untuk karyawan. "Malah
saya menjadi anggotanya," kata Rorimpandey. Di situ wartawan
jelas tergolong karyawan. "Di tempat kami," katanya lagi,
"wartawan itu juga majikan karena mereka diberi kesempatan
memegang saham. "
Tentu saja, tidak banyak seperti di tempat 'tauke' Rorimpandey.
SSW baginya tidak perlu, asalkan wartawan mengadakan perjanjian
kerja. Tapi justru dengan perjanjian kerja, benar juga Adam
Malik berkata: "Jangan membohongi diri -- wartawan itu adalah
buruh," meskipun ada yang menjadi tauke.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini