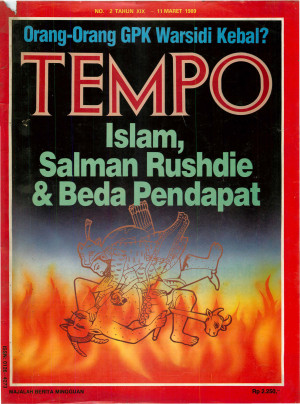ADA seorang mahasiswa yang bertanya, "Pak, apakah tulisan wartawan ini tidak melanggar kode etik pers?" Ia lalu memperlihatkan satu media massa yang memuat cerita panjang tentang Jusuf Randy di dalamnya. Jusuf si Raja Komputer di situ dituduh terlibat dalam beberapa perkara. Tanpa tedeng aling-aling, media itu juga menyebut identitas Sang Raja, lengkap dengan latar belakang keluarganya. Padahal, kata mahasiswa itu, Jusuf Randy belum tentu bersalah. Singkatnya, menampilkan lengkap identitas obyek berita yang belum divonis pengadilan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran asas praduga tak bersalah. Benarkah? Persoalan inilah yang dibahas panjang lebar pada "Diskusi Kode Etik Pers Dalam Pelaksanaannya" -- diselenggarakan atas kerja sama Majalah TEMPO dan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Jawa Barat. Menurut Sukarni Ilyas, redaktur TEMPO yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut, gaya tulisan seperti cerita Jusuf Randy sama sekali tak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Dikatakannya, pada tahun 1977 PWI pernah meneluarkan 10 Pedoman Penulisan Tentang Hukum PWI, yang antara lain berbunyi: ... pers dapat saja menyebut lengkap nama tersangka/tertuduh, jika hal itu demi kepentingan umum. Bagaimanapun juga, prinsip adil dan fair harus tetap diperhatikan. Maksudnya, pemberitaan harus dibuat berimbang, agar tidak sampai mempengaruhi jalannya persidangan. Masalahnya di sini, apakah seorang hakim bisa terpengaruh oleh pemberitaan yang memuat perkara yang sedang ditanganinya. Itulah soalnya. Sekali waktu, Hakim Agung Bismar Siregar pernah berucap, "Kalau hakim sampai terpengaruh, berarti hakimnya yang goblok." Lagi pula, tak pernah ada rumusan tegas dari PWI, kapan sebuah berita bisa dianggap telah menghakimi seseorang. Pendapat Bismar dibantah oleh bekas Ketua Mahkamah Agung Prof. Oemar Senoadji, yang bertindak sebagai pembahas dalam diskusi tersebut. Katanya, pemberitaan media massa sangat mungkin mempengaruhi putusan hakim. Ini pernah terjadi di tahun 1950-an. Ketika itu, seorang hakim begitu yakin bahwa tersangka yang diadilinya adalah tersangka palsu, alias bukan tertuduh yang sebenarnya. Tapi karena media massa begitu gencar memojokkan terdakwa, ditambah unjuk rasa sekelompok orang yang menuntut agar tersangka dihukum berat, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman maksimal. Untunglah, hakim di pengadilan tinggi -- karena perkara itu naik banding -- tak sampai terpengaruh. Ia memvonis terdakwa sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalaninya. Jadi, "Pada kenyataannya, saya melihat, pers bisa mempengaruhi putusan hakim," kata Oemar. Tentang penulisan identitas terdakwa, Oemar tidak keberatan, asalkan perkaranya sudah digelar di meja hijau. "Pengadilan itu kan sudah openbaar sifatnya. Apalagi kalau perkaranya sangat erat dengan kepentingan umum," tuturnya. Ternyata, masih banyak saja media yang menyamarkan identitas tersangka dalam pengadilan. Caranya, dengan menyingkat nama atau memuat foto terdakwa dengan mata tertutup. Padahal, tidak semua tersangka senang dengan gambar seperti itu. H.R. Dharsono -- bekas Pangdam Siliwangi -- misalnya, yang dituduh terlibat subversi. Atau Sirajuddin alias Pak De, tertuduh dalam pembunuhan Dice. Mereka, menurut Sukarni, akan lebih senang, "jika gambarnya dimuat dengan senyum mengembang, ketimbang dengan mata tertutup." Satu hal lagi yang penting, pers harus memberitakannya seimbang, sesuai dengan fakta. Artinya, selain suara jaksa, pers harus pula mengutip pembelaan terdakwa. Dan untuk menghindari asas praduga tak bersalah, "janganlah pers memberikan komentar," begitu Oemar menekankan. Lain halnya Dja'far Assegaf, Ketua Dewan Kehormatan PWI. Menurut dia, teknik penulisan berita telah jauh berkembang. Media massa kini tidak lagi hanya membeberkan berita-berita langsung, tapi juga dibumbui dengan opini. Apalagi bagi sebuah majalah yang terbit mingguan, misalnya. Untuk merangkai sebuah berita, mau tidak mau media itu harus menyelipkan opininya. Soal apakah sebuah berita melanggar asas praduga tak bersalah, atau dalam kata lain telah melakukan triol by the press, Dja'far Assegaf lalu merujuk pada banyak aturan pers yang belum jelas. Sialnya, kode etik pers yang sudah ada sekarang pun nyaris tak pernah dibaca lagi oleh sebagian besar wartawan. Pernah PWI melakukan penelitian tentang penghayatan kode etik pada sejumlah wartawan. Dan hasilnya sungguh mengecewakan. Hanya 15% wartawan yang hafal pasal-pasal kode etik. Yang benar-benar menghayati hanya 5%. Dan 80% sisanya hafal pun tidak. Etik Pers, menurut Assegaf, pada intinya menyiratkan sikap pers yang bebas dan bertanggung jawab. Hanya saja, hal itu tampaknya masih memerlukan penjelasan, agar ada keseragaman interpretasi. Wajar bila kini Dewan Pers menyusun penjabaran kode etik pers, yang hasilnya akan disiarkan secara teratur kepada semua jajaran media massa. Memang, istilah "bebas dan bertanggung jawab" yang populer itu sulit dicari batasannya. Tapi, menurut Oemar Senoadji, yang dimaksudkan adalah bertanggung jawab pada diri sendiri. Artinya, pers sendirilah yang menentukan, apakah sebuah berita atau foto layak dimuat atau tidak. Menurut Assegaf, kode etik tidak hanya berkaitan dengan asas praduga tak bersalah, tapi berkaitan pula dengan pornografi dan sadisme. Ia prihatin, karena masih banyak media yang menonjolkan dua hal tersebut, tanpa menimbang akibatnya pada pembaca. Misalnya saja, ada koran yang memuat sebuah berita dengan judul "Saya Masih Doyan Laki-Laki". Di banyak negara, mungkin berita seperti itu tak jadi masalah. Tapi di Indonesia? "Generasi macam apa yang akan lahir kalau disuguhi berita-berita seperti itu," kata Assegaf. Di pihak lain, Wakil Gubernur Jawa Barat, Suryatna Subrata, bicara tentang mutu berita. "Berita yang tidak obyektif akan membuat sumber-sumber berita menutup pintu pada wartawan," katanya, seperti memperingatkan. Pak Suryatna benar. Bahkan berita yang obyektif pun bisa saja membuat wartawan diboikot. Biasalah tuntutan lingkungan.Budi Kusumah, Hasan Syukur
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini