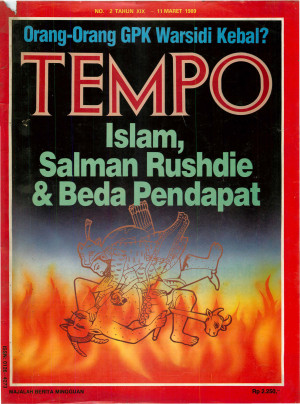LAGU "Gaudeamus igitur ... iuvenus dum sumus ..." bergema di ruang aula barat ITB (Institut Teknologi Bandung), Kamis pagi pekan lalu. Itulah yang mengandakan hari jadi ke-30 lembaga pendidikan tinggi teknologi yang prestisius ini. Upacara peringatan itu lalu disusul denan Pameran ilmiah dan festival kesenian, meski tak sesemarak perayaan tahun-tahun sebelumnya. Di balik upacara itu tersimpan keprihatinan, sekaligus impian. Warga ITB, seperti umumnya warga akademik di republik ini, prihatin karena tak berdaya menghadapi aktivitas penelitian dan pemberian beasiswa yang terus merosot sejak awal tahun 1980-an. Maklum, pemerintah terpaksa memotong sebagian anggaran bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, gara-gara ditohok oleh merosotnya harga minyak. Seperti halnya di perguruan tinggi negeri yang lain, usaha untuk memburu dana di luar pemerintah sudah ditempuh. Beberapa industri swasta sudah diajak kerja sama berdasarkan kontrak bersifat komersial. Dan sejumlah alumnusnya yang berhasil hidup makmur tak segan merogoh kocek untuk menggemukkan kas bekas almamater mereka. Semua itu belum bisa mengimbangi kemerosotan dana dari pemerintah. Situasi itu memang merepotkan, apalagi ditambah kenyataan kecilnya gaji dosen. "Bagaimana dosen-dosen itu bisa mengikuti perkembangan kalau gajinya hanya cukup untuk seminggu?" ujar Iskandar Alisahbana, bekas Rektor ITB yang kini lebih banyak bergerak di bidang bisnis. Dengan gaji seperti sekarang, terlalu berat bagi para dosen untuk membeli buku atau ikut konperensi ilmiah tingkat internasional. Lebih runyam lagi, kebanyakan industrialis masih terjerat dalam tradisi membeli lisensi. Alias masih berkutat di dunia perakitan, sehingga tak peduli pada temuan-temuan baru perguruan tinggi lokal, termasuk ITB. Alhasil, tak sedikit hasil karya ilmiah yang kemudian sekadar jadi penghias laboratorium dan pengisi halaman di jurnal-jurnal ilmiah. Untung, Bank Dunia ikut merasakan keprihatinan itu. Tahun lalu, lembaga keuangan dunia itu memberikan pinjaman Rp 280 juta kepada ITB, untuk membiayai 29 penelitian teknologi maju. Apakah pinjaman itu berlanjut atau tidak, tergantung kemampuan ITB menjual hasil penelitiannya kepada pemerintah dan swasta. Caranya? Rektor ITB Wiranto Arismunandar punya resep. "ITB harus putar haluan. Jangan menjadi menara gading tempat para profesor bersembunyi, menakutkan," katanya. "ITB harus sering menyapa masyarakat." Tanpa putar haluan, Arismunandar khawatir, jangan-jangan jerih payah orang ITB cuma menimbulkan krisis hubungan dengan masyarakat. Lho? Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang pesat. Alhasil, para akademisi ITB bisa makin tersuruk ke dalam dunianya sendiri. Apalagi kalau kegiatan akademik mereka tak klop dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pendekatan itulah, ITB harus melesat sebagai ujung tombak ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan Profesor Samaun Samadikun, alumnus ITB yang kondang sebagai jagoan mikroelektronika, memimpikan agar ITB bisa menjadi motor dari kelahiran semacam Lembah Silikon di AS, yang semula dipelopori oleh Universitas Stanford. Di sana, kini berkumpul para ahli dari berbagai raksasa industri yang hanya berkonsentrasi pada penelitian dan pengembangan mikroelektronika. Gagasan itu sebenarnya sudah dipraktekkan oleh Alisyahbana dan rekan-rekannya sejak tahun 1970. Dia mengacu pada Kawasan Ilmu (Science Park) yang dibangun oleh Universitas Singapura untuk menumbuhkan industri teknologi tinggi sebagai kelanjutan dari hasil-hasil yang dicapai oleh para dosen. Untuk itu, semasa menjadi rektor, Alisyahbana menerapkan rumus: 3 untuk kampus, 2 untuk ngobyek, 1 untuk keluarga. Benar atau tidaknya gagasan Alisyahbana dan Samadikun agaknya masih bisa diperdebatkan. Setidaknya oleh Dody Tisnaamidjaja, ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Katanya, "Sekarang, di seluruh dunia, perguruan tinggi bukan lagi pemimpin terdepan ilmu dan tenologi." Sebab, banyak lembaga pemerintah dan swasta yang sanggup meneliti dan mengembangkan ilmu dan teknologi serta penerapannya, yang tak mungkin dimiliki sebuah universitas. Nah, di sini Dody punya usul untuk menutup celah antara dunia universitas dan industri. Program konvergensi namanya. Yakni sebuah pola kerja sama berkesinambungan, bukan berdasarkan kepentingan sesaat, seperti yang sedang berjalan. Lembaga-lembaga penelitian nonuniversitas mengizinkan para mahasiswa pascasarjana memakai laboratorium mereka. Sedangkan para mahasiswa S1 bisa praktek di pabrik-pabrik. Usul Dody sudah terbukti keampuhannya di AS. Bahkan di sana, penelitian pesanan dari dunia industri dijadikan ukuran untuk menentukan kualifikasi seorang dosen. Sedangkan para mahasiswa S1 diberi tugas berpraktek langsung di dunia profesi yang akan ditempuh. Karena itu, dunia industri AS melaju lebih cepat ketimbang di Eropa. Dulu, sebelum menyadari ketertinggalannya, dunia universitas di Eropa memegang teguh tradisi memisahkan diri dari dunia industri. Maka, temuan-temuan baru para peneliti di kampus harus melewati proses yang lebih rumit dan lama sebelum sampai ke tangan konsumen. Para lulusannya pun juga jadi lebih canggung ketika menapak keluar kampus. Hanya saja, agar program konvergensi tak merepotkan dunia industri, kualitas pendidikan di kampus-kampus tentu harus dibenahi sejak tingkat pertama. Tak hanya dalam soal pembaruan kurikulum, tapi juga kualitas dosen, yang merupakan persoalan paling merunyamkan. Bayangkan, sampai sekarang sebagian besar dosen bagi S1 cuma berijazah S1. Padahal, idealnya, harus S1 plus. "Jumlah dosen yang berijazah S2 dan S3 tak lebih dari 50%," kata Doddy.Praginanto, Tommy Tamtomo (Jakarta), Sigit Haryoto (Bandung)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini