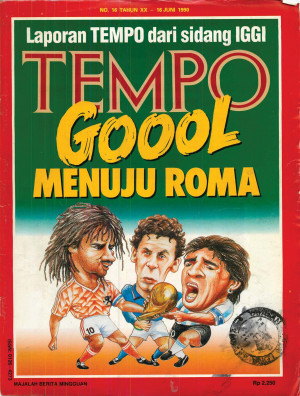PERUSAHAAN kok (shuttlecock) tertua "Garuda", PT The First Garuda Shuttlecock Industry (FGSI) kini diperebutkan ahli waris pendirinya, mendiang Liem Khe Siang. Anak tertua Khe Siang, Liem Hok Seng, pekan-pekan ini menggugat pemilik dan Presiden Direktur PT FGSI, Nyonya Liem Kiem Teng, dan Liem Khe Bie (Budiono), di Pengadilan Negeri Tegal, Jawa Tengah. Hok Seng, 52 tahun, menuding kedua adik kandung ayahnya itu telah menguasai PT FGSI tanpa hak. Tak tanggung-tanggung Hok Seng juga menggugat ibu kandungnya sendiri beserta dua adik kandungnya, serta tiga familinya, karena mereka berpihak pada Kiem Teng dan Budiono. Menurut Hok Seng, pada 1939, ayahnya bersama dua kakaknya, Nyonya Kiem He dan Khe Oen, mendirikan PT FGSI. Perusahaan itu kemudian berkembang pesat, bahkan belakangan mampu memproduksi 11 merek kok Garuda dan mengekspor ke mancanegara. Untuk ekspor digunakan bahan kok dari bulu itik, sedangkan untuk pasar dalam negeri dipakai bulu burung impor dari Taiwan. Kini, kata Hok Seng, aset PT FGSI sekitar Rp 8 milyar. Tapi pada 1957, sewaktu Khe Siang sakit keras, kata Hok Seng, terjadi pengambilalihan perusahaan itu. "Ayah dipaksa Kiem Teng dan Budiono menjual pabrik," tuturnya. Maka, lahirlah akta jual beli tertanggal 23 Juli 1960, melalui Notaris Lie Kwee Nio di Bandung. Pada Januari 1961, Khe Siang meninggal dunia dalam usia 48 tahun. Sejak itu perusahaan itu menjadi ajang sengketa antarkeluarga. Anak kandung Kiem He, J.A. Setyoso, misalnya, mengungkit-ungkit riwayat pengalihan pabrik tadi. Jual-beli itu sebenarnya cuma etok-etokan (pura-pura) saja," ujar Setyo- so. Maksudnya tak lain agar PT FGSI tetap berjalan. Anehnya, pada 1970, dicapai kesepakatan antara Setyoso dan Kiem Teng, Budiono, serta Nyonya Khe Siang bahwa mereka masing-masing memiliki seperempat saham PT FGSI. Mereka pun sepakat memberi Setyoso bagian berupa uang tunai Rp 3 juta, mesin bubut, plus biaya pemindahan listrik. Sebaliknya, Setyoso -- yang kemudian mendirikan pabrik kok Gajah Mada -- tak boleh menggunakan merek Garuda. Toh pertikaian belum selesai. Pada 1980, giliran Khe Oen, pendiri yang haknya dikesampingkan sama sekali, menuntut. Tapi sampai tingkat kasasi (1986), gugatannya dipatahkan pengadilan. Pada 1983 giliran Kiem Teng dan Budiono memperkarakan Setyoso. Itu gara-gara Setyoso melanggar perjanjian 1970 karena menggunakan merek Garuda Star. Tapi pada 1989, pengadilan memvonis bebas Styoso. Sebab itu, ia balik menggugat kedua pengadu tadi karena telah mencabut perjanjian 1970 secara sepihak. Setyoso menang, Kiem Teng-Budiono naik banding. Belum tuntas soal perjanjian 1970, kini Hok Seng menghunus kapak perang. Ia merasa lebih berhak menguasai PT FGSI daripada Kiem Teng-Budiono. Sebaliknya, Kiem Teng dan Budiono tetap bertahan bahwa hak kepmilikan Khe Siang atas PT FGSI sudah dijual kepadanya pada 1960 itu. Jadi, "Perusahaan ini bukan lagi harta peninggalan Khe Siang, yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya," kata mereka. Herannya, ibu kandung Hok Seng, Lie Swie Lan Nio, membenarkan dalih itu. Memang, katanya, mendiang suaminya masih meninggalkan warisan berupa perabot rumah tangga dan piutang Rp 700 ribu. "Semua barang itu masih kami gunakan, tapi piutang itu sudah habis untuk keperluan hidup," ucap Swie Lan. Lain lagi komentar Setyoso, yang menganggap gugatan terhadap dirinya itu salah alamat. "Seharusnya gugatan itu ditujukan kepada Kiem Teng, Budiono, dan ibu penggugat," katanya. Sebab, haknya sendiri (seperempat bagian) di PT FGSI sudah diambilnya -- meskipun belum seluruhnya. Apa pun putusan pengadilan nanti, perkara ini agaknya bisa menjadi peringatan bagi para konglomerat bahwa harta melimpah itu belum tentu akan membuat kedamaian bagi para ahli waris kelak. Happy S., Bandelan A. (Tegal)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini