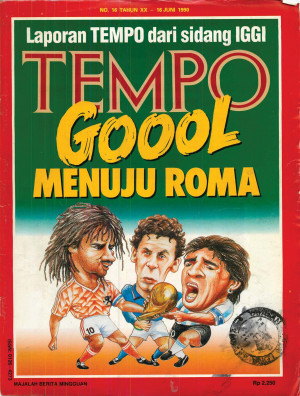SAMPAI seberapa keras angin demokratisasi yang kini bertiup di seantero dunia menyumbang perubahan rezim di Burma? Secara tradisional Burma sangat xenofobia (antiasing) karena sejarah. Di abad ke-17 dan 18 negeri ini sangat agresif dan Muangthai, juga India, jadi korban utamanya. Di zaman itu raja-raja Burma berambisi atau bermimpi menjadi Bodhisatva. Karena itu, Muangthai, yang memiliki beberapa pusaka Budha, dan India, tanah lahir sang Budha, mesti di bawah kekuasaan mereka. Muangthai atau Bangkok dapat mengelakkan agresi Burma. Perhatian pun berbelok menuju India, yang kala itu di bawah kekuasaan Inggris. Pada 1823 tentara Burma menyerbu India Timur (Asam). Celaka. Inggris membalas serangan ini dengan mengirimkan ekspedisi laut menduduki Burma. Serangan balasan ini tak pernah diperhitungkan oleh raja-raja Burma. Sejak itu kerajaan Seribu Pagoda ini kocar-kacir. Dalam waktu tiga tahun, dari arah selatan, perang Anglo-Burma menyebabkan jatuhnya daerah demi daerah kaya Burma ke tangan Inggris. Ditambah dengan terisolasinya cakrawala pemikiran para raja dan elite politik Burma sebagai akibat sikap narsistis seperti yang tercermin dalam cita-cita menjadi Bodhisatva atau Raja Budis Universal atau Budha duniawi, pada akhirnya itu semua mempengaruhi masalah suksesi. Pergantian raja di Burma tidak dapat diselesaikan. Memang, di kebanyakan kerajaan Asia -- dari kekaisaran otoman di Turki sampai Mataram di Jawa -- masalah suksesi ini pelik dan sering menyebabkan runtuhnya kerajaan. Pun di Eropa, sebagaimana terjadi dengan Polandia. Karena selalu kacaunya suksesi di Polandia, akhirnya masuk para tetangga yang kuat Rusia, Prusia, dan Austria -- membagi daerah koloni hingga akhir Perang Dunia I. Kembali ke Burma, di abad ke-19 putra-putra raja yang banyak sekali itu -- karena ada sistem poligami -- saling membunuh untuk merebut tahta. Dan pembunuhan itu sungguh mengerikan: karena mereka yang berdarah raja tak boleh dibunuh oleh manusia, para putra raja yang kalah diserahkan pada kaki-kaki gajah. Tradisi ini yang dianggap di luar peri kemanusiaan menambah alasan bagi Inggris untuk mencaplok seluruh Burma. Masuknya kaki kolonialisme di Burma agak berbeda dengan jatuhnya Asia Tenggara pada umumnya. Penjajahan di Burma dilakukan melalui perang, dan Burma dapat dikatakan diduduki secara militer. Pengalaman seperti itu mungkin hanya dialami oleh Aceh, yang memaksa Belanda berperang puluhan tahun - 1870-1910. Mungkin juga sama dengan yang terjadi atas Banten, kerajaan yang di masa kolonial selalu resah. Kolonial Inggris lalu menghapus kerajaan Burma, dengan cara membuang keluarga raja ke India (Calcutta). Elite bangsawan India di Burma pun disingkirkan sama sekali dari pemerintahan Burma. Sebaliknya, Inggris membiarkan kelas menengah India (misal- nya kaum pengusaha, pedagang, dan tuan tanah) beremigrasi secara besar-besaran ke Burma -- negeri ini dijadikan salah satu provinsi dari India. Maka tanah-tanah petani Burma diambil alih oleh orang-orang asing itu. Akibatnya, kemiskinan pun meruyak di antara rakyat Burma. Ini bisa terjadi karena Inggris, tanpa mempertimbangkan "hukum adat" -- seperti juga dilakukan Belanda di Indonesia -- memberlakukan hukum Inggris. Singkat kata, Burma merasakan kolonialisme sebagai pengalaman yang sangat kasar. Pengalaman kolonial itulah kemudian membentuk sikap xenofobia Burma. Oleh para sejarawan, kerajaan Burma memang dianggap berkebudayaan inward-looking (melihat ke dalam). Berbeda misalnya dengan Muangthai. Dalam menghadapi Barat pada akhir abad ke-18 Muangthai memindahkan ibu kota ke Bangkok di pesisir. Sementara itu, Burma tetap mempertahankan di pedalaman -- seperti halnya Kerajaan Mataram di Jawa. Yang membangun Yangon (nama lama Rangoon) adalah Inggris. Baru pada 1886, kota pantai ini diresmikan sebagai ibu kota Burma. Bila setelah negeri ini merdeka elite politiknya tetap empertahankan Rangoon sebagai ibu kota, juga rezim militernya Ne Win, menandakan bahwa elite politik telah memiliki sedikit pengertian tentang pentingnya hubungan internasional dikembalikannya nama Yangon untuk Rangoon di masa rezim militer Ne Win menunjukkan bahwa penyakit xenofobia di Burma kambuh kembali. Untunglah, lapisan bawah rupanya lebih membuka diri terhadap dunia internasional. Aung San SUI Kyi, misalnya, meski bersuamikan seorang Inggris, tetap populer. Bahkan partainya, Liga Nasional Demokrasi, berani minta bantuan Amerika Serikat -- meski tak dipenuhi. Menangnya Suu Kyi tampaknya menunjukkan bahwa mereka yang berpihak pada pembaruan, yang berjalan searah dengan bertiupnya angin demokrasi internasional, yang bakal di atas angin. Dan ini tak cuma terjadi di dunia politik. Pun di bidang ekonomi. Jepang, yang memiliki salah satu sistem ekonomi keuangan nasional yang paling kuat memainkan peran di dunia ekonomi internasional, akhirnya harus menyesuaikan juga dengan permainan internasional, yang diisyaratkan dengan merosotnya saham dan yen Jepang di bursa uang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini