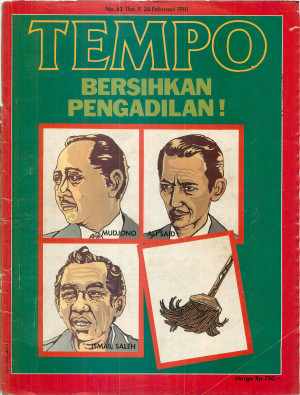TUJUAN penertiban dalam tubuh badan-badan peradilan adalah
agar kekuasaan kehakiman benar-benar ampuh dalam menegakkan
hukum dan memberi rasa keadilan pada masyarakat.
(Pidato Presiden pada pengambilan sumpah Ketua Mahkamah Agung
RI).
ALI Said, Ismail Saleh, Mudjono apakah ke-3 nama ini yang
disebut tiga pendekar penegak hukum Pemunculan ketiga jenderal
lulusan PTHM (Perguruan Tinggi Hukum Militer) tersebut, yang
dilantik 18 Februari lalu, tampaknya memang dalam usaha
penertiban dunia peradilan, yang belakangan ini berjalan dengan
cukup sambutan.
Orang umumnya memang memandang lembaga peradilan dengan
mencemooh. Untuk mengambil contoh kecil saja: martabat hakim di
mata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia sudah
sangat merosot. Ini tercermin dari pengumpulan pendapat, atau
poll menjelang diskusi di FH-UI tentang kedudukan hakim akhir
pekan lalu.
Mungkin karena Opstib baru saja mengumumkan kebejatan praktek
beberapa hakim senior di Pengadilan Negeri akarta Pusat, 83%
dari 167 mahasiswa yang ikut dalam poll itu, menyatakan tak
berminat menjadi hakim. Alasannya, di samping merasa tak ada
panggilan, ada yang terus terang khawatir profesi hakim tak
dapat menyejahterakan kehidupan mereka. Yang terang, kesan yang
dibangun para hakim selama ini cukup jelek di mata mahasiswa
kurang berperan dalam penegakan hukum.
Tak bisa dielakkan, kesan ada kekuatan ekstrajustisial yang
mempengaruhi kekuasaan hakim, sangat mendalam. Baik pengaruh
dari penguasa maupun dari sebuah benda yang bernama uang.
Adnan Buyung Nasution, pembicara dalam diskusi yang meriah itu
(di samping Hakim Tinggi Bismar Siregar), merumuskan dalam
kata-kata ketidakpercayaan mahasiswa akan lembaga yang sekarang:
"Dengan sistem hukum dan politik sekarang ini," kata Buyung,
"betapa pun hebatnya tiga pendekar hukum, tidak akan membawa
angin baru."
Mudjono, Ketua Mahkamah Agung yang baru, menurut Buyung, memang
hebat. Mulai dari cara bekerjanya ("betah di kantor sampai larut
malam"), kejujurannya ("boleh dibilang lugu") sampai dengan
ketegasannya ("berani bcrsikap keras kepada hakim senior"). Kata
Buyung, semua itu tak usah diragukan lagi. Tapi sistem hubungan
pemerintah-pengadilan atau judikatif-eksekutif "hanya membuat
Mudjono seperti dikorbankan dalam medan yang bisa
menghancurkannya sendiri."
Advokat dan juga Direktur LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta
itu seperti hendak mengembalikan urusan pada persoalan lama.
Kedudukan hakim di sini belum pas benar: Mahkamah Agung hanya
mengurus hakim-hakimnya dari segi teknis justisial. Selebihnya
urusan administrasi, penempatan personil dan yang penting: gaji
-- diurus atau dikuasai eksekutif, Departemen Kehakiman. Atau
dengan kalimat klise, kepalanya ibarat berada di Mahkamah Agung,
perutnya masih diurus Departemen Kehakiman.
Karena masalah perut begitu penting, kata Buyung, maka dalam
sistem yang berlaku sekarang ini hakim "lebih merasa sebagai
pejabat negara, ambtenaar, daripada menjadi hakim yang otonom."
Akibat lebih jauh, katanya, "bisa kita lihat selama ini: jaksa
dan hakim yang satna-sama pegawai negeri, sering terlihar
memanipulasi undang-undang dan peraturan -- apalagi bila perkara
sudah menyangkut kepentingan pemerintah."
Apa yang dikemukakan Buyung, sebenarnyalah, bukan hal baru --
meskipun ia dapat saja mengemukakan contoh-contoh baru. Soal itu
sudah menjadi perdebatan sejak 10 tahun terakhir ini. Yaitu
sejak lahirnya Undang-undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman
(UU No. 14/1970. Ketentuan baru, yang diharapkan mendudukkan
para hakim pada tempatnya yang terpisah dari deretan pegawai
negeri, dinilai sangat mengecewakan. Beberapa yang menyangkut
kedudukan hakim -- seperti organisasi, administrasi dan keuangan
tadi -- memang masih diatur di bawah kekuasaan eksekutif.
Meskipun dalam peraturan yang sama ditegaskan adanya peradilan
yang bebas dari campur tangan badan atau instansi mana pun.
Sejak itu, hingga kini, masih dipertanyakan: adakah
undang-undang tentang kekuasaan peradilan yang bebas itu juga
melepaskan tekanan terhadap hakim? Memang tidak semua hakim
mudah tunduk kepada tekanan dari luar. Meski, tak bisa tidak,
lebih banyak sikap mereka yang terbentuk oleh hirarki
kepegawaian loyal kepada si pemberi gaji.
Pada mulanya, tahun-tahun pertama berlakunya UU yang mengatur
kedudukan hakim, bekas Menteri Kehakiman Lukman Wiriadinata (70
tahun) pernah mengatakan: "Harus dipisahkan antara kebebasan
personil dan institusional". Kebebasan institusional, kata
pengacara tua ini, boleh merupakan langkah awal sebelum muncul
ketentuan bagi kekuasaan judikatif mengurus personilnya sendiri.
Banyak hakim yang merasa telah mengenyam kebebasan institusional
itu. Namun tak kurang pula yang mengeluh. Misalnya, dalam kasus
Pluit, ada yang merasa terpaksa membebaskan Endang Wijaya dari
tahanan karena harus memenuhi "permintaan" instansi lain.
Sedangkan seorang anggota DPR, V.B. da Costa, tak kurang-kurang
pula mengetengahkan beberapa bukti -- kelepaksaan atau bukan --
bahwa badan pengadilan tertinggi negara memenuhi permintaan
pihak eksekutif yang dianggapnya melanggar kebebasan
institusional pengadilan. Da Costa malah sampai mencerca
Mahkamah Agung, dengan mengatakannya telah berpraktek anti
justitieel dan bahkan curang.
SERANGAN yang agak terbuka ialah ketika Endang Wijaya, yang oleh
pengadilan dilepaskan dari tahanan, tiba-tiba di tangkap dan
ditahan Laksusda Jaya. Kalangan hukum serentak menuduh Laksus
"mencampuri kewenangan pengadilan". Seno Adji ketika itu
menjawab campur tangan tersebut dengan tak kurang pedasnya:
"Bahkan Presiden saja tak pernah mengungkit-ungkit putusan
pengadilan".
Sementara itu kebebasan personil, yang belum juga memperoleh
bentuk, sudah lama tak jadi pembicaraan -- sebelum Buyung
Nasution bicara minggu lalu. Hingga 10 tahun berlalu, peraturan
tersendiri tentang gaji dan tunjangan hakim, masih merupakan
janji undang-undang. Begitu pula kebebasan personil, setelah
institusional, seperti diharapkan orang macam Mr. Lukman,
rupanya macet.
Adnan Buyung Nasution -- seperti banyak yang lain -- ingin
pemisahan mutlak antara kekuasaan badan eksekutif dan judikatif.
"Mengapa tidak menyerahkan segala macam urusan gaji,
pengangkatan dan penempatan hakhn sepenuhnya kepada Mahkamah
Agung?" katanya.
Namun Presiden Soeharto, seperti sambutannya dalam upacara
pengambilan sumpah Ketua Mahkamah Agung dan para Hakim Agung
yang baru, pekan lalu masih belum menyinggung soal pemisahan
kekuasaan. Yang harus dikembangkan, kata Presiden, justru
kerjasama. "Tentu saja," sambung Presiden, "dalam mengembangkan
kerjasama tadi, kedua-duanya harus teguh menjalankan wewenang
dan tugas masing-masing."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini