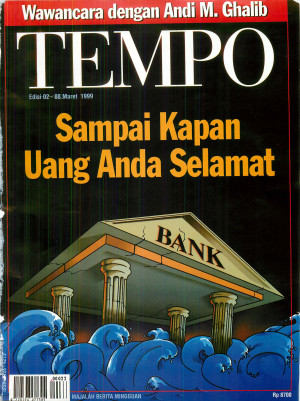AKSI unjuk rasa kini tak lengkap tanpa sidang pengadilan. Hal seperti ini sudah bisa diperkirakan, terutama sejak Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diberlakukan. Sejak Lebaran Februari silam, puluhan mahasiswa yang berdemonstrasi digiring ke meja hijau. Mereka dihukum denda masing-masing sekitar Rp 2.000, berdasarkan Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang larangan membuat keramaian di tempat umum tanpa izin polisi.
Pada 10 Februari lalu, misalnya, 51 mahasiswa divonis denda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka dianggap bersalah karena melakukan pawai sehari sebelumnya tanpa memberi tahu polisi. Waktu itu, bersama dengan mahasiswa lainnya, mereka berunjuk rasa di Jembatan Semanggi, Jakarta. Mereka menuntut pemberantasan Soehartoisme, pertanggungjawaban utang luar negeri, dan pengusutan tragedi Semanggi.
Kemudian, pada Jumat, 26 Februari, 47 mahasiswa juga divonis denda di pengadilan yang sama. Setelah itu, Senin pekan lalu, vonis denda pun ditimpakan pada 46 mahasiswa yang sebelumnya dianggap melakukan arak-arakan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ke Universitas Pancasila.
Dan pada Jumat pekan lalu, 17 mahasiswa yang ditangkap petugas keamanan dalam aksi di dekat Tugu Proklamasi dikenai vonis serupa. Sebelumnya, mereka menuntut pemerintahan transisi karena pemerintahan Presiden B.J. Habibie dianggap gagal. Aksi ini berbuntut insiden berdarah dan ''penyerangan" terhadap kampus Akademi Bahasa Asing-Akademi Bisnis Indonesia (ABA-ABI), yang terletak di kawasan Matraman, Jakarta, oleh aparat keamanan.
Di persidangan, para mahasiswa sepertinya tak hendak mengakui peradilan. Dalam pengadilan terhadap 47 mahasiswa, misalnya, para tertuduh tampak enggan menyimak vonis hakim. Bahkan 46 mahasiswa menutup mulutnya dengan plester. Mereka mengenakan kaus putih dengan berbagai tulisan bernada protes. Menurut mahasiswa, aparat keamananlah yang sewenang-wenang menangkap dan menahan mereka, padahal mereka sudah membubarkan diri.
Sementara itu, Daniel Panjaitan, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang membela beberapa mahasiswa, berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana pada peradilan itu tidak tepat. ''Bila penyampaian pendapat tak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, sanksinya kegiatan itu dibubarkan, bukannya dipidana. Lagi pula, Pasal 510 KUHP yang bersifat umum tak bisa digunakan untuk penyampaian pendapat," katanya.
Tanpa ragu, kepolisian justru menyatakan bahwa tindakan mereka sudah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. ''Mereka melakukan unjuk rasa tak sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena tak memberitahukannya lebih dulu kepada kami. Kalaupun tindakan kami dianggap represif, selama dilandasi undang-undang, ya, legal dan sah," kata Kepala Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Metro Jakarta, Kolonel Polisi Alex Bambang Rihatmojo.
Kalau demikian caranya menegakkan hukum, bukan mustahil kelak polisi hanya akan sibuk memukuli mahasiswa lalu menggiring mereka ke meja hijau. Meski vonisnya cuma denda Rp 2.000, fenomena itu mencuatkan problem hukum yang serius. Dari gebuk dan denda, tinggal satu tahap lagi untuk memidanakan aksi unjuk rasa, yang akhirnya menimbulkan stigma pidana. Itulah pola lama yang cenderung mengkriminalkan perbedaan pendapat dan menindas aksi unjuk rasa. Kalau pola keras ini dipertahankan, besar kemungkinan aksi protes justru akan meningkat. Kelak, bukan hanya reputasi Indonesia di bidang hak asasi manusia semakin tercela, tapi kepercayaan investor asing juga tak kunjung pulih. Singkat kata, dampak ekonomi dan politiknya bisa sangat memberatkan kita.
Dulu, para pengamat demokrasi menganggap bahwa kebebasan berpendapat tak boleh dikekang. Sebaliknya, tindakan aparat yang sewenang-wenanglah?terhadap demon-stran?yang mesti diatur. Pendapat mereka itu merujuk pada kasus penembakan di Universitas Trisakti dan tragedi berdarah Semanggi.
Ternyata peristiwa serupa terulang pada insiden demonstrasi di dekat Tugu Proklamasi, Jakarta. Pada Kamis pekan lalu, para demonstran bukan hanya digebuk oleh aparat, tapi juga dikejar-kejar sampai ke dalam kampus ABA-ABI. Akibatnya, kampus itu rusak dan lima mahasiswa luka parah. Sebanyak 33 mahasiswa ditangkap, 17 orang di antaranya sudah divonis denda, dan selebihnya masih ditahan polisi, dengan tuduhan menghasut massa dan menyerang petugas.
Masalahnya kini, mengapa kekerasan terhadap mahasiswa harus dipertahankan. Sebaliknya, polisi bersikap ''lepas tangan" terhadap massa yang mengamuk?di Ambon, misalnya. Kalau strategi seperti ini berlanjut, bukan mustahil nanti secara de facto polisi hanya menangani aksi mahasiswa, pencuri ayam, dan penjahat narkotik, sedangkan anggota Keamanan Rakyat (Kamra) diberi tugas menangani amuk massa. Pembagian tugas seperti ini akan menyenangkan bagi polisi, tentu saja, tapi sama sekali tidak menjawab masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Paling tidak, sama sekali tidak akan mengangkat citra polisi, yang pada April 1999 direncanakan mandiri, keluar dari ''payung ABRI."
Happy Sulistyadi, Hardy R. Hermawan, dan Iwan Setiawan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini