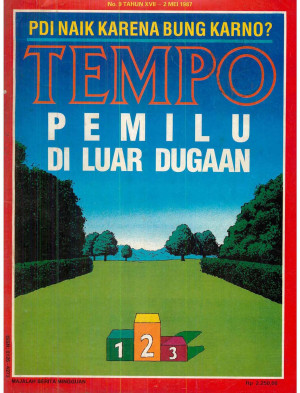LIMA tahun sekali, mereka mencari rakyat. Mereka perlu. Datang dengan mobil atau pesawat terbang, di udara panas dan gerah, ke pelbagai pelosok, mereka melakukan hal-hal yang selama ini hampir tak pernah mereka lakukan: bersuara keras di depan publik, menyanyi di depan publik, bertepuk-tepuk, berjoget, melakukan banyak hal yang tak biasa mereka kerjakan. Tujuan: menarik perhatian. Menarik hati. Meminta. Dan rakyat itu - atau khalayak ramai itu - akhirnya mulai tahu: orang-orang nun jauh di atas sana ternyata bisa membutuhkan simpati orang-orang jelata. Proyek-proyek pembangunan berturutturut dibuka. Hak-hak rakyat didengungkan lagi. Hadirin kadang boleh bertanya tentang apa sa1a, termasuk soal monopoli ataupun Porkas, meskipun tak selalu dijawab demikian jelas. Dan anak-anak muda boleh ngebut dan jungkir balik dan menyatakan apa yang mereka sukai di atas motor dengan cara yang bising di jalan-jalan tanpa helm, bahkan dilindungi polisi, yang entah dengan keajaiban apa bisa mengatur lalu lintas tanpa macet total, dengan sabar. Tak gampang untuk tak melihat keluarbiasaan itu. Para menteri, tokoh partai, pejabat, birokrat, aparat, berpencar menemui rakyat. Dan sang rakyat, semula sebuah abstraksi, tiba-tiba muncul dengan pelbagai tingkah, berjalan atau cuma berdiri, mengacungkan jari atau bengong, berseru ataupun membisu. Mereka bukan lagi cuma data di kantor Biro Pusat Statistik. Memang, pemilu di Indonesia tak bisa diharapkan menghasilkan perubahan yang berarti dan mencengangkan. Ada suara yang dibeli secara langsung maupun tak langsung - dengan uang ataupun kedudukan. Ada peserta-peserta rapat umum yang memperoleh Rp 5.000 seorang, di samping kaus gratis. Ada banyak sekali hura-hura, dan kampanye menjadi sebuah karnaval, dan sedikit sekali orang memperhatikan program apa dari Golkar atau dari PPP atau dari PDI. Bahkan siapa kelak wakil mereka di DPR, bagaimana mutunya sebagai wakil, mungkin tak ada yang peduli. Tapi lima tahun sekali, setidaknya, orang-orang penting pada menatap rakyat dengan sedikit lebih cermat. Dan seluruh Indonesia pun dipertautkan lagi. Pemilu memang makan begitu banyak ongkos, resmi ataupun tak resmi. Tapi ternyata - setidaknya di tahun 1987 - ia bukan suatu upacara yang sia-sia. Ada orang-orang yang tak memilih, atau sengaja membuat kartu suaranya tak berlaku, karena tak berharap akan ada ang berubah setelah hasil diumumkan nanti. Tapi ada juga seperti tampak pada anak-anak muda yang dengan gegap gempita ikut pawai PDI, seperti kelihatan pada orang-orang PPP di Aceh, yang tetap mengacungkan jari satu biarpun pada rombongan pawai Golkar yang setengahnya tak peduli tentang hasil. Bagi mereka pemilu adalah kesempatan menyatakan diri, memaklumkan sikap, ke dalam kancah politik nasional. Dalam suatu momen yang agaknya jarang terjadi, mereka seakan-akan secara bergelora merasakan, ke ulu hati, bahwa Indonesia - Indonesia yang besar ini - adalah bagian hidup mereka. Dalam momen itulah tanah air seolah-olah dipertautkan lagi, justru di dalam persaingan politik. Jakarta lebih dekat ke segala penjuru. Sebaliknya, tiap penjuru jadi lebih terdengar di Jakarta. Perbedaan tetap perbedaan, tetapi pada saat hal itu diakui sebagai sesuatu yang sah, dalam suatu kontes yang tak dibikin-bikin, seluruh peristiwa justru menggarisbawahi kenyataan yang ajaib ini:kenyataan tentang kesatuan kita, republik kita, kenangan kolektif kita. Orang bisa memilih dengan alasan apa saja - dan tiap alasan layak menimbulkan renungan slapa saJa. Saya kenal seorang Ibu tukang pijat yang tetap dengan yakin memiiih Golkar, biarpun hampir semua tetangganya memilih PDI ataupun PPP. "Karena saya datang dari desa, dari Sukorejo, karena di sana kami tidak lagi makan gaplek dan jalan-jaian jadi bagus dan di dekat kami dibangun bendungan," begitu alasannya. Bagi seorang intelektual kota yang 700 km jauhnya dari desa seperti itu, seorang intelektual yang lazimnya ragu benarkah rakyat kecil selama ini sccara yakin memilih Golkar kalimat Si Ibu Pemijat bisa merupakan konfrontasi pertamanya dengan rakyat. Saya juga dengar scorang pemuda berkampanye untuk PDI, karena baginya PDI - dengan bendera merah bergambar banteng, dengan posisinya bukan sebagai partai yang berkuasa - memberikan getar dan clan kejuangan, "bukan bonus, bukan duit, bukan materi," katanya, "yang kami sudah punya." Bagi seorang pejabat yang cuma bisa membujuk dengan cek dan proyek, yang mengira semua orang seperti dirinya yakni loyal karena boleh royal - pernyataan si anak muda bisa merupakan benturan pertamanya dengan idealisme. Juga alasan pemilih PPP ini: "Pemilu bukanlah pesta dengan sajian seekor binatang korban," katanya. Ia memilih PPP agar tak ada kelompok yang punah sementara kemenangan dirayakan. Sebab, betapapun ruwet pimpinannya, "kelompok" seperti PPP tetap masih bagian dari kenyataan sosial Indonesia. Dan demokrasi, kata orang, hanya bisa dimulai dengan mengakui kenyataan seperti itu. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini