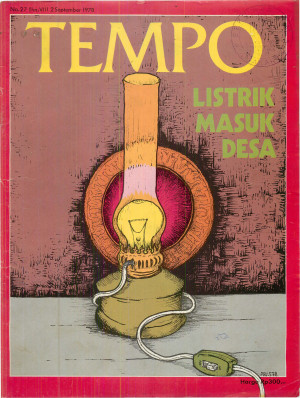TIGA tahun setelah perang Vietnam selesai, kehadiran Amerika
Serikat di Asia Tenggara menimbulkan tanda tanya yang belum
sepenuhnya dijawab oleh pemerintahan Carter.
Keadaannya hampir-hampir sama dengan situasi setelah perang
dunia kedua. Amerika, yang dengan offensif tentaranya mampu
menguasai Asia Tenggara, toh memilih Jepang sebagai sasarannya.
Negara-negara Asia Tenggara, dengan perkecualian Pilipina,
diserahkan kembali kepada negara-negara kolonial Eropah
sekutunya. Ketika Amerika memperluas pengaruhnya di Asia
Tenggara, tahun 1950an dan 1960an, kehadirannya ditanggapi
dengan sikap ambivalen, bahkan banyak yang mencurigainya.
Walaupun mengalami "trauma Vietnam", sikap seperti di atas
tampaknya-tidak akan terulang. Amerika sekarang tidak hanya
terikat oleh peranan globalnya, tapi juga oleh modal yang telah
ditanamnya di negara-negara Asia Tenggara. Dengan proteksinya
terhadap kepulauan Palau -- yang berbatasan dengan Morotai --
Amerika bahkan sudah memberikan tanda-tanda kehadiran yang aktif
secara militer. Dengan demikian, peran Jepang atau Australia
tidak bisa menjadi versi baru dari peran negara kolonial Eropah
setelah perang dunia kedua.
Tapi sikap Amerika terhadap Asia Tenggara sekarang dalam banyak
hal mencerminkan pola perumusan kebijaksanaan dari pemerintahan
Carter. Dengan kebijaksanaan politik luar negeri yang dikuasai
grup Trilateral, tujuan utama Amerika diarahkan pada
negara-negara industri di Eropa Barat, Amerika Utara dan Jepang.
Ketiga kelompok ini disebut Trilateral, suatu grup yang diilhami
oleh Presiden Chase Manhattan Bank, David Rockefcller, dan
dipimpin Zbigniew Brzezinski, sekarang Ketua Dewan Keamanan
Nasional AS dan penasehat politik utama Presiden Carter.
Gagasan Trilateral ini didukung oleh banyak kaum intelektuil
Amerika, seperti Samuel Huntington, Daniel Bell dan senator
Daniel Patrick Moynihan. Pandangan mereka didasarkan pada
keyakinan bahwa terdapat batas-batas dalam usaha mencapai suatu
welfare state (negara kesejahteraan) di negara industri. Jika
program-program "negara kesejahteraan" dilanjutkan, maka
negara-negara industri akan mengalami krisis berat. Karena itu,
diperlukan kerjasama Trilateral untuk merundingkan kebijaksanaan
perekonomian bersama.
Di AS, gagasan ini merupakan reaksi terhadap usaha-usaha ke arah
"negara kesejahteraan" yang dipelopori oleh sayap liberal dari
Partai Demokrat, seperti senator Edward Kennedy dan almarhum
Hurbert Humphrey.
Dalam kebijaksanaan luar negeri, titik berat pada garis
Trilateral ini dijalankan dengan tekun oleh Menlu Cyrus Vance
dan Brzezinski. Akibatnya, wilayah-wilayah dunia yang lain,
seperti Asia Tenggara, tidak memperoleh prioritas penting. Di
kalangan anggota Kongres, masalah Asia Tenggara juga tidak
mendapat perhatian utama.
Dengan masa jabatan hanya dua tahun, maka anggota-anggota
Kongres tidak mau terlibat dalam isyu-isyu yang bisa menyebabkan
mereka tidak terpilih lagi. Isyu Asia Tenggara, yang
mengingatkan para pemilih AS pada Vietnam, masih tetap merupakan
isyu yang menimbulkan perpecahan di negara tersebut. Sebagian
masyarakat berpendapat bahwa AS perlu membantu Vietnam dalam
pembangunannya. Sebagian lainnya berpendapat bahwa "Vietnam
tidak perlu disebut-sebut lagi karena merupakan masa silam yang
buruk."
Karena itu, baik anggota yang konservatif maupun liberal
sama-sama menghindarkan munculnya isyu tersebut, sehingga
Kongres tidak bisa mendorong pihak eksekutif untuk lebih aktif
memperhatikan masalah Asia Tenggara.
Dengan demikian, profil rendah dari politik Amerika di Asia
Tenggara sekarang banyak disebabkan oleh timbulnya sikap
isolasionisme terbatas di kalangan rakyat AS setelah perang
Vietnam, serta oleh gerakan di kalangan kaum intelektuil yang
menginginkan AS untuk memusatkan peranannya hanya pada
negara-negara Trilateral dan negara-negara besar seperti Uni
Soviet dan RRC.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini