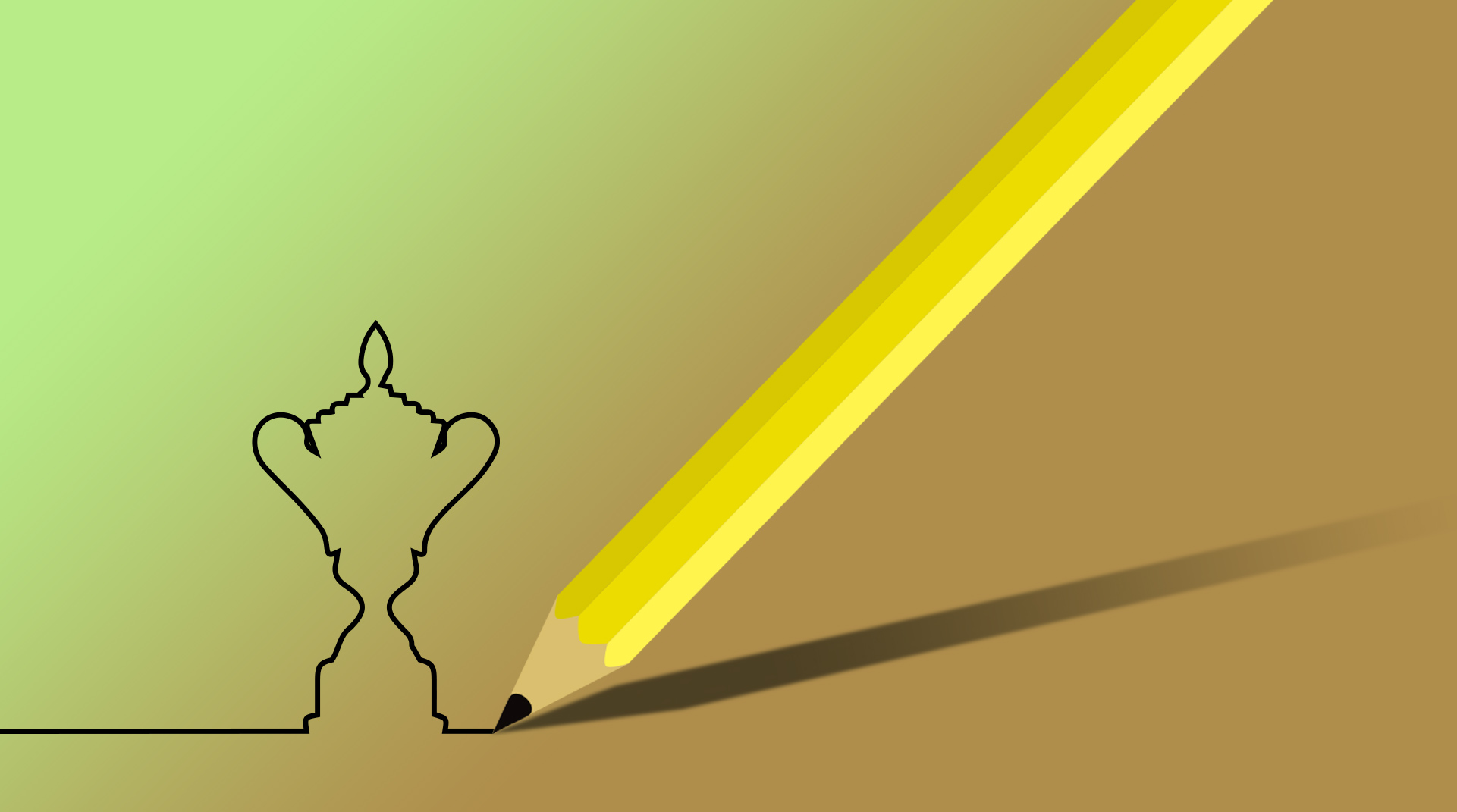PADA akhir Januari lalu, pemerintah kerajaan Arab Saudi menahan sekitar 30 dai atau ustad muda "fundamentalis-radikal". Mereka didakwa menghasut rakyat karena, melalui ceramah dan khotbah, mereka mengecam pedas meluasnya korupsi di lingkungan istana Raja Fahd. Mereka juga mengecam partisipasi Riyadh dalam proses perundingan ArabIsrael yang digagas oleh AS dan keterlibatan Saudi dalam Perang Teluk II. Selain itu, mereka juga menuntut perluasan partisipasi politik rakyat. Ada empat hal menarik dari kejadian tersebut. Pertama, sejak peristiwa kelompok "Imam Mahdi" yang menduduki Kabah (1979), praktis tidak terdengar adanya gerakan kaum "fundamentalis" di Saudi. Kedua, para ustad yang ditahan itu semuanya penganut mazhab Wahabi, yang merupakan "mazhab resmi" di negara Dinasti Al Saud ini. Artinya, "tesis" yang memandang gerakan "fundamentalisme" sebagai selalu dimotori atau mendapat inspirasi dari kaum Syiah (seperti di Iran, Irak, dan Libanon) atau kelompok Ikhwanul Muslimin (seperti di Mesir, Aljazair, Suriah, dan HAMAS di Palestina), menjadi gugur. Ketiga, munculnya gerakan "fundamentalisme-radikal" di negara yang relatif sudah makmur seperti Saudi -- kendati tampaknya belum begitu meluas -- juga menggugurkan "tesis" yang menganggap "fundamentalisme hanya bisa tumbuh subur di kalangan masyarakat miskin". Ini, misalnya, terlihat dari analisa-analisa yang mencoba melihat latar belakang keberhasilan Front Penyelamatan Islam di Aljazair. Keempat, adanya tuntutan bagi perluasan partisipasi politik mencerminkan bahwa demokratisasi memang menjadi salah satu masalah krusial di Dunia Arab, di samping masalah Palestina dan soal pemerataan kesejahteraan. Hal ini menjadi lebih menarik lagi jika dikaitkan dengan perkembangan di Aljazair. Di negara ini, proses demokratisasi yang tengah berjalan dihentikan secara tiba-tiba hanya oleh sebuah prasangka. Prasangka itu berbunyi: "Kalau partai Front Penyelamatan Islam (FIS) berkuasa, maka Aljazair akan menjadi sebuah Republik Islam, dan kalau Aljazair menjadi negara Islam, maka demokrasi serta hak-hak asasi manusia tidak ada!" Masya Allah! Adalah para pemimpin, pakar, dan media massa Barat yang mengembuskan prasangka itu (perhatikan misalnya, ulasan-ulasan yang dibuat Time, Newsweek, The Economist, International Herald Tribune, Voice of America, BBC London). Memang sungguh aneh. Baratlah yang menjunjung tinggi asas "praduga tak bersalah", tapi asas ini tidak berlaku sama sekali dalam kasus Aljazair dan negara-negara Arab lainnya. Tidak heran jika Youssef Azmeh, dalam tulisannya berjudul Halt to Moslem Militancy in Algeria Brings Relief (The Jakarta Post, 16 Januari 1992), melontarkan pertanyaan bernada sinis, "Why is democracy good when it brings a pro-Western regime and bad when it brings an Islamic republic?" Dan, menurut Azmeh, "The aborting of Algerian elections as an example of the hypocricy of Westerninfluenced liberalism. Di Saudi memang bukan hanya kalangan muda "fundamentalis" yang menuntut perluasan partisipasi politik, tapi juga kalangan kelas menengah berpendidikan Barat yang menghendaki liberalissi di segala bidang. Termasuk di antaranya kaum wanita yang selama ini, misalnya, tidak diperkenankan menyetir mobil sendiri. Bisa jadi ini merupakan salah satu dampak dari bercokolnya pasukan Sekutu di Saudi selama Krisis Teluk lalu. Situasi itu agaknya memberikan peluang bagi munculnya konflik antara kaum "fundamentalis" dan kaum "liberalis" di Saudi, kendati saat ini mereka sama-sama menuntut demokratisasi dan perluasan partisipasi politik. Dan jika konflik demikian terjadi, hampir pasti Barat akan mendukung kaum "liberalis" yang bisa menjamin langgengnya kepentingan mereka di Saudi. Namun, sebuah proses demokratisasi di Saudi maupun di negara-negara Arab lain akan tetap dihadang oleh dua kendala utama. Pertama, tradisi demokrasi belum mengakar di Dunia Arab. Ini berbeda dengan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah non-Arab, seperti Turki, Iran, dan Israel. Kedua, sebagaimana kasus Aljazair, Barat, khususnya AS, tidak akan membiarkan berjalannya proses demokratisasi yang memberikan peluang bagi kemenangan kaum "fundamentalis". Padahal di Dunia Arab sampai saat ini merekalah yang paling berpeluang meraih kemenangan. Masalahnya, seperti dikatakan Azmeh, "Demokrasi itu hanya bagus jika menghasilkan rezim pro-Barat." Belum lama ini, sewaktu Presiden Bush hendak bertemu dengan PM RRC Li Peng di Markas PBB, kalangan Kongres AS memprotes keras dengan dalih, "Kini tidak ada lagi tempat bagi para diktator." Seperti diketahui, Li Peng dituduh sebagai yang paling bertanggung jawab atas tragedi penindasan terhadap gerakan prodemokrasi di Lapangan Tienanmen. Tapi, ironisnya, "para diktator Arab" justru tetap dibiarkan terus berkuasa. * Staf peneliti LIPI