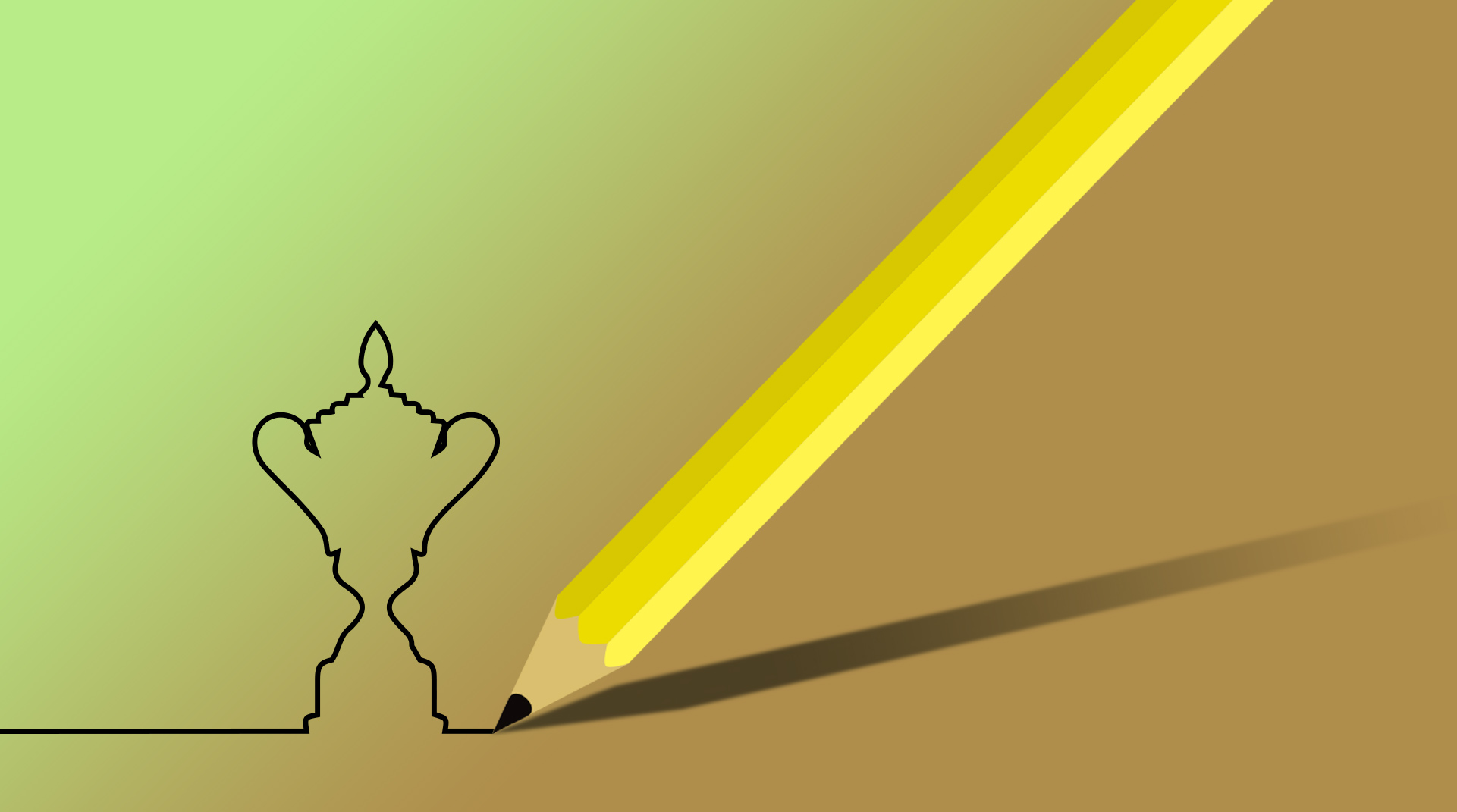PASANG surutnya kehidupan pers di Indonesia seirama dengan perubahan dan perkembangan sistem sosial politik ekonomi bisnis yang kita alami. Kita lihat sejarah. Setelah selesai perang kemerdekaan, Indonesia sebenarnya tetap melanjutkan struktur sosial ekonomi Hindia Belanda: kekuatan ekonomi bisnis yang menguasai mayoritas pendapatan bruto Indonesia waktu itu adalah "Tiga Besar" bank dan "Lima Besar" perusahaan dagang yang semuanya milik orang Belanda, ditambah jaringan perusahaan Inggris dan AS. Perusahaan itu meliputi produk barang konsumsi ringan, seperti sabun, margarine dari Unilever, Bir Bintang, Bir Anker, sepatu Bata, ban Dunlop dan Goodyear, sampai industri hulu, seperti mesin, mobil (General Motors), dan minyak bumi (Shell, Caltex). Surat kabar berbahasa Belanda, seperti Jawa Bode (mulai terbit 1852), De Locomotief (juga 1852), dan Soerabaiasch Handelsblad (1866) didukung oleh promosi iklan perusahaan-perusahaan itu. Di tengah piramida terdapat pers peranakan Cina yang diwakili oleh Keng Po (antikomunis, sejak 1923) dan Sin Po (berkiblat ke kiri, sejak 1910) dan juga misalnya di Semarang ada Kuang Po (kanan) dan Sin Min (kiri). Kemudian ada pers yang dikelola oleh wartawan dan penerbit pribumi, yang pada awalnya memang lebih merupakan wadah perjuangan politik. Mereka ini secara bisnis "ketinggalan" dari pers Belanda dan peranakan Cina. Keadaan ini berlanjut sampai dengan zaman "demokrasi liberal" (sampai 1957), ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer. Meskipun pada periode ini surat kabar seperti Pedoman (pribumi) sudah mencapai oplah 30.000, mendekati Keng Po yang 39.000. Koran pribumi lain yang kuat adalah Merdeka (dipimpin oleh B.M. Diah), Indonesia Raya (Mochtar Lubis), dan Berita Indonesia (Sumantoro). Struktur itu berubah dengan ditutupnya koran berbahasa Belanda milik Belanda serta diambil alihnya seluruh perusahaan Belanda, yang kemudian jadi "perusahaan negara", termasuk percetakan pers. Sejak 2 Desember 1957 tamatlah riwayat pers Belanda di bumi Indonesia yang telah berusia 105 tahun itu. Yang tersisa tentu saja pers yang dikelola kaum keturunan Cina dan pers yang dikelola oleh "pribumi". Tahun 1957, Statistik BPS menyebut 96 surat kabar dengan oplah rata-rata 9.200, di antaranya 17 pers milik keturunan Cina dengan oplah rata-rata 7.400. Pers "keturunan Cina" ini kemudian mengadakan pembauran kepemilikan. Keng Po menjadi Pos Indonesia. Menarik untuk dicatat bahwa golongan kiri yang kurang setuju pergantian nama, sebagai lawan dari golongan pembauran, di bidang pers juga "rela" ganti nama: Sin Po menjadi Warta Bhakti. Zaman "Manipol" Situasi politik zaman pasca"demokrasi liberal" yang disebut sebagai masa "demokrasi terpimpin" dengan doktrin "Manipol" itu, yang kian lama didominasi golongan kiri, memojokkan grup Keng Po. Baik Pos Indonesia maupun majalah Star Weekly dibredel di zaman ini. Grup Sin Po menjadi dominan, dengan Warta Bhakti yang terbit sore merajai dunia pers Indonesia. Sementara itu, di tempat kedua, Berita Indonesia merajai koran pagi. Surat kabar lain, seperti Pedoman dan Indonesia Raya kena bredel, dan Merdeka "telantar", karena pemimpin redaksinya, B.M. Diah, jadi duta besar. Surat kabar politik lain, seperti Suluh Indonesia (alat Partai Nasionalis Indonesia) dan Harian Rakyat (alat PKI) survive, tapi pangsa pasar bisnisnya tak mampu mendekati Berita Indonesia dan Warta Bhakti. Di daerah, koran yang diterbitkan oleh tokoh yang saya sebut "Walisanga Pers", seperti Waspada, Mimbar Umum (Medan), Suara Merdeka (Semarang), Kedaulatan Rakyat (Yogya), Surabaya Pos (Surabaya), dan Pedoman Rakyat (Makassar) tetap hidup di tengah gelombang politik yang penuh pembredelan itu -- bahkan sampai kini. Tapi mereka harus menyesuaikan diri dengan ketentuan kontrol waktu itu: surat kabar harus mempunyai cantolan partai atau kekuatan sospol yang berinduk ke pusat Jakarta. Maka Suara Merdeka, misalnya, harus berinduk ke Berita Yudha di Jakarta. Adapun Berita Yudha adalah kelanjutan Berita Indonesia, yang kena bredel bersama sejumlah besar koran lain (termasuk Merdeka) akibat desakan PKI. Kelanjutan ini mungkin karena backing TNI-AD yang waktu itu menahan derasnya kekuasaan PKI. Ketika keadaan berbalik setelah 1965 dan peristiwa "G30S", Warta Bhakti yang kena bredel. Tempatnya langsung diisi oleh Sinar Harapan. Posisi Berita Yudha sebagai koran pagi nomor satu tetap tidak tergoyahkan. Waktu itu Kompas, yang baru lahir tahun 1965 (sebelum "G30S"), masih belepotan wajah dan tipologinya. Ciri masa ini ialah secara umum dapat dikatakan bahwa tak ada lagi dikotomi pers keturunan Cina dengan pers nasional pribumi, sebab sudah tak ada lagi koran yang "eksklusif" seperti Keng Po, Sin Po, dan Sin Min. Pada periode yang saya sebut bulan madu pers dan pemerintah, antara 1966-1974, terjadi lagi persaingan sengit. Koran yang dibredel di "zaman Manipol" diizinkan terbit kembali: Abadi, Indonesia Raya, dan Pedoman. B.M. Diah (yang jadi Menteri Penerangan di awal Orde Baru) mempelopori cetak off set dalam sejarah penerbitan pers di Indonesia. Hingga awal dekade 1970-an, Sinar Harapan dan Berita Yudha tetap merajai pers Jakarta. Oplah Kompas baru menembus 100.000 pada tahun 1972 dan menembus 200.000 pada tahun 1975. Peristiwa "Malari", 1974, menutup periode bulan madu pemerintah dengan pers. Kena bredel adalah Abadi, Pedoman, Harian Kami, Indonesia Raya, Nusantara, The Jakarta Times. Waktu itu, TEMPO (didirikan oleh Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, dan kawan-kawan, termasuk saya) baru berumur tiga tahun, dengan oplah sekitar 20 ribu. Oplah total seluruh surat kabar di Indonesia tahun 1974 hanya 1 juta, yang berarti suatu kemunduran dibandingkan dengan tahun 1957 dihitung secara per kapita. Proteksi dan Kartel Di bidang politik terjadi pula keguncangan (demonstrasi besar mahasiswa) dan terjadi lagi pembredelan atas koran, seperti Kompas, Pelita, Sinar Harapan, Merdeka, dan Berita Buana. Tapi segera surat kabar yang dibredel boleh terbit kembali. Menurut saya, Pemerintah dengan demikian masih mengakui unsur "citra demokratis" dari eksistensi pers, dan tak sewenang-wenang, walaupun memiliki kekuasaan berlebih yang tak terimbangi oleh kekuatan sosial politik masyarakat. Namun, sejak saat itu, pers relatif menjadi agak jinak. Ada pencabutan SIUPP Jurnal Ekuin, Prioritas, dan Sinar Harapan pada usia 25 tahun (1986). Tahun 1980, terhadap pers Indonesia yang dianggap sudah cukup kuat diberlakukan jiwa dan semangat UU antimonopoli dengan membatasi jumlah halaman maksimal 12 halaman dan ruangan iklan maksimal 35%. Sejak 1974, sebenarnya pers Indonesia secara keseluruhan juga telah diproteksi dari pendatang baru. dengan dihentikannya pengeluaran SIT baru kecuali dalam hal yang sangat khusus dengan restu penguasa politik. Sekarang pembatasan jumlah halaman berangsur ditingkatkan menjadi 16 dan 20 halaman, namun iklan tetap hanya antre di media peringkat atas, meskipun dengan tarif per 1.000 pembaca (cost per thousand) yang lebih mahal dari koran Singapura The Staits Times. Terjadi proses yang lebih tepat disebut acquisition oleh pers kuat terhadap pers lemah atas dasar keterpaksaan yang menimbulkan pelbagai kontradiksi legal dan praktis. Misalnya ketentuan bahwa investor baru maksimal hanya boleh menanam modal 35%, tapi dalam praktek tidak ada orang yang mau menanam modal hanya untuk memperoleh minoritas saham. Sementara itu, bentuk Perseroan Terbatas harus tunduk kepada Kitab Hukum Dagang, artinya kekuasaan tertinggi jatuh ke tangan pemegang saham. Ini tak serasi dengan ketentuan bahwa nama Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi harus terkait dengan SIUPP, hingga terjadilah dualisme yang bakal sering menimbulkan konflik dalam kerja sama antara pemilik SIUPP lama dan investor baru. Contoh terakhir adalah konflik antara pemilik lama dengan investor baru (Ika Muda Group) dalam kasus harian Berita Buana. Ketentuan pembatasan SIUPP juga sangat menghambat lahirnya Jakob Oetama dan Goenawan Mohamad baru, sebab para wartawan muda dasawarsa 1990-an tak mungkin memperoleh kesempatan menikmati SIUPP secara gratis. Yang terjadi ialah masuknya konglomerat dengan modal raksasa yang mampu membayar wartawan profesional dengan "gaji dan fasilitas berapa saja" asalkan mereka bersedia menjadi "crew" penerbitan yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh konglomerat. Masa Depan Pers Indonesia barangkali adalah satu-satunya lembaga dalam struktur sosial ekonomi bisnis, yang mampu mengadakan Indonesianisasi kepemilikan secara tuntas dan menghilangkan struktur warisan kolonial baik lapisan atas Belanda maupun lapis perantara keturunan Cina, dan langsung menguasai peringkat puncak struktur pers. Ini berarti pers Indonesia sudah mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri secara bisnis industrial walaupun eksistensi dan survivalnya masih dibayangi oleh pedang Damocles pencabutan SIUPP. Namun, justru karena sudah berada pada puncak piramida bisnis, pers Indonesia tertawan oleh kemapanan dan sangat sulit menjalankan fungsi dan misi sebagai pengemban hati nurani rakyat yang sejati. Juga oligopoli dalam bisnis pers tampaknya tidak akan terelakkan. Dari sekitar 260 buah SIUPP, menurut pemantauan Pusat Data Bisnis Indonesia, sekitar 100 SIUPP berada di tangan sepuluh besar kelompok media massa dan 160 buah lainnya berada pada kondisi rawan yang memerlukan injeksi dana investor sekitar Rp 160 milyar bila rata-rata penerbitan memerlukan investasi dan modal kerja sekitar Rp 1 milyar. Yang patut dipertimbangkan ialah akibat distorsi kebijakan yang mendorong kelompok pers terjun ke sektor nonpers dan akibat proteksi yang menjadikan SIUPP komoditi mahal, hingga konglomerat diundang masuk pers. Maka, pada akhir abad ini, kita di Indonesia barangkali akan menyaksikan kembalinya arwah zaman Java Bode, dalam bentuk pertautan yang amburadul antara konglomerat dan pers. Menurut saya, amburadul yang salah kaprah ini sangat membahayakan dan mengancam kesinambungan prinsip dan fungsi pers selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat. Hanya satu jalan bisa mencegah dominasi konglomerat nonpers dalam dunia pers nasional, yaitu pembukaan Modal Ventura untuk generasi muda wartawan profesional. Ini akan menumbuhkan pers independen dengan profesionalisme yang dihargai bukan hanya dengan sedekah 20~. Diperlukan kerja sama Ventura yang memadai untuk menjamin otonomi, otoritas, dan kredibilitas yang tidak rawan oleh conflict of interest akibat campur aduknya tugas jurnalistik dan kepentingan investasi.