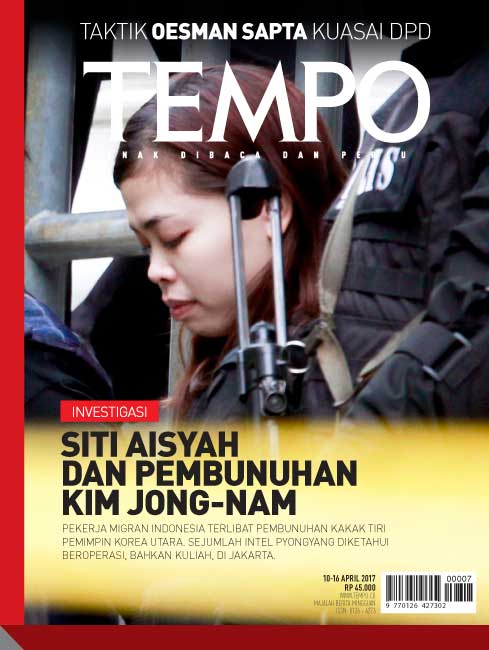Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Atheisme tak lahir di masa modern, tak juga ketika ada seseorang yang dengan cemas mewartakan bahwa "Tuhan sudah mati".
Antara tahun 800 dan 500 sebelum Masehi, di India, di masa ketika Upanishad mulai disusun sebagai śruti (kitab), sudah terdengar pernyataan-pernyataan yang menampik Wujud yang kekal dan kuasa. Surga dan neraka dinafikan, para pendeta diejek. Dalam salah satu Upanishad, ada bagian yang menyamakan para pendeta dengan sebarisan anjing: yang satu memegang ekor anjing yang mendahuluinya, dan semua mengulang, dengan takzim, kalimat yang sama.
Upanishad Swasanved bahkan membiarkan bagian yang lebih brutal: kitab-kitab suci disebutkan hanya hasil kerja orang gila yang congkak, dan orang banyak diperdaya kata-kata berbunga hingga mereka percaya kepada "dewa" dan "orang suci".
Dalam jilid pertama The Story of Civilization Will Durant ada nukilan tentang cerita Verocana yang selama 32 tahun di kahyangan jadi murid Prajapati. Sang Mahadewa mengajarkan "Ingsun, Diri yang bebas dari mala, tak lekang oleh umur, tak bisa mati, tak bisa sedih, tak bisa lapar... yang hasratnya adalah Kasunyatan". Tapi ternyata Verocana kembali ke bumi dan mengajarkan doktrin yang durhaka: "Orang yang membuat dirinya bahagia di bumi... akan beroleh dunia yang kini dan nanti."
Demikianlah di sudut-sudut India, sebelum Buddha lahir (yang ajarannya juga tak akan berbicara tentang Tuhan), hidup orang-orang bijak yang tak peduli adanya dewa, juga para pemikir materialis yang ingkar. Ajita Kesakambali, misalnya, menganggap manusia hanya tanah, air, api, dan angin: "Si pandir maupun si pandai, setelah tubuh mereka lumer, terputus, dimusnahkan... mereka bukan apa-apa." Bahkan dalam Ramayana ada tokoh bernama Jabali yang berkata kepada sang raja muda dari Ayodhya: "Tak ada hari kemudian, Rama, harapan dan iman manusia hanya sia-sia."
Sebuah era yang seru: para cendekiawan berkelana dari tempat ke tempat, muncul di dusun-dusun, tepian hutan, dan lereng bukit. Di antara mereka para Paribbajaka mengajarkan logika sebagai kiat pembuktian; mereka berbicara tentang tak-adanya Tuhan. Di bagian lain, para Charvaka menegaskan bahwa agama adalah sesuatu yang sesat, sebuah penyakit, dan hanya dipeluk kencang oleh orang ramai yang merasa bingung ketika pengetahuan tumbuh dan iman longsor. Mereka adalah pendahulu Marx yang berabad-abad kemudian menggemakan kesimpulan yang mirip: "Agama adalah desah makhluk yang tertindas, hati di dunia yang tak punya hati, dan sukma dari dunia yang tak punya sukma." Agama, bagi Marx, adalah candu orang ramai.
Tapi jika agama hanyalah ekspresi manusia--juga penghiburnya--jika agama bukan sesuatu yang datang dari langit, di manakah Tuhan? Tak ada?
Sekian abad sebelum Masehi, di India, di masa yang disebutkan di atas, tampaknya sebuah perubahan terjadi. Khalayak datang berbondong-bondong mendengarkan para atheis berbicara atau berdebat. Bangunan besar dibangun buat menampung mereka. Waktu itu--mungkin tak jauh berbeda dengan masa kini--agama begitu penting di masyarakat, tapi ditandai kecemasan sosial dan psikologis yang akut. Makna rohaninya pudar dan orang merasakan hal itu. Iman jadi peraturan dan amal baik jadi pameran. Ibadah tak lahir dari rasa syukur dan takjub kepada Tuhan, tapi karena ada otoritas yang mewajibkannya. Di Jerman abad ke-18 Hegel juga melihat gejala ini; ia menyebutnya sebagai "Positivität" agama: "Perasaan ditumbuhkan dengan mekanistis dan melalui paksaan, amal dikerjakan atas perintah dan kepatuhan...."
Pendek kata, agama telah kehilangan sifatnya yang "subyektif". Sadar atau tak sadar, yang merasa beriman sebenarnya telah jadi semata-mata obyek, bukan dirinya sendiri. Ia "hilang bentuk/remuk". Ia terasing dari tindakan dan dunianya. Ia tak merdeka, hanya bisa menghadap ke satu arah dengan ketakutan. Agaknya itulah yang digambarkan Chairil Anwar dalam sajak "Doa":
Tuhanku
aku mengembara di negeri asing
Tuhanku
Di pintu-Mu aku mengetuk
aku tidak bisa berpaling
Sajak ini, meski mengandung protes, adalah puisi yang religius. Apa yang menggetarkan adalah saat Tuhan disebut sebagai Ia yang bisa diajak berbicara, Ia yang tak bertakhta dikelilingi benteng yang tinggi--meskipun manusia, dalam agama yang "positif", yang dogmatis, mengabaikan bahwa di dekat-Nya ada pintu.
Dengan kata lain, Tuhan dalam "Doa" bukan Tuhan yang sudah jadi berhala--bukan Tuhan yang dibentuk dan dirumuskan manusia, ditopang agama yang hanya untuk kepentingan si manusia. Tuhan, Dewa, Berhala: membatu, kedap, tegar, tak responsif kepada apa yang khas, yang partikular, dalam hidup.
Saya kira itulah yang terjadi ketika atheisme berkecamuk: orang menampik Tuhan di masa yang sama ketika agama membekukan Tuhan dan meniadakan pintu. Kini dan 2.800 tahun yang lalu.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo