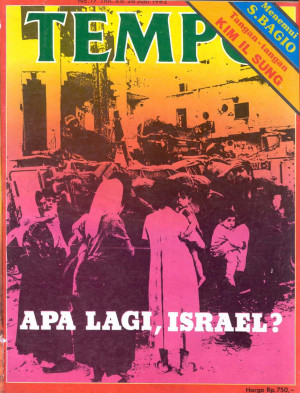BEN-GURION suatu hari membentangkan tangannya lebar-lebar, dan
berkata, "Jika kau letakkan di satu tangan semua idaman di
dunia, dan di tangan yang lain keselamatan hidup Israel, aku
akan memilih yang kedua. Sebab mereka yang mati tidak memuji
Tuhan . . . "
Mereka yang mati mungkin tak memuji Tuhan, yang kalah bahkan tak
bisa memuji diri sendiri. Ben-Gurion, pendiri Israel, perdana
menteri pertama, memang berbicara tentang kenyataan-kenyataan
dunia yang keras dan tidak tenteram. Dia seorang yang sehat
pikiran, tapi sejauh manakah etika survival yang terus-menerus
dianggap sah itu tak menyebabkan orang jadi telanjur?
Rabbi Meir Kahane, bekas pemimpin Liga Pertahanan Yahudi di
Amerika, datang ke Israel dan mendirikan organisasi yang disebut
Kach. Salah satu idenya: mengusir orang Arab yang berada di
wilayah kekuasaan Israel ke luar negeri itu. Tanpa Kach toh
sudah banyak orang Palestina terusir -- seperti orang Yahudi
dahulu pun diusir dari satu tempat ke tempat lain, meskipun
untuk orang Palestina, penyair W.H. Auden tak menulis sajak Lagu
Orang Usiran. Tidakkah Rabbi Kahane bukan bentuk yang lebih
ekstrim dari dorongan kekerasan yang laten ?
Orang bisa mengatakan, memang, bahwa sejak zaman Musa dalam
Perjanjian Lama, bangsa Yahudi bukanlah bangsa yang biasa dengan
kelunakan hati. Tuhan dalam persepsi mereka adalah Yahwe yang
cepat murka. "Siapa saja pada hari Sabbat melakukan pekerjaan,
harus dihukum mati!", demikian perintahnya. Dan ketika suatu
ketika rakyat Yahudi berbuat dosa di Syitim, Yahwe pun
memerintahkan kepada Musa: "Ambillah semua kepala rakyat dan
sulakanlah di hadapan Yahwe di siang hari. . ."
Di tangan para penulis lima buku pertama Kitab Perjanjian Lama,
demikian tulis Will Durant dalam bagian awal The Story of
Civilization, Yahwe menjadi Tuhan yang imperialistik dan
ekspansionis. "Ia tak akan membawakan omong-kosong seorang
pencinta damai, ia tahu bahwa Tanah yang Dijanjikan sekalipun
hanya dapat direbut, dan dipertahankan, dengan pedang ia dewa
perang karena ia harus demikian . . ."
Durant kemudian secara selintas menyebutkan, bahwa setelah
melalui masa berabad-abad, Yahwe yang penuh api itu
perlahan-lahan berubah jadi Tuhan yang lembut dan penuh kasih
seperti yang dibawakan Yesus. Selama berabad-abad itu, bani
Israel mengalami kekalahan militer, ketaklukan politik dan juga
di lain pihak, perkembangan moral.
Hanya kekalahankah yang bisa mengajari sebuah bangsa untuk jauh
dari "dewa perang"? Jika benar demikian, Israel harus
dikalahkan, ditaklukkan -- seperti dulu yang dilakukan oleh
Nebuchadrezzar dari Babilonia. Artinya perang besar harus
kembali.
Masalah yang pelik ialah bahwa di zaman seperti ini kekerasan
seperti itu bisa berarti ketelanjuran lebih jauh. Dalam novel
The Fifth Horseman karya Dominique Lapiere dan Larry Collins,
dikisahkan bagaimana Presiden Ghaddafi berhasil memasang sebuah
bom hidrogen di Kota New York. Ia mengancam Gedung Putih: bila
Amerika tak berhasil memindahkan Israel dari Tepi Barat Sungai
Yordan, bom itu akan diledakkan.
PRESIDEN Amerika pun mendesak Perdana Menteri Begin. Bahkan ia
menyiapkan pasukan AS untuk, kalau perlu, menghadapi pasukan
Israel di wilayah yang diduduki itu. Begin, yang sakit jantung
itu, menelan pilnya lalu memimpin sidang rahasia kabinet Israel:
Libia akan digempur pesawat terbang yang membawa senjata nuklir
. . .
Berita tentu berakhir dengan banyak orang yang selamat. Tapi
novel itu cukup menyelipkan kengerian puncak, menjelang hancur
leburnya bumi. Ketika itu yang mati bukan saja tak memuji Tuhan,
tapi juga tak bisapaham. mengapa sejarah jadi begini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini