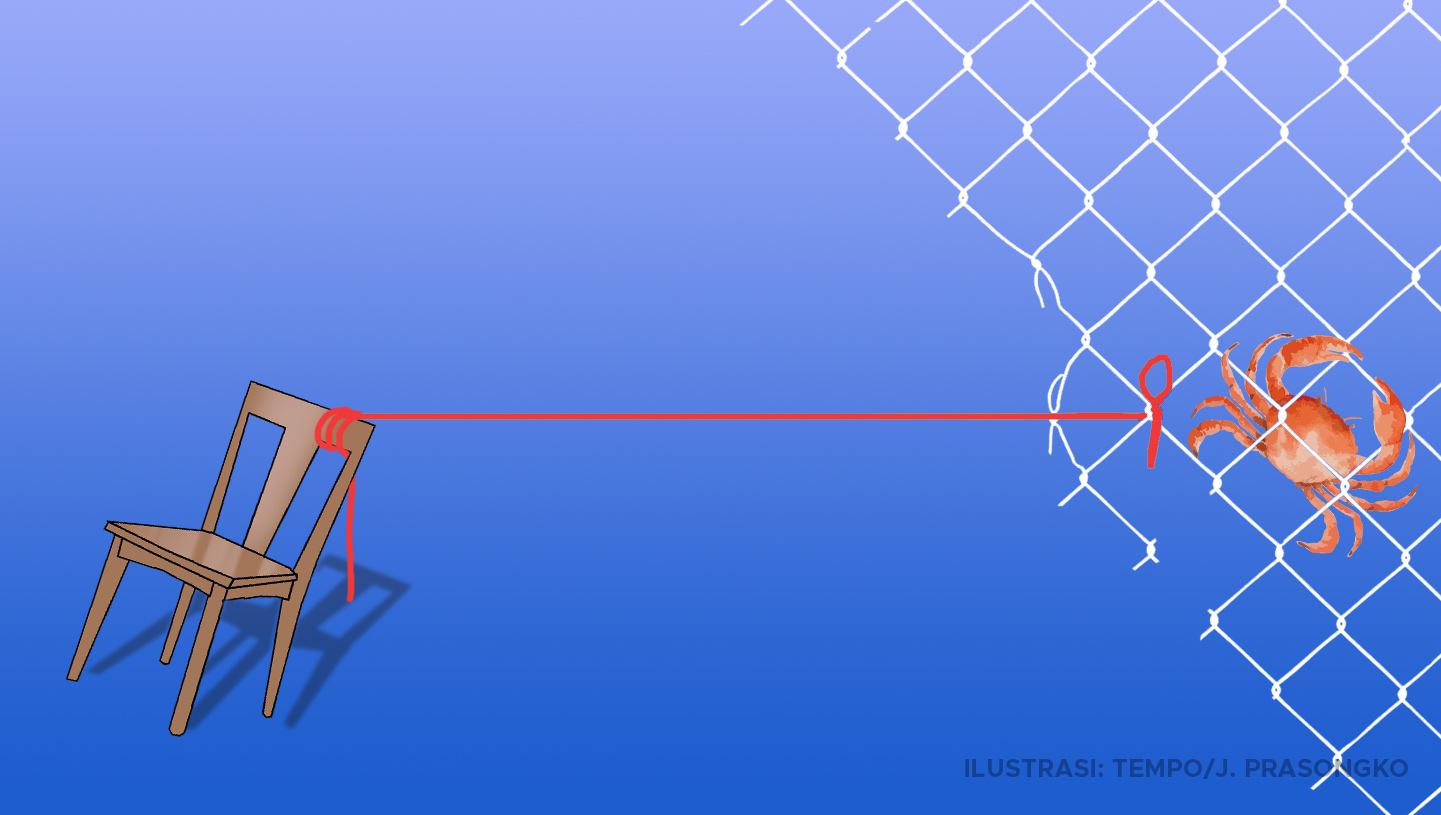Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di sebuah kota, di sebuah negeri, di mana kekerasan terdengar sebagai ungkapan keberanian (bom bunuh diri, pembantaian di siang hari, bentrokan berdarah atas nama geng atau agama), kita memang perlu bertanya: apa arti "keberanian"?
Pertanyaan yang tua sekali. Lebih dari 2.000 tahun yang lalu, sejumlah orang berkumpul di sebuah palaistra di Athena. Mereka juga memperdebatkan hal itu; mereka Sokrates, dua orang jenderal, dan sejumlah orang lagi. Platon, murid Sokrates yang termasyhur itu, menciptakan kembali debat itu dalam sebuah tulisan, "Lakhes" ( ), mengikuti nama salah seorang jenderal yang ikut aktif di dalamnya. Kita beruntung. Buku Mari Berbincang Bersama Platon: Keberanian (Lakhes) adalah terjemahan dan tafsir A. Setyo Wibowo atas karya kuno itu. Terbit September 2011, ditulis dengan bahasa Indonesia yang terang dan hidup, buku ini datang di waktu yang tepat.
Tapi tidak tiap buku dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang sukar—dan tidak tiap dialog Sokrates memuaskan mereka yang ingin kepastian. Bahkan Lakhes termasuk "dialog aporetik", sebuah proses mencari jawab yang berakhir buntu. Di bagian akhir Sokrates berkata, "Jadi, Nikias, kita belum berhasil menemukan apa itu keberanian."
Tapi justru karena itu manusia, juga yang hidup semenjak itu, mencari terus. Dan, seperti Sokrates, tak henti-hentinya menyoal tiap kesimpulan. Kita tak jera dengan aporia. Berkali-kali kita tengok percakapan yang terdahulu, juga percakapan Sokrates, dan kita coba telaah di mana ia benar di mana ia khilaf.
Saya (bukan pakar filsafat Yunani) memberanikan diri untuk melihat di mana ia khilaf: bagi saya, Sokrates terlalu cenderung memprioritaskan rumusan. Definisi adalah panglima. "Ayo," katanya kepada Lakhes, "cobalah merumuskan… apa itu [kodrat] keberanian."
Dalam pengantarnya, Setyo Wibowo menyebutkan kecenderungan itu: Sokrates selalu ingin menemukan definisi. Ia inginkan rumusan yang universal bagi "hal-hal yang etis yang ia diskusikan". Di sini, "universal" berarti bisa diterapkan pada semua kasus, bisa berlaku "untuk semua manusia dengan perilaku mereka yang beragam".
Tapi tiap definisi sebuah reduksi. Perilaku yang beragam selamanya berlangsung dalam pengalaman yang beragam, pengalaman yang konkret. Terutama dalam Grenzsituation, "situasi perbatasan", antara hidup dan mati, antara selamat dan celaka. Dalam situasi genting itu tiap pilihan menyangkut bukan cuma kesadaran, bukan cuma proses penalaran, tapi juga endapan trauma, magma nafsu dan hasrat.
Hanya di permukaan saja si X, ketika memilih, berperilaku seperti si Z: katakanlah laku keduanya punya titik-titik persamaan—semacam indikator bahwa ada sesuatu yang universal. Titik-titik persamaan itulah yang dikonsolidasikan dalam sebuah rumusan.
Tapi dengan demikian sebuah definisi mengabaikan titik-titik lain yang tak sama, tak terhingga, dan tetap tersisa. Padahal, dengan "sisa" itu, seutuhnya, kita akan tahu bahwa sebuah perilaku adalah sebuah pengalaman utuh yang tak bisa dijadikan formula.
Begitulah keberanian. Keberanian para pembajak pesawat yang menabrakkan diri ke Menara Kembar New York 11 September 2001 punya titik persamaan dengan keberanian seorang prajurit yang menubruk granat yang meledak agar teman-temannya selamat; tapi masing-masing mengandung pertimbangan, pengalaman, dan hasrat yang sama sekali lain.
Itu sebabnya semua rumusan Jenderal Lakhes dan Jenderal Nikias tentang keberanian akhirnya tak bisa pas ketika dihadapkan dengan kasus yang berbeda-beda. Sia-sia saja mereka memenuhi keinginan Sokrates yang sia-sia: mencapai kriteria yang bisa berlaku kapan saja dan di mana saja. Andai kata mereka juga hidup di zaman ini, mereka akan kaget: tauladan keberanian Sokrates sebagai prajurit yang melawan tentara Sparta—dalam pertempuran dengan tombak, perisai, dan tubuh yang nyaris telanjang—tak akan berlaku untuk abad ke-21, ketika perang dijalankan dengan pesawat terbang yang tanpa pilot.
Dengan itu pula kita sebenarnya bisa mempersoalkan benarnya asumsi bahwa "keberanian" hanya lahir dari perang dan kekerasan—seperti terbayang dari percakapan 2.000 tahun yang lalu. Dengan itu pula kita perlu bertanya benarkah keberanian bisa dianggap sifat utama manusia—atau bagian dari keutamaan umumnya.
Saya kira Platon, dengan Lakhes, bukan orang yang tepat untuk mempersoalkan itu. Ia keturunan raja-raja Athena. Ia seorang aristokrat yang mendapatkan bintang jasa dari salah satu peperangan membela negerinya. Ia melihat sejarah dari ketinggian dan menganggap Ide (juga definisi) di atas perubahan dan perbedaan hidup. Pandangannya tentang perang dan keberanian berbias kebangsawanan: keberanian adalah bagian dari gairah untuk keagungan.
Ia bukan orang zaman ini. Di zaman ini, di antara kita, perang semakin "aman": yang penting bukan lagi keberanian fisik melainkan kalkulasi yang rapi. Tapi juga semakin terkutuk: yang penting bukan keagungan melainkan kepentingan.
Di zaman ini, telah lahir kesaksian Brecht.
Dalam Mutter Courage und ihre Kinder, lakonnya yang kocak tapi juga muram, perang mendapatkan wajah yang culas: perang adalah bisnis melalui cara lain. Komandan hanya memuji keberanian para serdadu yang menyerbu petani miskin. Sementara itu keberanian yang heroik mencelakakan, seperti terjadi pada Julius Caesar yang dibunuh. "Beneidenswert, wer frei davon!" seru sebuah lagu di adegan ke-9. "Beruntunglah orang yang bebas dari itu!"
Kini kita mengerti kenapa Sokrates tiba di jalan buntu.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo