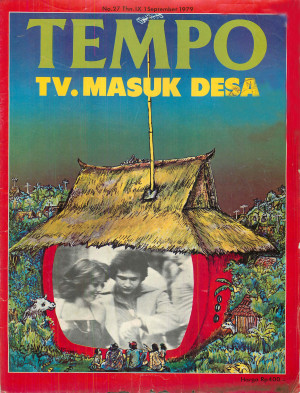KROMODIRDJO sudah kerasukan modernisasi selama 5 tahun tinggal
di Jakarta. Bininya tidak bunting-bunting lagi akibat menelan
pil lebih dari sekaleng biskuit. Kesemuanya itu diperolehnya
cuma-cuma dari Puskesmas terdekat sambil, disertai sanjungan
yang ramah dan membesarkan hati. Namun, rasa manusiawinya masih
ada tersisa dalam dirinya, terbukti dari rasa iba yang terkadang
timbul mendengar kisah kerabat dari desa yang setengah mati
ketakutan dianggap berindikasi Gestapu semata-mata karena tidak
ikut ber-KB. Orang-orang tradisional yang dungu itu rupanya
keliru berpikir beranak atau tidak beranak sama saja
sengsaranya, khusus dalam hal ketidaksanggupan pengembalian
kredit pupuk.
Dan biarpun selama 5 tahun itu Kromodirdjo sudah dua kali
berpindah atap, pertama karena rumahnya terpenggal untuk proyek
jalanan hingga yang tersisa hanya bagian dapur dan kakus, kedua
karena tergusur samasekali--tuntas menurut istilah orang
sekarang --namun dia tetap segar-bugar bagai orang baru keluar
dari restoran. Mengapa tidak, karena di atas reruntuhan rumahnya
kini tegak berdiri sebuah toko besar yang acap diliriknya dengan
rasa kagum walau tak pernah sekalipun berbelanja di sana. Di
toko ajaib itu dijual orang hampir semua keperluan orang hidup,
mulai dari jengkol yang tersimpan dalam lemari es hingga motor
bot.
Kalaulah ada saat-saat mengecilkan hati, ini hanyalah perkara
keputusan bebas-becak yang memaksanya hidup bergelandangan
sebulan dua. Tak jadi apa! Berkat modal asing banyak masuk,
suatu mukjizat zaman tersembur bagai sudah seorang dewa,
Kromodirdjo segera diterima bekerja di pabrik shampoo, suatu
pekerjaan yang tak pernah dialami oleh 7 jenjang nenek-moyangnya
ke atas. Setiap seruling pabrik bersiul di pagi hari dia
bergegas dengan semangat yang menyala-nyala Cukup tidak cukup
gaji tak pernah menggodanya untuk mogok karena dia sudah hakkul
yakin mogok itu perbuatan setan.
Perkembangan rohaninya secara keseluruhan menunjukkan kemajuan
luar biasa. Kromodirdjo menaruh kpercayaan kepada pembesar -
pembesar apa saja - tanpa ragu sedikit pun. Sikap ini amat
penting buat kelestarian suatu pemerintahan, seperti halnya
sikap yang diperlukan oleh setiap kepala stasiun terhadap lok
kereta api. Andaikata pun mereka mengatakan matahari terbit di
Barat dan tenggelam di Timur, dia kan menelannya tanpa
dikunyah. Konon pula ucapan-ucapan berkenaan dengan angkutan di
hari Lebaran yang dijamin serba kecukupan tak perlu ragu maupun
bimbang. Hal ini pula yang mendorongnya berkeputusan bahwa
Lebaran tahun ini mesti pulang kampung.
Bukan Pulang Berlebaran Biasa
Tapi, bukan pulang kampung berlebaran biasa seperti pikiran
orang dulu-dulu melainkan jauh lebih mendalam dari itu. Dia
tidak sekedar mau nyekar di kuburan, tidak sekedar Ingin
bersilaturahmi dengan handai tolan sanak famili: Kromodirdjo
ingin berminalaidin dengan Bupati beserta ibu yang menurut
pendengarannya berkenan menerima salam sembali dari setiap
peminat tanpa pandang bulu dari lepas lohor hingga asar. Bupati
beserta ibu akan tegak berdiri di lendopo Kabupaten hingga
kedua betis beliau kesemutan, saling bermaaf-maafan baik
menyangkut dosa besar maupun kecil, seraya juadah dihidangkan
tak putus-putusnya.
Tak salah lagi, pikir Kromodirdjo, inilah salah satu hasil
kemerdekaan yang penting. Jauh nian bedanya dengan nasib yang
menimpa kakeknya di masa lampau, berulang kali dihardik ndoro
Bupati hingga terkencing-kencing tanpa sebab-sebab yang jelas
bahkan tanpa berbuat kekhilafan samasekali. Dan jauh nian
bedanya dengan omong-kosong cerita Anton Chekov -- kalau saja
sempat dibacanya -perihal rakyat jelata yang mati ketakutan
hanya karena bersin hingga ingusnya jatuh di atas kepala
seor.ang jenderal dari balkon sebuah teater. Orang Rus yang
malang!
Saat yang dinanti pun tiba. Sesudah berdesakan naik kereta api
bagai kumpulan belut dalam keranjang, sesudah terlongo-longo
melihat perubahan besar di kampungnya, sesudah segala macam yang
tak ada gunanya disebut satu persatu di sini, Kromodirdjo
berhasil menginjakkan kaki di pendopo Kabupaten tanah tumpah
darahnya.
Dengan kepercayaan kepada diri sendiri sebagaimana galibnya
dimiliki penduduk urban, diterkamnya tangan Bupati, digenggamnya
dengan takzim dan pesona, dipintanya beribu-ribu maaf dan
pembesar tertinggi di kawasan itu pun meminta maaf kepadanya
terhadap apa saja yang telah dilakukan baik sengaja maupun
tidak, baik dalam artian dinas maupun pribadi. Seorang Bupati
minta maaf kepada bekas warganya yang pindah ke kota besar
mencari sesuap nasi bukanlah kejadian biasa! Ini peristiwa yang
layak tercatat dalam buku sejarah pelajaran anak-anak sekolah.
Sesudah itu ada sedikit pidato. Bupati yang tidak berpidato
bukanlah Bupati samasekali. Seakan-akan khusus ditujukan kepada
Kromodirdjo, Bupati menguraikan di luar kepala data-data
kemajuan daerah, bukan saja jumlah rumah sekolah dan jumlah
murid yang berhasil tertampung, melainkan juga jumlah hasil ikan
dan bebek yang melonjak dibanding Lebaran lalu.
Dan seakan-akan khusus ditujukan kepada Kromodirdjo, sang
pembesar yang berpakaian serba putih dengan anak kancing kuning
keemasan itu dengan kelembutan seorang paman menganjurkan agar
warganya yang sudah terlanjur berhamburan ke kota besar supaya
lekas-lekas kembali menetap di kampungnya masing-masing. Karena
sesungguhnya pembangunan daerah bukanlah teruntuk Bupati dan ibu
seorang, melainkan buat semua orang yang berakal sehat. Apalagi
tak ada Bupati di atas dunia ini yang mampu melakukan apapun
sendirian, hatta sebuah solokan sekecil apapun. Partisipasi,
sekali lagi partisipasi, kunci dari segala-galanya, demikian
Bupati menutup pidatonya setengah menjerit. Minal Aidin Wal
Faizin!
Nyaris menitik airmata Kromodirdjo mendengar pesanpesan keramat
itu. Dia bertekad boyong ke desa asal pada kesempatan pertama
yang memungkinkan, kalau perlu sambil jalan kaki. Yang sedikit
menjadi pikirannya hanyalah kerja apa yang akan dilakukannya
karena dia tidak punya tanah lagi walau sejengkal pun. Tapi itu
soal kecil, bisa dipecahkan belakangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini