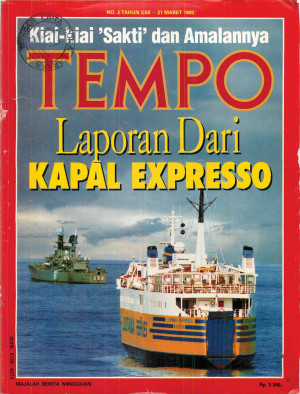PADA umur 82 tahun, Isaiah Berlin mengatakan, "Saya praktis telah hidup melalui seluruh abad ini." Bagi sejarawan ini, abad ke-20 adalah "abad terburuk yang pernah dialami Eropa". Mereka yang kini belum mencapai umur 30 mungkin akan merasa pernyataan itu janggal. Bagi penduduk Eropa, Amerika, dan Asia yang di tahun 1990-an belum lagi mencapai 30, dunia di sekitar adalah dunia yang necis, walaupun dengan letupan kekerasan di sanasini. Tetapi Berlin hidup di antara 1909 dan 1992. Pada umur lima sampai sembilan tahun ia mengalami perang besar pertama yang disebut sebagai "perang dunia". Pada umur 30-an ia menyaksikan perang dunia kedua. Di antara itu ia pasti mendengar, sayup-sayup, pembersihan atas para petani oleh Stalin, atas nama komunisme. Ia pasti terkena, langsung atau tak langsung, ketika jutaan orang Yahudi (termasuk anak-anak mereka) hendak dimusnahkan oleh Hitler. Perang dunia kedua juga menghancurkan pelbagai kota: pada umur 36 Berlin pasti mendengar bom atom dijatuhkan di dua kota di Jepang. Setelah itu seluruh dunia ketakutan. Di Dunia Pertama dan Kedua, orang menyiapkan perang termonuklir. Di Dunia Ketiga, orang membantai orang lain. "Dalam hidup saya," kata Berlin seperti yang dikatakannya dalam sebuah interview dalam The New York Review of Books akhir November 1991, "hal-hal mengerikan terjadi lebih dari di masa yang mana pun dalam sejarah. Lebih buruk, saya kira, bahkan ketimbang di masa serbuan bangsa Hun." Tetapi Isaiah Berlin masih beruntung. Abad ke-20 akan segera habis, dengan sejumlah harap dan sedikit suka cita. Perang Dunia Ketiga, dalam bentuk yang dibayangkan semula, yakni antara dua kekuatan super dan dengan bom-bom yang super, urung terjadi. Pelbagai bangsa tampak kian sadar bahwa perang bukan jalan yang paling cocok. "Orang bisa berharap," kata Berlin, "bahwa setelah pelbagai bangsa jadi lelah dari perkelahian, pasang berdarah itu akan surut". (Kalau pasang itu tetap saja mengancam, Berlin masih punya harapan: ia akan segera meninggalkan dunia yang brutal ini). Tapi gambaran masih baur. Dunia masih menunjukkan demam yang berasal dari abad-abad lampau: kegandrungan untuk membentuk dan mempertahankan sebuah "tanah air" sendiri, dengan penduduk asal, tujuan dan perbatasan sendiri. Itulah nasionalisme: suatu "impian" tentang suatu komunitas yang "sebangsa dan setanah air". Atau dalam kata-kata Benedict Anderson, dengan bukunya yang ringkas tapi brilyan itu, suatu "imagined community". Demam itulah yang kini merundung orang Israel, Palestina, Serbia, Kroasia, Armenia, Azerbeijan, Myanmar, Indonesia: harap-harap cemas dalam mewujudkan sebuah kesatuan dengan simbol, mitos, tapal batas, "sejarah nasional", dan "cita-cita nasional". Kalau perlu dengan kekerasan. Bisakah itu berakhir? Perlukah itu berakhir? Isaiah Berlin datang dengan sebuah kearifan klasik: ia menolak nasionalisme (yang brutal itu), tetapi ia juga mengenggani apa yang disebutnya "kosmopolitanisme": (yang menurut dia "kosong" itu). Ia menghendaki adanya suatu "nilai-nilai bersama", dalam jumlah minimum tetapi cukup besar, yang harus diterima oleh pelbagai manusia di dunia ini. Tetapi ia juga menampik keras keseragaman dunia yang kini semakin dimungkinkan oleh teknologi. Bagi Isaiah Berlin, sebagaimana bagi Herder (pemikir dan penyair nasionalisme Jerman yang dikaguminya) di alam semesta yang terdiri dari pelbagai dunia yang otonom, tak perlu ada sebuah matahari. Itu akan merupakan "imperialisme budaya", katanya. Baginya, sebagaimana bagi Herder, kebudayaan yang beraneka ragam di bumi ini bukanlah ibarat planet, tapi ibarat "bintang-bintang yang tak bertabrakan". Berlin menganggap bahwa proses pemiripan satu kebudayaan dengan kebudayaan lain bukan akan melahirkan "sebuah kebudayaan universal yang satu", melainkan sebuah "kematian kebudayaan". Betapa bagus. Tapi yang belum dijelaskan oleh Berlin ialah dari mana dan bagaimana datang dan tumbuhnya "nilai-nilai bersama dalam jumlah minimum tetapi cukup besar" yang ia sebut tadi. Nilai-nilai berkembang dan diterima orang banyak bukannya tanpa sumber dan tanpa konflik. Sebagian orang punya apa yang disebut oleh Antonio Gramci sebagai "hegemoni", sebagian yang lain tidak. Ketika masing-masing menyadari perlunya "mandiri", maka bentrok, rasa terasing dan tersisih -- awal dari demam itu -- terjadi. Barangkali ini cuma bukan ciri abad ke-20: sejarah memang sering membuat kita sayu. Goenawan Mohamad .
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini