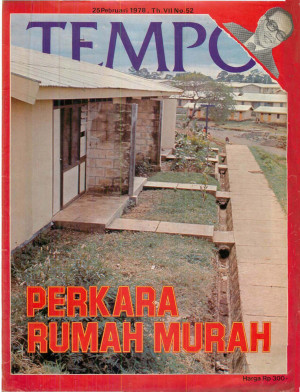KEBEBASAN memang bukan segala-galanya. Banyak kenyataan
sepanjang sejarah membuktikan itu: kemerdekaan bisa disisihkan
sebagai bukan barang suci, dan si pelaku tetap merasa tanpa
dosa. Seorang pemikir pernah berkata-suaranya khas untuk abad
ini: "Jika kemerdekaan yang saya miliki menyebabkan sesuatu yang
tidak adil, saya harus bersedia melepaskannya."
Di bulan Maret 1941 S. Takdir Alisjahbana memuat tulisannya
sendiri dalam majalah Poedjangga Baroe. Tulisan itu,
sesungguhnya dimaksudkan untuk majalah berbahasa Belanda De
Fakkel, berjudul serius: Individualisme en
Gemeenschapsbewustzijn in de Moderne Indonesische Letterkunde.
Dalam salah satu kalimatnya ia berkata: "Kecenderungan
individualisasi dalam masyarakat Indonesia .... harus diartikan
begini: membebaskan diri untuk ditawan dengan sukarela dan penuh
kesadaran."
Lebih 30 tahun kemudian, ketika Takdir telah berusia 70,
kata-kata serupa ini masih bisa terdengar kembali--satu hal yang
menunjukkan bahwa banyak persoalan masih tetap sama dalam hidup
kita. "Kita tidak boleh terhenti pada pengagungan kebebasan,"
kata Takdir, "bahkan sebaliknya pembebasan individu harus melulu
dilihat dalam fungsi kemasyarakatannya."
Keluar dari pena Takdir, pendirian itu sebenarnya tak
mengejutkan. Di akhir 1936 ia berpolemik dengan rekan
segenerasinya, Sanusi Pane. Ia menolak pendirian "seni untuk
seni". Alasannya ia nyatakan dengan gaya bersemangat yang khas:
"Kita sebagai bangsa yang berpal-pal jauh tertinggal di
belakang, kita sebagai bangsa yang dalam segala lapangan masih
harus mulai dari semula .... tiap-tiap kita harus penuh sesak
oleh pekerjaan pembangunan untuk memberikan tempat yang layak
bagi bangsa kita di tengah-tengah dunia .... "
Dan Takdir pun menolak kesenian hanya sebagai sport mewah. Dapat
kia duga bahwa ia pun akan mengecam kebebasan yang hanya
dipergunakan untuk kebebasan, sebab itu pun suatu barang lux.
Luxesport semacam ini, bagi Takdir, bukan milik kita. Kita
sedang dalam apa yang disebutnya sebagai zaman kerja
"rekonstruksi". Kemewahan itu harus kita tunda, sampai "zaman
yang lebih masak". Yakni, "apabila perjuangan perbaikan nasib
dan kedudukan bangsa sudah menenang di teluk yang sunyi dan
tiada berombak," apabila "segala perjuangan dan penderitaan
telah melenyap dalam bahagia dan kedamaian."
Sebagai seorang yang tajam dan jernih dalam merumuskan fikiran,
sebagai seorang penulis esei yang justru jadi hidup di saat-saat
Polemik, Takdir seakan-akan tak terbantah. Sanusi Pane pun tak
cukup kuat menjawab. Tapi kita yang hidup lebih panjang dari
Sanusi, dan menyaksikan perjalanan sejarah yang sering
mengecewakan, bisa bertanya: kapankah "teluk yang tiada
berombak" yang dijanjikan Takdir itu hadir?
Jawabannya: kita tidak tahu. Tapi kita bisa tahu, lebih dari
Takdir, bahwa sebuah bangsa yang matang sebaiknya bertolak dari
pra-anggapan bahwa teluk sunyi itu hanya mimpi. Bukan untuk
berputus-asa, melainkan justru untuk bersiap menghadapi
putus-asa. Bukan untuk melihat diri sebagai sesuatu- yang
terkutuk membatu, tapi untuk melihat diri sebagai jeram: kita
hidup antara arus dan tebing, antara enersi dan perbatasan.
Karena memang tak ada bangsa yang akan tanpa konflik, tak akan
ada bangsa yang bersih dari penderitaan. Sementara itu juga tak
ada bangsa yang Pada dasarnya buntu sama sekali dari kemungkinan
menyelesaikan konflik, dan macet sama sekali untuk mengatasi
penderitaan.
Di situlah sebenarnya kebebasan bisa dilihat sebagai sesuatu
yang berperan. Ia bukan kemewahan yang nikmat ia adalah
kewajiban yang dalam. Dengan kebebasanlah
kemungkinan-kemungkinan baru untuk menyelesaikan konflik dapat
dicari.
Dengan kebebasan-lah alternatif-alternatif diperoleh. Karena itu
bila kebebasan mati, seperti kata seorang cendekia, ia tak akan
mati sendirian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini