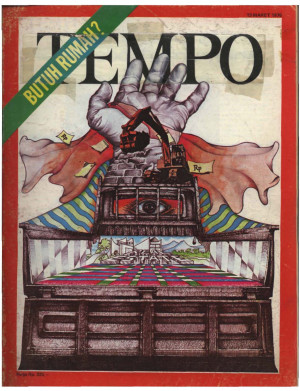PIDATO pengukuhan Guru Besar Dr. Emil Salim pada Dies Natalis
UI, 14 Pebruari yang lalu cukup memberikan aksentuasi yang
gamblang mengenai apa sebenarnya tujuan pembangunan nasional.
Juga tentang peranan apa yang dikehendaki dari cendekiawan
sebagai pengemban amanat suara hati nurani masyarakat.
Sebenarnya bagi mereka yang pernah membaca definisi Prof. Paul
Baran mengenai apa yang dimaksud dengan kelompok intelektuil
atau cendekiawan, apa yang dikemukakan Prof. Emil Salim bukan
sesuatu yang baru. Karena justru peranan intelektuil inilah
yang menjadi aksentuasi ceramah Prof. Dr. Widjojo pada
saat-saat kita menggerakkan atau merintis lahirnya orde baru
tahun 1966.
Paul Baran -- menurut terjemahan Prof. Widjojo -- telah
mendefinisikan "intelektuil" sebagai berikut: "Seorang
intelektuil pada azasnya adalah pengeriik masyarakat, seorang
yang pekerjaannya adalah mengidentifikasi, menganalisa dan
dengan demikian membantu mengatasi rintangan jalan yang
menghambat tercapainya susulan masyarakat yang lebih baik,
lebih berperi- kemanusiaan dan lebih rasionil. Dengan demikian
ia menjadi hati nurani masyarakat dan jurubicara dari
kekuatan-kekuatan progresif yang terdapat dalam tiap periode
tertentu dari sejarah -- dan dengan demikian mau tidak mau
dianggap 'pengacau'dan seorang yang menjengkelkan bagi ruling
class".
"Subversi"
Nah, seberapa jauh para cendekiawan kita telah betul-betul
memenuhi syarat Paul Baran, terutama dalam mencapai sasaran
pembangunan sebagai pencerminan adanya perencanaan ekonomi?
Sangat mudah untuk menyatakan atau mengatakan apa yang disebut
"tanggungjawab sosial" seorang cendekiawan, tetapi tidak mudah
melaksanakannya tanpa adanya "kecurigaan" atas maksud baiknya.
Terutama di negara yang sedang berkembang, di mana suatu kritik
selalu diidentikkan dengan "subversi" atau "mengganggu ke
tertiban dan keamanan ". Demikian pula sangat sulit untuk
menafsirkan apa yang dimaksud dengan "penggunaan kebebasan
mimbar dalam bentuk yang kreatif, konstruktif dan
bertanggungjawab, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat",
selama dalam interpretasi rumusan GBHN tersebut masih tersirat
"selera" kelas yang berkuasa yang berlindung di belakang slogan
"demi keamanan dan ke Tujuan pembangunan nasional cukup
gamblang, yakni "membangun manusia Indonesia seutuhnya". Bukan
hanya dengan meningkatkan produksi tetapi sekaligus mencapai
perataan pembagian pendapatan, demikian GBHN. Keadilan sosial
sebagai refleksi dari pada pembagian pendapatan yang merata
harus bisa tercermin dalam bentuk "kesempatan kerja bagi setiap
warga negara dan dari kesempatan kerja tersebut mereka bisa
hidup layak". Ini jelas tuntutan UUD 1945, khususnya pasal 27
ayat 2. Namun telah tercapaikah pelaksanaan perencanaan ekonomi
untuk mewujudkan amanat tersebut?
Kesempatan kerja bagi setiap warga negara untuk bisa hidup
layak, tidak saja menyangkut masalah ekonomi. Tapi juga
menyangkut "harga diri" manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia
tanpa kerja tidak saja mengakibatkan ia tergantung pada orang
lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, tapi juga akan
kehilangan harga dirinya. Betapa tepatnya perumusan dalam GBHN
itu!
Jelaslah kiranya bahwa yang penting bukan bagaimana perumusan
atau "das Sollen"nya, tapi bagaimana implementasinya. Untuk itu
sekali lagi kami tuliskan apa yang patut dicatat dalam definisi
Prof. Emil Salim, yakni bahwa "peranan cendekiawan di negara
berkembang adalah lebih dari sekedar menjadi intelek yang
menjual keahlian dan ilmunya kepada siapa yang menggajinya".
"Peranan cendekiawan di negara berkembang seperti halnya di
Indonesia sekarang ini adalah ahli yang memiliki tanggungjawab
sosial. Ia adalah pemikir dan sekaligus pembawa suara hati
nurani masyarakat...." Interpretasi dari definisi tersebut cukup
jelas sebagai ajakan, janganlah para cendekiawan demi sesuap
nasinya menjual martabatnya atau melacurkan intelektualitasnya.
Dapatkah tantangan ini terjawab secara positif, terutama bagi
calon-calon intelektuil masa datang?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini