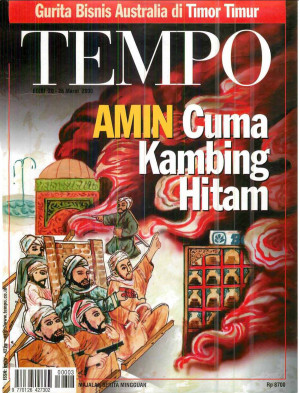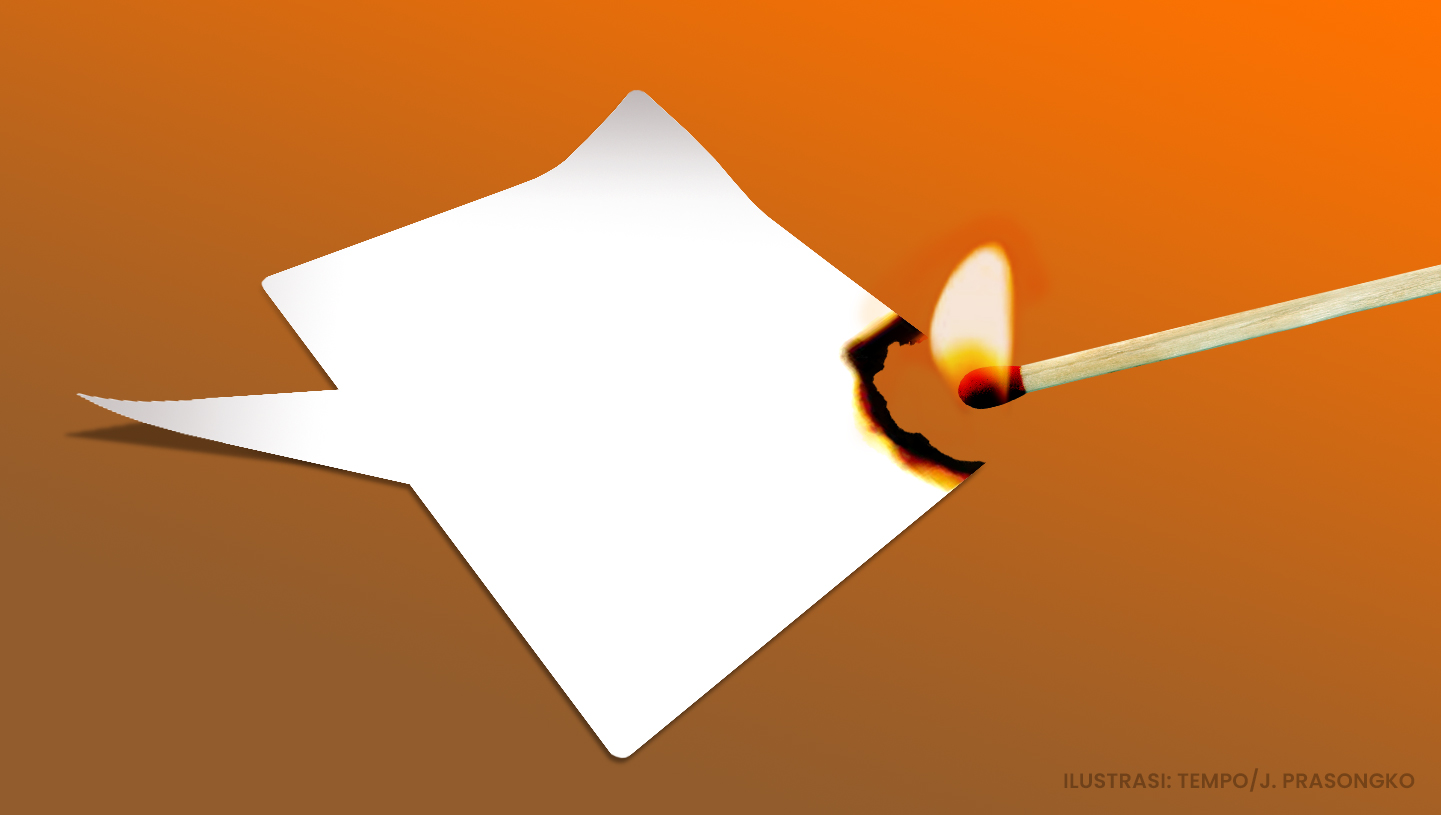Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
![]() Seno Gumira Ajidarma
Seno Gumira Ajidarma
Budayawan
|
TEORI warung kopi mengatakan: memahami Indonesia itu belum sahih jika tidak mengerti kebudayaan Jawa, dan mengaku tahu kebudayaan Jawa itu belum sempurna jika tidak mengenal Yogya, dan mengaku paham Yogya adalah omong kosong tanpa pengetahuan tentang wayang, dan tahu wayang adalah sia-sia jika tidak tahu apa artinya "dagadu".
Dagadu itu ada. Bagaimana tidak disebut eksis jika kata "dagadu", yang terbaca di kaus oblong dan tas yang bergambar mata itu, menjadi fenomena yang mewabah. Sebagai fenomena budaya, terbacanya dagadu itu adalah keajaiban dunia makna. Dagadu identik dengan gambar mata karena bunyi "da-ga-du" berasal dari "ma-ta-mu". Adapun "matamu" dalam bahasa Jawa-Yogya adalah suatu kata makian. Jika seseorang mengucapkan, "Matamu!", itu merupakan reaksi bahwa ia tidak setuju dengan pendapat Anda. Namun, makian ini tidak mempunyai konotasi menghina, melainkan menunjukkan keakraban. Bagaimana bunyi da-ga-du berasal dari ma-ta-mu? Prinsipnya bisa dilacak dari sebuah rumus yang mengacu pada 20 huruf Jawa: ha na ca ra ka
Dengan memperpadankan baris ke-1 dan ke-3, serta baris ke-2 danke-4, bunyi ma-ta-mu jika "dibalik" akan menjadi da-ga-du. Cara berbahasa macam ini di Yogya disebut basa walikan (bahasa terbalik), artinya menunjuk pada susunan 20 huruf Jawa. Sebetulnya basa walikan juga disebut sebagai basa maling (bahasa pencuri), basa sacilad (bahasa bajingan), dan basa gali (bahasa preman). Inilah bahasa dunia bawah tanah, bahasa kaum marginal yang bukan hanya tidak pernah, tapi juga dianggap tidak perlu diakui, apalagi diresmikan—karena bahasa ini digunakan oleh orang-orang yang berada di luar ketertiban. Barangkali, mula-mula bahasa ini digunakan sebagai bahasa rahasia untuk melindungi segala tindakan melawan hukum. Namun, kemudian bahasa ini memberikan suatu predikat kepada mereka, suatu identitas: menjadi suatu selubung transparan yang bermain antara penghilangan dan penegasan suatu citra. Mereka ingin menunjukkan siapa diri mereka, tapi karena tidak mungkin, hal itu diungkapkan dengan suatu bahasa yang tidak dipahami "dunia-yang-diakui". Itulah budaya paria, yang begitu tertindasnya sehingga berputar-putar involutif di bawah tanah. Demikianlah, adanya huruf mengandaikan adanya suatu nilai yang adiluhung dalam kebudayaan. Namun, kelahiran huruf Jawa (baru) tersebut dibayang-bayangi oleh sebuah legenda berdarah. Dalam legenda Ajisaka (Dharmabrata, 1948: 10-11), dikisahkan tentang Sembada, yang diminta untuk menjaga keris oleh Ajisaka, dan Dora, yang diminta untuk mengambil keris itu, juga oleh Ajisaka. Akhir kisah begitu tragis sehingga Ajisaka, yang berduka, melahirkan 20 huruf itu, yang mempunyai arti : ada utusan
Asal-usul huruf Jawa (baru) ini, yang sudah dipakai pada abad XV, tentu mempunyai penjelasan yang ilmiah sesuai dengan disiplin paleografi, yang boleh dirujuk misalnya lewat Vogel (1918), Poerbatjaraka (1952), Damais (1955), Casparis (1975), atau Molen (1985). Namun, sebuah legenda hadir karena peristiwa yang mengesankan. Huruf Jawa dilahirkan oleh pertumpahan darah. Tidakkah ini berarti bahwa kebudayaan adiluhung hanya mungkin tumbuh dalam naungan suatu kekuasaan—dan kekuasaan itulah yang berdiri di atas piramida korban manusia? Kebudayaan itu mestinya memuliakan manusia, tapi kebudayaan yang melahirkan dan dihidupkan huruf Jawa tidak mampu memanusiakan orang-orang pinggiran, kaum kecu, yang harus menciptakan bahasanya sendiri. Masih muliakah suatu kebudayaan yang tidak mampu memberi pengakuan kepada budaya orang-orang tertindas? Sementara identitas remaja Jakarta mendapatkan legitimasi dalam Kamus Bahasa Prokem (Henri Chambert-Loir & Pratama Raharja, 1985), dan Kamus Gaul kaum waria yang disusun Debby Sahertian (1999) laku keras, basa walikan tetap tinggal marginal di lingkungan budaya yang dilengkapi proyek Javanologi. Basa walikan, tak pernah disentuh studi apa pun, sebagai imbas sudut pandang arogan budaya adiluhung tersebut. Bagi saya, sungguh mencengangkan bahwa kebudayaan yang diandaikan memuliakan manusia justru mampu memojokkan budaya golongan yang tidak diakui dalam hirarki sosial sampai kepada taraf pemusnahan, sehingga hanya memiliki keterbalikan. Dengan begitu, kebudayaan adiluhung yang tidak mampu membebaskan sebenarnya sedang melakukan proses pelupaan sejarahnya sendiri. Sebab, kekuasaan yang berdarah, yang menaungi kebudayaan tersebut, hanya bisa ditancapkan oleh kaum kecu. Para priayi pun dulunya kecu. Jadi, mengingkari budaya paria berarti mengingkari asal usulnya sendiri. Barangkali itulah sebabnya setiap kali saya melihat gambar mata bertuliskan "dagadu", saya merasa senang karena saya menafsirkannya sebagai budaya paria yang menguak takdir. Bahasa Jawa yang adiluhung mungkin masih selamat sebagai bahasa museum, tapi basa walikan lebih dari itu—menyeruak dan mengalami sukses. Sedikit banyak, basa walikan kini menjadi bahasa pergaulan. Tapi, bagaimana dengan nasib kaum kecu? Agaknya masih sama. Pada 1983, mereka dibantai penembak misterius, belakangan dijadikan provokator. Maka, sesuai dengan janji, apa artinya matamu yang dibalik menjadi dagadu? Dalam bahasa Indonesia, ia bisa diartikan: Dikau mempunyai mata,
Sukses dagadu adalah sukses suatu strategi politik berbahasa. Celakanya, memang suatu misteri yang sudah terbongkar tidak akan pernah menarik lagi seperti sebelumnya. Masalahnya, apakah masih diperlukan suatu bahasa terselubung jika tidak ada lagi hegemoni bahasa yang menindas kebebasan berpikir? Ada-tidaknya penindasan barangkali bisa dilacak dari cara berbahasa di sekitar kita. Terus terang, atau masih terselubung. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 1 Januari 2001  PODCAST REKOMENDASI TEMPO cari-angin marginalia bahasa  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |