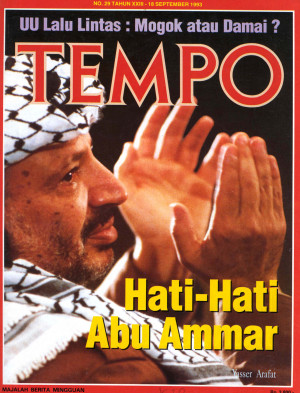ADA perilaku hukum yang menarik. Yaitu tentang protes terhadap suatu undang-undang. Undang-undang No. 14 tahun 1992 yang mengatur perlalulintasan di jalan serta pengangkutan barang, disingkat UULAJ, merupakan contoh undang-undang yang ditolak dan diprotes oleh masyarakat. Tentu saja penolakan itu tidak dilakukan mutlak oleh 180 juta orang Indonesia. Sebagai contoh, ada yang semula anti-UULAJ, tapi, sesudah mengalami musibah di jalan, berbalik menjadi setuju. Bagaimanapun mereka yang menolak telah mencapai kemenangan, dan UULAJ pun ditunda berlakunya sampai satu tahun, hingga 17 September, Jumat pekan ini. Masalah yang banyak disebut sebagai biang penolakan adalah besarnya ancaman denda, dengan jumlah tertinggi Rp 12 juta buat para pengimpor mobil. Masalahnya mulai menarik bila kita juga membandingkan UULAJ tersebut dengan undang-undang yang lain. Menurut catatan saya, sejak tahun 1970-an, ''tarif ancaman denda'' menjadi progresif, dan tak ada yang mencantumkan ancaman di bawah Rp 1 juta. Bahkan, pelanggar ketentuan usaha perasuransian diancam denda maksimum Rp 2,5 miliar. Berikut kutipan UU dan besarnya ancaman denda tertinggi. Di antara para raksasa ancaman denda, ancaman tertinggi pada UULAJ nampak menjadi ''kurus'', tapi justru UU tersebut yang memancing resistensi keras dari masyarakat, yang akhirnya menyebabkan penundaannya. Walhasil, tingginya ancaman denda tidak bisa dijadikan satu-satunya faktor yang menentukan besarnya resistensi masyarakat. Faktor-faktor sosiologis kiranya perlu mendapatkan perhatian sepantasnya. Berbicara mengenai faktor sosiologis tersebut, kita dihadapkan kepada para adresat dari suatu undang-undang, sasaran undang-undang itu. Sebagai perbandingan, mengapa ancaman denda dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang enam kali lebih tinggi daripada UULAJ tidak menimbulkan resistensi atau protes yang besar? Ancaman denda Rp 100 juta dalam UUPLH ditujukan kepada setiap orang, artinya secara potensial siapa saja bisa menjadi ''perusak lingkungan''. Dalam UUPLH, perbuatan yang dikategorikan sebagai merusakkan lingkungan itu sangat luas, sehingga siapa saja, bekerja dalam bidang apa saja, umur berapa saja, cukup ''mudah'' untuk melakukannya. Misalnya yang disebut sebagai menimbulkan ''perubahan dalam sifat fisik'' dari lingkungan, yang tentunya bisa mempunyai spektrum begitu luas, mulai dari mencabut tanaman atau menebang pohon, sampai ke membakar hutan. Jadi, pedang Damokles yang berharga Rp 100 juta itu setiap detik terus berayun-ayun di atas kepala setiap orang Indonesia. Tapi mengapa kehadiran UUPLH itu mulus-mulus saja? Sebaliknya, ancaman maksimum Rp 12 juta UULAJ mengguncangkan seluruh tanah air, itu pun ancaman yang hanya tertuju kepada kelompok yang sangat terbatas, yaitu khususnya para importir kendaraan. Yang mungkin bisa menjelaskan hal itu adalah kaitan antara kehadiran undang-undang dan karakter sosiologis adresat. Karakter sosiologis di sinidi kaitkan pada kemampuan suatu kelompok menampilkan dirinya dalam masyarakat secara menonjol. Publik yang dihadapi oleh UUPLH itu demikian luas sehingga menjadi sangat kabur. Keadaan tersebut sangat mengurangi kemampuan publik untuk bisa mengorganisasikan diri dan tampil di masyarakat, apalagi untuk bersuara keras. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan kelompok para sopir angkutan umum dan pengusaha angkutan yang menjadi semacam ''primadona'' dalam UULAJ. Mereka merupakan kelompok kecil dengan solidaritas tinggi dan jauh lebih ''militan'' daripada publik dalam UUPLH. Masih perlu ditambahkan posisi strategis yang ditempati pekerjaan mereka, yaitu transportasi umum. Faktor berikutnya adalah faktor emosionalitas. Persisnya, keadaan ekonomi mereka umumnya, hingga mereka bisa mengklaim diri sebagai ''orang-orang kecil''. Karena itulah, ''gerakan resistensi'' tersebut bisa memperoleh simpati yang cukup luas, juga masuk ke kalangan yang cukup vokal, yaitu para mahasiswa. Ditambah pemberitaan pers, kompletlah barisan yang membentuk kekuatan resistensi terhadap UULAJ. Gabungan sekalian faktor sosiologis tersebut melepaskan suatu ledakan sosial yang kita ketahui semua. Tapi, sebetulnya, tak ada undang-undang yang tidak menghadapi resistensi masyarakat. Sebab, hakikat hukum antara lain untuk membatasi kebebasan dan keleluasaan orang agar tak bertindak menurut keinginannya sendiri. Masalahnya, ada resistensi yang masih bisa dikelola, ada yang sudah terlalu sulit dikelola tanpa menimbulkan benturan yang besar. Persoalan terutama terletak dalam sosialisasi, atau dalam sosiologi hukum disebut ''masa pelibatan'' (engagement period). Dalam masa itu kesempatan memperlihatkan dan mendiskusikan substansi UULAJ secara lebih proporsional bisa dilakukan. *) Guru besar di Fakultas Hukum Undip
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini