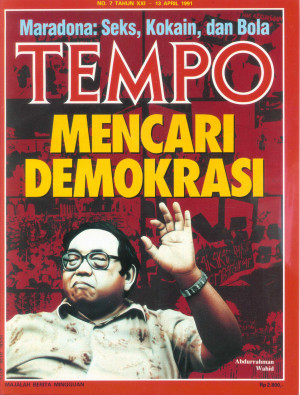TAHUN 1945 adalah tahun ketika orang sibuk, bersiap, bermimpi, tentang perubahan. Di belakang mereka: malam pekat orang ter- jajah. Di depan mereka: fajar menyingsing. "Di Timur matahari, mulai bercahya...," kata sebuah lagu W.R. Supratman, yang ditulis beberapa tahun sebelumnya, membayangkan apa yang akan terjadi. Dengan optimisme. Maka, masa itu memang masa harapan. Sebuah pertemuan para pemimpin masyarakat Indonesia merancang sebuah bentuk bagi Indonesia yang sedang akan merdeka. Jika kita baca kini hasil notulen pertemuan Mei-Juni 1945 itu, yang dikumpulkan oleh Muhammad Yamin, dapat kita lihat bahwa salah satu eksponen optimisme besar itu adalah seorang ahli hukum yang tampaknya cukup disegani: Soepomo. Kelebihan Soepomo bukan hanya karena ia seorang ahli hukum profesional di antara para politisi yang berkumpul hari itu. Soepomo juga seorang ahli hukum adat: ia punya apresiasi yang besar terhadap apa yang "asli Indonesia" -- yang "Timur". Artinya, ia bisa mengibarkan apa yang sangat penting dikibarkan dalam pagi harinya nasionalisme itu: rasa bangga bahwa kita tak kalah dari "Barat'. Maka, "Timur"-nya Soepomo adalah Timur yang indah. Dan "Barat", bagi Soepomo -- seperti anggapan para pemikir politik Indonesia sebelumnya -- adalah lingkungan budaya yang memakai "individualisme". Di situlah berkecamuk keserakahan, pertentangan antaranggota masyarakat, penguasaan oleh segelintir orang kuat atas masyarakat umumnya, kapitalisme, imperialisme, dan seterusnya, dan seterusnya .... "Timur", sebaliknya, bercirikan "kekeluargaan". Di "Timur" tak ada keserakah- an. Tak ada pertentangan antaranggota masyarakat. Tak ada penguasaan oleh segelintir orang kuat atas masyarakat umumnya. Di "Timur", orang besar, atau sang pemimpin, "bersatu jiwa dengan rakyat seluruhnya". Dalam salah satu pidatonya di tahun 1945 itu, Soepomo mengatakan, "Semangat kebatinan, struktur kerohanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti...." Benarkah Soepomo? Bagi saya, kesimpulannya hanya berdasarkan serangkaian teks, yang mengatur ketentuan mana yang harus dilakukan dan mana yang jangan dilakukan. Dengan kata lain, ia mengabaikan kenyataan sejarah, bahwa adat asli yang mencerminkan "struktur kerohanian" bangsa kita itu pada hakikatnya juga hasil suatu proses perkembangan sosial. Bukan mustahil dalam proses itu berlangsung pelbagai konflik kepentingan antara pelbagai kelompok masyarakat. Soepomo tak bisa melihat bahwa masyarakat kita -- seperti masyarakat yang mana pun -- juga mengandung sengketa dalam dirinya. Setidaknya antara pihak yang berkuasa dan tidak. Soepomo mengabaikan sejarah pelbagai pemberontakan petani yang meletus di Jawa di sekitar awal abad ke-20. Ia juga mengabaikan adanya konflik sosial dalam Perang Padri, kesewenang-wenangan penguasa menjelang Perang Diponegoro, kezaliman Amangkurat, benturan elite pribumi dalam Perang Aceh, dan lain-lainnya. Yang lebih menakjubkan ialah bahwa ia, yang menganggap sistem "totaliter" sebagai sistem yang baik, di pertengahan tahun 1945 itu masih memuji Naziisme Hitler baginya, "pikiran nasional sosialis" adalah "cocok dengan alam pikiran ketimuran". Pada pertengahan 1945 itu Soepomo rupanya tak melihat betapa payahnya meninjau asas "kekeluargaan" dalam diri Amangkurat, Hitler, dan kekuasaan Dai Nippon di Asia. Namun, agaknya, ini termasuk dalam demam di Timur-matahari. Soepomo lebih tertarik kepada mitos yang menghibur, yang menceritakan keluhuran, ketimbang sejarah yang menceritakan cacat dan kebusukan. Ia lebih tertarik kepada Das Sollen, apa yang sebaiknya, dan mencampuradukkan itu dengan Das Sein, apa kenyataannya. Maka, ketika ia berkata bahwa para pemimpin Republik Indonesia kelak "harus bersatu jiwa dengan rakyat seluruhnya" ia lupa bahwa yang harus belum tentu bisa dijadikan asumsi. Bagaimana kalau nanti para pemegang kekuasaan negara itu sewenang-wenang terhadap hak-hak rakyat? Ah, tak mungkin, begitulah kurang lebih argumen Soepomo. Maka, ia pun menolak usul Bung Hatta, agar beberapa hak rakyat, misalnya hak menyatakan pendapat, dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. "Pertanyaan yang mempersoalkan bagaimana halnya kalau hak seseorang untuk bersidang dilanggar oleh pemerintah, sebetulnya berdasar atas kecurigaan terhadap negara ...," kata Soepomo mengecam Hatta. "Dengan kata lain, itu suatu pertanyaan yang individualistis." Dengan kata lain, Negara tak boleh dicurigai, Pemerintah tak boleh disyakwasangkai, dan soal hak-hak rakyat, percayalah, kita semua satu keluarga.... Tahun 1945 memang tahun yang tak akan bisa terulang. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini