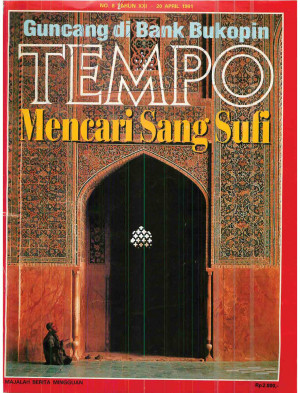SEORANG penjual buah memasang sebuah poster di kedainya: "Buruh Sedunia, Bersatulah!" Adakah ia seorang komunis? Adakah ia seorang warga negara yang patuh? Kita tidak tahu. Penjual buah itu mungkin tak pernah ada. Kalaupun ada, ia seorang Ceko-Slovakia, barangkali tinggal di sebuah sudut jalan di Praha. Ia muncul dalam sebuah tulisan Vaclav Havel, Kekuasaan Orang-Orang yang tak Berkuasa, yang ditulisnya ketika ia masih seorang sastrawan pembangkang, yang berkali-kali kena tindak, dulu ketika ia belum jadi presiden republik. Havel juga hanya menyebut sang penjual buah sebagai contoh: jenis manusia yang lazim hidup dalam sebuah sistem " pascatotaliter" -- sebuah sistem sonder demokrasi, tapi juga tanpa kediktaturan yang lazim. Dalam sistem itu, yang berjalan adalah kompromi-kompromi otomatis. Si penjual buah memasang poster itu tak dengan sendirinya, karena yakin bahwa buruh sedunia perlu bersatu. Ia hanya melakukan itu karena orang lain melakukannya -- seperti seorang camat nun di sudut Aceh atau Irian memasang slogan Visit Indonesia Year 1991, tanpa harus yakin bahwa turisme sangat penting bagi hidupnya dan masyarakatnya. Sebab itu, adalah bagian dari ritual kepatuhan yang sudah digariskan oleh pihak "atas" atau oleh tekanan orang sekitar. Maka, si penjual buah tak peduli apa sebenarnya makna kalimat dalam poster itu. Ia hanya mengembik lantaran ia merasa begitulah adat hidup di kandang kambing -- hingga ia pun, secara pelan-pelan, mentransformasikan diri jadi kambing. Ia takut untuk jadi lain-dari-yang-lain, jadi kontroversial, nyentrik, ndugal dan tak patuh. Pesan "Buruh Sedunia, Bersatulah" bukannya ia tujukan kepada para buruh yang kebetulan belanja di kedainya -- sebagaimana halnya pesan Visit Indonesia Year 1991 yang dipasang di dusun Aceh (dalam bahasa Inggris, tentu) tak ditujukan kepada turis, apalagi penduduk setempat. Isi kalimat dalam poster itu tak penting. Sebab, pesan yang sebenarnya dari poster itu adalah kehadirannya itu sendiri. Ia semacam isyarat. Jika diterjemahkan dalam kata-kata, isyarat itu berbunyi, (dalam kata-kata Havel): "Saya, penjual buah XY, tinggal di sini dan tahu apa yang harus saya lakukan. Saya berbuat menurut cara yang diharapkan dari diri saya.... Saya patuh dan sebab itu saya berhak untuk tidak diganggu". Tapi mengapa isyarat harus disusun sebagai isyarat? Mengapa poster di kedai buah itu tak berbunyi, "Saya takut dan sebab itu taat penuh"? Dalam analisa Havel, seandainya poster itu berbunyi demikian, sang penjual buah tak akan bisa bersikap acuh tak acuh kepada isi kalimatnya. Seandainya poster itu berbunyi demikian, si penjual buah akan merasa malu, sebab, kata Havel, "ia juga seorang manusia dan karenanya punya harga diri." Agar rasa malu itu tak terbit, isyarat pun dipilih. Juga penting: teksnya setidaknya bisa memberi peluang bagi si penjual buah untuk membela diri. Misalnya, dengan mengatakan, "Apa salahnya, sih, bila buruh sedunia bersatu?" Dengan demikian, poster itu menolong si penjual buah untuk menyembunyikan betapa rapuh dasar kepatuhannya. Ia bukan saja takut terhadap tilikan orang lain, tapi juga terhadap saat ketika ia mawas dirinya sendiri. Ia ingin mengenakan sesuatu yang lebih hebat ketimbang sekadar perisai. Lebih hebat dari sekadar kedok. Ia ingin pakai sesuatu yang luhur, yang sebenarnya baju ziarah gemerlap. Dan itu, menurut Havel, adalah ideologi. Di depan tilikan hati nurani, ideologi berfungsi sebagai dalih. Ideologi menyediakan suatu ilusi, bahwa sistem yang berlaku itu "selaras" dengan tertib hidup alam semesta dan manusia. Ilusi itu dipegang baik oleh yang mendukung sistem maupun yang jadi korban sistem itu. Maka, justalah yang menopang permukaan yang rata dan rapi itu. Dan sistem yang ditegakkan di atas permukaan itu pun berusaha agar justa itu tak retak sedikit pun. Sang sistem takut ambles. Sebab, apa gerangan yang bakal terjadi seandainya si penjual buah menulis pada posternya, terus terang, Saya takut dan sebab itu berpura-pura taat? Guncangan akan timbul. Biarpun si penjual buah itu kerempeng dan tak berwibawa, ucapannya akan tiba-tiba memberikan alternatif yang selama ini disingkirkan -- sebuah alternatif yang pada hakikatnya cocok dengan batin orang banyak: batin yang tak ingin bohong terus-menerus, tak ingin jadi kambing terus-menerus. Batin yang merindukan bahwa embik harus diganti dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan martabat manusia. Maka, benar seperti yang dikatakan Havel, "Di bawah permukaan rapi kehidupan dalam kebohongan, tertidur lapisan hidup yang tak nampak". Di sana bersembunyi sikap terbuka untuk mengakui kebenaran. Dan di sanalah hidup batin orang-orang yang tak berkuasa, tak berkekuatan. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini