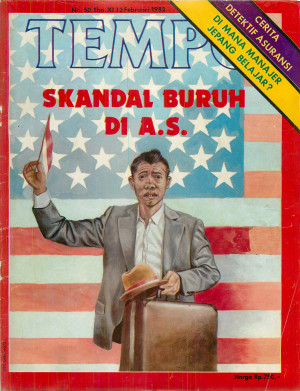DORNA, guru yang baik, mengajar para muridnya bagaimana
membidik. "Ada seekor burung kutilang di dahan sana," katanya.
"Siapkan anak panah dan jemparingmu."
Para murid siap. Mereka memandang ke arah yang ditunjukkan sang
pendeta.
"Apa yang kalian lihat?," tanya Dorna.
"Burung di dahan itu," sahut para murid, hampir serempak.
Syahdan, hanya Arjuna -- seorang murid yang serius -- yang
menjawab lain. Putra Pandu yang tak banyak omong itu menyahut
pelan, "Hamba melihat sepotong leher kutilang, guru."
Dan ia benar. Ia ternyata bisa memanah sang burung tepat di
bawah kepalanya. Leher itu patah, binatang itu terjungkal. Si
pemanah telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. "Itulah
ilmu, anak-anakku," konon kata Dorna. "Suatu proses yang
memerlukan pemusatan pikiran, pancaindera dan kemauan."
Kisah itu berakhir. Tapi moralnya menjangkau ke tengah kita:
bahwa menuntut ilmu memang memerlukan semacam pembersihan diri
-- penyingkiran pelbagai macam distraksi, segala hal yang
mengakibatkan ikhtiar kita tak punya fokus. Para ibu dan bapak
sering mengisahkan pula bagaimana seorang kesatria bertapa untuk
menambah kesaktiannya. "Dia akan duduk, diam bagaikan arca.
Pandangnya hanya melihat ke ujung hidung."
Mungkin dengan dasar cerita seperti itulah Daoed Joesoef dan
Nugroho Notosusanto menghendaki para mahasiswa tak usah ikut
dalam "politik praktis" di sekolah. Pusatkan dirimu. Tetapkanlah
pandargmu. Arahkan minatmu hanya untuk ilmu yang kau pelajari.
Jangan berisik. Jaiigan tengok kiri jangan tengok kanan.
Konsentrasi, konsentrasi ! Pada suatu saat nanti kau akan lulus
dari proses ini. Setelah itu, bukan urusan lembaga perguruan
tinggi lagi unk mengaturmu . . .
Tapi kenapa tetap ada saja mahasiswa yang menolak gagasan
seperti itu?
Mungkin soalnya sederhana saja: bukan karena para mahasiswa itu
anak titipan kekuatan politik dari luar. Mereka toh bukan lagi
seperti mahasiswa di tahun 50 dan 60-an. Mereka tak berada di
tengah situasi ketika partai politik berada di pucuk pamornya,
dan punya kader di kalangan universitas. Mereka adalah anak-anak
masa kini, ketika partai politik rudin dan memikirkan kursi saja
sudah susah.
Maka jika para mahasiswa itu tak betah untuk hanya berada di
laboratoria (yang memang apak), jika mereka enggan terus
berkerut di depan para pengajar (yang memang itu-itu
juga)--agaknya pertama-tama karena kampus terlalu santai dan
mereka teramat muda.
Di masyarakat yang tak mengenal universitas, di pedusunan yang
jauh, anak-anak seusia mereka langsung terjun "jadi orang". Di
masyarakat tempat kampus-kampus berdiri, kemahasiswaan praktis
merupakan perpanjangan masa transisi sebelum dewasa.
Perpanjangan itu (yang juga berarti penundaan) dalam dirinya
mengandung benih keresahan. Terutama dalam masyarakat ini. Di
satu pihak masyarakat memandang perguruan tinggi dengan begitu
hormat: para pengajar di sana disebut sebagai mahaguru dan murid
sebagai mahasiswa. Di lain pihak, masyarakat di luar itu tak
dapat segera memberi peran besar kepada orang-orang yang
terhormat itu.
Tak heran bila kampus terkena oleh pelbagai ilusi. Ilusi yang
terbesar ialah ilusi tentang kekuatan. Ilusi itu kadang sehat:
ia bisa memberi semangat bahwa universitas bukan alat birokrasi
yang tanpa kebebasan dan kreativitas. Tapi sampai tingkat
tertentu ilusi itu menyebabkan para mahasiswa tak bisa
membedakan politik sebagai gashuku dan politik di pertempuran
yang sebenarnya.
Dalam kehidupan politik yang sebenarnya, kampus dan
atribut-atributnya (termasuk jaket) tidaklah dengan sendirinya
sumber legitimasi kekuasaan. Untuk legitimasi itu perlu proses
yang lebih panjang. Apalagi untuk kekuasaan itu sendiri.
Arjuna berhasil belajar memanah, bukan dengan begitu saja. Toh
dia tak berhenti di sana. Dia beberapa kali bertapa. Dia ikut
menjalani pembuangan dalam hutan. Apa gerangan yang dilihatnya
selama itu, dengan begitu sabar dan tekun?
"Hamba melihat sepotong leher musuh itu, guru."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini