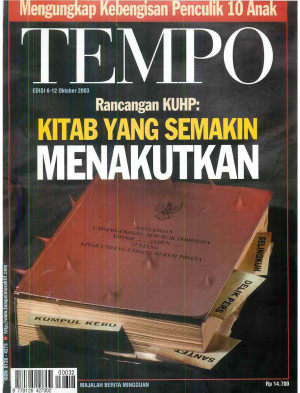Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dua gelegar mengagetkan seperti petir—api murub—asap hitam membubung—pekik berpuluh-puluh suara kesakitan yang serentak.... Kebuasan itu memang bisa tampak seperti sebuah spectacle, baik di New York pada tahun 2001 maupun di Bali pada tahun 2002.
Kita seakan-akan menyaksikan lukisan Hutan Terbakar Raden Saleh dalam tiga dimensi, atau satu adegan opera Götterdämmerung karya Wagner. Mungkin sebab itu, ketika dua pesawat Boeing 767 ditabrakkan para teroris ke Menara Kembar di New York, dan bangunan kukuh itu runtuh, dan 3.000 mati, Stockhausen, komponis Jerman terkenal itu, berucap, "Itulah karya seni terbesar untuk seluruh kosmos."
Tapi orang marah mendengarnya. Teror sebagai karya seni, korban sebagai tontonan, para pembunuh sejajar dengan para jenius? Stockhausen dikecam; sejak itu ia tutup mulut. Tapi salahkah sang komponis untuk mengatakan demikian, di zaman ketika setiap benda, setiap tindak, dapat dinyatakan sebagai "seni"? Pada tahun 1911 pelukis Marcel Duchamp mengikutsertakan sebuah sentoran kencing ke dalam sebuah pameran seni rupa di New York. Sebuah "revolusi" pun terjadi. Pada tahun 2001 seharusnya tak mengejutkan lagi jika Stockhausen membaptiskan penghancuran Menara Kembar sebagai sebuah "karya seni".
Apa gerangan "seni" dan apa gerangan yang bukan? Di museum seni rupa Tate Modern, London, ada sebuah karya Paul McCarthy, Rocky (1976). Karya itu sebuah rekaman video: si seniman telanjang, memasang sarung tinju, wajahnya ditutup topeng binatang; seraya seakan-akan menyerang memukul, ia meninju tubuhnya sendiri. Kini orang bisa menunjukkan inilah beda antara McCarthy dan seorang Palestina yang meledakkan dirinya sendiri: Rocky diletakkan di Tate Modern karena ia dinyatakan sebagai "seni" dan dibuat oleh seorang seniman.
Itulah hasil sampingan "revolusi" Duchamp: berseni atau tidaknya X tak lagi ditentukan oleh indah atau tidaknya X, melainkan sepenuhnya oleh sebuah fatwa. Bagaimana X menyentuh hati para penikmat atau pengamat, tak lagi penting. Hubungan antara X dan penikmat bahkan praktis tak dibicarakan. Sang seniman adalah Sang Penentu. Beberapa tahun yang lalu Danarto memasang sebuah kanvas kosong, putih, di sebuah pameran Taman Ismail Marzuki. Karena ia seorang Danarto—waktu itu ia telah diakui sebagai sastrawan yang memulai penulisan "realisme magis" di Indonesia dan juga seorang pelukis—kita pun diyakinkan bahwa kanvas kosong itu sesuatu yang punya potensi untuk menyentuh hati dan menimbulkan permenungan, misalnya tentang "sepi" dan "ketiadaan".
Dengan begitu sang seniman diletakkan dalam posisi dengan fondasi kukuh. Tapi sebenarnya itu hanyalah separuh cerita. Separuh lainnya menunjukkan bahwa posisi itu didapatnya juga karena ada pusat kesenian, atau sebuah galeri ternama, atau karena seorang kurator yang johari dan sejumlah kritikus yang menulis di media tenar. Diakui atau tidak, sang seniman adalah sebuah tokoh yang ditopang oleh institusi dan geografi yang "tepat". Seandainya Danarto menggantungkan pigura kosongnya di pojok stasiun bus, orang mungkin akan memakainya untuk tempat pengumuman "Awas Copet!"
Seperti Danarto, Stockhausen punya otoritas, Stockhausen bisa dibungkam, atau jadi lucu, tapi bagaimanapun, sebuah fatwa tetap krusial. Gelegar dan kebuasan yang spektakuler 11 September 2001 itu memang bisa dianggap bukan "karya seni", sebab Muhammad Atta dan kawan-kawannya tak menyatakan diri mereka seniman dan tak hendak mempersembahkan teror itu sebagai sebuah performance. Tapi pentingkah niat mereka? Harold Rosenberg, kritikus seni rupa untuk The New Yorker, pernah mengatakan bahwa sepotong kayu yang diketemukan di pesisir bisa saja jadi "seni".
Dengan kata lain, selama sebuah otoritas membaptiskan sesuatu sebagai "seni" atau "seni modern"—sepotong kayu di pasir, sebuah jembatan yang dibungkus terpal, sebuah piano yang dirusak, mungkin juga sebuah gedung yang dihancurkan—semuanya bisa dikeramatkan dalam wacana kesenian.
Memang di situ tampak ada otoritas yang begitu kuasa, hingga bisa memfatwakan X jadi Y begitu saja. Tapi yang merisaukan bukan itu. Yang merisaukan juga bukan anarki dalam menilai. Susan Buck-Morss, dalam Thinking Past Terror: Islamism and Critical Theory on the Left (Verso, 2003), dengan tepat menunjukkan ada yang lebih mencemaskan: pembenaran "ontologis".
Pembenaran ontologis adalah yang mengatakan, "Karena X ada di Taman Ismail Marzuki, maka X sebuah karya seni." Ini berbeda dengan pembenaran "epistemologis", yang mengatakan, "Karena X adalah sebuah karya seni, maka ia ada di Taman Ismail Marzuki."
Pembenaran ontologis juga bisa kita temukan dalam pernyataan ini: "Karena AS negeri yang beradab, ia menghormati hak asasi manusia." Pembenaran epistemologis: "Karena AS menghormati hak asasi manusia, ia sebuah negeri yang beradab."
Dalam pembenaran ontologis, apa pun yang dilakukan AS, karena negeri ini menurut definsinya "beradab", tak akan melanggar hak asasi. Sebaliknya dalam pembenaran epistemologis, masih ada kemungkinan untuk dipersoalkan, benarkah AS sebuah negeri yang beradab.
Sama halnya dengan perkara lain: "Karena aku berjihad, maka jalanku secara definisi suci." Ini berbeda dengan pernyataan ini: "Karena yang kujalankan sesuatu yang suci, maka aku berjihad." Statemen terakhir ini membuka diri untuk ditelaah, benarkah yang kujalankan "sesuatu yang suci."
Pembenaran epistemologis memang mengandung keterbukaan, pertanyaan, dan sikap kritis—juga kepada diri sendiri. Pembenaran ontologis tidak. Dan agaknya itulah yang berlangsung ketika "aku" berilusi bahwa "aku"-lah yang punya fondasi untuk menentukan yang indah dan tak indah, yang suci dan tak suci. Dari sini apa pun akan tampak sah, juga kekejaman, gelegar bom, jerit kematian....
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo