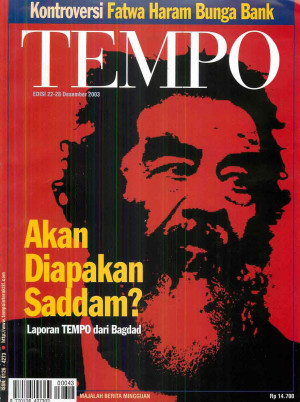Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JIKA Anda tergolong mereka yang gemar menjelajah selera musik ke mana-mana, jangan percayai MTV sepenuhnya. Soalnya, stasiun televisi anak nongkrong itu mirip biro perjalanan yang menawarkan beragam paket tamasya tapi sesungguhnya cuma memberikan pilihan tempat tujuan yang ada di dunia ini secara terbatas. Kita memang bisa menyimak aneka musik, 24 jam sehari. Tapi apa yang lalu-lalang dengan genit maupun ingar-bingar di layar kaca itu hampir semuanya adalah pesona yang sudah disiapkan sedemikian rupa, yakni daya tarik yang dipilih, ditata, didandani, dan dikemas secara industri sehingga siapa pun yang menikmatinya percaya memang sedang berada di "surga". Maka, harap maklum jika di sana orang tak menemukan genre musik progressive rock.
Radio sebenarnya masih lebih baik; beberapa stasiun punya program khusus yang memutar dan mendiskusikan komposisi-komposisi progressive rock. Tapi jatah waktu siarnya sangat singkat dibandingkan dengan keseluruhan jam dan hari siar yang ada—misalnya 1-2 jam sekali sepekan. Untuk progressive rock, yang di antara komposisinya ada yang menelan waktu 20 hingga 30 menit (walau jarang, sih), program-program itu jadi sulit berpengaruh di kalangan pendengar, kecuali mereka yang memang sudah tergolong "umat lama".
Setidaknya, ada tiga hal yang membuat progressive rock penting. Pertama, bukan saja genre ini tak pernah mati, meski tergulung dari mainstream musik rock oleh gelombang punk dan new wave pada akhir 1970-an, tapi bahkan terus berkembang dan kini boleh dibilang menjalani masa hidupnya yang lain. Kedua, sesungguhnya pada progressive rock kita bisa melihat semua kemungkinan eksplorasi musik rock, berbagai eksperimen teknik, maupun tema yang hanya mungkin lahir dari pikiran yang terbuka—jika bukan semata karena jagonya pemain bermain instrumen. Ketiga, khusus di Indonesia, inilah dunia yang dalam dua tahun terakhir memperlihatkan hiruk-pikuk berdirinya Indonesian Progressive Society, berlangsungnya Indonesia Progressive Festival, serta rilis album grup-grup baru.
Progressive rock (atau rock progresif, jika mengikuti aturan pengalihan bahasa; tapi, hei, siapa peduli) boleh dibilang genre musik yang nyaris hidup di semestanya sendiri. Dua orang bisa memberikan definisi yang berbeda. Satu saja pertanyaan terlontar, di forum mana pun, pada kali yang kesekian juga, diskusi bisa berlangsung panjang. Tapi, dengan mendengar, siapa saja cenderung mudah sepakat mana yang masuk kriteria progressive rock dan mana yang bukan.
Pada hakikatnya, progressive rock adalah genre yang mengambil banyak gaya musik sebagai unsur pembentuknya, bisa klasik, jazz, folk... apa saja, dan—tentu saja—rock itu sendiri. Durasi lagu-lagunya umumnya panjang, (dulu) satu lagu saja bisa menghabiskan satu sisi album berformat vinyl atau piringan hitam (pernah ada kelakar, misalnya, bahwa membeli Close to the Edge, salah satu album klasik progressive rock dari grup Yes, sayang uangnya karena cuma mendapat tiga lagu). Dalam banyak kasus, lagu-lagunya juga bermula ke sesuatu arah tapi lalu berakhir dengan hal lain yang sama sekali berbeda. Identitas lain adalah birama yang bisa berubah-ubah dalam satu lagu dan virtuositas para instrumentalisnya. Semua kerumitan itu membuat orang memberikan julukan musik atas angin.
Lahir ketika gairah untuk melompat ke kancah baru dalam musik begitu meluap, menjelang akhir 1960-an, progressive rock bermula dari sukses eksperimen The Beatles dalam Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967). Album yang menurut majalah Rolling Stone "mendefinisikan dengan mewah optimisme revolusioner psikedelia dan seketika menyebarkan gospel cinta, LSD, spiritualitas Timur, dan gitar listrik ke seluruh dunia" inilah yang waktu itu seperti menimbulkan sebuah perlombaan. Banyak grup mencoba membuat karya yang lebih mendobrak, di antaranya The Moody Blues dan The Nice.
Persaingan berlangsung singkat. King Crimson menyalip semua upaya yang ada ketika, pada 1969, grup baru yang dimotori gitaris Robert Fripp ini merilis In the Court of the Crimson King. Sebuah big bang. Sampul album yang mengekspos secara provokatif ekspresi ketakutan sesosok muka berwarna merah berbicara dengan sendirinya tentang apa yang terkandung di dalam kemasan. Dalam suatu kesempatan, Fripp belakangan melukiskannya sebagai "sebuah serangan sempurna ke indra keenam". Mungkin ia mendramatisasi. Tapi yang pasti In the Court lalu menjadi landasan bagi sebuah genre yang kini disebut progressive rock.
Pada 1970-an progressive rock menyebar luas, memikat bukan saja penggemar baru tapi juga industri rekaman (Chrysalis, Atlantic Records, Virgin Records). Grup yang muncul dan bereksperimen sebelum King Crimson pun satu per satu memperoleh kesempatannya sendiri untuk mencetak sukses, masing-masing dengan ciri khasnya—yang kemudian menjadi dasar pengelompokan (subgenre) di dalam progressive rock. Pink Floyd, dengan Dark Side of the Moon (1973), bahkan masuk ke deretan artis dengan album paling laku dalam sejarah rock. Grup lain yang menyumbangkan karya monumental sekaligus menghimpun penggemar fanatik, kalaupun tak menjadi hit maker, di antaranya adalah Yes, Genesis, Van Der Graaf Generator, Gentle Giant, Jethro Tull, dan Emerson, Lake and Palmer. Dari Amerika Utara bisa disebut Kansas dan Rush.
Popularitas grup-grup itu masuk juga di Indonesia pada dasawarsa yang sama, sebagian malah hingga 1980-an. Yang mesti disebut ikut berperan dalam penyebarannya adalah majalah Aktuil, "bacaan wajib" anak muda gaul pada 1970-an, dan label rekaman Yess, yang khusus merekam dan menjual album-album progressive rock. Beberapa grup rock pun terpengaruh, sebagian malah biasa diasosiasikan dengan salah satu dari kampiun progressive rock itu, misalnya SAS (Emerson, Lake and Palmer), God Bless (Kansas, Genesis), dan Giant Step (Gentle Giant). Sejumlah album sempat diproduksi dengan "nyawa" progressive rock, di antaranya Guruh Gipsy (1977), Titik Api (Harry Roesli, 1977), Giant on the Move (Giant Step, 1978), Rara Ragadi (1978), Cermin (God Bless, 1980), Produk Hijau (Wow!, 1983), dan Laron-laron (Makara, 1986).
Zaman yang riuh itulah yang kini diingat orang, setelah Discus, grup yang didirikan oleh gitaris Iwan Hasan pada 1996, menjadi pelopor bangkitnya kembali progressive rock di Indonesia, dengan merilis 1st pada 1999 dan ...tot licht! pada 2003. Menyusul Discus, lewat label hasil kerja sama Indonesian Progressive Society dan Sony Music Indonesia, tahun ini, album In Memoriam, Purgatory, dan tak lama lagi Imanissimo telah masuk pasar. Sebelumnya beberapa grup seperti Cozy Street Corner, Pendulum, Kekal, Smesta--juga In Memoriam dan Imanissimo—malah sudah mengedarkan demo atau berjualan album lewat jalur independen.
Tentu saja wajar jika ada harapan yang menggelembung. Ketika progressive rock mati suri, dan para pelopornya dan generasi kedua pengusungnya harus berjuang di "bawah tanah" pada 1980-an, atau menyeberang dan bermain-main dengan pop, penggemarnya (para proggers) di Indonesia boleh dibilang terserang virus bete. Kecuali satu-dua kelompok baru, misalnya Marillion, mereka praktis tak mendapatkan lagi album-album terbaik yang pernah ada, bisa karena memang incommunicado, tapi juga terhalang oleh berlakunya royalti untuk setiap penjualan rekaman (mana ada label yang mau membayar royalti dengan imbalan hasil penjualan memble). Grup-grup lokal pun nol besar. Keadaan berubah setelah sejak awal 1990-an bermunculan penerus progressive rock di mana-mana, di antaranya para pengibar "panji-panji" subgenre baru progressive metal, dan Internet memberikan kemudahan untuk mendapatkan karya-karya baru. Nama Dream Theater, Pain of Salvation, Spock's Beard, The Flower Kings, dan masih banyak lagi, segera masuk ke perpustakaan kalangan proggers. Rilis oleh label besar berturut-turut empat album grup lokal dalam setahun ini jelas menyempurnakan daftar belanjaan yang tadinya cuma berupa album grup asing.
Ada alasan lain. Menyimak album-album lokal itu sama dengan menjajal medan petualangan baru. Ada excitement. Rasa penasaran dan ekspektasi macam-macam bertemu secara klop dengan beragam kejutan, dari segi komposisi maupun tema, juga bunyi-bunyian.
Baik secara musikal, konsep, maupun eksekusinya, mereka layak memperoleh dua acungan jempol (lima jika perlu, dan jika Anda punya sebanyak itu). Kalaupun di sana-sini terasa nuansa Dream Theater, Mr. Bungle, Dixie Dregs, After Crying, jazz, fusion, metal, atau apa saja, ya, itu natural. Kecuali peminat baru yang langsung melompat dari wilayah yang biasa-biasa saja, tak ada telinga atau gagasan yang steril dari gangguan suara-suara dan bebunyian yang sudah ada sebelumnya. Menurut B.B. King, salah satu legenda blues yang namanya kerap disebut sebagai sumber inspirasi, "Tidak ada orang yang mencuri; kita semua ini meminjam."
Meski begitu, agar optimisme tak berlebihan, harus disebut bahwa situasinya berbeda dibandingkan dengan 30-an tahun lalu. Kini tak ada lagi revolusi serius di kalangan anak muda, pemberontak meluas terhadap kemapanan yang melahirkan bermacam gaya musik. Progressive rock bukan lagi sesuatu yang sama sekali baru, yang punya daya pikat tak tertahankan; kecuali subgenre progresif yang mengeksplorasi metal yang masih digandrungi anak muda, lebih banyak subgenre yang cenderung sulit untuk menerobos selera anak muda. Sederhana saja, jika audiens tetap terbatas pada generasi 1970-an, jangkauannya pun tak akan jauh—jika bukannya malah tiarap lagi.
Label khusus, dalam situasi begitu, barulah satu hal—seperti Virgin Records yang, dulu, didirikan hanya untuk mengakomodasi progressive rock. Festival pun, yang sempat dua kali digelar, pada tahun 2001 dan 2002, belum berarti apa-apa jika penyelenggaraannya tak bisa rutin. Supaya hidup kali ini bertahan lama, dan generasi baru para petualang bisa digaet, sembari terus membuka tujuan-tujuan eksotis lain, masih banyak yang mesti dilakukan. Berupaya keluar dari kelaziman menjadi alternatif yang penting. Sebab, meminjam kata-kata Frank Zappa—gitaris, komposer, dan salah satu figur terkemuka dalam eksperimen dengan rock—tanpa itu tak ada yang namanya progresif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo