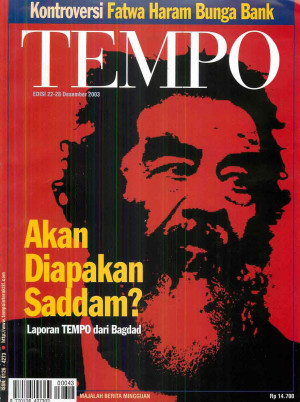Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEPANJANG 2003 panggung seni rupa di Indonesia tampak berupaya memperluas dataran permainannya. Seraya menunjukkan bahwa di sana tak cuma ada sejumlah keramaian, agaknya juga tumbuh kesadaran untuk lebih ngotot memahami pelik sekaligus beragamnya praktek seni rupa kita. Ingatlah umpamanya CP Open Biennale "Interpellation" dan Festival Seni Rupa Video "OK", yang berlangsung di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta.
CP Open Biennale adalah bienal seni rupa internasional (nasional "plus") yang pertama di Indonesia, yang telah berjasa mencantumkan ibu kota ini—menurut The New York Times—"on the map". Jakarta kini menjadi satu titik yang berdenyut dalam rangkaian peristiwa seni rupa internasional yang perlu ditengarai dan ditengok. Tetapi, sesudah rombongan pertama perupa kontemporer Indonesia yang mulai memasuki berbagai forum seni rupa internasional di awal 1990-an (Heri Dono, Arahmaiani, Dadang Christanto, Krisna Murti, dan lain-lain), berikutnya tak tampak gelombang perupa yang lebih besar mengekor di belakang jalur itu.
Sementara "permintaan" terhadap para seniman Asia tetap tinggi di negeri-negeri Barat yang selama ini memagari diri dengan ukuran-ukuran yang mereka anggap paling klop alias universal, kita mungkin nyaris hafal membaca, cuma perupa kita yang itu-itu saja yang dianggap memenuhi "syarat". Pada tahun ini, untuk pertama kalinya empat perupa kita (Arahmaiani, Dadang Christanto, Made Wianta, Tisna Sanjaya) tampil di Paviliun Indonesia dalam Bienal Venezia ke-50, Italia; sedangkan Heri Dono muncul dalam pameran ini di luar konteks nasional.
Secara sambil lalu perupa Heri Dono pernah menyebutnya dengan metafora pergantian musim. Ada kalanya musim semi datang ditandai meruahnya seniman yang "naik kelas" ke forum internasional, diikuti oleh musim rontok para seniman ini berdasarkan seleksi alam. Sebuah simposium seni rupa internasional di Galeri Nasional Indonesia mengiringi pameran CP Open Biennale, September silam, memperdebatkan para kurator internasional yang cenderung bernafsu menghemat ongkos seraya memendekkan jalur dengan cara mengundang seniman favorit yang sudah mereka kenal. Suatu campuran antara seleksi alam dan politik inklusi/eksklusi boleh jadi adalah pilihan jawaban paling mudah.
Jika forum internasional bukanlah suatu tapal batas terakhir bagi karier seorang perupa kontemporer, ke mana para seniman itu akan pergi? Tentunya tak cukup wigati menimbang kuota besar atau kecil yang disediakan oleh kantong-kantong seni rupa di luar untuk menakar perkembangan dan peliknya sosok kita sendiri. Maka yang kita perlukan adalah juga panggung permainan yang bermutu atau menantang di dalam negeri sendiri.
Dalam hal ini baiklah kita menoleh ke Cina, yang sejak dekade 1990 agresif menjajakan para perupanya keluar seraya tak lupa menggarap ladangnya sendiri di dalam. Setelah pameran China/Avant-Garde (1989) di National Art Gallery, Beijing, yang menenggelamkan para perupa Cina ke kolong gerakan bawah tanah, diikuti oleh embargo politik negara-negara Barat akibat peristiwa pembantaian gerakan prodemokrasi di Tiananmen, seni rupa kontemporer Cina tampak beroleh dorongan angin baru melalui sejumlah pameran ke luar. Semenjak pameran-pameran Mao Goes Pop di Museum Seni Rupa Kontemporer Sydney, Australia (1993), dan terutama China's New Art, Post 1989 yang berkeliling ke berbagai negara di Eropa dan Amerika (1994-97), perupa Cina susul-menyusul menarik perhatian dunia seni rupa di Barat. Forum bienal lokal maupun internasional di dalam negeri pun dipacu.
Jika gagasan lawatan bagi karya sejumlah perupa kontemporer kita seperti pameran "Awas! Recent Art from Indonesia" (1999-2002) ke berbagai tempat di Asia, Australia, dan Eropa mungkin masih akan lama terulang, menyediakan forum bermutu di dalam negeri sendiri kiranya perlu. Itulah agaknya peluang sekaligus manfaat yang tampak disediakan melalui CP Open Biennale. Di dalam forum mana para perupa yang namanya belum dikenal (namun karyanya bermutu) dapat bersanding dengan para perupa "internasional" ternama kalau bukan kita sendiri yang menggagasnya?
Forum penting lainnya adalah Festival Seni Rupa Video "OK" pada Juli silam, yang berhasil memanfaatkan jaringan yang utamanya digagas, dikelola, serta diperluas oleh kalangan seniman sendiri (artist's initiative). Festival ini, yang diikuti oleh puluhan perupa video dari dalam dan luar negeri serta komunitas perupa video seperti Pulse, Afrika Selatan; Video Art Centre, Tokyo; dan Videotage, Hong Kong; diselenggarakan oleh kelompok "ruangrupa" di Jakarta.
Kita tahu jenis seni rupa yang disebut sebagai media baru telah tumbuh belakangan ini, khususnya di kalangan perupa muda di Jakarta dan Bandung, yang menaruh minat terhadap perkembangan teknologi informasi serta budaya pemasaran citra alias hiburan, yang seluruhnya sedang berkembang ke arah bahasa multimedia. Jenis seni ini cukup sering dipahami sebagai suatu genre seni rupa yang dicari kaitannya dalam sejarah seni dengan sebuah genre yang lain. Namun suatu pemahaman yang lebih kontekstual perihal peleburan dikotomi antara "budaya" (atau seni) dan "bukan budaya" atau nonseni (misalnya perkembangan seni yang memetik inspirasi dan mediumnya dari sejumlah instrumen perkembangan teknologi), akan melihatnya sebagai sebuah link, yakni seni yang mengaitkan dirinya dengan berbagai elemen dan gagasan teknologi serta ragam budaya mutakhir, yang sering tampak tak ada hubungannya dengan perkembangan seni sebelumnya, apalagi "seni tinggi".
Tatkala perangkat televisi mulai masuk ke dalam karya seni, sebuah periode kompleks perihal persepsi dan penciptaan seni dan nonseni tengah terjadi. Misalnya seni rakitan, lingkungan, happening, musik konkret, puisi konkret, seni pop, gerakan seni Fluxus, sampai film-film avantgarde. Pada masa di sekitar 1960-an itulah wacana seni rupa video mulai di Barat.
Festival Seni Rupa Video "OK" (di Bandung pada Agustus 2002 telah berlangsung bavf-NAF #1 atau The Bandung Video, Film, and New Media Art Forum) menyadarakan kita akan mekarnya sebuah link baru di kalangan perupa muda yang mempunyai habitat dan cara diskusi yang berbeda dengan seniman-seniman yang selama ini berada di sebuah genre tertentu. Ade Dermawan dari "ruangrupa" menyebutnya sebagai para perupa yang tertarik pada "masalah-masalah persentuhan praktek seni rupa dengan masyarakat urban dan budaya kontemporer".
Saya juga ingin mengutip Greg Streak, perupa video yang tinggal dan bekerja di Durban, Afrika Selatan, yang memahami upaya komunitas "ruangrupa" ini dengan kalimat yang tepat: "... Mereka sukar dijelaskan karena mereka melompat keluar dari 'komidi putar' ketika penuh, dan kita tidak melihat mereka semenjak itu, meskipun tahu mereka ada di sekitar kita. 'Nonkonformis' yang pandai menyesuaikan diri...."
Namun komunitas "ruangrupa" barangkali bukanlah jenis yang pandai menyesuaikan diri, karena mereka membawa kepada kita pusat perhatian lain yang tak ada di dalam pasar malam, melainkan terhampar di sepanjang jalan ramai di tengah kota, tempat orang-orang mengagumi gambar-gambar yang terus-menerus berpendar dari toko-toko televisi yang dipenuhi dengan litani musik, film, tontonan, iklan, dengan tata warna yang seindah warna aslinya. Mungkin saja di tempat-tempat semacam itulah, berpendar juga sebuah kalimat dari Umberto Eco, "... the frantic desire for the Almost Real arises only as a neurotic reaction to the vacuum of memories; the Absolute Fake is offspring of the unhappy awareness of a present without depth."
Demikianlah sebuah kurasi pameran di bawah panji-panji seperti trienal, bienal, dan festival, yang berusaha menampilkan irisan tertentu perkembangan seni rupa mutakhir, justru sering tak perlu mengadopsi genre seni yang mapan, dan diam-diam telah mengakhiri dan menetapkan batas-batas representasinya sendiri. Dengan memahami potongan-potongan penampang semacam ini sebuah trienal malahan mengkhususkan diri pada medium tertentu yang selama ini cenderung dilupakan, misalnya seni grafis seperti pada Triennale Seni Grafis di Bentara Budaya Jakarta. Justru suatu genre yang selama ini tampak mendiami wilayah yang tak populer dapat dikurasi dan didorong untuk menemui publiknya sendiri, yang selama ini tersembunyi atau barangkali terhalang oleh tebalnya dinding kemapanan tertentu.
Janganlah heran jika Biennale (lokal) Yogyakarta VII—setelah absen empat tahun—yang menampilkan 22 perupa terpilih dalam pameran Countrybution di Taman Budaya Yogyakarta melahirkan bermacam reaksi karena meninggalkan paradigma dan cara pandang tertentu yang cenderung melakukan mistifikasi terhadap suatu medium seni rupa, seperti medium seni lukis konvensional. Melalui panji-panji bienal, trienal, maupun festival seni rupa yang tampak marak pada tahun ini, kaitan-kaitan antara paradigma serta praktek seni rupa tertentu dan perkembangan mutakhir masyarakatnya dapat didiskusikan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo