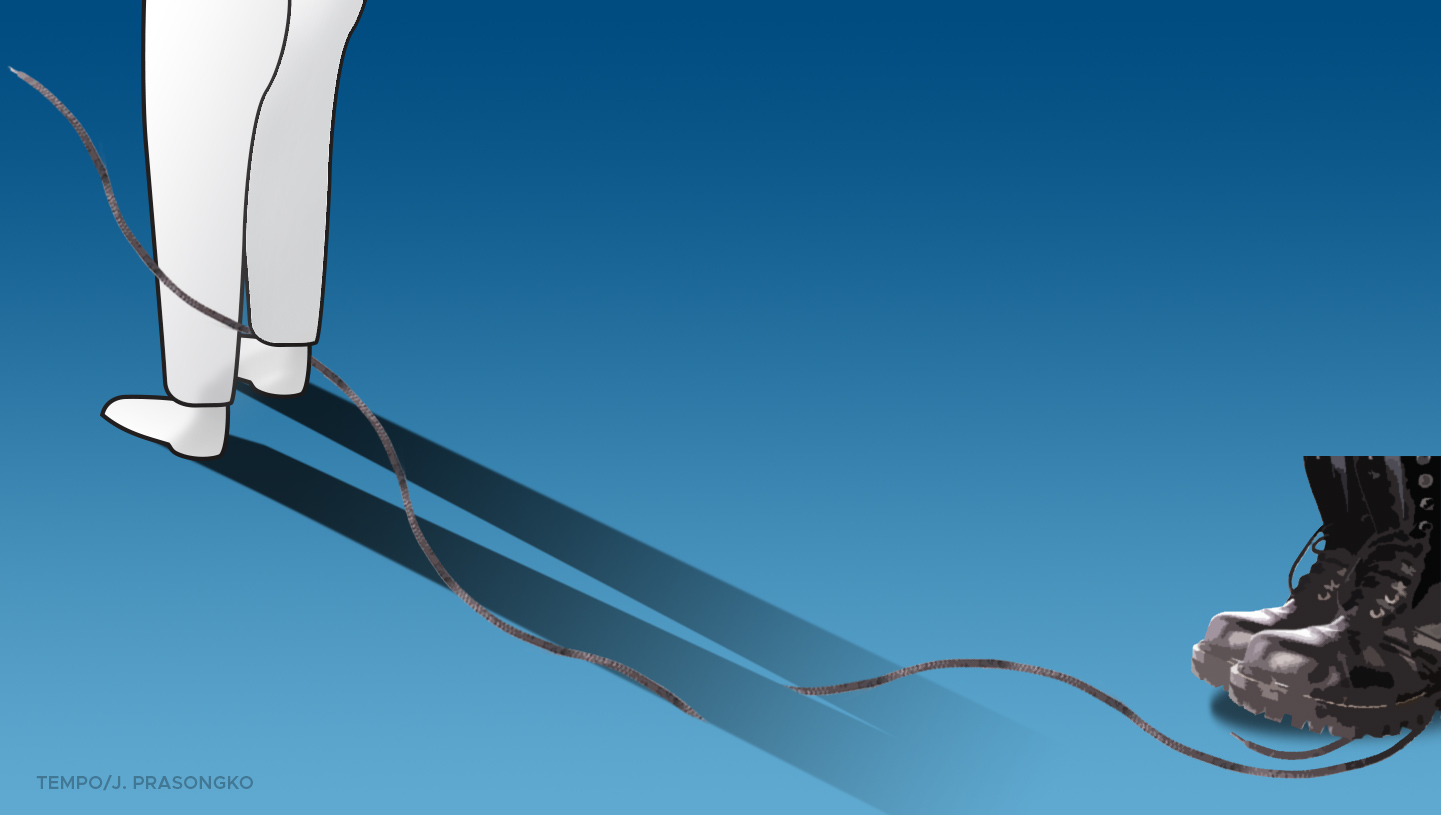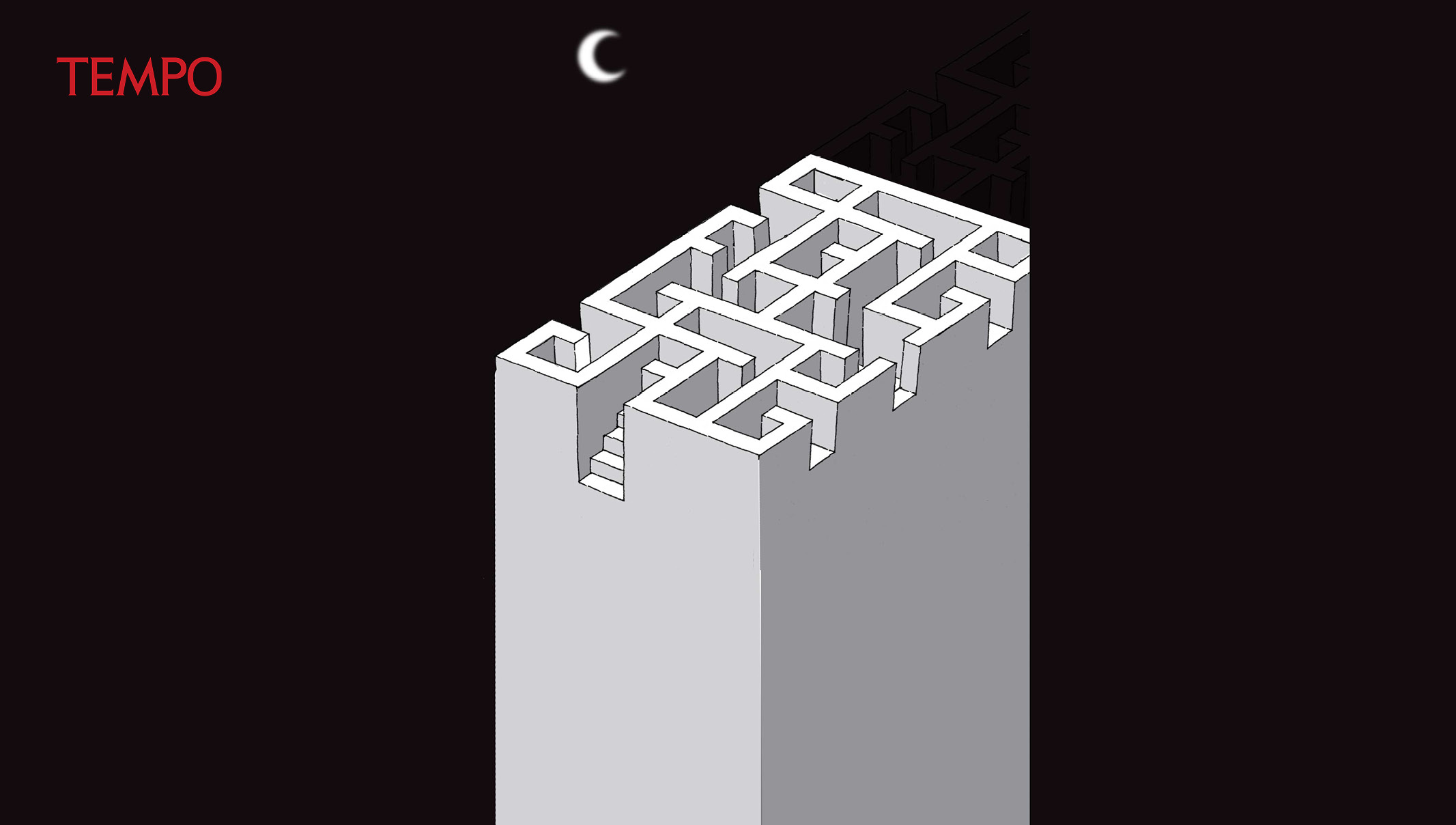Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kemala Atmojo
Pengamat Perfilman
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kata "pajak", bagi sebagian orang, termasuk orang film, memang terasa ngeri-ngeri sedap. Sebab, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Demikian juga pajak daerah. Karena sifatnya memaksa, suka tak suka harus dibayar. Para wajib pajak tidak bisa menuntut imbalan langsung dari pajak yang dibayarkan, tapi rakyat berhak mendapat pelayanan umum yang maksimal.
Hal ini berbeda dengan retribusi. Pembayar retribusi berhak atas imbalan dari nilai yang dibayarkan. Sebab, retribusi merupakan pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Sudah lama sebagian insan perfilman Indonesia mendengungkan ucapan "pembebasan pajak", "keringanan pajak", "pengurangan pajak", "persamaan pajak", dan lain-lain. Salah satu yang dituju dengan pernyataan di atas adalah pajak hiburan berupa pertunjukan film yang tidak sama besarnya di setiap daerah. Besar-kecilnya pajak ini pada akhirnya ditanggung bersama antara pemilik bioskop dan produser film. Dengan demikian, wajar jika mereka berkepentingan untuk meneriakkan masalah ini.
Persoalan inilah yang kembali mengemuka dalam forum konsultasi antara pemerintah (Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri) dan insan perfilman Indonesia yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta pada 11 November lalu. Pada intinya, hampir semua pemangku kepentingan perfilman yang hadir menginginkan keseragaman besaran pajak di seluruh Indonesia, yakni 10 persen. Dengan demikian, ada kepastian, dianggap tidak memberatkan, dan pada akhirnya dapat menarik investor untuk membuka usaha bioskop di daerah.
Dasar hukum pajak daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas dasar undang-undang itu, setiap daerah kemudian menerbitkan peraturan daerah untuk menentukan besar-kecilnya pajak hiburan, dari 10 sampai 35 persen. Untuk DKI Jakarta, selain untuk tontonan bioskop, angka 10 persen itu berlaku buat pameran yang bersifat komersial, pajak pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, pijat refleksi, pusat kebugaran, dan beberapa bidang lainnya. Khusus untuk hiburan lain, seperti diskotek, kelab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan spa, ditetapkan setinggi-tingginya 75 persen. Tapi, karena sudah dikenai pajak hiburan, beberapa jenis jasa kesenian dan hiburan tidak dikenai pajak pertambahan nilai, seperti tontonan film, tontonan pertandingan olahraga, dan pergelaran kesenian.
Namun, untuk mendukung kemajuan perfilman nasional, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 115 Tahun 2012 yang intinya membebaskan sebagian pajak hiburan untuk produksi film nasional. Bentuknya adalah pembebasan sebagian pajak (75 persen) dari setiap harga tanda masuk. Maka, dari nilai 10 persen pajak hiburan yang masuk ke daerah, 75 persennya dikembalikan kepada pemilik film. Tujuannya agar dapat membantu produser untuk terus memproduksi film.
Persentase pembebasan itu kemudian diubah pada masa Gubernur DKI Joko Widodo. Melalui Peraturan Daerah DKI Nomor 148 Tahun 2014, pembebasan yang tadinya 75 persen tersebut diubah menjadi 50 persen. Kebijakan ini terus dilanjutkan pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga kini. Beberapa daerah lain, seperti Ternate dan Kubu Raya, Kalimantan Barat, juga memberikan keringanan dengan cara yang berbeda-beda. Namun masih banyak daerah yang menetapkan pajak hiburan di atas 10 persen.
Menurut saya, jalan yang bisa ditempuh insan perfilman adalah ikut mendorong revisi Undang-Undang Pajak Daerah. Dalam revisi itu bisa ditentukan bahwa untuk pajak tontonan hanya boleh maksimal sebesar 10 persen atau mengeluarkan pajak tontonan dalam kelompok hiburan sehingga bisa diatur dalam pasal tersendiri. Tapi itu jalan yang panjang.
Langkah yang lebih praktis dan cepat adalah meminta Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan para kepala daerah dan memberi pengertian agar pajak tontonan tidak lebih dari 10 persen. Argumentasi yang disampaikan harus meyakinkan. Misalnya, dalam usaha bioskop, efek domino yang ditimbulkan cukup banyak. Selain membuka lapangan kerja, banyak usaha lain, seperti restoran, yang bisa dikenai pajak sendiri. Pemerintah daerah juga bisa mendapat pemasukan dari retribusi parkir. Film sebagai produk budaya, selain menghibur, bisa menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat.
Kerelaan para kepala daerah untuk menyeragamkan tarif itu bisa selaras dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk memberi keringanan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu untuk perfilman.