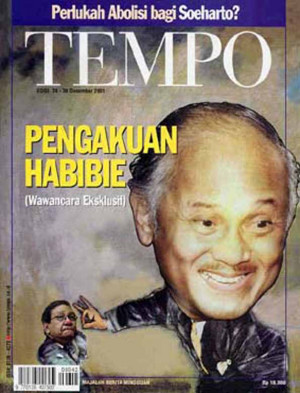SEPARATISME itu merusak tulang sumsum konstitusionalisme. Hak untuk memisahkan diri dari negara kesatuan bukanlah bagian dari konstitusi yang demokratis, walaupun memang perceraian tak jarang punya dasar kuat secara moralitas. Dengan kata lain, hak moral tidak selalu sejalan dengan konstitusionalisme—suatu sistem yang mendewasakan manusia untuk mengatur diri sendiri dalam wadah bersama.
Yang perlu diupayakan, menurut Sunstein, adalah suatu konstitusi yang deliberatif, suatu ”konstitusi berdasarkan musyawarah”. Cass Sunstein adalah guru besar hukum tata negara di Universitas Chicago dan aktif di Center on Constitutionalism yang didirikan oleh universitas tersebut di Eropa Timur, kawasan dunia yang paling parah dilanda gerakan separatis. Ia turut merumuskan konstitusi baru untuk negeri-negeri eks komunis di wilayah itu.
Otonomi Warga Negara
Di masa lalu, istilah ”musyawarah” dalam UUD kita diartikan sebagai yang lemah harus menerima yang diperintahkan oleh yang kuat, dan sekarang ditafsirkan sebagai yang kalah suara harus turut kepada yang menang suara. Pada mata kuliah hukum tata negara di Chicago, arti ”musyawarah” berbeda dengan artinya dalam UUD 1945.
Pertama-tama, konstitusi yang demokratis adalah konstitusi yang bertujuan memberikan otonomi kepada semua warga negara. Menurut Amartya Sen, sepanjang sejarah dunia belum pernah ada kelaparan di negeri yang menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis dan pers yang bebas. Kewenangan mengurus diri sendiri ini hanya bisa dicapai bila kebijakan yang ditempuh adalah yang paling mendekati kebenaran.
Kebijakan semacam itu hanya bisa dicapai jika diperbincangkan secara mendalam dalam suatu majelis yang terdiri atas orang yang tidak selalu sejalan pikirannya serta senantiasa membuka diri bagi data, pengetahuan, dan informasi baru tentang masalah yang menuntut perumusan kebijakan. Majelis diskusi seperti itu tidak akan mengambil posisi ekstrem karena kebinekaan anggotanya. Para pesertanya selalu dipaksa saling menenggang rasa dan berempati karena mereka mewakili kepentingan yang sering berbeda.
Kompromi yang dicapai dalam musyawarah seperti itu—dan yang membuka pintu selebar mungkin bagi informasi sebanyak mungkin—merupakan suatu kebajikan politik yang sangat membantu pertumbuhan demokrasi. Kesinambungan musyawarah inilah yang dirusak oleh upaya atau ancaman memisahkan diri.
”Separasi menutup jalan menuju sikap mental yang esensial bagi demokrasi,” ujar Sunstein. Lalu ia mengutip A Theory of Justice John Rawls: ”Dalam kehidupan sehari-hari, pertukaran pendapat dengan orang lain melunakkan keberpihakan kita dan memperluas wawasan kita; kita didorong untuk melihat hal-hal dari sudut pandang orang lain, dan kita dibuatnya sadar akan keterbatasan daya lihat mata kita….
Manfaat suatu diskusi terletak pada kenyataan bahwa pengetahuan dan kemampuan berakal sehat seorang wakil rakyat pembuat undang-undang pun terbatas. Tiada se-orang pun di kalangan mereka mengetahui segala yang diketahui orang lain, atau mencapai kesimpulan yang sama seperti kesimpulan yang biasanya mereka tarik bersama. Diskusi adalah suatu cara bagi kita untuk memadukan informasi dan memperluas kawasan argumen kita.”
Alasan ’Cerai’
Ditinjau sepintas lalu, argumen kaum separatis terdengar absah belaka. Buat apa memaksa diri kalau sudah tak mau hidup dalam persatuan bangsa? Bukankah menentukan nasib sendiri merupakan hak bangsa-bangsa (baca ”suku-suku”) yang diakui masyarakat beradab di seluruh dunia? Bukankah alasan, seperti yang diajukan oleh Gerakan Papua Merdeka, bahwa di masa lalu telah terjadi penggabungan paksa yang tidak sah merupakan argumen yang cukup persuasif?
Juga, mengapa upaya mempertahankan integritas etnis dan kebudayaan yang diancam oleh hegemoni golongan suku dan kebudayaan lain harus dipersalahkan? Bukankah suatu hak yang amat asasi bagi suatu masyarakat untuk membebaskan diri bila terus ditindas, direbut haknya yang paling dasar, dan ditelantarkan secara ekonomis?
Alasan-alasan yang terkesan sangat altruistis itu kurang memuaskan. Ternyata, di balik semua motif tersebut ada faktor-faktor lain yang mendorong separatisme. Suatu daerah sering terdorong memisahkan diri karena di wilayahnya terdapat sumber alam yang kaya, dan para tokoh daerah itu tak sudi berbagi hasil dengan daerah-daerah lain. Moralitas politik separatisme seperti ini sangat diragukan.
Alasan memisahkan diri yang lebih serius adalah eksploitasi ekonomis. Manfaat yang diisap dari daerah tersebut tidak diimbangi manfaat yang ditanam kembali ke daerah itu secara adil. Di Indonesia, alasan ini men-dominasi masalah Aceh dan Irian. Beberapa daerah lain, meski tak menuntut cerai, terus menggerutukan ketidakadilan perlakuan ”pusat” terhadap ”daerah” mereka. Moralitas politik alasan ini cukup kuat.
Tapi alasan ini tetap kurang kuat untuk dijadikan pasal konstitusi yang menjamin kebebasan bercerai dari wilayah bersama. Argumen Sunstein di sini agak lemah. Ia menyebut solusi jaminan hak berpisah dalam konstitusi sebagai upaya second best karena masih ada pemecahan cara lain.
Ada lagi alasan daerah untuk lepas dari negara kesatuan, yaitu bahwa di masa lalu penyatuan itu melalui tindakan agresi. ”Kalau tindakan agresi dan aneksasi itu berlangsung di masa lalu yang tak terlalu jauh,” ujar Sunstein, ”hak memisahkan diri itu memang masuk akal.” Apakah pengertian ”di masa lalu yang tak terlalu jauh” itu? Sunstein tak menjelaskannya.
Jelas, pengertian ini tidak mencakup agresi bangsa Amerika dan Australia terhadap bangsa-bangsa asli di kedua negeri itu. Soal jangka waktu tampaknya kurang tepat sebagai alasan memberi atau menolak hak pemisahan atas dasar agresi. Agresi India terhadap Goa tampaknya boleh, sedangkan agresi Indonesia terhadap Timor Timur tidak boleh, walaupun pihak yang diserang sama, Portugal.
Alasan historis ini juga mulai sering terdengar di kalangan orang yang memperjuangkan agar Irian lepas dari Indonesia, meski duduk perkaranya pada 1960-an berbeda. Mengambil contoh Amerika Serikat ketika menganeksasi Hawaii, aneksasi Timor Timur juga melalui kebangkitan elemen dalam masyarakat Timor Timur yang bersikeras mau bergabung dengan Indonesia. Tentara Indonesia, seperti halnya tentara Amerika di Hawaii, datang sekadar melindungi dan membantu kekuatan aneksasi setempat. Begitu juga dengan Kashmir, begitu pula dengan Afganistan dulu dan sekarang.
Sunstein menampakkan kelemahan argumen di bagian-bagian ini karena para konstitusionalis tak berdaya bila berhadapan dengan kekuasaan nyata, baik domestik maupun internasional. Ia lebih jernih ketika membuat daftar kerugian separatisme.
Kerugian ’Cerai’
Pengakuan konstitusional terhadap hak memisahkan diri berdampak buruk bagi kehidupan politik yang demokratis. Orang jadi malas berkompromi, ogah memecahkan masalah bersama. Dan dalam perundingan, daerah yang punya hak memisahkan diri akan bertahan sampai kemauannya terpenuhi.
Hak memisahkan diri bisa digunakan sebagai strategi berunding. Beban bisa diringankan dan manfaat bisa ditingkatkan dengan cara mengancam cerai. Bila kepentingan daerah terancam sedikit saja, ancaman berpisah bisa menggagalkan rencana ekonomi ataupun politik nasional. Kemacetan pemerintahan bisa terjadi walaupun kesulitan yang mungkin dialami daerah hanya bersifat sementara.
Ini dapat saja terjadi kendati di kemudian hari terbukti bahwa suatu peristiwa yang sangat merugikan dapat tercegah bila rencana politik atau ekonomi tersebut dilaksanakan. Misalnya suatu daerah penghasil tembakau menentang kenaikan cukai rokok, padahal hasil cukai itu bisa mengatasi masa paceklik yang ekstrapanjang di daerah lain.
Ancaman memisahkan diri bisa saja di-pakai bila pemerintah pusat memutuskan untuk berperang, atau membuat undang-undang guna melindungi lingkungan hidup, atau menambah ataupun mengurangi bantuan kepada sektor pertanian. Bayangkan parahnya keadaan bila satu-satunya daerah yang menghasilkan suatu produk yang sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah lain tiba-tiba mengancam mau hidup sendiri.
Pada dasarnya, ketidaksetujuan Sunstein atas dimasukkannya kebebasan memisahkan diri dalam konstitusi adalah karena hal itu meniadakan tujuan utama suatu konstitusi, yaitu memajukan upaya mengatur diri sendiri dalam satu wadah pengaturan konstitusional.
’Cascade’
Peristilahan yang digunakan Sunstein kebanyakan asing bagi awam, kendati arti di baliknya membuat kita berdebar-debar menyaksikan potensi temuannya. Sebut saja cascade, yang digunakannya untuk menggambarkan gerak pengaruh dalam suatu masyarakat. Cascade barangkali lebih tepat diterjemahkan sebagai ”menjalar” daripada ”menyebar luas”.
Ada pula istilah reason-giving. Sunstein percaya, makin banyak dan beragam penjelasan dan argumen dalam suatu sistem politik, makin demokratis sistem tersebut. Enclave deliberation sangat menarik. Istilah ini dapat diartikan ”berdiskusi di kalangan sendiri”, yaitu diskusi yang berlangsung dalam lingkungan suatu kelompok yang terdiri atas anggota-anggota yang pandangannya sama.
Enclave deliberation diperlukan untuk ”mematangkan” pandangan-pandangan kelompok. Tapi, di pihak lain, hasil diskusi di antara anggota kelompok yang pandangannya serupa akan selalu membuat mereka lebih ekstrem daripada sikapnya sebelum diskusi. Lebih dari itu, jika posisi yang diambil anggota kelompok sudah cenderung ekstrem sebelum masuk ke arena diskusi, dan diskusi dilakukan untuk memutuskan suatu langkah yang harus diambil, langkah mereka bersifat lebih ”nekat”.
Kesimpulan dari enclave deliberation Sunstein: suatu diskusi di antara, misalnya, orang-orang yang bersimpati pada usaha memerdekakan Aceh atau Irian akan selalu membuat posisi yang mereka ambil setelah diskusi lebih ekstrem daripada sebelum diskusi. Bila diskusi semacam itu sering dilakukan, dan pada suatu ketika para peserta diskusi memutuskan untuk mengambil langkah tertentu, langkah itu akan ditempuh dengan mengambil risiko yang cukup besar.
Apakah kemudian diskusi semacam itu harus dilarang? Tidak. Pengekangan kebebasan pertukaran pikiran berlawanan dengan demokrasi—dan dengan konstitusionalisme Sunstein. Yang dapat dilakukan adalah membujuk orang-orang kelompok itu untuk mengikutsertakan orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka dan orang-orang yang mempunyai banyak informasi tambahan. Tujuannya adalah agar keputusan yang diambil lebih bermutu karena sudah melewati proses musyawarah dan diperkaya dengan informasi yang tadinya mungkin belum diketahui.
Akhirnya, Profesor Sunstein menyajikan mekanisme yang dinamai ”incompletely theorized agreement on a general principle”. Tampaknya maksud konsepsi Sunstein ini adalah memecah prinsip besar yang dipersengketakan ke dalam prinsip-prinsip lebih kecil yang mungkin disetujui.
Kalau proses persetujuan kecil-kecilan ini cukup banyak terjadi dalam suatu jangka waktu yang panjang, sangat mungkin pihak yang bersengketa akan sadar bahwa cekcok mereka lebih bersifat emosional ketimbang prinsipiil. ”Incompletely theorized agreement” sering dicapai dalam keputusan mahkamah konstitusi atau mahkamah agung mengenai masalah yang menyangkut prinsip besar.
Nono Anwar Makarim
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini