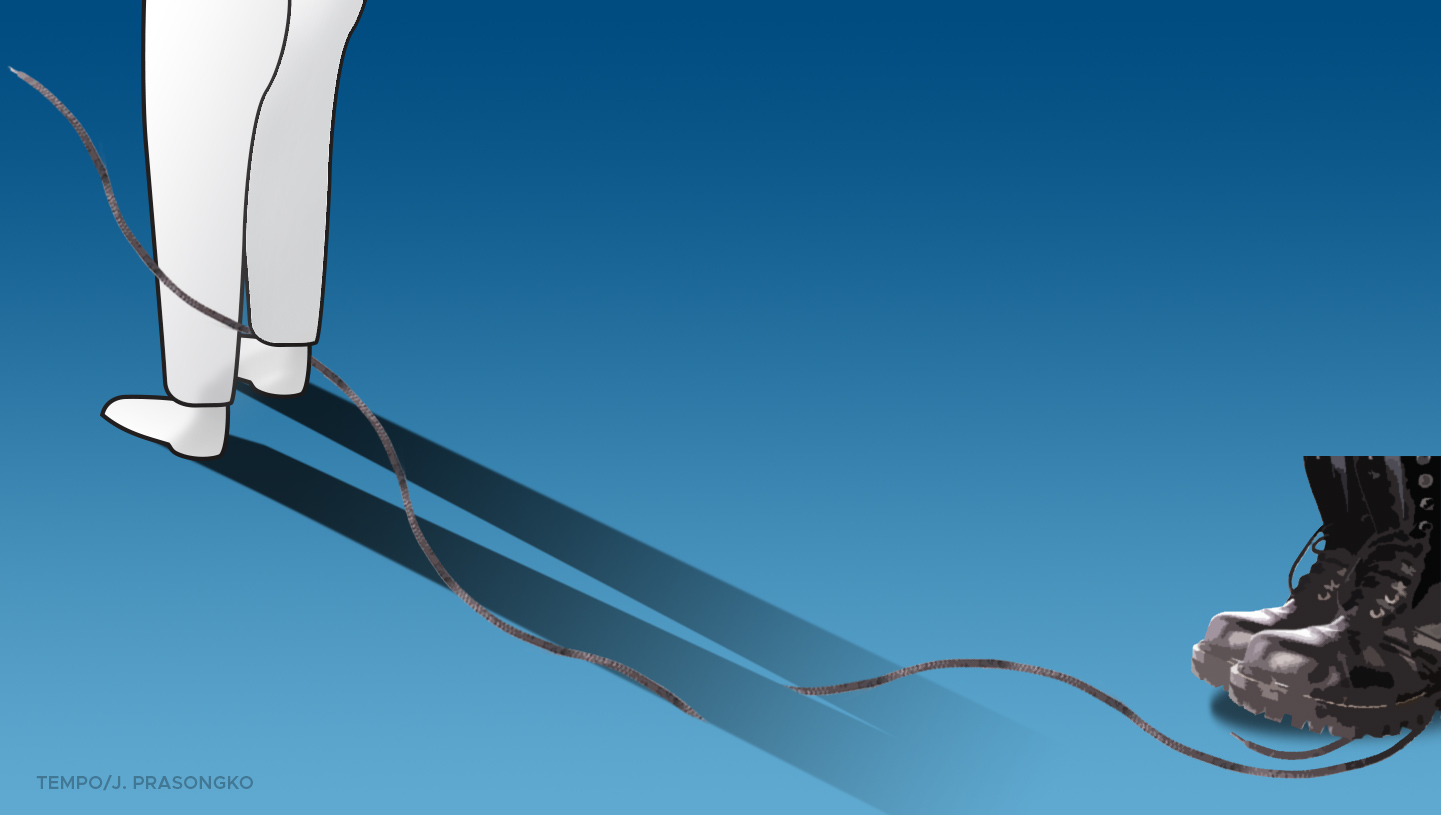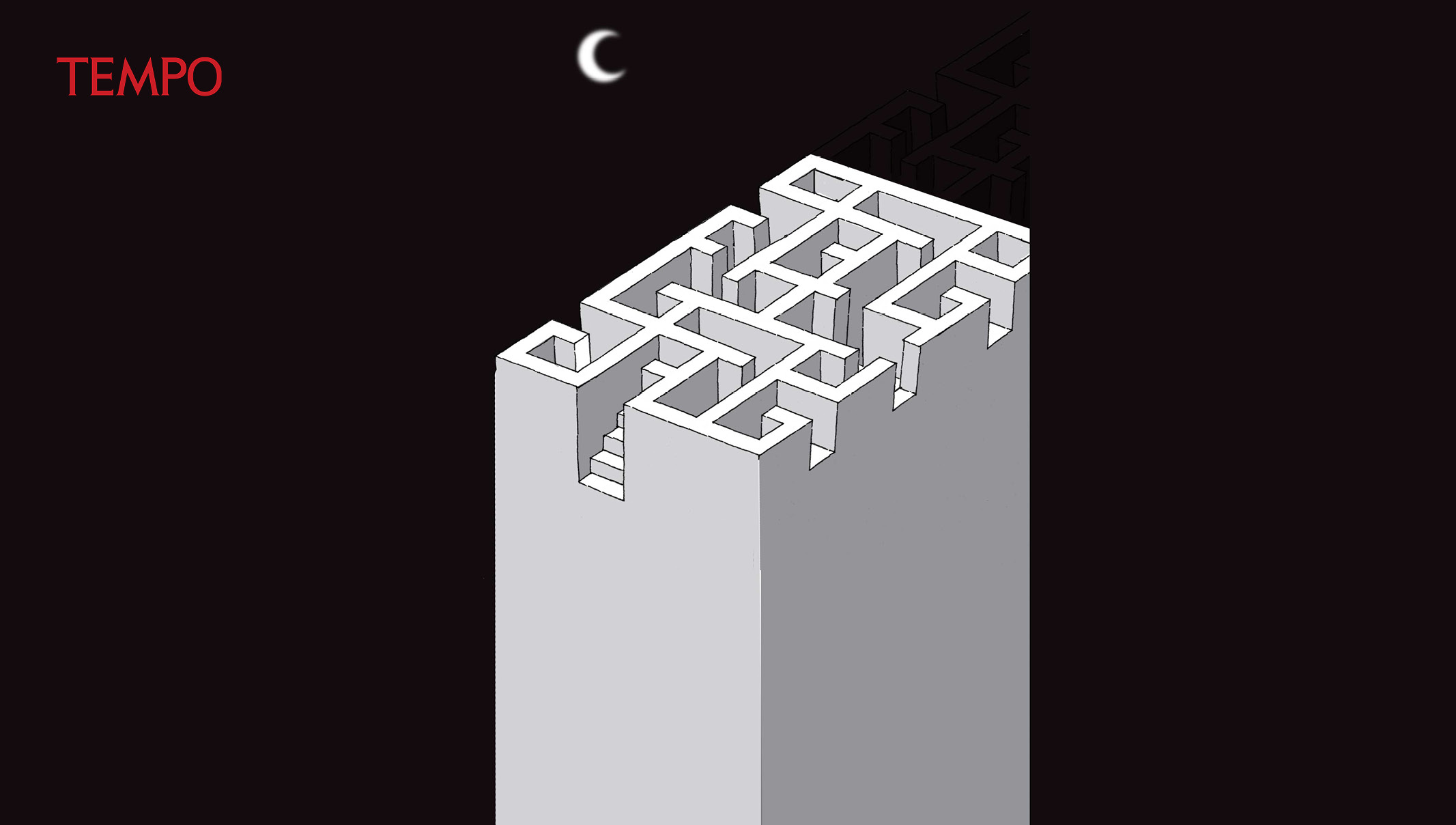Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Masa kampanye pemilihan kepala daerah, tiga bulan terakhir, justru mempertontonkan suasana berdemokrasi yang keruh. Para kandidat di hampir semua daerah yang secara serentak menggelar pemilihan pada Rabu pekan ini terjebak pada isu-isu primordial ketimbang menawarkan substansi.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo