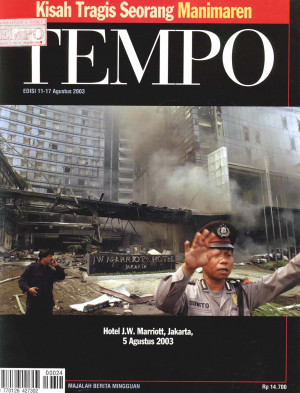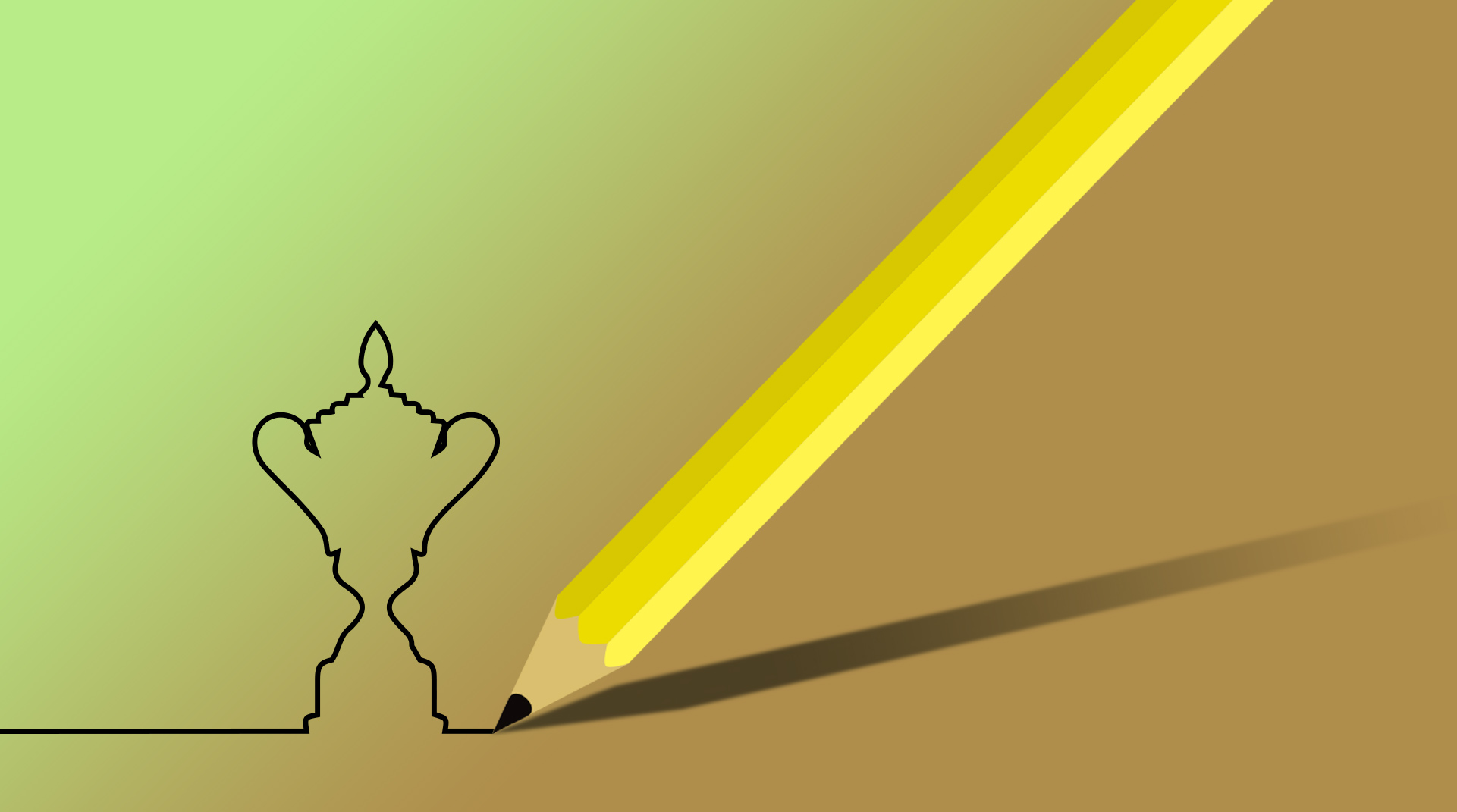Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketika Partai Golkar menggagas konvensi untuk menjaring calon presiden, banyak orang yang terkesima. Partai Golkar, yang selama ini digambarkan sebagai partai pro-status quo, ternyata mampu membuat manuver politik brilian, yang sepertinya memberi harapan bahwa proses demokratisasi dalam proses pencalonan presiden bisa dimulai. Tak mengherankan jika banyak tokoh yang mendaftar. Sampai-sampai seorang Nurcholish Madjid pun terbawa arus untuk ikut berharap bahwa konvensi itu akan menjadi latihan berdemokrasi sekaligus melahirkan calon presiden yang teruji integritas dan programnya. Sayang, harapan yang pada mulanya bergelora itu secara perlahan mulai surut. Gagasan konvensi itu seperti sebuah mainan politik yang tak ada kaitannya dengan demokrasi. Mengapa demikian?
Aturan main konvensi tampaknya tidak cukup jelas menjamin terjadinya proses demokrasi. Ada banyak loopholes yang bisa dimanfaatkan oleh para peserta konvensi, terutama yang mempunyai kekuasaan dan uang. Sekarang saja kita sudah melihat peserta konvensi muncul dalam tayangan iklan televisi, sehingga tak bisa dibantah bahwa uang akan mendikte proses pemilihan calon presiden ini. Kita juga melihat persyaratan calon peserta konvensi yang tak mengindahkan status tersangka atau terdakwa, sehingga seorang yang sudah dihukum bersalah oleh pengadilan tinggi—tetapi menunggu putusan Mahkamah Agung—dapat mendaftarkan diri sebagai peserta konvensi. Etika politik memang sudah tak berarti apa-apa di negeri ini.
Penayangan iklan dan masuknya tersangka atau terdakwa di dalam daftar peserta konvensi memang tidak melanggar hukum karena memang tak ada hukum yang dilanggar. Sekarang, siapa saja bebas memasang iklan, asal punya uang. Ini bisa disebut curi start, dan itu tidak fair terhadap peserta konvensi lainnya. Seharusnya aturan konvensi dibuat jelas dan rinci sehingga iklan-iklan curi start bisa dihindari. Sayangnya, peserta konvensi lainnya lebih memilih berdiam diri dan seolah berusaha mengerti bahwa semua ini adalah konsekuensi logis dari lemahnya aturan main konvensi. Bisa dibayangkan nanti bahwa keikutsertaan dalam konvensi pemilihan calon presiden Partai Golkar akan menguras pundi-pundi uang yang amat banyak. Jumlah ini pun kelak harus dilipatgandakan ketika proses pemilihan presiden sebenarnya dilakukan pada pertengahan tahun 2004. Tak disadari bahwa membiarkan hal ini sama artinya dengan melegalkan praktek money politics dalam kancah politik.
Di negeri yang katanya supremasi hukum itu dihormati ternyata proses hukum itu sendiri tak dihormati. Memang kita menganut asas praduga tak bersalah, tetapi asas ini seharusnya tak boleh ditafsirkan secara harfiah. Karena dalam teori ilmu hukum, setiap soal itu selalu dilandasi oleh filsafat hukum yang berpihak kepada keadilan. Jadi, apabila kepada seseorang sudah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, seharusnya asas praduga tak bersalah itu dibaca telah dinyatakan bersalah sampai ada putusan lain yang menyatakan tak bersalah. Sayang, filsafat hukum itu tak dipedulikan oleh banyak kalangan, termasuk masyarakat advokat dan politikus. Tak salah jika kita menyimpulkan bahwa konvensi Partai Golkar ini tak akan memperbaiki wajah demokrasi di negeri ini. Wajah demokrasi itu tetap suram.
Kepentingan elite Partai bermain sangat kuat, dan longgarnya aturan main konvensi adalah bukti bahwa pada dasarnya konvensi itu hanyalah sebuah political design. Dari permukaan konvensi itu kelihatannya akan memperbaiki citra Partai Golkar yang sudah terpuruk, tetapi dari sisi lain sesungguhnya hanya merupakan ritual demokrasi yang semu. Bagaimanapun, elite politik Partai Golkar tak sudi menerima kehadiran orang-orang di luar mereka, apalagi mengharapkan calon presiden dari luar kalangan Partai Golkar. Jadi sesumbar orang-orang Partai yang mengatakan bahwa bisa saja calon independen diusulkan oleh sebuah partai tak lebih dari isapan jempol belaka. Di sini partai politik merasa mempunyai hak monopoli untuk menjalankan negeri ini, dan orang-orang di luar partai politik tak punya hak sama sekali.
Amendemen UUD 1945 tak secara tegas melarang calon independen untuk maju dalam pemilihan presiden, tetapi itu harus dilakukan melalui partai politik atau gabungan partai politik. Dari wacana yang berkembang, kita semua tahu bahwa orang-orang partai tak akan pernah ikhlas membuka pintunya bagi orang-orang nonpartai. Di sini ideologi tak penting, yang penting adalah monopoli partai politik dikawal bersama. The name of the game is political interest. Atas nama political interest inilah dagang sapi terjadi, baik dalam UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan yang paling baru adalah UU Mahkamah Konstitusi. Dagang sapi politik tersebut berkisar pada lemahnya kontrol finansial partai, dana kampanye, persyaratan calon presiden, dan kewenangan uji materiil Mahkamah Konstitusi. Dalam iklim dagang sapi politik yang mewabah sekarang ini, apa kita mungkin berharap akan iklim politik demokratis? Apa mungkin partai seperti Partai Golkar memulai proses demokratisasi?
UU Nomor 31/2002 tentang Partai Politik memang tidak mengatur perihal demokrasi internal partai, tetapi beberapa pasal seharusnya bisa ditafsirkan implisit mensyaratkan dibangunnya demokrasi internal partai, termasuk pemilihan ketua ranting, cabang, wilayah, dan pusat. Karena perwujudan demokrasi itu ada pada pundak partai politik, maka partai politik itu dalam dirinya mesti demokratis. Di sinilah fungsi pendidikan dan penyadaran politik itu dilakukan. Kegagalan demokrasi, dengan demikian, adalah dosa-dosa partai politik? Ya, kalau membaca UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden, dan Wakil Presiden, kesimpulan di atas tidaklah terlalu keliru, tetapi banyak orang yang berpikiran sehat yang tak mau serta-merta menimpakan semua kesalahan pada partai politik. Pemerintah dan civil society juga harus bertanggung jawab, walau hak-hak politik warga civil society di luar partai telah disandera oleh partai politik.
Dari sisi tanggung jawab dan pendidikan politik inilah konvensi Partai Golkar harus dilihat. Seharusnya ajang itu merupakan kesempatan emas bagi Partai Golkar untuk mematrikan identitas dan citra baru sesuai dengan semboyan yang diusungnya sejak pemilu 1999. Antusiasme yang mencuat ke permukaan seharusnya menjadi dorongan untuk melakukan investasi politik sekaligus sebagai warming up menghadapi Pemilu 2004. Tetapi lemahnya aturan main membuat konvensi ini menjadi sekadar panggung yang tak memberi teladan berdemokrasi. Politik uang begitu kental sehingga Cak Nur buru-buru mundur tak mau kecebur lebih jauh. Jajaran partai di daerah dengan enteng bertanya tentang "gizi", dan pertanyaan mengenai "gizi" ini jauh lebih penting ketimbang visi.
Kita mula-mula tak sepenuhnya sadar bahwa "gizi" itu identik dengan uang. Tetapi, setelah kita tahu bahwa "gizi" itu sama dengan uang, konvensi yang akan dilaksanakan oleh Partai Golkar itu tak akan berarti banyak bagi demokrasi. Dalam arti, yang keluar dari konvensi itu bukanlah putra terbaik negeri ini, tetapi justru orang yang punya kuasa dan uang, orang yang bisa saja melakukan apa saja untuk mencapai tujuan. Lagi-lagi kita harus mengakui bahwa Lord Acton benar ketika dia mengatakan power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Jadi jangan heran bahwa dari ajang konvensi ini kita akan berpapasan dengan korupsi kekuasaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo