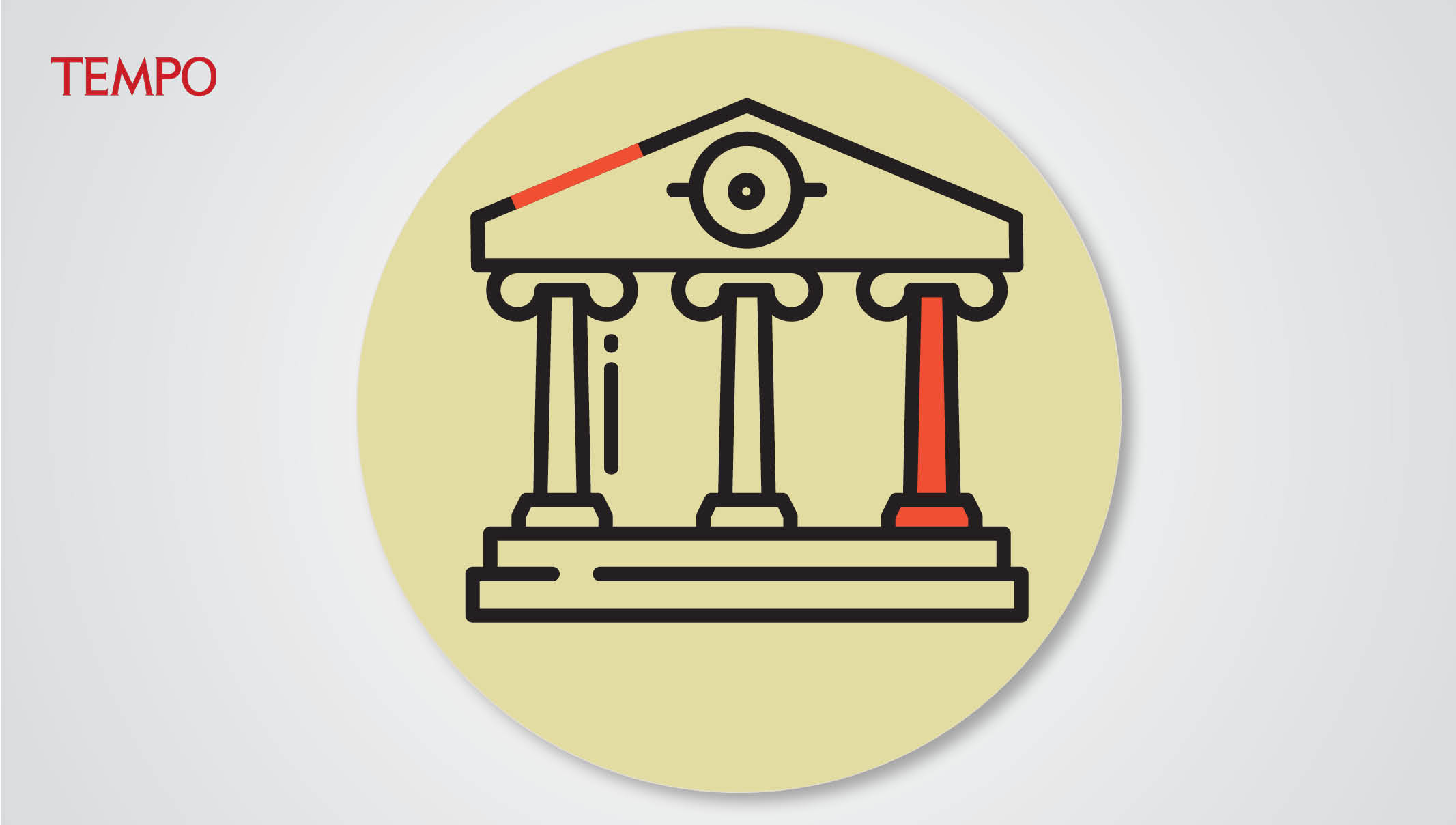Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DENGAN korupsi yang begitu mengakar di lembaga peradilan, masih bisakah masyarakat berharap mendapat putusan hakim yang adil?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sangat wajar jika publik tak lagi mempercayai lembaga peradilan. Kasus suap yang menyeret Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan menunjukkan dengan terang benderang bahwa putusan hakim (selalu) bisa diperdagangkan dan berpihak pada mereka yang berani membayar mahal. Maka menumbuhkan kepercayaan terhadap para hakim dan pejabat di lembaga yang seharusnya teragung itu kini seperti—meminjam istilah grup lawak lawas Srimulat: "hil yang mustahal".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung pada Rabu, 10 Mei lalu. Hasbi bakal menyusul dua hakim agung, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh, yang telah diseret ke pengadilan dalam kasus sama. Secara berjemaah, bersama sejumlah pegawai MA, mereka menerima suap miliaran rupiah untuk mengurus putusan perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana.
Kasus yang menjerat para petinggi Mahkamah Agung ini memperjelas anggapan bahwa palu hakim tak pernah lepas dari cengkeraman makelar kasus. Sebelumnya, pada Maret 2021, bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman, divonis enam tahun penjara karena menjadi makelar kasus. Namun lembaga peradilan tertinggi itu tak pernah sungguh-sungguh membersihkan diri dari kelakuan korup personelnya. Reformasi peradilan yang berulang kali digaungkan oleh MA tak lebih dari slogan kosong.
Baca Wawancara Ketua Komisi Yudisial: Ada Mafia Peradilan di Mahkamah Agung
Salah satu penyebab bobroknya lembaga peradilan adalah nihilnya pengawasan terhadap perilaku hakim. Mahkamah Agung sendiri yang merusaknya pada 2006 dengan mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Komisi Yudisial. Setelah Mahkamah Konstitusi—yang sejumlah hakimnya juga pernah terlibat suap—menerima permohonan itu, tak ada lagi pengawasan ketat terhadap para hakim. Pengawasan internal MA terbukti tak mampu membenahi kerusakan lembaga peradilan.
Kebobrokan lembaga peradilan tak hanya disebabkan oleh hakim atau panitera yang bermental korup. Kerusakan juga disumbangkan oleh sikap masyarakat yang mendiamkan atau memaklumi kebobrokan itu. Bisa jadi banyak orang berkeyakinan bahwa setiap orang yang beperkara di pengadilan harus menyiapkan uang pelicin. Tanpa setoran, tak mungkin perkara bisa dimenangi. Pada saat yang sama, bukannya terus membangun sistem demi perbaikan, hakim dan panitera tanpa malu memanfaatkan anggapan tersebut dengan mengeruk duit dari kasus yang diadili.
Baca liputannya:
Publik mungkin tak menyadari, atau tak peduli, bahwa kerusakan lembaga peradilan berdampak besar dan luas. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat terakhir untuk mencari keadilan telah berubah menjadi tempat mencari kemenangan dengan cara transaksional. Para penjahat, termasuk koruptor, tak lagi menganggap MA sebagai pengadilan yang menakutkan karena semua bisa dibeli. Posisi hakim yang tak lagi imparsial juga membuat lembaga peradilan mudah diintervensi oleh kepentingan politis yang menguntungkan penguasa.
Baca: Mengapa Mafia Kasus Leluasa Bermain di Mahkamah Agung?
Perkara demi perkara yang menjerat petingginya seharusnya menyadarkan pemimpin MA untuk merombak total manajemen lembaga itu. Ketua MA Syarifuddin, yang akan menjabat hingga 2025, masih punya waktu untuk memperbaiki berbagai kelemahan di lembaganya, terutama pengawasan dalam proses peradilan. Hakim dan panitera korup pun tak boleh lagi dilindungi dan bebas dari sanksi. Tanpa ada ketegasan terhadap hakim mata duitan seperti itu, pengadilan akan terus menjadi sarang korupsi.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Artikel ini terbit di edis cetak di bawah judul "Misi Mustahil Membenahi Lembaga Peradilan"