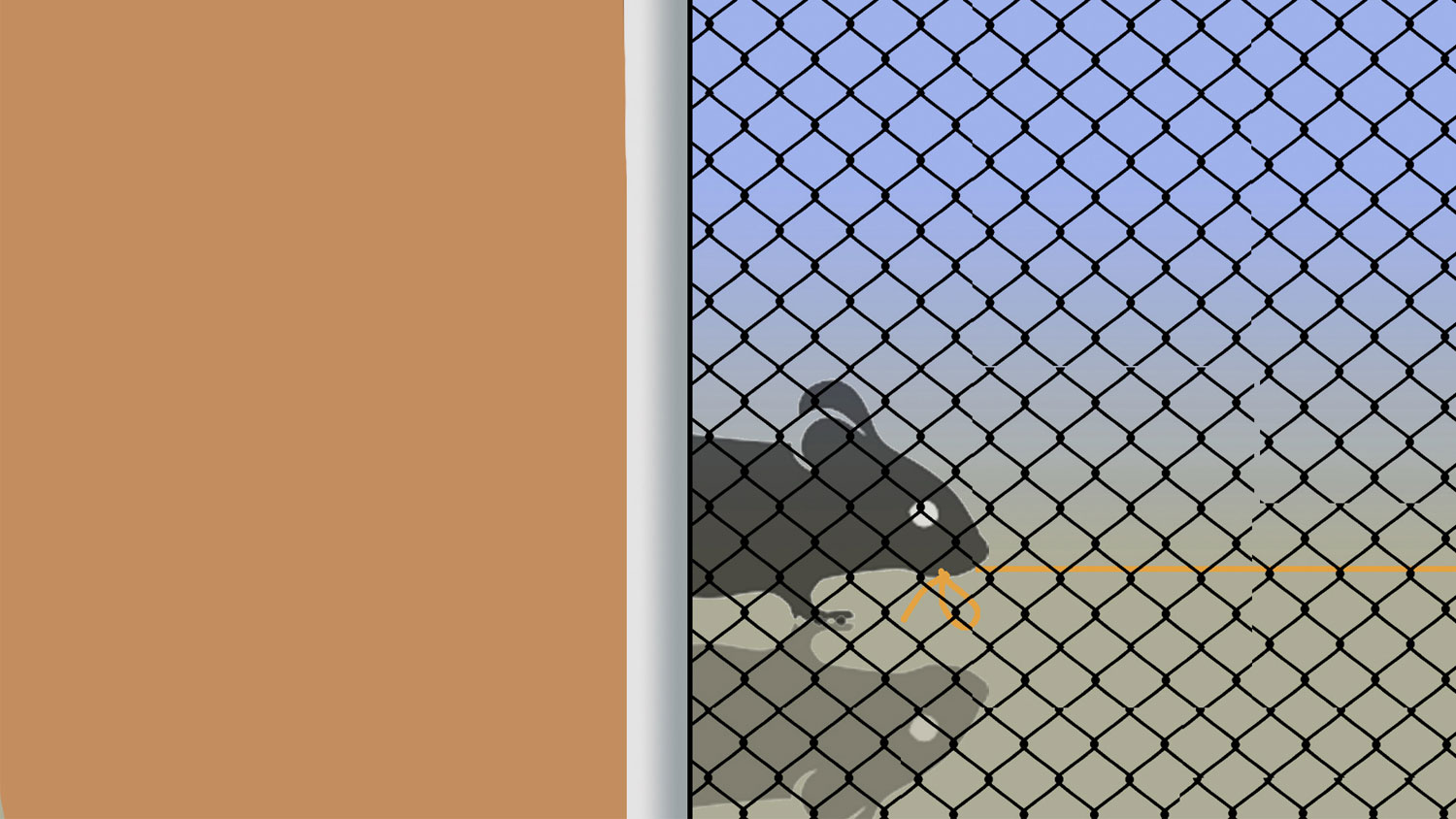Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Sejumlah mantan pegawai KPK diangkat sebagai aparatur sipil negara di kepolisian.
Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo berencana membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Polri perlu mengatasi korupsi kultural dan struktural di lembaganya.
Kurnia Ramadhana
Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bertepatan dengan Hari Antikorupsi Internasional, puluhan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dianggap tidak memiliki wawasan kebangsaan oleh Ketua KPK Firli Bahuri, dilantik sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Kepolisian RI. Menariknya, pelantikan mereka sebagai ASN ini tanpa harus melalui proses tes wawasan kebangsaan (TWK) yang sangat absurd itu. Tentu ini semakin membuktikan bahwa TWK ugal-ugalan versi KPK tersebut memang tidak pantas diberlakukan di suatu instansi negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Momen pelantikan ini sebenarnya bukan sesuatu yang ideal dan layak untuk diglorifikasi. Sebab, perpindahan mantan pegawai KPK ke Korps Bhayangkara terjadi karena turbulensi politik dan ketidakmampuan Presiden Joko Widodo dalam mengambil sikap yang konkret. Temuan dua lembaga negara, Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang penyelenggaraan TWK, misalnya, enggan ditindaklanjuti oleh Presiden. Padahal, dengan kewenangan yang besar, Presiden mampu mengembalikan Novel Baswedan dkk untuk bekerja kembali di KPK. Namun, yang terjadi sebaliknya, Presiden malah melempar tanggung jawab itu kepada Kepala Polri.
Saat pelantikan berlangsung, ada satu ide dari Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo yang penting untuk diulas lebih lanjut, yakni rencana pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kabarnya, nomenklatur baru itu akan menggantikan fungsi Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan pertanggungjawabannya pun bukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal lagi, melainkan langsung di bawah pengawasan Kepala Polri. Konsep ini sebenarnya bukan hal baru karena dua Kepala Polri sebelumnya, Sutarman dan Tito Karnavian, juga pernah membicarakan hal serupa, tapi ide itu menguap begitu saja.
Kehadiran bekas pegawai KPK di kepolisian tentu membawa harapan yang baik terhadap perbaikan citra Korps Bhayangkara. Ini bukan suatu hal yang mudah. Kepolisian selama ini sudah telanjur dicap sebagai lembaga korup oleh masyarakat, yang antara lain dikonfirmasi dalam survei Global Corruption Barometer 2020 yang menempatkan kepolisian sebagai salah satu lembaga terkorup. Buruk rupa kepolisian ini ditambah lagi dengan sikap arogan dan kekerasan yang dilakukan anggotanya kepada masyarakat hingga muncul tagar #PercumaLaporPolisi.
Sebelum masuk lebih jauh pada efektivitas Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada baiknya memetakan dan membedah lebih dulu bagaimana sebenarnya masalah korupsi di kepolisian. Setidaknya ada dua jenis korupsi yang masih belum mampu dibenahi, yakni yang struktural dan kultural. Korupsi struktural berhubungan dengan integritas individu anggota Korps Bhayangkara. Praktik korupsi menjalar hampir di seluruh lini kerja kepolisian, dari urusan tilang, administrasi pengurusan surat izin mengemudi, reserse, hingga skala besar seperti “rekening gendut” yang banyak melibatkan perwira tinggi Polri. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch, setidaknya sudah sembilan pejabat elite kepolisian yang tersandung praktik korupsi. Beberapa di antaranya adalah Susno Duadji dan Djoko Susilo hingga Prasetijo Utomo dan Napoleon Bonaparte.
Solusi untuk memberantas korupsi struktural ini hanya dua, yakni kehendak politik dan keberanian dari Kepala Polri. Selama ini, analogi “ikan busuk” yang sering diutarakan Kepala Polri baru terbatas pada penyelesaian isu kekerasan dan belum masuk lebih jauh ke permasalahan korupsi. Pertanyaan sederhananya, apakah Kepala Polri berani mencopot kepala kepolisian resor, kepala kepolisian daerah, atau jajaran elite Polri lain jika mereka terlibat korupsi? Dari sini masyarakat dapat benar-benar mengukur keseriusan Kepala Polri untuk membenahi institusinya sendiri.
Salah satu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk menilai integritas anggota Polri adalah kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dengan menggunakan LHKPN, Kepala Polri dapat memilah mana yang akan dijatuhi sanksi administratif karena tidak patuh dan mana yang akan diteruskan ke bagian penindakan karena adanya peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar. Selama ini, isu kepatuhan LHKPN kerap diabaikan oleh Kepala Polri, yang secara tidak langsung akan melanggengkan praktik korupsi karena banyak penerimaan tidak wajar diperoleh anggota kepolisian.
Korupsi kultural dapat merujuk pada kebiasaan yang sepertinya sudah mengakar di kepolisian, yakni the code of silence. Istilah ini dikenal dalam berbagai literatur untuk menggambarkan sikap saling menutupi atau bahkan melindungi ketika anggotanya terlibat kejahatan. Contoh konkretnya mudah ditemukan, misalnya konflik “Cicak Vs Buaya” atau saat Polri memberikan bantuan hukum kepada anggotanya yang merupakan pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan. Sikap yang berlebihan seperti ini akan semakin memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat.
Korupsi kultural ini sebenarnya lahir dari budaya “siap, komandan!” yang selalu tampak di lembaga penegak hukum. Dari sana terlihat tidak adanya ruang korektif bagi anggota atas apa pun yang disampaikan oleh atasannya. Maka dibutuhkan penguatan whistle blowing system dan pemberian reward kepada anggota yang berani melaporkan atasannya. Jaminan keamanan bagi pelapor juga harus dipastikan oleh Kepala Polri secara langsung.
Selain dua masalah di atas, kebijakan internal Polri dalam hal promosi jabatan layak dikritik. Selama ini, praktis tidak ada transparansi indikator dan ruang partisipasi masyarakat ketika menentukan calon anggota Polri yang akan menempati posisi strategis. Untuk itu, akan sangat baik jika kemudian Kepala Polri dapat mendesain ulang sistem promosi jabatan dengan menampilkan daftar kandidat dan meminta masukan masyarakat sebagai salah satu komponen pertimbangannya. Uji coba konsep itu bisa dimulai pada level kepala kepolisian daerah dan jabatan-jabatan strategis di Markas Besar Polri. Jika hal ini dilakukan, Kepala Polri akan mendapatkan pemimpin-pemimpin kepolisian di daerah yang memiliki rekam jejak baik dan kemampuan untuk menerjemahkan program besar pembenahan Polri menjadi suatu agenda konkret.
Berkaitan dengan rencana pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebaiknya Kepala Polri memasukkan bagian pembenahan lingkup internal kelembagaan pada nomenklatur baru itu. Bagian ini nanti bisa diisi oleh mantan pegawai KPK. Terlebih, model pertanggungjawaban langsung kepada Kepala Polri akan mempermudah implementasi kebijakan pembenahan lingkup internal Polri. Yakinlah, jika hal ini bisa direalisasi, pemberantasan korupsi di Polri benar-benar memasuki lembaran baru.
Tentu hal ini bukan pilihan mudah bagi mantan pegawai KPK dan bahkan mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa saat ini mereka resmi menyandang status sebagai ASN Polri. Namun arah politik hukum suatu saat akan berubah seiring dengan masifnya protes masyarakat yang semakin jengah akan kebobrokan KPK di bawah komando Firli Bahuri.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo