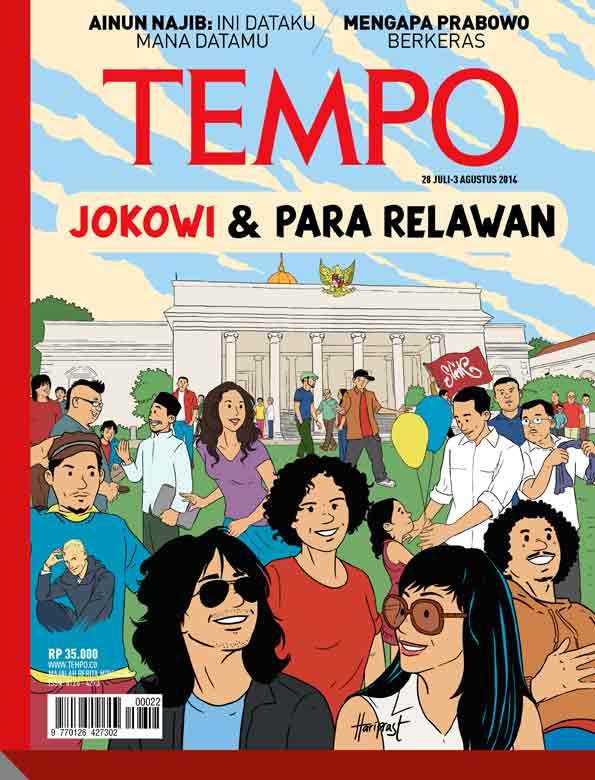Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kau tak memihak. Kau tak ingin pandanganmu tersekat barikade. Kau ingin tunjukkan, di balik tiap barikade, baik di kubu yang di sana maupun yang di sini, bertengger yang kotor dan keji. Ada siasat dan alat penghancuran yang disiapkan. Kau ingin tegaskan bahwa peranmu ("Aku cendekiawan," katamu) adalah melawan itu. Ingin kau garis-bawahi kembali nalar yang jernih, standar kebaikan yang tak berat sebelah, dan hati nurani yang didengar.
Sebab itu kau tak ingin memihak.
Tapi aku memihak.
Baiklah aku jelaskan kenapa. Di hari-hari pemilihan presiden 2014 ini, justru dengan memihak—tapi tak asal memihak—aku memutuskan ikut dalam ikhtiar menemukan tujuan yang kau ingin capai, tujuan yang aku ingin capai.
Bedanya: aku tak berdiri di menara pengawas. Bagiku menara pengawas itu hadir di jarak yang semu. Ia tampak jauh, atau menganggap diri jauh, menjulang ke dekat langit. Tapi fondasinya terletak di sepetak tanah. Lokasinya tidak cuma akrab dengan pucuk pohon yang hijau, tapi juga dengan air payau dan pelbagai tahi. Aku tak ingin berada di menara itu bukan karena tak nyaman dengan najis. Aku tak ingin di sana karena merasa tak bisa pura-pura menatap bumi dari luar sejarah yang bergolak.
Pandanganku mungkin terbatas. Mungkin aku kehilangan perspektif yang mencakup semua. Tapi aku tak pernah yakin bahwa "melihat" selalu sama dengan "mengetahui", dan "mengetahui" sama dengan "mengalami". Ketika aku memihak, ada yang hilang dari penglihatanku, tapi aku mengalami sesuatu.
Yang sangat menonjol dalam pemilihan presiden 2014 adalah peredaran fitnah yang deras, dalam derajat yang tak pernah dialami sejarah politik Indonesia. Mungkin ini bisa terjadi karena perpindahan fokus dari ideologi ke tokoh—sebuah tren yang menegas karena kekuasaan televisi. Di layar yang gemilang itu, wajah dan citra lebih penting ketimbang program dan pikiran. Dan wajah dan citra itulah yang oleh fitnah hendak dirusak.
Tapi fitnah yang menderas itu juga karena persaingan politik telah diperlakukan sebagai permusuhan absolut. Kau tentu ingat, "perang" telah dipakai untuk menggambarkannya. Lebih tajam lagi: perang antara "kafir" dan "Islam". Dalam permusuhan yang mutlak itu, tak ada lagi nilai-nilai yang dianggap berlaku bersama. Fitnah dan dusta dihalalkan, karena pertarungan macam itu adalah pertarungan tanpa kemungkinan rekonsiliasi. Pihak yang memfitnah merasa pantas mengecualikan diri dari nilai-nilai bersama tentang yang jujur dan yang tidak.
Persaingan politik 2014 dengan segera berubah jadi perjuangan moral—satu hal yang membuatnya sengit, berkibar-kibar, tapi juga tragis.
Ketika politik bertaut dengan tuntutan moral, orang ramai memang merasa menemukan sebuah arah—sebuah arah yang bernilai dan sebab itu menggerakkan hati. Dari sinilah lahir partisan yang intens. Tak ada lagi sikap acuh tak acuh, yang umum berkembang ketika demokrasi jadi sekadar prosedur, ketika demokrasi tak banyak mengubah keadaan. Yang timbul adalah rasa cemas dan amarah, menyaksikan kebohongan dan usaha penipuan beranak-pinak—dan bisa menang.
Reaksi terhadap itu adalah militansi yang tanpa diperintah. Ada akal sehat bersama yang dihina. Kau, yang mengambil jarak dari gelora dan keramaian itu, tetap tak memihak. Kau malah mencemooh, "Betapa naifnya orang ramai itu!" Tapi aku tak yakin lagi yang kau usahakan adalah kembalinya nalar, standar nilai yang adil, dan hati nurani yang peka.
Tapi harus aku akui, ada benarnya yang kau lihat.
Sebab ketika perjuangan politik berkembang jadi pertarungan moral, orang sering lupa: dalam sejarah, tak ada pertarungan antara kebaikan dan keburukan yang selesai. Tuntutan agar kebaikan terlaksana di sebuah negeri tak pernah terpenuhi. Ketaksabaran akan menyusul, terkadang melahirkan teror dan penindasan. Atau kekecewaan.
Politik adalah jalan yang efektif buat mengubah dunia dan kekecewaan, tapi politik sesungguhnya bukan jalan yang baik. Raymond Aron pernah menulis, politik mengandung "pakta dengan kekuatan-kekuatan neraka". Politik, sebagai perjuangan ke arah kekuasaan, selamanya menjurus ke kekerasan: ke arah negara di mana kekerasan jadi hak eksklusif.
Tapi justru dari situlah aku mendapatkan sesuatu. Tiap saat aku dipaksa berharap dan cemas. Tiap kali aku belajar kembali meniti buih antara "kekuatan neraka" dan tuntutan moral yang menggerakkan hati jutaan orang tempat aku terpaut. Tiap saat kutemukan kemungkinan dan keterbatasan manusia, kebusukan dan kemuliaannya, egoisme dan kemauannya berkorban. Tiap kali aku merasa perlu mengakui: manusia itu mungkin ada dalam diriku.
Tentu kau tak mengalami itu. Kau berdiri aman jauh dari barikade, berkomentar sesekali dengan pintar. Aku tak tahu adakah yang mendengar.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo