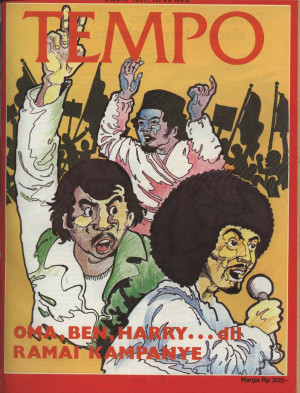SEMUA orang bisa jadi duta. Entah tergolong kebejatan orla entah tidak, sampai-sampai pada saat yang hampir berbarengan 7 wartawan berhamburan ke luarnegeri, jadi kepala perwakilan, berjas serta dasi, mengangkat gelas anggur dan mengangguk-angguk, isap cerutu atau cangklong, naik mobil berbendera, menjadi tontonan ke mana lewat. Sejak dunia terkembang, paling tidak sejak republik Italia dan Venesia di abad 15 mula kali membuka perwakilan di ibukota masing-masing, belum pernah begitu banyak wartawan jadi duta. Adam Malik, BM Diah, Sukrisno, Asa Bafagih, Armunanto, Tahsin, Djawoto. Dan semua duta bisa berhenti mendadak sebelum waktunya. Jika pecah perang antar kedua negara. Jika terjadi peruhahan revolusioner baik di negeri pengirim ataupun penerima duta. Jika salah satu negara itu melenyap. Sebab, duta tidak mungkin mewakili angin, bukan? Atau jika si duta menghembuskan nafas yang penghabisan, baik karena suratan ajal, atau lewat cara yang diputuskannya sendiri, misalnya nyemplung ke dalam kolam atau melompat dari jendela tingkat empat. Dan jika sang duta ugal-ugalan, baik menurut gaya lama atau baru. Mendoza, duta Spanyol untuk kerajaan Inggeris tahun 1584 dihalau seperti garong karena dia ikut komplotan menggulingkan Ratu Elizabeth. Tiga tahun kemudian, 1587, duta Perancis L'Aubespine, bukan sekedar mau menggulingkan, melainkan langsung menghabiskan nyawa sang Ratu Untung tidak sampai diusir, cuma dipesan wanti-wanti jangan sekali lagi main-main seperti itu. Barangkali karena pembawaan atau kegemaran, duta Perancis berikutnya, de Bass, juga bergabung dengan gerombolan ingin membunuh Cromwell. Kontan, dalam tempo 24 jam, mesti siap dengan koper menyeberang selat Kanal. Sedangkan ugal-ugalan gaya baru banyak berkait dengan rangkapan peranan selaku intel, entah CIA, entah KGB, entah Dirrecion General de Inteligencia-nya Kuba. Dubes Kuba untuk Jepang, Ricardo Cabisas Ruiz, senantiasa menyelipkan sepucuk pistol di pinggang, dan menyimpan senapan mesin serta granat tangan serta bahan peledak di kantor. Diplomatnya di PBB, Lazaro Eddy Espinosa Bonet, diusir karena ketahuan motret-motret kediaman Presiden Nixon di Key Biscayne dan punya informasi lengkap perjalanan liburan Presiden ke Florida. Djawoto Akan halnya dubes Tahsin untuk Tanzania, cara berhentinya ada sedikit lain. Karena tidak berkenan dengan pemerintah baru di Indonesia, dan pemerintahan baru pun tidak pula menyukainya, begitu saja pergi tinggalkan pos menjinjing tas, entah ke arah mana. Rupanya, bukan anak sekolah saja yang bisa minggat. Tentang dubes Djawoto di Peking, bagaikan layang-layang putus talinya, terpental tanpa status, akibat perubahan politik di dalam negeri, dan putusnya hubungan diplomatik, pecah berantakan berkeping-keping. Jika tadinya saling sentuh dan sapa seperti layaknya famili dari satu kakek kini berganti umpat cemooh, cerca dan cela. Habislah poros-porosan, terkutuk tujuh turunan. Namun, tak seorangpun berkehendak putus hubungan ini berkepanjangan sampai hari kiamat. Indonesia juga tidak. Seribu beda pendapat boleh berkembang, seribu faham boleh selisih, perkara buhul-membuhul bukan halangan. Masalahnya, kapan? Terhitung sejak kedubes RRT dihujani batu-batu, beribu kata sudah terucap, beribu keterangan sudah keluar, dari mulut pejabat ini dan pejabat itu, perkara menormalisir hubungan kedua negara. Kadang terasa seperti sudah di depan hidung, kadang menjauh dan sayup-sayup, kemudian muncul lagi dengan gegap gempita, untuk selanjutnya tenggelam selama 6 atau 7 bulan, dan kembali dengan nada seperti sediakala, seperti belum pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Suara di awal tahun-70an: Normalisasi? Itu perkara gam.pang. Perkara kirim surat. Karena hubungan sekedar terputus, buat nyambungnya cukup tulis surat, masukkan ke dalam amplop, jebloskan di kantorpos, atau titip orang juga bisa. Belakangan, soal kirim surat ini menjadi tidak begitu gampang lagi, karena ada masalah susulan: Siapa yang mesti lebih dulu kirim surat? Jakarta atau Peking? Keduaduanya tidak ada yang lebih dulu kirim surat. Tidak jelas lagi, siapa menunggu surat siapa. Jalan Di Tempat Bulan Oktober 1972 tiba-tiba soal normalisasi tidak menjadi urusan tulis-menulis surat belaka, melainkan berubah jadi perkara berat yang tidak sembarang orang kuasa memutuskan. Tidak Kabinet, apalagi Menlu. Sebab, tak lain dari Menlu Adam Malik sendiri yang menyuarakan agar supaya masalah hubungan Indonesia-RRT diserahkan pada keputusan MPR. Alangkah jauh beda antara "cukup tulis surat" dengan "diserahkan MPR" bukan? Apa yang terjadi sesudah itu sudah sama tahu, tidak sepotong kata pun sidang MPR 1973 menyebut-nyebutnya. Tahun berikutnya, nada kembali berenteng-enteng. Jangankan nyebut MPR, DPR pun tidak. Suara yang biasa terdengar seperti ini: Soal normalisasi soal waktu. Soal normalisasi soal Indonesia. Soal normalisasi soal dalam negeri. Soal normalisasi tergantung sikap RRT. Soal normalisasi lihat saja nanti. Soal normalisasi tunggu saatnya yang tepat. Soal normalisasi diurus pelan-pelan jangan terburu-buru. Soal normalisasi dilihat untung-ruginya. Soal normalisasi soal dua belah pihak, tentu saja. Soal normalisasi .....dan seterusnya. Sampai di manakah kita gerangan sekarang ini? Bagaikan jalan di tempat, tidak sampai di mana-mana. Tiada kenormalan dalam normalisasi. Coba disimak ucap Menlu Adam Malik yang paling baru: Indonesia harus menormalisir hubungan diplomatik dengan RRT. Usaha kita sedang mengarah ke sana. Tapi, tidak seorang pun bisa memastikan kapan normalisasi itu bisa terlaksana. Setahun? Dua tahun? Entahlah. Sedangkan Menlu saja tidak tahu persis, bagaimana pula kita-kita orang. Wallahualam bissawab !
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini