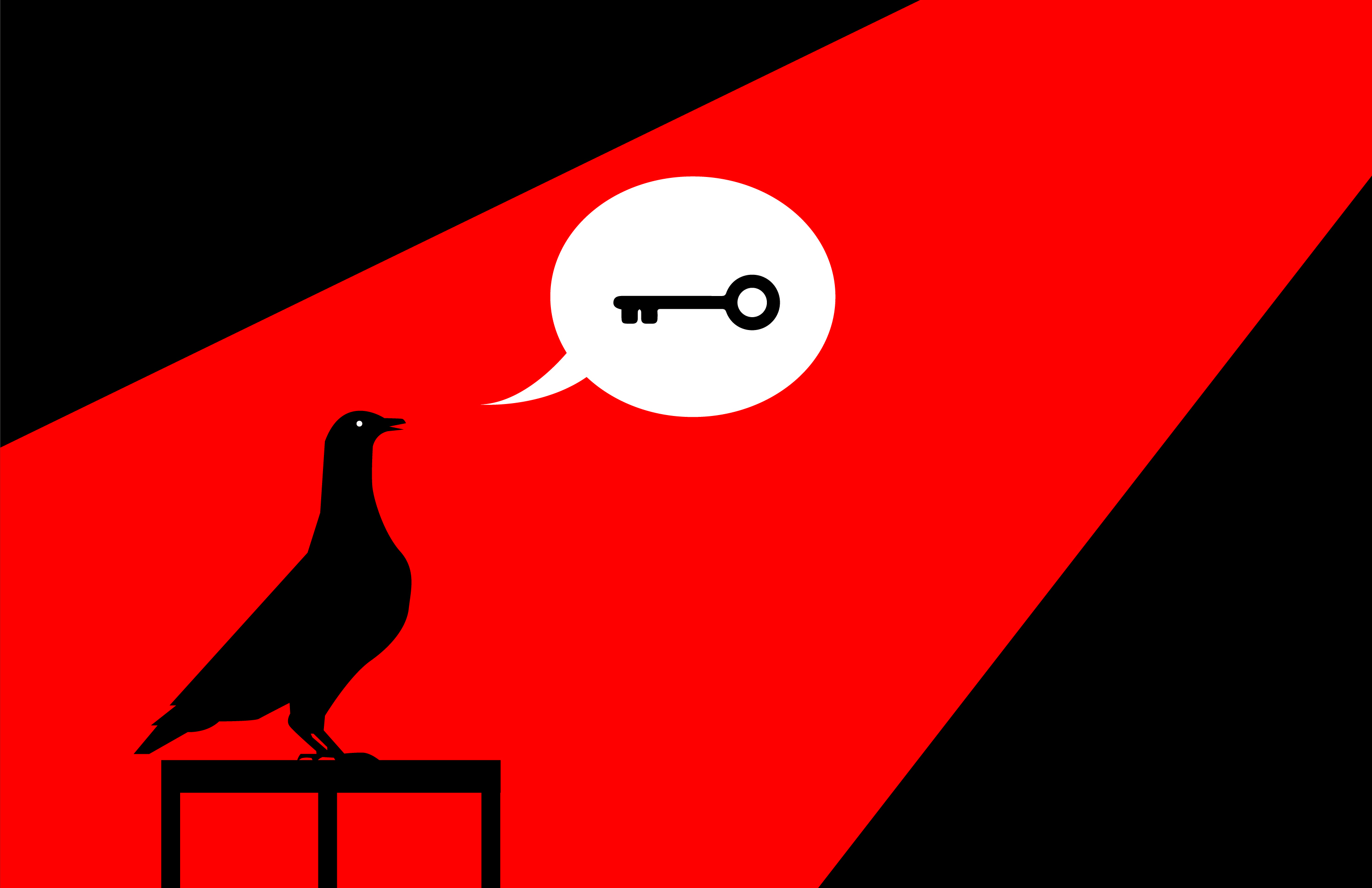Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Reformasi pernah membakar semangat mahasiswa untuk melakukan perubahan pada 1998.
Namun reformasi pada masa kini hanyalah mitos usang tanpa makna.
Banyak agenda reformasi yang tidak terpenuhi hingga kini.
Sri Lestari Wahyuningroem
Dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta dan Research Fellow Carr Center for Human Rights Policy, Harvard Kennedy School
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Reformasi, ketika didengung-dengungkan pada 1998, menjadi sebuah cita-cita besar yang membakar semangat, bukan saja mahasiswa, tapi juga seluruh elemen bangsa yang waktu itu menginginkan perubahan dalam waktu cepat. Perubahan dari rezim yang merepresi ke demokrasi serta dari keterpurukan sosial-ekonomi ke kesejahteraan. Reformasi, dalam perjalanannya, lambat laun menjadi mitos. Hari ini, 25 tahun kemudian, mitos itu sudah usang dan tanpa makna.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Georges Sorel, filsuf sosial Prancis, memberi makna dan atribut politik pada konsepsi "mitos". Mitos politik, menurut Sorel (1990), digunakan untuk menggambarkan visi masa depan yang mengilhami gerakan massal atau revolusioner berskala besar. Visi ini demikian kuat sehingga seolah-olah menghadirkan realitasnya sendiri dan menentang berbagai kritik rasional. Begitu pula dengan reformasi 1998, yang memberikan gambaran masa depan Indonesia yang demokratis dan berdaulat sekaligus membakar semangat gerakan.
Sebagai sebuah visi, reformasi terus-menerus digaungkan setiap tahun hingga kini. Kita terus didongengi aksi heroik masa mahasiswa serta bagaimana nyawa saudara-saudara kita harus menebus mahalnya harga reformasi melalui penembakan dan kerusuhan massal di banyak wilayah. Waktu seolah-olah tidak beranjak dari tahun tersebut, dan memang demikianlah sebuah mitos akan menegasikan berbagai peristiwa-peristiwa penting lain sesudah dongeng itu dibuat. Refleksi kritis menjadi tidak bermakna. Cukup dongeng itu saja yang dibahanakan, terutama oleh mereka yang berkuasa, sebagai cara untuk melegitimasi kekuasaan.
Enam tuntutan reformasi rasanya sekarang sudah usang dan kehilangan makna. Dari enam tuntutan itu, yang pertama, mengadili Soeharto, sudah tidak mungkin dipenuhi. Soeharto menikmati impunitas sampai akhir hayatnya. Mereka yang terafiliasi serta mendapat manfaat dari Orde Baru sudah mentransformasikan kekuatan dan pengaruhnya dengan tampilan-tampilan baru, tapi dengan sifat tamak kuasa yang sama. Setiap lima tahun, aktor-aktor yang sama berkompetisi dan membangun koalisi dengan oligark untuk memperkuat posisi masing-masing.
Tuntutan kedua, amendemen Undang-Undang Dasar 1945, sudah dilakukan tidak kurang dari empat kali sejak 1999 hingga 2002. Amendemen ini mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan republik. Namun, faktanya, hal itu malah memindahkan sentralitas kekuasaan dari pimpinan eksekutif (presiden) ke pimpinan partai politik, meskipun sama-sama dalam model presidensial.
Tuntutan ketiga adalah otonomi daerah. Undang-undangnya terbit pada 1999, tapi desentralisasi dilaksanakan pada 2004. Berkat desentralisasi, daerah bisa lebih cepat dan tanggap melakukan pembangunan masing-masing. Namun, berkat desentralisasi pula, korupsi meningkat di daerah. Selain itu, terjadi perubahan tren konflik dari pusat ke daerah, khususnya konflik sumber daya alam dan agraria. Meskipun tiga tahun pandemi Covid-19 melanda, tren konflik tanah dan agraria tetap meningkat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 212 konflik pada 2022. Angka yang paling tinggi berasal dari sektor perkebunan (99 kasus) dan wilayah paling banyak konflik ada di Jawa Barat (25 kasus).
Sementara itu, penolakan terhadap dwifungsi ABRI, tuntutan keempat reformasi, juga punya catatan tersendiri. Militer secara resmi tidak lagi memiliki fraksi khusus di Dewan Perwakilan Rakyat serta tidak mengelola aset dan lembaga ekonomi negara. Namun kita masih sangat bisa merasakan keterlibatan militer di ruang sipil dengan pemberian posisi-posisi publik di kementerian atau lembaga sipil kepada personelnya, serta pelibatan militer dalam keamanan lokal dan pendayagunaan sumber daya alam. Personel militer secara individual juga masih memiliki akses terhadap bisnis, baik yang kecil maupun besar. Selain itu, tentu saja, partai politik masih mengakomodasi personel militer, khususnya yang sudah pensiun, bahkan memberi mereka posisi penting.
Tuntutan reformasi lainnya adalah menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejak 2013, indeks persepsi korupsi Indonesia konsisten di angka 32 hingga 40. Pada 2022, indeks Indonesia ada di angka 34 dari skor 100, yang menempatkan Indonesia di posisi ke-110 dari 180 negara yang disurvei (Transparency International, 2022). Kita bersyukur memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir dari semangat reformasi. Namun lembaga yang seyogianya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi ini juga berjuang untuk tetap memiliki integritas dan independensi setelah beberapa kali ada upaya memandulkannya, termasuk melalui revisi Undang-Undang KPK.
Agenda terakhir adalah penegakan supremasi hukum. Bank Dunia mencatat indeks penegakan hukum Indonesia konsisten berada di posisi minus hingga 2021, dengan menempati posisi ke-68 dari 139 negara yang disurvei. Pemerintah melakukan sejumlah terobosan hukum untuk memastikan penegakan hukum berjalan dan mempermudah penyelesaian masalah. Sayangnya, inisiatif pemerintah, seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak secara massal, justru memihak pemodal dan mengeksploitasi lingkungan.
Selain itu, ruang kebebasan sipil semakin sempit dengan diterapkannya hukum yang cenderung represif dan membungkam kebebasan berekspresi. Ini sejalan dengan indeks demokrasi Indonesia (IDI) dalam beberapa tahun terakhir. Penegakan hukum juga tidak dilakukan secara adil dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama yang terjadi di masa lalu. Impunitas masih terjadi dan akan tetap mengganjal hadirnya keadilan bagi para korban yang tak lelah melakukan aksi damai setiap Kamis di depan Istana Negara. Keadilan untuk mereka yang menjadi korban reformasi, dari kasus penghilangan paksa para aktivis dan mahasiswa hingga korban kerusuhan Mei 1998, juga masih menjadi pertanyaan.
Jadi, masihkah reformasi bermakna untuk kita maju melangkah? Mungkin kini waktunya kita menyudahi mitos reformasi, mengglorifikasi satu penggalan peristiwa yang menandai sebuah perubahan, tapi tetap mengingat bahwa agenda perubahan itu masih jauh panggang dari api. Reformasi terbukti tidak menjadi bagian dari selebrasi politik para elite yang hari-hari ini disibukkan dengan berbagai transaksi. Bagi mereka, reformasi hanya bisikan samar-samar dan nanti diumbar sebagai legitimasi dalam kontestasi politik pada Pemilu 2024. Kalau sudah demikian, benarlah reformasi hanya mitos yang sudah usang tanpa makna.
PENGUMUMAN
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak, foto profil, dan CV ringkas.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo